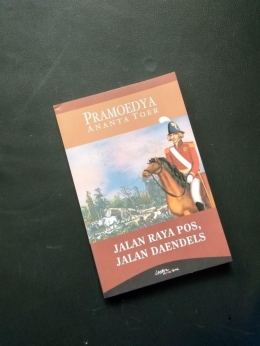Bulan Agustus bukan hanya menjadi perayaan kemerdekaan bagi Republik Indonesia, namun juga menjadi kegalauan bagi masyarakat Indonesia. Karena, di waktu yang sama Indonesia terjadi perselisihan yang didasari oleh adanya praktik rasial di Pulau Jawa.
Kejadian itu kabarnya terjadi di Malang dan Surabaya, namun publik lebih terfokus di Surabaya. Karena, kabarnya memang di situlah letak awal mula kejadiannya. Namun, bagaikan api yang menyentuh kayu kering, maka gejolak yang terjadi di Surabaya tersebut juga merembet ke daerah-daerah lain, seperti Semarang dan Bandung.
Namun, kejadian yang lebih parah justru terjadi di Papua. Dikarenakan adanya unjuk simpatisan terhadap kejadian di Jawa, beberapa orang di Papua menggelar aksi demonstrasi. Namun, nahasnya aksi itu juga berujung pada perusakan infrastuktur pemerintah dan publik.
Kekacauan di Papua itu juga tidak hanya merugikan pihak pemerintah, namun juga masyarakat. Karena keamanan untuk menggelar pendidikan terganggu, begitu pula dengan keamanan menggelar pertandingan sepakbola (Persipura vs Bali United). Ini yang membuat bukan hanya masyarakat Papua yang menderita kerugian, namun juga masyarakat Indonesia secara umum.
Rasisme memang harus dilawan. Namun, selama negeri ini memiliki akal untuk membangun negara, maka akal itulah yang harus dilakukan. Tidak hanya berlaku untuk pemerintah, namun juga untuk masyarakat. Kita harus tetap jernih dalam menghadapi permasalahan di kalangan masyarakat termasuk dalam hal rasisme.
Pemerintah harus tegas, itulah yang diinginkan oleh masyarakat khususnya masyarakat Papua. Mereka harus mendapatkan kesetaraan, karena mereka memang sama seperti masyarakat di daerah lain. Mereka juga punya kapasitas untuk berkarya dan membangun bangsa ini untuk lebih maju.
Maka dari itu, isu rasisme harus dilawan dengan tegas. Namun tidak dengan separatisme. Justru lawan dari rasisme adalah "unitisme" (kita akrab dengan istilah Nasionalisme), persatuan. Kita harus bersatu sebagai Indonesia dari Sabang sampai Merauke selamanya. Itulah yang harus kita lakukan untuk melawan rasisme.
Sehingga, isu separatisme yang kemudian mengarah pada isu referendum Papua menjadi perihal yang seratus persen tidak bisa diterima oleh akal kita sebagai warga Indonesia yang tetap menginginkan persatuan. Mengapa?
Karena, referendum hanya terjadi pada wilayah yang hampir 100% tidak mendapatkan keadilan di suatu negara. Di sini, referensi pembanding yang dihadirkan adalah Spanyol dengan kasus referendum Catalunya. Walau diyakini ini adalah informasi yang didapatkan oleh masyarakat dunia internasional, namun apa yang terjadi di Catalunya bisa disebut sebagai kejadian yang lebih buruk dibandingkan apa yang terjadi di Papua.

Memang, jika ditilik riwayatnya dari dulu -masa pemerintahan orde lama, orde baru, dan reformasi awal- hingga saat ini, apa yang terjadi di Papua sebenarnya juga mirip dengan apa yang dialami oleh masyarakat di Catalunya. Namun, seiring berjalannya waktu, permasalahan itu (kesenjangan dan lainnya) mulai dihadapi dan diperbaiki. Ada beberapa hal yang dapat dilihat dari segi apapun dalam melihat bentuk perbaikan tersebut.
Pertama adalah pertumbuhan cendekiawan dari Papua. Hal ini tidak lepas dari banyaknya anak muda Papua yang dapat berkuliah, baik itu di perguruan tinggi di Papua maupun di Indonesia. Bahkan beberapa orang di Papua juga dapat bersekolah di perguruan tinggi Australia. Artinya, Papua melalui SDM-nya sudah mengalami peningkatan dari masa ke masa.
Hal ini tentu tidak lepas dari terbukanya peluang yang diberikan oleh pemerintah. Termasuk ketika dunia pendidikan berkolaborasi dengan dunia olahraga. Maka, banyak anak-anak muda di Papua yang dapat mengenyam pendidikan tinggi melalui beasiswa jalur minat dan bakat yang dimiliki, khususnya dalam bidang olahraga.
Kedua, adalah perkembangan infrastruktur. Program pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) untuk Papua sudah mengalami peningkatan. Termasuk bagaimana pemerintah menetapkan Papua untuk menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2020. Itu artinya Papua punya kesempatan untuk menjadi wilayah yang sama seperti Jawa, Sumatera, dan lainnya untuk menggelar ajang nasional.
Ajang ini pula yang kemudian dapat dikorelasikan dengan keberadaan infrastruktur yang semakin memadai. Tidak hanya pada infrastruktur olahraga yang ditingkatkan, namun juga sarana publik lainnya. Inilah yang dapat membuat masyarakat Indonesia (orang Papua dan bukan orang Papua) yang ada di Papua diprediksi dan seharusnya akan semakin nyaman dan aman.
Ketiga, kesejahteraan yang terus dikembangkan di Papua. Hal ini dapat dicontohkan dengan harga BBM yang setara antara Papua dengan di Jawa. Sehingga, tidak ada lagi perbedaan "standar ekonomi" antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa (sebenarnya tidak hanya Papua yang mengeluh tentang perbedaan harga BBM dan sembako).
Alur peningkatan kesejahteraan ini tidak akan bisa terwujud jika infrastruktur tidak memadai. Seperti yang pernah diungkap oleh Presiden Jokowi pada suatu kesempatan yang menyatakan bahwa (sudah dikutip bebas oleh penulis), bagaimana masyarakat (di Papua) dapat sejahtera (dan setara dengan Pulau Jawa) jika kondisi lapangan (maksudnya infrastruktur) di sana tidak memadai.
Untuk itulah infrastruktur diperlukan, pembangunan diperlukan. Melalui itu pula, persaingan Indonesia dengan negara lain di bidang pemajuan dan kemakmuran dapat dilakukan.
Logika inilah yang dipakai untuk mengembangkan Papua dan dipegang erat-erat oleh Presiden Jokowi sampai saat ini. Bahkan, beliau dengan tegas menyatakan bahwa pembangunan (dan kesejahteraan) di Papua adalah prioritas di masa pemerintahannya. Misi inilah yang seharusnya dapat menjadi kekuatan masyarakat (khususnya masyarakat Papua) untuk ber-positive thinking terhadap pemerintah.
Lalu apakah pembangunan Papua itu adalah senjata penting bagi Indonesia untuk merangkul Papua?
Antara ya dan tidak.
Tidak, karena, pembangunan yang apalagi bersifat fisik tidak dapat langsung terlihat fungsinya bagi masyarakat setempat. Namun dapat pula dikatakan ya, karena melalui pembangunan, misi untuk kesejahteraan dapat dimulai dan berlangsung.
Hal ini dapat merujuk pada situasi di salah satu daerah di Papua yang menggambarkan keadaan pendidikan yang memilukan karena faktor medannya. Daerah itu sebenarnya memiliki gedung sekolah (SD), namun karena aksesnya (jalan menuju sekolah) tidak memadai, membuat tenaga didik enggan bekerja di tempat tersebut.
Baca ulasannya di sini: Pendidikan di Pedalaman Asmat (Petrus Pit Supardi)
Faktor ini membuat sekolah tersebut semakin tidak terawat dan tidak dijalankan sebagaimana fungsinya. Apabila jalan dan keberadaan pemukiman yang memadai, maka dapat dipastikan para tenaga didik itu akan bersedia kembali mengajar.
Penilaian ini tentu di luar dari aspek kemanusiaan, karena guru juga manusia biasa yang terkadang memikirkan faktor keselamatan dan kenyamanan sebelum memikirkan bagaimana cara untuk mencerdaskan muridnya.
Dari sini, kita bisa melihat bahwa keberadaan pembangunan, secara pasti akan dimanfaatkan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Situasi ini tentu sama seperti Indonesia di masa penjajahan Belanda.
Jika Belanda tidak membangun (di buku Pram dinyatakan diperlebar) Jalan Daendels, mungkin pertumbuhan ekonomi dan lainnya di Pulau Jawa akan lebih lambat dari saat ini.
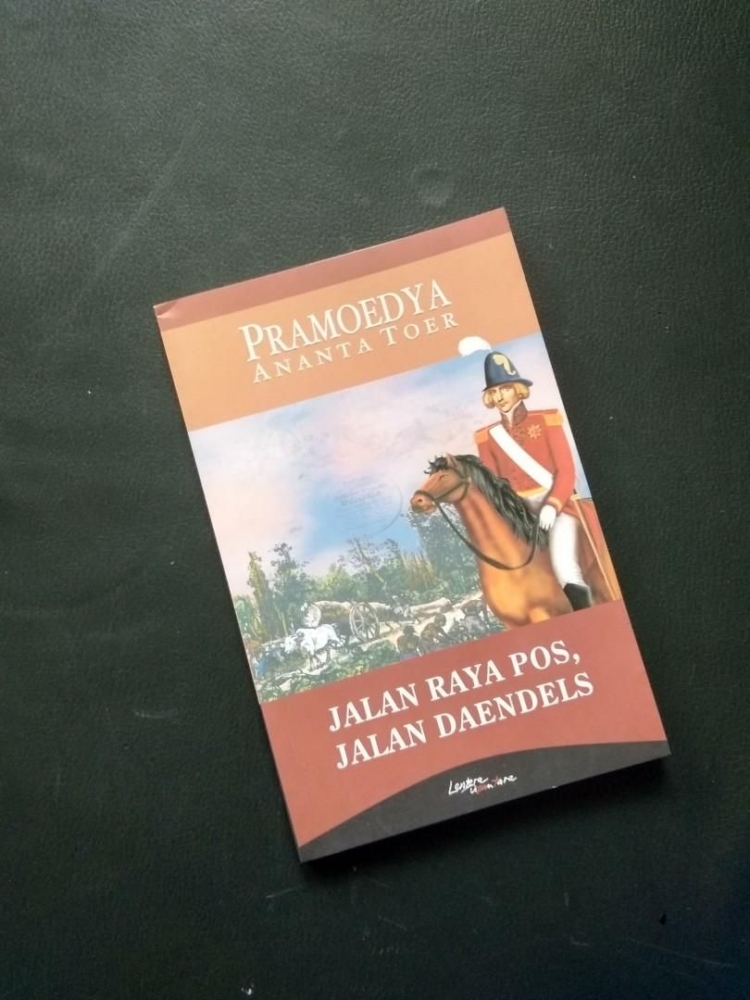
Di masa itu pula asumsi masyarakat Jawa tentu juga akan menyatakan jika mereka tidak akan menggunakan jalan itu. Apalagi jalan itu dibangun dengan pengorbanan nyawa sanak keluarga. Namun, buktinya kita saat ini telah "menjajah" jalan itu dengan berbagai jenis kendaraan dengan berbagai jenis ban yang berbeda dan tentunya dengan kebanggaan.
Inilah yang perlu dilihat oleh masyarakat Indonesia, tidak hanya masyarakat Papua, bahwa pembangunan itu perlu dan sangat perlu lagi jika pembangunan itu dilakukan di Papua. Karena, memang itulah yang diperlukan saat ini sebelum benar-benar terlambat.
Lalu bagaimana soal kesejahteraan? Apakah pasca pembangunan, kesejahteraan akan mengikuti?
Jika pembangunan itu bergantung pada ketersediaan dana dan utang yang dimiliki pemerintah pusat, maka kesejahteraan itu bergantung pada nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat. Apakah kita sudah memiliki budi yang kuat atau belum, itulah yang nanti akan menentukan bagaimana kesejahteraan akan terjadi khususnya di Papua.
Jika merujuk kembali pada kisah pendidikan di atas, kita tentu tahu bahwa kemanusiaan itu bukan berpatok pada pemerintah pusat saja. Bukan perpatok pula pada masyarakat Indonesia non Papua (yang dikenal lebih cerdas). Namun, berpatok pula pada masyarakat yang ada di Papua. Apakah mereka yang sudah mendapatkan pengembanan tugas sudah mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan benar?
Inilah yang kemudian perlu digarisbawahi, yaitu kemawasan diri. Kita masing-masing perlu mawas diri. Sebagai orang Jawa atau yang (dianggap) berkulit tidak hitam, dan juga beragama mayoritas, harus mawas diri bahwa tidak semua pandangan kebaikan berdasarkan identitas (ras) tersebut akan menjamin nilai-nilai luhur. Mereka juga pasti punya kesalahan yang tidak sedikit.
Sedangkan bagi orang non Jawa, (dianggap) berkulit nyaris seperti arang dan beragama minoritas, tentu harus mawas diri bahwa perselisihan berdasarkan rasisme tidak dapat diselesaikan dengan separatisme. Karena, di antara mereka pula tidak sepenuhnya terdapat orang-orang yang progresif yang nantinya dapat menjamin kesejahteraan jika mereka merdeka.
Seperti yang terlihat di kasus sekolah yang tak terawat itu, kita bisa melihat bahwa di Papua juga masih ada orang-orang yang belum memiliki solidaritas dan keberanian untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.
Sehingga, kemerdekaan dan isu referendum tersebut tidak akan serta-merta akan menumbuhkan semangat untuk lebih baik (yang kini sebenarnya sudah berada di level berkembang) melainkan justru mengembalikan misi mereka untuk membangun tatanan dari awal.
Situasi ini dapat dilihat di Timor Leste (tanpa bermaksud menyinggung ataupun merendahkan negara tersebut) yang sampai saat ini juga masih kesulitan untuk berkembang. Namun, di sisi lain dengan keberadaan referendum, wilayah-wilayah yang memang ingin merdeka pada akhirnya juga akan memiliki haknya untuk menentukan nasib sendiri seperti Catalunya -walau mereka belum tentu langsung maju seperti Spanyol.
Mereka (masyarakat Catalunya) seharusnya memang dapat membangun diri mereka sebagai negara baru. Apalagi jika menilik pada informasi internasional yang memperlihatkan bagaimana Spanyol (dengan Madrid-nya) berupaya untuk dapat menghambat pertumbuhan potensi bagus dari Catalunya di segala aspek (ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya).
Inilah yang membedakan antara Catalunya dengan Papua. Catalunya tidak memiliki kesempatan untuk berkembang karena pihak pemerintah pusat memberlakukan peraturan-peraturan khusus yang harus dijalankan oleh masyarakat Catalunya.
Bahkan, situasinya semakin buruk ketika pemerintah Spanyol memberlakukan penyeragaman, seperti bahasa dan budaya. Inilah yang membuat masyarakat Catalunya seperti mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
Situasi ini tentu berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Budaya Papua diakui, bahasa daerah di Papua juga tidak dipermasalahkan. Bahkan mereka dapat menggunakannya ketika bertemu dengan sesama orang Papua ketika berada di tempat rantauan.
Hal yang tentunya dapat diakui oleh semua masyarakat Indonesia -tidak hanya orang Papua, yang mana mereka masih tetap dapat menggunakan bahasa daerahnya masing-masing ketika bertemu dengan sesama asal daerahnya.
Walau bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan, namun bahasa daerah bukan sebagai bahasa perpecahan. Inilah yang membuat pemerintahan Indonesia (sebenarnya) tidak begitu buruk, apalagi harus dipandang kurang adil dan memicu (isu) separatisasi.
Dari sini, kita dapat melihat bahwa Indonesia sudah cukup baik dalam mengelola negaranya khususnya dalam menghormati perbedaan pada masyarakatnya. Hal inilah yang seharusnya menjadi nilai bagus yang harus dipertahankan oleh kita semua.
Jangan sampai, ketika pemerintah sudah berupaya mati-matian menyetarakan derajat masyarakatnya, kita sebagai masyarakat justru saling mencela adanya perbedaan.
Jadi, apakah Papua senasib dengan Catalunya?
Di satu sisi (jika seandainya penulis adalah orang Papua), kita dapat menilai Papua senasib dengan Catalunya. Masyarakat Papua punya potensi SDA yang memadai dan juga SDM unggul di bidang-bidang tertentu, seperti olahraga salah satunya.
Maka, mereka juga merasa perlu dianggap sama-sama memiliki kualitas. Sehingga, mereka juga punya peluang untuk mandiri -punya otonomi yang tepat dan sesuai kebutuhan.
Namun di satu sisi (sebagai orang Indonesia), Papua tidak senasib dengan Catalunya. Karena, Papua masih diperhatikan oleh pemerintah, besar-kecil dan cepat-lambat, Papua masih diayomi oleh pemerintah (pusat dan daerah). Bahkan, sebenarnya ini juga perlu dialamatkan pada pemerintah daerahnya, apakah mereka sudah menjalankan visi-misi yang progresif untuk daerahnya masing-masing atau belum.
Kendalanya secara umum di polemik ini adalah visi-misi. Pemerintah itu cara kerjanya tidak begitu sama dengan pihak swasta. Inilah yang membuat cara kerja pemerintah itu dapat dinilai lamban dan tidak besar dalam menjangkau masyarakatnya, khususnya dalam hal kesejahteraan.
Jangankan di Papua, masyarakat di wilayah lain -termasuk Jawa- juga tidak semuanya merasa sejahtera. Masih banyak pengangguran pula di Jawa dan itu adalah fakta-realitas yang tidak bisa dipungkiri dan dihilangkan dengan keajaiban satu malam.
Inilah yang menjadi permasalahan bagi pemerintah, yaitu, mereka punya banyak pekerjaan rumah dengan menanggung seluruh wilayahnya. Belum lagi jika berbicara soal rezim dan prioritas. Masing-masing masa pemerintah pasti memiliki prioritas tersendiri.
Situasi inilah yang tidak sama jika disandingkan dengan pihak swasta. Karena, mereka hanya perlu menanggung sepersekian persen dari masyarakat yang ada di wilayah Indonesia untuk mereka coba rangkul dan biasanya itu juga berkaitan dengan keuntungan yang dapat mereka raih.
Sebut saja PT. Djarum Indonesia atau Djarum Foundation. Mengapa mereka dapat memiliki program beasiswa? Mengapa mereka dapat terlihat lebih mengayomi anak muda Indonesia? Karena, mereka punya program CSR yang jelas dan mereka dituntut untuk bekerja berdasarkan berhasil dan tidak berhasil dalam waktu yang relatif lebih singkat daripada pegawai di pemerintahan.
Inilah yang membuat program kemanusiaan yang dijalankan pihak swasta lebih cepat dan (terlihat) tepat sasaran. Karena mereka tidak harus mencakup semua wilayah yang ada di Indonesia.
Freeport sejak dulu sampai sekarang pun hanya mampu mengeruk tanah Papua dan sudah selayaknya pula mereka memperhatikan masyarakat setempat. Begitu pula pihak-pihak swasta lain.
Oleh karena itu, menjadi merdeka atau menuntut kesejahteraan dan kesetaraan itu tidaklah mudah (sesuai angan-angan). Karena harapan-harapan itu tidak hanya membutuhkan peran pemerintah dalam merealisasikannya, namun juga berdasarkan peran masyarakatnya.
Jika masyarakatnya masih mengikat paham-paham separatisme, radikalisme, dan lain-lain, pemerintah juga akan kesulitan untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat, karena mereka pasti harus menghentikan terlebih dahulu ekstrimis-ekstrimis tersebut.
Seandainya, Indonesia tidak banyak berkonflik dengan sesamanya, mungkin pemerintahnya akan semakin perhatian dengan masyarakatnya. Bahkan mungkin di setiap rumah akan diperiksa apakah orang-orang didalamnya sudah makan atau belum. Hehehe...
Namun, pada kenyataannya, tidak ada negara di dunia ini yang tidak berkonflik. Entah konflik besar-kecil ataupun laten, setiap negara hampir selalu memilikinya. Apalagi jika negara itu adalah Indonesia yang memiliki wilayah yang tidak sempit.
Jadi, apakah kita bisa bersatu kembali dan fokus menatap ke depan sebagai masyarakat Sabang-Merauke? Itulah yang perlu kita pikirkan dan wujudkan bersama.
Malang, 3-4 September 2019
Deddy Husein S.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H