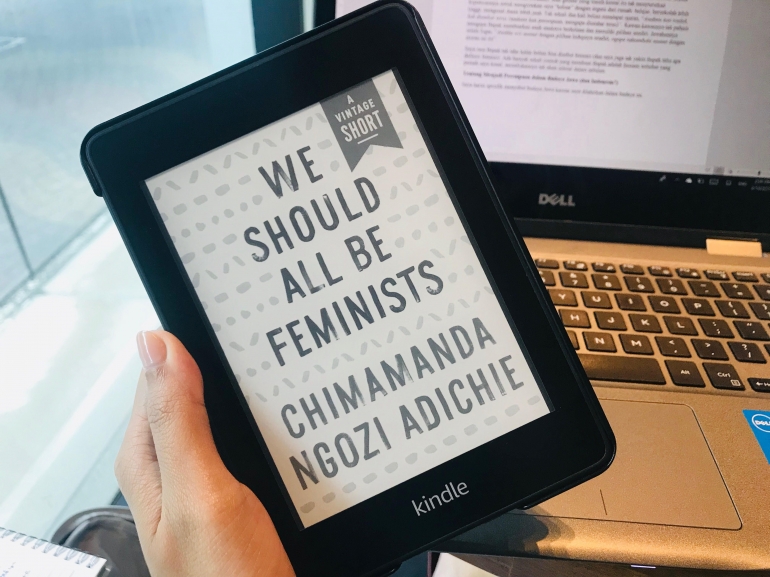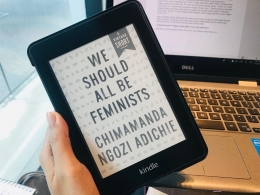Meski sejak lama mendengar gaung istilah "feminis" dan "feminisme", saya cenderung kurang tertarik untuk mendalami atau mengetahui lebih banyak tentang label ini. Saya juga tidak membaca buku apapun yang berkaitan dengan feminisme, tidak terlalu sering terpapar isunya, meski memiliki beberapa kawan yang menyebut dirinya feminis.
Di Twitter saya acap menjumpai label ini digunakan dan dengan sentimen yang cukup terpolarisasi, ada stereotipe bahwa feminis adalah mereka yang selalu marah-marah dengan ketidakadilan terkait gender, ada pula yang melihat feminis sebagai sosok mengagumkan dengan keberanian luar biasa mendobrak budaya patriarki.
Jadi, seperti apa sebenarnya feminis dan feminisme itu?
Feminis yang Bahagia
Beberapa waktu lalu saya membaca esai singkat dari Chimamanda Ngozi Adichie, seorang penulis, pembicara, dan aktivis yang banyak menulis tentang feminisme, negara kelahirannya (Nigeria), dan ragam aspirasi yang dimilikinya sebagai seorang perempuan yang berdaya. Esai singkat yang dielaborasi dari TED Talk mengenai tema yang sama ini berjudul "We Should All Be Feminists (Kita Semua Sebaiknya Menjadi Feminis)" ini menceritakan mengenai permenungannya terhadap fenomena feminisme.
Menurut Chimamanda, istilah feminis memang menjadi stereotipe yang agak kurang positif. Ada yang mengatakan padanya bahwa feminis itu perempuan yang nggak bahagia, sehingga Chimamanda pernah menyebut dirinya "happy feminist (feminis yang bahagia)". Ada yang mengatakan padanya bahwa feminisme itu budaya Barat dan nggak sesuai dengan Nigeria, jadi Chimamanda kemudian menyebut dirinya "happy African feminist (feminis Afrika yang bahagia)".
Membaca ceritanya membuat saya tersenyum-senyum sendiri.
Yang digarisbawahi Chimamanda kemudian bukan tentang stereotipe dan definisi secara ilmu dan buku teks, ia menutup esainya dengan definisinya sendiri tentang feminis: bahwa ada bias gender di dunia ini, dan seorang feminis adalah mereka yang menyadarinya dan mau berusaha untuk memperbaikinya.
Feminis Terhebat yang Saya Tahu
Dengan definisi Chimamanda dan definisi kamus, feminis terhebat yang pernah saya tahu (dan kenal) adalah mendiang ayah saya.
Bapak, begitu saya menyebutnya, memang menginginkan anak laki-laki. Saya tidak begitu paham mengenai alasan lengkapnya, yang saya tahu Bapak menginginkan anaknya untuk memiliki hobi, minat, dan passion yang mirip dengannya. Bapak menyukai olahraga dan cukup serius menekuni hobi main sepak bola, kemudian beralih menjadi wasit sepak bola.
Sewaktu kecil saya sering dibawa Ibu menyaksikan pertandingan yang diwasiti oleh Bapak. Saya, tentu, tak mengerti pertandingannya. Saya hanya senang melihat Bapak berlari di lapangan (dan tentu senang dengan ragam jajanan yang bermunculan saat ada pertandingan). Rasanya lebih 'lengkap' bila saya terlahir laki-laki, yang mungkin akan memiliki minat dan hobi yang sama dengan Bapak dan bisa dilatihnya bermain sepak bola.
(Kenyataannya memang dulu saat SD saya pernah ditawari Bapak untuk masuk sekolah wasit sepak bola. Bayangkan jika dulu saya menyanggupinya, mungkin saya akan menjadi satu dari sedikit perempuan, dan bila berhasil, cukup keren juga ya mungkin saya sekarang: wasit perempuan pertama di Indonesia? -- tambahkan hestek halah)
Tidak, Bapak tidak kecewa bahwa anak pertamanya (dan kemudian keduanya) perempuan. Justru dengan pandangannya tentang bagaimana anak diarahkan untuk berkembang, beliau tidak memberikan batasan gender pada anak-anaknya. Diajaknya saya bermain layang-layang dan pergi ke sawah, dibiarkannya saya bermain kotor-kotoran dengan kawan-kawan yang banyak laki-lakinya.
Di sekolah (karena Bapak dulu kebetulan guru di SD tempat saya belajar), Bapak mendobrak "norma" dengan mengizinkan saya (dan siapapun murid perempuan yang berani) untuk menjadi ketua kelas, pemimpin upacara, pembawa bendera, pemimpin regu pramuka. Ini hal yang biasa banget di masa sekarang, namun di awal tahun 1990-an dan di desa yang cukup jauh dari kemajuan, apa yang Bapak lakukan adalah sebuah hal yang berbeda (dan luar biasa).
Bapak tidak mengenal pandangan bahwa perempuan Jawa itu tugasnya 3M: masak, macak, manak (memasak, berdandan, dan beranak). Bias gender yang masih kental itu tak menyurutkan keputusannya untuk mengizinkan saya "keluar" dengan segera dari rumah: belajar, bersekolah lebih tinggi, mengenal dunia lebih jauh.
Tak sekali dua kali beliau mendapat ujaran, "Anakmu kan wedok, kok diumbar terus (anakmu kan perempuan, mengapa diumbar terus)". Kawan-kawannya tak paham mengapa Bapak membiarkan anak-anaknya berkelana dan memiliki pilihan sendiri. Jawabannya selalu lugas, "Anakku wis mumet dengan pilihan hidupnya sendiri, ngopo tak tambahi mumet dengan aturan ini itu".
Saya rasa Bapak tak tahu kalau beliau bisa disebut feminis (dan saya juga tak yakin Bapak tahu apa definisi feminis). Ada banyak sekali contoh yang membuat Bapak adalah feminis terhebat yang pernah saya kenal, menuliskannya tak akan selesai dalam sebulan.
Tentang Menjadi Perempuan dalam Budaya Kita
Saya harus spesifik menyebut budaya Jawa karena saya dilahirkan dalam budaya ini. Bahwa bias gender itu ada dalam budaya Jawa tidak kemudian berarti ia tidak ada bahwa dalam budaya lain. Mengenali bias gender ini juga tak mudah, budaya telah menjadi cara hidup yang diimani dan dipraktikkan turun temurun sehingga seolah tak ada yang salah dengan cara tersebut.
Sama seperti Kartini yang tak memiliki kesempatan yang sama seperti kakak-kakaknya yang laki-laki, pada masa itu memang pendidikan dan pengetahuan (serta jejaring dan perkawanan) disebut lebih penting untuk laki-laki dibanding perempuan.
Dalam pekerjaan saya sekarang pun saya banyak menemui bias gender, misalnya dalam forum komunitas, perempuan cenderung tidak bersuara bila mereka hadir bersama dengan laki-laki. Ini adalah batasan budaya, bahwa perempuan tidak boleh terlalu banyak berpendapat. Mereka baru bersuara bila forumnya hanya dihadiri oleh perempuan, atau bila diajak berbicara secara privat.
(Tentu saya juga harus menggarisbawahi bahwa bias gender dari sisi laki-laki itu banyak. Bahwa laki-laki harus berprofesi "maskulin", misalnya. Pembagian peran maskulin dan feminin ini membuka ruang diskusi yang sangat lebar).
Dulu saya pernah ingin menjadi astronot. Alasannya sederhana: saya sangat, SANGAT, terinspirasi oleh Ibu Pratiwi Sudarmono. Membaca profilnya di sebuah majalah (atau koran ya?) membuat saya kagum, apalagi melihat fotonya berseragam astronot. Meski saya sudah membaca buku-buku anak-anak yang bercerita tentang astronot, baru kali itu saya lihat astronot perempuan.
Ketika saya bilang ingin jadi astronot, banyak yang gimana ya, sedikit menertawakan begitu. Termasuk seorang jurnalis lokal yang dulu mewawancarai saya untuk profil siswa berprestasi (ehem). Mereka heran karena bagi perempuan Jawa dan di lingkup lingkungan saya waktu itu, sekolah paling tinggi ya bila beruntung S1. Lalu kerja jadi PNS atau menjadi ibu rumah tangga. Pilihannya tak sebanyak sekarang, dan jelas tak sebanyak laki-laki yang bisa menjadi apa saja dan merantau jauh ke mana saja.
(Soal "diumbar" tadi, bila yang merantau laki-laki; maka yang datang adalah pujian. Beda ceritanya karena saya perempuan).
Agaknya Bapak melihat norma tentang perempuan ini sebagai tantangan dalam mendidik saya. Dulu saya tak tahu konsep bias gender ini (karena saya sejujurnya tak begitu merasakannya, Bapak mengizinkan saya mengalami banyak hal). Meski demikian, saya ingat Bapak berulangkali mengatakan pada saya bahwa bila saya ingin berhasil (dan bila ingin orang melihat saya mampu), saya harus membuktikan kerja keras dan komitmen saya.
Saya ingin menjadi ketua kelas, saya harus buktikan saya rajin dan mampu berkomunikasi baik dengan kawan-kawan sekelas. Saya ingin menjadi pemimpin upacara, saya harus latihan. Bila siswa laki-laki mudah saja dipilih karena berbadan tegap dan bersuara keras, saya harus latihan sering-sering agar bisa bersuara sama keras dan tegas.
Kata Bapak, "Untuk menjadi setara dengan laki-laki, seringkali kamu harus 2 kali lebih baik, 2 kali bekerja lebih keras."
Ujaran yang pahit? Terkesan begitu.
Bias gender juga acap ditemui dengan indikator kepemimpinan. Katanya, semakin tinggi pucuk pimpinan, semakin sedikit perempuan yang ada di sana. Misalnya saja untuk perusahaan-perusahaan besar yang termasuk dalam Fortune 500.
Tahukah Anda berapa jumlah CEO perempuan yang ada dalam daftar tersebut? Hanya 24 orang, kurang dari 5%. Meski demikian, sebuah survei dari Grant Thornton mencatat bahwa persentase bisnis yang memiliki setidaknya 1 perempuan dalam tim manajemen senior meningkat setiap tahunnya (75% di tahun 2018), angka yang terbilang lumayan. Memang pucuk pimpinan bisnis masih didominasi laki-laki, fakta yang tidak bisa dipungkiri.
Saya termasuk orang yang lebih percaya akan merit (kualitas yang baik), siapapun yang lebih qualified selayaknya mendapatkan tugas atau posisi yang sesuai, tak peduli dia laki-laki atau perempuan; dan bahwa perempuan tak diistimewakan HANYA karena dia perempuan. Yang menjadi catatan saya: dari pengalaman saya, bagaimana Bapak membesarkan saya, dan bagaimana saya melihat fenomena di sekitar saya; menyadari adanya bias gender membuat saya lebih mawas diri dan peka terhadap situasi.
Bila ada kondisi yang perlu diperbaiki, saya bisa berpikir dengan kesadaran itu dan memutuskan tindak lanjut yang sesuai. Dengan definisi Chimamanda bisa dibilang saya feminis, dan bahwa saya mendukung feminisme. Entahlah, terkadang bagi saya label itu menjebak dan mengkotak-kotakkan kita menjadi entitas yang berbeda-beda.
Jadi, menurut Anda, seperti apa sebenarnya feminis dan feminisme itu? Atau jangan-jangan kita tak perlu pusing dengan dua istilah ini?
Tabik,
Citra
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H