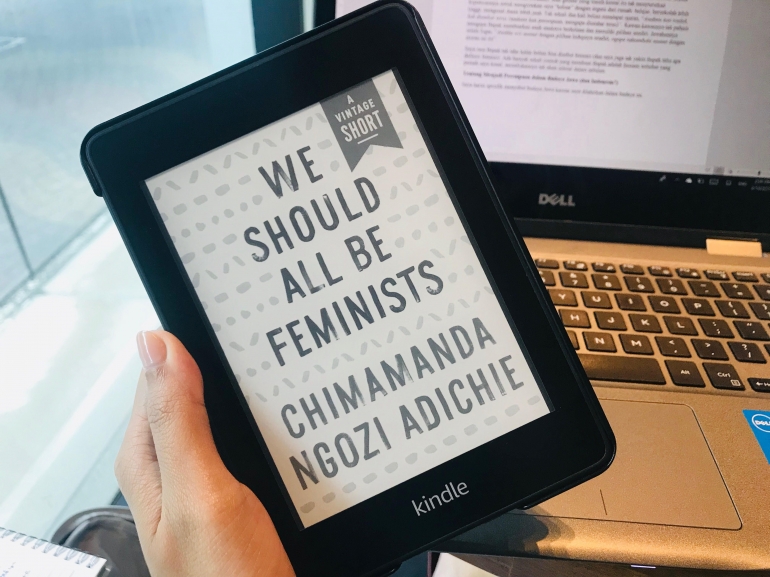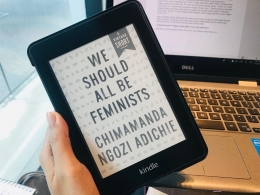(Kenyataannya memang dulu saat SD saya pernah ditawari Bapak untuk masuk sekolah wasit sepak bola. Bayangkan jika dulu saya menyanggupinya, mungkin saya akan menjadi satu dari sedikit perempuan, dan bila berhasil, cukup keren juga ya mungkin saya sekarang: wasit perempuan pertama di Indonesia? -- tambahkan hestek halah)
Tidak, Bapak tidak kecewa bahwa anak pertamanya (dan kemudian keduanya) perempuan. Justru dengan pandangannya tentang bagaimana anak diarahkan untuk berkembang, beliau tidak memberikan batasan gender pada anak-anaknya. Diajaknya saya bermain layang-layang dan pergi ke sawah, dibiarkannya saya bermain kotor-kotoran dengan kawan-kawan yang banyak laki-lakinya.
Di sekolah (karena Bapak dulu kebetulan guru di SD tempat saya belajar), Bapak mendobrak "norma" dengan mengizinkan saya (dan siapapun murid perempuan yang berani) untuk menjadi ketua kelas, pemimpin upacara, pembawa bendera, pemimpin regu pramuka. Ini hal yang biasa banget di masa sekarang, namun di awal tahun 1990-an dan di desa yang cukup jauh dari kemajuan, apa yang Bapak lakukan adalah sebuah hal yang berbeda (dan luar biasa).
Bapak tidak mengenal pandangan bahwa perempuan Jawa itu tugasnya 3M: masak, macak, manak (memasak, berdandan, dan beranak). Bias gender yang masih kental itu tak menyurutkan keputusannya untuk mengizinkan saya "keluar" dengan segera dari rumah: belajar, bersekolah lebih tinggi, mengenal dunia lebih jauh.
Tak sekali dua kali beliau mendapat ujaran, "Anakmu kan wedok, kok diumbar terus (anakmu kan perempuan, mengapa diumbar terus)". Kawan-kawannya tak paham mengapa Bapak membiarkan anak-anaknya berkelana dan memiliki pilihan sendiri. Jawabannya selalu lugas, "Anakku wis mumet dengan pilihan hidupnya sendiri, ngopo tak tambahi mumet dengan aturan ini itu".
Saya rasa Bapak tak tahu kalau beliau bisa disebut feminis (dan saya juga tak yakin Bapak tahu apa definisi feminis). Ada banyak sekali contoh yang membuat Bapak adalah feminis terhebat yang pernah saya kenal, menuliskannya tak akan selesai dalam sebulan.
Tentang Menjadi Perempuan dalam Budaya Kita
Saya harus spesifik menyebut budaya Jawa karena saya dilahirkan dalam budaya ini. Bahwa bias gender itu ada dalam budaya Jawa tidak kemudian berarti ia tidak ada bahwa dalam budaya lain. Mengenali bias gender ini juga tak mudah, budaya telah menjadi cara hidup yang diimani dan dipraktikkan turun temurun sehingga seolah tak ada yang salah dengan cara tersebut.
Sama seperti Kartini yang tak memiliki kesempatan yang sama seperti kakak-kakaknya yang laki-laki, pada masa itu memang pendidikan dan pengetahuan (serta jejaring dan perkawanan) disebut lebih penting untuk laki-laki dibanding perempuan.
Dalam pekerjaan saya sekarang pun saya banyak menemui bias gender, misalnya dalam forum komunitas, perempuan cenderung tidak bersuara bila mereka hadir bersama dengan laki-laki. Ini adalah batasan budaya, bahwa perempuan tidak boleh terlalu banyak berpendapat. Mereka baru bersuara bila forumnya hanya dihadiri oleh perempuan, atau bila diajak berbicara secara privat.
(Tentu saya juga harus menggarisbawahi bahwa bias gender dari sisi laki-laki itu banyak. Bahwa laki-laki harus berprofesi "maskulin", misalnya. Pembagian peran maskulin dan feminin ini membuka ruang diskusi yang sangat lebar).
Dulu saya pernah ingin menjadi astronot. Alasannya sederhana: saya sangat, SANGAT, terinspirasi oleh Ibu Pratiwi Sudarmono. Membaca profilnya di sebuah majalah (atau koran ya?) membuat saya kagum, apalagi melihat fotonya berseragam astronot. Meski saya sudah membaca buku-buku anak-anak yang bercerita tentang astronot, baru kali itu saya lihat astronot perempuan.