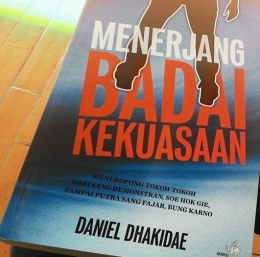Pagi ini, Selasa (6/4/2021), di tengah kesibukan mendapatkan kabar terbaru dari sanak kerabat di NTT, ruang sosial media dan berbagi pesan singkat diinterupsi oleh kabar duka berganda.
Saat perhatian masyarakat NTT diaspora tengah tercurah pada musibah bencana alam di kampung halamannya, kepergian dua tokoh NTT semakin mempertebal kesedihan.
Mula-mula datang dari Bali. Umbu Wulang Landu Paranggi, tutup usia di RS Bali Mandara, Sanur pukul 03.55 WITA. Salah satu penyair besar di negeri ini lahir di Kananggar, Waikabubak, Sumba Barat. Belum sempat merayakan ulang tahun ke-78 pada 10 Agustus nanti, ia pergi.
Kepergian Presiden Penyair Malioboro itu sontak mengundang keriuhan di jejaring sosial media. Tak butuh waktu lama, tagar #UmbuLanduParanggi, #PresidenMalioboro, hingga #MaiyahBerduka menjadi topik tren menyusul ribuan kicauan duka di jagad maya itu.
Walau namanya tak sempat mengemuka di daftar tren di twitter, kepergian Daniel Dhakidae tak lama berselang, mengundang simpati luas. Lahir di Toto-Wolowae, Nagekeo, 22 Agustus 1945, Daniel Dhakidae meninggal di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (MMC), Jakarta Selatan, pukul 07.24 WIB.
Seperti Umbu Paranggi yang mengejutkan banyak orang, demikian juga Daniel. Seperti Umbu yang membangkitkan ingatan dan kenangan publik, begitu pula Daniel.
Tidak terhitung berapa banyak orang yang berkabung atas kepergian dua orang itu. Tidak hanya sanak saudara yang bertalian darah, orang-orang dari beragam latar belakang pun ikut bersedih. Jelas, kedua orang itu, sudah memberi arti bagi banyak orang. Dengan cara masing-masing, mereka membuat tidak sedikit orang merasa kehilangan.
Rujukan jurnalistik dan politik
Umbu dan Daniel sama-sama lahir di NTT. Dari rahim berbeda mereka hadir, atas cara tertentu mereka dibesarkan.
Selanjutnya, berkelana ke tujuan berbeda. Kemudian panggilan mereka itu mengerucut pada apa yang kita kenal sekarang. Umbu sebagai penyair. Sementara Daniel berpredikat ahli politik dan media, dengan horizon wawasan yang luas, termasuk menguasai sejumlah bahasa asing, Latin tak terkecuali. Harum nama keduanya semerbak ke mana-mana, baik di dalam maupun di mancanegara.
Sepanjang jalan kenangan hidup mereka, ada banyak peninggalan. Sejumlah jejak langkah prestasi dan pencapaian mereka bisa dikemukakan, walau tak utuh.
Daniel yang meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara dari Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (1975), kemudian meraih Master of Arts bidang Ilmu Politik dari Cornell University (1987) dan PhD di bidang pemerintahan dari Department of Government, dari universitas yang sama (1991).
Disertasinya berjudul "The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism, Political Economy of Indonesian News Industry" menjadi salah satu sumbangan penting bagi bangsa ini.
Apresiasi penghargaan the Lauriston Sharp Prize dari Southeast Asian Program Cornell Univeresity menjadi bukti. Banyak jurnalis senior hari ini masih menjadikan karya akademik itu sebagai pegangan dan referensi. Tidak sedikit yang mendapuknya sebagai salah satu rujukan terbaik tentang sejarah jurnalisme di tanah air.
Menariknya, disertasi itu berisi kritik tajam pada Kompas. Namun, Kompas dengan segala kebesaran hatinya justru melihat Daniel sebagai aset penting untuk ikut membantu mengembangkan kerja jurnalistik sehingga kepadanya kemudian diberikan kepercayaan sebagai kepala Penelitian dan Pengembangan (Litbang).
Jabatan itu diemban sejak 1994 hingga pensiun, 2005. Setelah itu, ia masih tetap mengabdi di Palmerah sebagai Kepala Ombudsman.
Di samping itu, ia pernah menjadi redaktur majalah Prisma, salah satu majalah terkemuka dan bereputasi baik, Ketua Dewan Redaksi Prisma (1979-1984), hingga menjadi Wakil Direktur Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada 1982-1984.
Daniel menulis dan menyunting sejumlah buku. Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (2003) adalah salah satu master piece-pemikirannya yang "memeriksa kaum cendekiawan dalam pergulatannya dengan kekuasaan, modal, dan kebudayaan...."
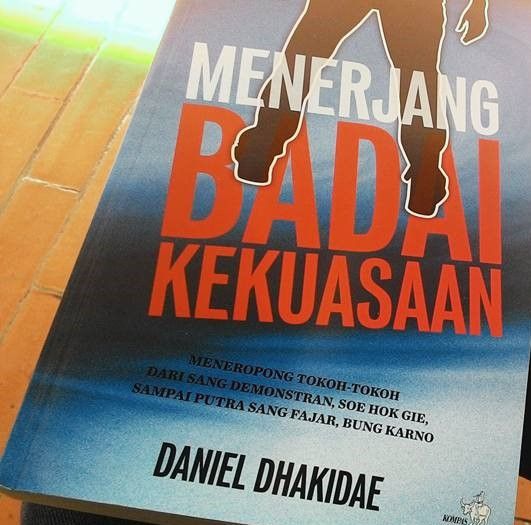
Buku Merjang Badai Kekuasaan cukup menyita perhatian sejak diterbitkan tahun 2015. Buku berisi 15 tokoh yang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan dengan cara masing-masing.
Dibagi dalam tiga bagian utama. Bagian pertama bertajuk "Kekuasaan Kaum Tak Berkuasa," (powerfulness of the powerless) menampilkan sosok-sosok seperti Soe Hok Gie, Poncke Princen, Toety Azis, Pramoedya Ananta Toer, dan Rusli. Mereka ini tidak memegang kekuasaan dalam arti politik-kenegaraan.
Bagian kedua, "Kekuasaan Kaum Terbuang" (power of the outcasts). Rohimah, Taufik, Kusni Kasdut, dan Henky Tupanwael yang dicap sebagai penjahat dan "sampah masyarakat" kala itu. Walau begitu, mereka ini dianggap memiliki semangat dan kekuatan untuk memberikan pengaruh pada masyarakat.
Sementara itu bagian terakhir, "Kaum Berkuasa dan Ke-tak-kuasa-an" (powerlessness of the powerful) berisi ulasan dan tinjauan kekuasaan di tangan Mohammad Hatta, Margono Djojohadikoesoemo, Sam Ratulangi, Frans Seda, Abdurrahman Wahid "Gus Dur", dan Soekarno.
Selain itu, Daniel bersama Vedi Renandi Hadiz menyunting buku berjudul "Social Science and Power in Indonesia" (2005). Ia memberi kata pengantar di buku Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang (2008).
Selain sejumlah buku yang masih menjadi rujukan di bidang ilmu politik, pemerintahan, jurnalisme, dan demokrasi, buah-buah pemikirannya yang tajam dan bernas juga tersebar di berbagai surat kabar dan majalah, serta tersampaikan melalui aneka forum diskusi dan ceramah, baik di dalam maupun di luar negeri.
Guru para guru
Lahir di Sumba, Umbu malah jatuh hati dengan kota lain. Ia memilih Yogyakarta sebagai tempat ia belajar. Jejak pendidikan formalnya tercatat di SMA BOPKRI Yogyakarta, Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Janabadra Yogyakarta.
Di tempat itu pula ia mendalami dunia sastra dan seni budaya. Pembentukkan komunitas penyair Malioboro pada 1070-an menjadi rumah yang kemudian melahirkan dan membesarkan banyak penyair. Iman Budhi Santoso, Linus Suryadi A.G., Korrie Layun Rampan, Ragil Suwarno Pragolapati, hingga Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), adalah beberapa nama sastrawan beken yang diperhitungkan.
Melalui puisi dan esai ia berkarya. Sekaligus menginspirasi. Meski tidak memilih menerbitkan buku, komunitas yang diasuh, serta potongan-potongan karya yang ditelurkan lantas tersebar di sejumlah media, sepertinya labih dari cukup.

Tak heran, ia kemudian dikenal sebagai tokoh misterius dalam dunia sastra tanah air. Walau begitu, secara kasat mata kita masih tetap bisa merasakan kehadirannya melalui rubrik puisi dan sastra mingguan Pelopor Yogya, hingga rubrik Apresiasi di Bali Post.
Rubrik terakhir itu diasuh sepanjang masa tua hingga kepergiannya. Bali adalah satu dari tiga kota yang telah memikat hatinya, selain Yogya dan Bandung.
Oleh banyak orang, ia dianggap penjasa. Para "guru" sastrawan menyebutnya guru. Tidak hanya karena dedikasinya yang total di bidang itu, tetapi juga perjuangannya membidani kelahiran sastrawan-sastrawan besar yang kemudian ikut memperkaya kazanah dan menjaga harum sastra Indonesia tetap tercium dari waktu ke waktu.
Umbu, atas dedikasinya, diganjari penghargaan dari Festival Bali Jani 2020. Setahun sebelum itu, bersama arsitek Yori Antar, Umbu mendapat Penghargaan Akademi Jakarta di bidang humaniora.

Terobos-Anomali
Tulisan ini tidak bermaksud membandingkan Umbu dan Daniel. Tidak juga mencoba mencari-cari kesamaan, atau perbedaan masing-masing. Keduanya sudah menjadi besar di jalan masing-masing.
Ada sejumlah hal yang tidak bisa tidak ditemukan pada dua orang ini secara sama, walau dalam kadar berbeda.
Pertama, Umbu dan Daniel adalah dua tokoh besar. Yang satu adalah intelektual akademik, sementara satunya lagi, tidak bisa tidak disebut intelektual, hanya tempat penziarahannya di komunitas sastra.
Keduanya, sama-sama menelurkan buah pikir yang dalam, kritis, reflektif, bahkan berani menantang kemapanan, dalam bentuk beragam. Yang satu dalam bentuk esai politik dan tulisan ilmiah. Satunya lagi berupa esai sastra dan puisi.
Namun, ada satu hal yang tak bisa ditampik. Mereka tidak hanya bersuara melalui pena dan kertas, tetapi juga terlibat aktif di medan praksis. Ada yang pernah menjadi aktivis. Ada juga sebagai penggerak di tingkat komunitas.
Membaca tulisan-tulisan Daniel, kita akan menemukan kedalaman dan ketajaman. Tinjauan dan analisis tentang kehidupan politik misalnya, begitu bernas dan lugas. Ia pun tidak segan-segan mengkritik setiap praktik yang dianggapnya keliru.
Iqbal Basyari dalam tulisannya "Daniel Dhakidae, Intelektual Publik Itu Telah Berpulang" di kompas.id (6/4/2021), mengutip pandangan Ian Wilson, Pengajar di Murdoch University, Australia, meyebut Daniel sebagai pelopor berpikir kritis pada zaman Orde Baru.
Sumbangsih pentingnya di bidang jurnalistik adalah mengawinkan jurnalisme dan penelitian sosial. Kedua hal yang sebelumnya cukup sulit dijembatani akhirnya bisa dipadukan secara pas.
Media membutuhkan peneliti sosial untuk mendapatkan data yang akurat dan kaya. Sementara itu, jurnalis tidak bisa melepaskan diri dari fakta. Mengkombinasikan sejumlah pendekatan itu dalam produk jurnalistik dalam sebuah surat kabar yang dibatasi deadline adalah perjuangan yang diretas Daniel, kemudian menjadikan Kompas sebagai media terkemuka, karena kualitas jurnalisme bermutu.
"Daniel bisa mengawinkan keduanya sehingga muncul jalan keluar berupa opini publik. Wartawan menghubungi narasumber, sedangkan peneliti dari sisi masyarakatnya. Dia menjadikan peneliti di Litbang Kompas mengenal metodologi penelitian sekaligus ilmu sosiologi," tandas General Manager Litbang Kompas, Harianto Santoso seperti dikutip Iqbal Basyari.
Kedua, selain membuat terobosan, kehidupan mereka serentak anomali. Daniel adalah tokoh berpengaruh karena pergerakan dan pemikirannya. Pandangan-pandangannya di bidang politik sangat diperhitungkan.
Daniel sama sekali tidak tergoda untuk berpolitik-praktis. Ia tidak haus jabatan politis, yang bisa saja diperoleh dengan pengaruh, pemikiran, dan pergaulannya yang luas.
Ia tidak mau seperti apa yang disorotnya semasa Orde Baru. Memang berat pergulatan menjadi seorang intelektual dan cendikiawan. Godaan kekuasaan dan modal kadang begitu memikat. Tidak sedikit akhirnya terkontaminasi, lantas mengkhianati komitmennya.
Ia tetap memilih jalan yang konsisten diperjuangkannya selama bertahun-tahun. Sejak mahasiswa dan kepada setiap mahasiswa ia selalu memberikan bantuan dan menginspirasi mereka untuk tetap mengambil jarak dengan kekuasaan.
Tulisan-tulisan yang dihasilkan jelas menunjukkan sikap dan keberpihakannya. Keberaniannya berpikir kritis dan alternatif di zaman yang sangat tidak ramah untuk berbeda pandangan dan berpikir divergen adalah kredit tersendiri.
Sementara itu Umbu, dalam bentuk berbeda mengambil sikap yang sama. Ia tidak ingin dikenal sebagai penyair, apalagi penyair besar. Ia tak ingin disejajarkan dengan Chairil Anwar, Rendra, Sutardji Calzoum Bachri atau Taufiq Ismail. Ia malah curiga dan ingin menjauh dari popularitas sebagai penyair.
"Umbu menghadap Allah dalam keadaan berpuasa dari dunia, sebagaimana hampir seluruh usianya ia jalani dengan lelaku puasa atas berbagai tipuan kemewahan keduniaan, dengan kadar dan bentuk yang saya belum pernah menyaksikannya pada siapapun lainnya," Cak Nun dalam tulisannya MI'RAJ SANG GURU TADABBUR.

Secara metaforis, Umbu tidak ingin dikenal sebagai "pohon" besar yang gagah perkasa. Ia juga tak ingin disebut-sebut karena jasanya menaungi banyak penyair. Ia justru memilih menjadi "pupuk" yang mengorbankan diri untuk memberikan kehidupan banyak penyair.
Bagi Umbu, seperti penuturan Cak Nun, puisi dan kehidupan adalah satu. Kehidupan adalah puisi. Puisi yang mengandung keindahan, untuk menyeimbangkan kebenaran dan kebaikan. Rasa yang mesti menemani akal budi agar hidup terhindar dari konflik, pertentangan, permusuhan, dan perang.
"Umbu adalah manusia hati, bukan manusia akal pikiran yang rewel dan ruwet atau bahkan meruwet-ruwetkan diri sebagaimana orang-orang sekolahan di abad ini," demikian Cak Nun.
Terlepas seperti apa mereka ingin disebut dan bagaimana menyebut mereka secara pas, yang pasti, kini, kita akan mengenang mereka dari setiap perjumpaan, pemikiran dan hasil karya.
Dedikasi dan ketekunan mereka merawat martabat panggilan hingga ajal menjemput adalah peninggalan berharga yang sepatutnya ditiru.
Daniel di halaman pertama magnum opus, Menerjang Badai Kekuasaan menulis demikian. Vita brevis Dignitas Longa. Hidup manusia pendek, namun martabat panjang usianya.
Ya, martabat yang sudah kalian perjuangkan sekuat-kuatnya dan sehormat-hormatnya itu niscaya abadi. Selamat jalan para maestro!

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI