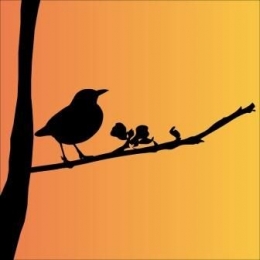Cuacanya memang menidurkan, dingin tapi bagaimana, sulit diterka dengan rasa yang lumrah. Ini seperti hal yang lebih sunyi dari tidur. Orang-orang yang datang semuanya membawa perasaan rumah mereka sehari-hari, datang membawakan momen rasa kesedihan, dari rasa-rasa yang lain yang ada dalam kehidupan kelompok.
Ada yang beriringan sembari berbicara pelan, seakan maklum akan kaidah kedukaan. Tapi aku merasakan seperti ada yang kurang atau tepatnya ada yang kurang pantas.
Batang pohon itu terlihat tidak besar, bahkan ku pikir pohon itu masih begitu muda, tampak dari kulitnya yang halus dan berwarna terang, demikian pula akarnya yang membekas masih beralur lembut menjulur. Tapi memang pohon itu kelihatan pohon mati.
Beberapa orang yang tiba di ruang itu berpegangan tangan mencitrakan suatu simpati, mereka bergiliran mendekati batang pohon itu dan menyentuhnya, dan beberapa yang lain menciumnya. Satu-dua orang di belakangnya bahkan menggaruk-garukkan cabang pohonnya, seperti mengusap-usap tangan yang sedang menganggur dan terkulai.
Aku pikir, orang-orang bertetangga itu seperti sok tau, terpancar dari ungkapan rasa superioritasnya kepada tetangga yang sederhana. Mereka meributkan pohon diam itu dan berbisik dengan ringan bahwa betapa mudanya pohon ini mati.
Bahkan beberapa dari emak-emak menangis, sehingga suasana semakin terasa menusuk. Apakah itu merupakan suatu cara yang lebih baik untuk mengatakan kematian dini? Aku melihat kepada pohon yang dingin itu dengan rasa halus, sehingga menangkap betapa tangisan itu terdengar keras dan kasar.
Kau tidak menciumnya? Bahkan tak hendak menyapanya?
Dua emak yang mengapitku berbisik sembari menyenggol lenganku. Aku hanya menggeleng, kulihat wajah mereka cemberut seakan aku melawan hukum dari lingkungan mereka yang sudah turun temurun.
Aku bodo amat, karena aku pernah tahu bahwa di dalam ruangan ini ada ruangan dalam yang dipakainya untuk sebuah hal yang lebih tenang dari sekedar tidur.
Apakah kalian melihatnya? Untung aku hanya mengatakannya dari dalam hati, sehingga aku tak perlu berkelahi mulut dengan mereka. Tapi aku tak tahan juga pada akhirnya, melihat mereka menularkan tangisan ke barisan yang lain sehingga ruang menjadi pikuk.
Kemudian aku mengambil tempat ke depan orang-orang itu, tepat di sebelah batang pohon yang tampak semakin kosong dan mati.
Saudara sekalian! Maaf saya harus mengatakan ini! Kataku sedikit volum. Dan mereka menatapku sambil meredakan tangis.
Saya pikir setiap kita yang hidup memiliki satu ruang dalam, begitu juga yang telah mati. Perkara kita sudah atau belum memakainya itu menjadi persoalan lain. Namun, please, hormatilah ruang dalam yang dimiliki masing-masing!
Aku mengucap seperti pidato. Dan hadirin yang kelihatan berduka itu menghentikan isak tangisnya. Entah mereka mengerti atau tidak, aku tak memikirkannya. Aku hanya menjaga suasana bahwa baru saja terjadi kekosongan pohon muda ini dan penghuni pohon ini tentu saja masih dalam keadaan ketidakpastian.
Aku yang sering bertemu dengan pohon ini mengerti betul bahwa menghadapi kekosongan dari ruang dalamnya adalah suatu pengalaman baru, meski akhirnya aliran alam akan membimbingnya.
Akhirnya mentari senja melewati kami, dan mereka yang bersimpati satu persatu mengundurkan diri dengan menelan kegelapannya sendiri-sendiri. Sedang aku masih menemani, berdiri disebelah batang kayu ini, aku hanya berdiri mematung ketika seekor burung hinggap pada ranting teratas pohon kosong itu.
Burung mungil itu berkicau dengan suara rendah, namun suaranya hampir tak terdengar, nyaris hilang tertelan angin senja. Aku memandang burung belia itu dan mengerti kehadirannya.
Lama ku menysun kata untuk menyatakan kepadanya bahwa dia harus pergi. Namun sang burung tak mau beranjak. Ku lihat mata bundarnya basah, sebagai mengatakan bahwa pohon ini adalah rumah yang dicintainya dan sekarang harus ditinggalkannya.
Kau harus pergi terbang! Kataku dengan suara halus takut menyinggungnya. Terlihat mahluk kecil bersayap itu merunduk ragu-ragu.
Terbanglah! Tak ada yang akan menangisimu lagi! Kataku meyakinkannya. Dia mengangkat kepalanya memandangku dengan mata seperti kaca. Sebentar kemudian dia bergerak memutar tubuh ringannya, namun kembali kepalanya berputar memandangku. Aku membalas tatap matanya sebagai tanda meyakinkannya. Sehingga pada akhirnya mahluk indah itu mulai mengepakkan kedua sayap dan mulai mengangkat tubuhnya perlahan dan meninggi dan semakin tinggi.
Aku memandangnya sampai dia menghilang, sambil berusaha menyembunyikan linangan air mataku. Aku takut seandainya dia mendengar tangisanku ini, mungkin saja akan membuatnya kembali ke tubuhnya, kayu aslinya ini, dan kupikir itu mungkin salah. Karena dia masih begitu muda.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H