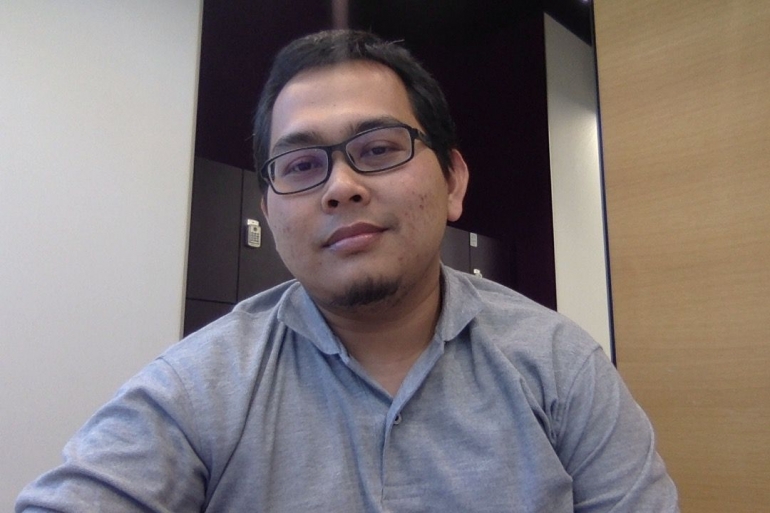Clayton, 18 September 2019
Ada dua hal yang saya tangkap ketika melihat bagaimana pembimbing saya mengajari para mahasiswa S1 bagaimana cara melakukan asuhan keperawatan jiwa. Dua hal itu adalah pake diagnosa medis dan wellness toolbox/recovery.
Tentu saja hal itu membuat saya kaget, karena sangat berbeda sekali dengan apa yang saya pelajari di Indonesia. Untuk yang nomer satu saya tanya, kenapa ga pake diagnosa keperawatan. Dengan simple nya dia menjawab, (maaf sebelumnya klo bahasanya agak kasar) "Nursing diagnosis is crap, it just not working for mental health".
Unbelievable, apakah dengan bicara seperti itu dia menjadi tidak cinta keperawatan, tentu tidak. Beliau sudah menjadi perawat bahkan sebelum saya lahir, WHATT?? Sudah menjadi PhD sebelum doktor perawat pertama ada di Indonesia, penulis buku ajar keperawatan level dunia dan CEO dari sebuah perusahaan yang khusus nanganin permasalahan bagi para migran dan orang dengan mental ilness serta punya jabatan tinggi di IPKJI nya Australia. Kurang apalagi.
Akan tetapi seolah terdoktrin, saya jadi termenung. Iya ya, emang ga jalan klo lapangan. Esensi recovery pasien ga keluar. Tapi beda ceritanya kalau hal tersebut diajukan untuk memudahkan (menyamakan) konsep belajar ilmu keperawatan jiwa. Tapi layaknya konsep KPK yang superpower, yang sedang digoyang oleh revisi UU nya, boleh dong konsep belajar keperawatan jiwa mahasiswa S1 di Indonesia dikaji ulang.
Terus apa yang dilakukan, ternyata jawabannya ada di nomer 2. Wellness toolbox and recovery. Wellness toolbox itu kayak formatnya, yang digunakan oleh pasien untuk merencanakan hidupnya selama proses dan setelah proses recovery. Tapi intinya sih di recovery.
Bicara tentang recovery, seorang Prof dari UK, Mike Slade (2009) membaginya jadi 2, clinical dan personal. Clinical lebih ke penurunan tanda dan gejala, personal ya perjalanan pasien, apa yang diinginkan pasien supaya bisa sembuh. Mahasiwa dan perawat nantinya belajar berkembang sesuai dengan platform clinical dan personal recovery tersebut.
Untuk clinical recovery, yang dilakukan mahasiswa dan perawat adalah belajar tentang penyakit, tanda dan gejala serta cure system yang ditujukan untuk penurunan tanda dan gejala sang pasien. Ya kalau saya membayangkan seperti yang dilakukan pada umumnya di keperawatan "Non Jiwa" ketika responsi. Mahasiswa dan perawat mengetahui penyakit, tanda dan gejala serta patofis obat.
Nah yang jadi inti ini justru di personal recovery. Hal tersebut yang menjadi pembeda antara keperawatan jiwa dengan yang lain. Kita bersama pasien diskusi tentang masalah yang sederhana, tapi dalam dan menyakitkan bagi orang yang mempunyai masalah. Kita bicara dengan pasien tentang apa yang buat dia sedih, pada saat apa suara keluar, ya mirip-mirip lah dengan apa yang kita lakukan selama ini di awal kita ketemu pasien.
Yang membedakan adalah pas sudah pengkajian. Ga usah ada diagnosa keperawatan baru, pake aja diagnose medis. Ga usah ada perencanaan, pake aja Toolbox, pas intervensi cukup curhat 15-30 menit dan banyakin denger. Ga usah keluarin pendapat kita kalau ga ditanya, belajar empati, dengerin apa kata pasien, ngurangin kerjaan, esensi dapet.
Soal standar kelilmuan kuasai Bab tentang Hubungan terapeutik dan Komunikasi terapeutik. Ga usah pake terapi yang berat model CBT atau logoterapi (Itu sudah bagian psikolog ma perawat spesialis jiwa). Sedap.
Awalnya, memang aneh bagi seorang Indonesian seperti saya, tapi believe me, metode seperti ini adalah standar umum di negara maju untuk keperawatan jiwa. Terus dokumentasinya gimana? Akan dibahas di curhatan selanjutnya.
Terus kerugiannya ada ga? Kalau dari pandangan saya ga ada. Cobalah buat penelitian, satu kelompok mahasiswa pake metode lama, yang satu pake metode seperti di atas. Mana yang lebih capek bagi mahasiswa/perawat? Mana yang lebih banyak nulis? Mana yang lebih puas pasiennya? Dan lebih lanjut lagi diagnosa keperwatan itu sebetulnya ga ngaruh juga buat klaim pembayaran.
Tanya aja ma orang BPJS. Kenapa kita ga seperti psikolog aja yang pake diagnosa medis untuk mentreatment pasien. Mungkin ada yang beranggapan beda dong, klo diagnosa keperawatan itu kan respon klien terhadap penyakitnya. Iya, tapi klo jadi sulit dan banyak nulis dan esensinya hilang, kenapa tidak dimodifikasi, toh cuman Indonesia yang punya konsep kayak gini.
Terus bagaimana memulainya?
Sebagai orang yang pernah mendapat masalah yang sangat berat, merasa bahwa semua orang di dunia ini memusuhi saya, dan menganggap diri sebagai seorang yang gagal dan bahkan pernah ngerasain "panic attack dan social phobia", saya menyadari bahwa dukungan yang tulus tanpa judgment itu yang paling dibutuhkan. Jangan bilang karena kita seorang perawat jiwa atau praktisi kesehatan jiwa harus bebas dari "traumatic life event". Apalagi klien dengan psikosis, yang mungkin mempunyai beban sekian kali lipat dari yang kita rasakan.
Untuk dunia pendidikan mungkin kita bisa menambah porsi diskusi mahasiswa tentang pengalaman pasien, apa yang terjadi dalam diri pasien, stigma yang pasien alami, harapannya untuk sembuh. Memperkenalkan hal yang "dalam" yang mungkin hanya ada di keperawatan jiwa (sama paliatif mungkin).
Hal itu dilaksanakan pada saat sedang responsi dengan pembimbing, bukan berfokus pada berapa kali diajarin menghardik, kenapa pasiennya ga bisa-bisa aja dsb. Tolong tinggalkan hal-hal yang too technical dan masuklah ke mode curhat, alam yang selama ini hanya dirasakan kalau hanya ada masalah di dalam keluarga dan teman dekat saja. Seperti kata pepatah "Klien dengan gangguan jiwa itu juga manusia" (Gitulah terjemahan bebasnya).
Untuk perawat, kalau lagi dokumentasi berhenti nulis banyak, capek. Kalau lagi ketemu pasien dan keluarga berhenti menggurui, itu juga capek. Mending kita dengerin dan kasih informasi saja.
Terima Kasih
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H