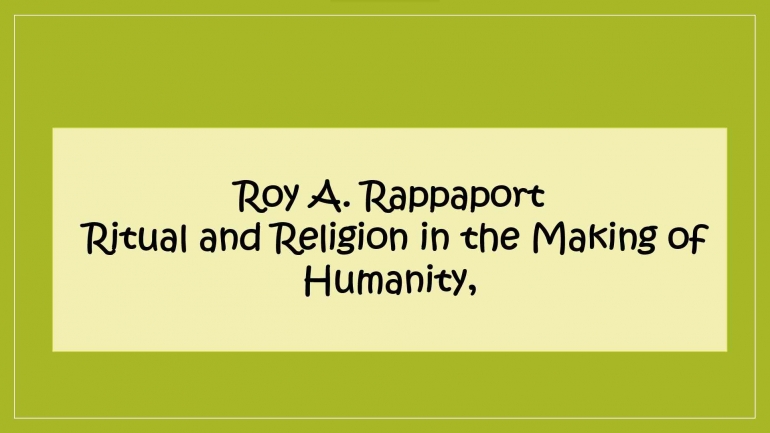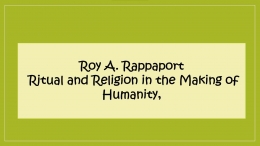Secara garis besar, agama-agama historis melampaui batas-batas kesukuan, tumbuh dalam konteks nasional, dan membuka cakrawala global, setidaknya dalam wilayah geografis sebuah peradaban besar. Dengan dorongan hati mereka sendiri, mereka berevolusi di mana-mana dari etnisisme ke suatu bentuk universalisme, dalam batas-batas politik setiap era dan konteks. Bahkan dalam kasus agama Ibrani, kita tahu mereka mengetahui keterbukaan terhadap semua bangsa, yang dinubuatkan dalam Yesaya, meskipun Yudaisme rabi, setelah diaspora, akhirnya dianggap sebagai agama nasional Yahudi. Di sisi lain, agama Kristen, dimulai dengan gerakan Yesus, membuka pesannya pada budaya Yunani-Romawi, dari tahun 30an dan 40an, sejalan dengan yang dilanjutkan dan dipertahankan oleh Paul dari Tarsus.
Sejarah kompleks masyarakat manusia, dan di dalamnya sejarah agama, memperlihatkan keberadaannya yang jauh dari keseimbangan: sistem mengatur dirinya sendiri, sistem mengatur ulang dirinya sendiri tanpa henti, menyusun ulang strukturnya dan menyesuaikan fungsinya. Secara umum, nampaknya setiap tradisi besar menghadirkan di dalamnya, sedikit banyak, semua kecenderungan, seolah-olah berupaya menggali seluruh potensi jiwa manusia. Hal ini memberikan arti penting yang berbeda-beda pada masing-masing faktor konstitutif, seperti mitos atau visi dunia, ritual atau simbolisasi yang dijalani, prinsip etika atau norma praktis, komunitas dan organisasi kelembagaan.
Dalam beberapa kasus, ia cenderung berkonsentrasi pada salah satunya. Demikian pula, ada penokohan di mana kita mengamati dekantasi khas terhadap salah satu kemungkinan pilihan atau orientasi, sedemikian rupa sehingga paradigma menjadi kombinasi pilihan yang kurang lebih ditandai dalam suatu orientasi, yang memberikannya profil sejarah tertentu. Tidaklah sulit untuk mengumpulkan sampel dari polaritas-polaritas ini, sebagai alternatif (tidak selalu sepenuhnya eksklusif) di sekitar suatu sumbu, meskipun perlu untuk menekankan gagasan tidak ada yang dapat menggantikan kebutuhan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap setiap kasus.
Unsur keagamaan melibatkan kodifikasi makna, penyampaian pesan dalam bentuk pikiran, pengalaman atau tindakan. Dan pesan ini melibatkan pengambilan posisi atau polaritas, eksplisit atau implisit, sehubungan dengan beragam aspek. Berikut adalah pencacahan beberapa pasangan oposisi yang disederhanakan dan skematis, untuk menunjukkan apa yang saya maksud: mengenai waktu, bersifat siklis/tidak dapat diubah; dari segi skala, kolektif/individu; mengenai kekuasaan, teokratis/demokratis; mengenai mediasi, mistik/profetik; mengenai keyakinan, narasi/dogmatis; mengenai pengetahuan, gnostik/sapiential; dari segi organisasi, karismatik/hierarki; mengenai ontologi, dualis/monist; mengenai ketuhanan, politeisme/monisme; mengenai konsepsi tentang tatanan kosmik/tuhan pribadi yang absolut; Adapun cita-cita hidup, monastik/sekuler; mengenai eskatologi, etika/apokaliptik; sedangkan untuk keselamatan, imanen/transenden; mengenai sikap terhadap norma, legalisme/kebebasan; mengenai hubungan sosial, egalitarianisme/klasisme atau elitisme; mengenai perbedaan seksual, androsentrisme/penyetaraan perempuan; sebagai sikap terhadap konflik, penghasut perang/damai.
Masing-masing tradisi besar, sepanjang sejarahnya, telah secara efektif mengeksplorasi berbagai alternatif mendasar dalam bidang agama, sebuah bidang yang sangat luas, meskipun tidak diragukan lagi terbatas. Di dalamnya kita dapat mendeteksi kutub tarik-menarik, sumbu perpindahan, percabangan, pergantian, pertentangan, interaksi intrasistemik dan ekosistem dalam kaitannya dengan konteks sosiokultural. Seperti yang dapat disimpulkan, kombinatorik bisa menjadi sangat luas dan kompleks, sebelum sintesis baru dan kemungkinan metamorfosis yang muncul habis.
Singkatnya, gagasan evolusi sistem keagamaan dipahami dalam arti ganda. Yang pertama mengacu pada perubahan dalam suatu tradisi, yang melaluinya terjadi transformasi sistem secara bertahap, melalui mutasi kecil yang bersifat endogen atau melalui asimilasi unsur-unsur eksogen tertentu. Dalam hal ini, evolusi direduksi menjadi menghasilkan varietas dalam spesies yang sama, yang dipertahankan. Pengertian yang kedua lebih radikal dan menyangkut evolusi sistem yang satu ke sistem yang lain sehingga memunculkan tradisi yang begitu terdiferensiasi sehingga menimbulkan munculnya mutasi-mutasi yang tidak dapat diasimilasikan dengan tradisi yang sudah ada sebelumnya, hingga melahirkan agama baru. Hal inilah yang terjadi pada lahirnya agama Buddha dari agama Hindu pada abad ke-6 SM, dan kelahiran agama Kristen dari agama Mosaisme atau agama Yahudi sebelum penghancuran Kuil Yerusalem oleh Romawi.
Ketika mengeksplorasi berbagai alternatif yang mungkin secara teoritis, berbagai elemen sistem keagamaan melakukan hal tersebut tergantung pada ceruk sosial yang tersedia dan sebagai respons terhadap perubahan tertentu dalam kondisi kehidupan kelompok sosial, kelas, atau kasta. Hal inilah yang terjadi dalam proses-proses besar, seperti ketika agama Buddha Mahayana beradaptasi hingga berkembang dan menjadi agama resmi Kerajaan Maurian India, pada abad ke-3 SM, di bawah naungan Kaisar Asoka. Analoginya, ketika Kekristenan mula-mula mereduksi radikalisme Yesus dan surat-surat Paulus yang otentik, untuk beradaptasi dengan masyarakat Romawi dan, kemudian, sepanjang abad ke-4, dimasukkan sebagai kredo resmi Kekaisaran Romawi. Dengan demikian, mekanisme yang mengintervensi adaptasi selalu ada, siap untuk diaktifkan setiap saat, dan mungkin mewakili kumpulan sumber daya yang entah bagaimana terpatri dalam skema atau struktur semangat manusia (Levi-Strauss 1964: 23). dan dibuat eksplisit dalam cetakan sejarah. Sifat konkrit dari skema mental ini, yang berhubungan dengan mekanisme budaya, akan diklarifikasi melalui kolaborasi antara psikologi evolusioner dan antropologi sosial.
Asumsi agama yang paling mendasar adalah adanya tatanan atau dimensi tak kasat mata yang mewujud dalam bentuk tertentu, sehingga memunculkan pencerahan akan ketuhanan, sakral, luhur, absolut, apapun istilahnya. Pencerahan semacam itu didasari melalui atribusi karakter ilahi, suci, unggul, dll., tanpa mengurangi karakternya, pada pengalaman, perkataan, pekerjaan, orang, tempat, objek tertentu. Hal ini terjadi terus-menerus, namun pada saat-saat istimewa, seperti saat-saat pendirian negara, proses tersebut dikodifikasikan dalam cerita-cerita dan praktik-praktik baru, sehingga memunculkan sebuah gerakan yang dipelihara oleh mereka dan mentransmisikan serta mengolahnya kembali.
Pada mulanya, tugas seorang penggagas, atau beberapa, atau mungkin penyusun, merupakan hal yang mendasar, meskipun namanya tidak selalu dilestarikan, seperti yang terjadi pada Akhenaten, Musa, Zoroaster, Laozi, Konfusius, Buddha Gautama, Socrates, Yesus, Nabi Besar Muhammad, dll. Masing-masing dari mereka merombak dengan caranya sendiri, dengan orisinalitas, warisan pemikiran yang mendahuluinya, dan menjadi - bahkan tanpa disengaja - pendiri sistem baru.
Sang pendiri pasti mengambil peran sebagai mediator yang istimewa dan penting bagi peristiwa epifani, apa pun varian manifestasinya: visi, inspirasi, wahyu, meditasi, pengalaman. Bagi saya, tampaknya ini merupakan persoalan sekunder apakah pencerahan tersebut dipahami atau tidak sebagai teofani, karena hal ini mempengaruhi tingkat bahasa dan penafsiran atas apa yang diwujudkan, bukan pada mekanisme yang mengkategorikannya.
Harus ditekankan mediator (jika itu adalah karakter, tetapi hal yang sama dapat dikatakan untuk setiap elemen mediasi) selalu merupakan realitas dunia ini yang, dalam kerangka keyakinan, diasumsikan berada dalam kontak atau komunikasi dengan dimensi yang tak terlihat, yang benar-benar nyata, yang sakral. Realitas tertinggi ini, pada gilirannya, sampai batas tertentu yang dapat dicapai, hanya muncul sebagai gagasan yang terkait dengan gagasan mediasi. Jadi keduanya terbentuk sebagai gagasan dunia ini.