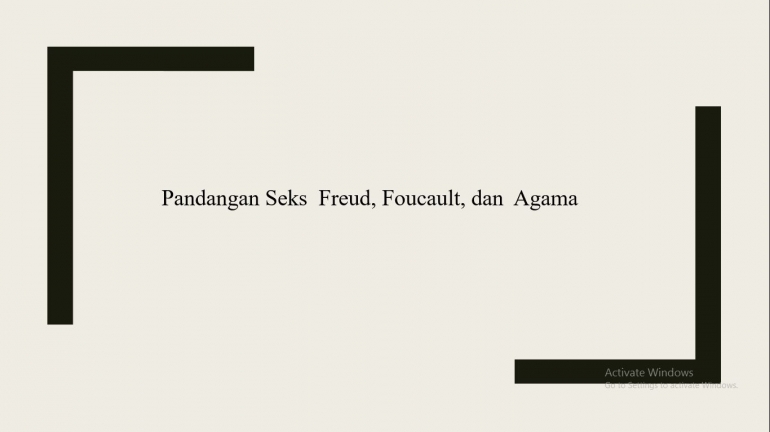Dualisme jenis kelamin secara khusus mengungkapkan ketergantungan satu sama lain. Di sini, bagaimanapun, tidak hanya persamaan mendasar dari kodrat antara pria dan wanita, tetapi keserupaan mereka dengan Tuhan yang dijelaskan dalam Genesis 1, 26 Tuhan menciptakan manusia sebagai gambar-Nya; dia menciptakan dia menurut gambar Allah. Dia menciptakan mereka sebagai laki-laki dan perempuan.
Meskipun teologi Kristen tidak pernah menyangkal pandangan fundamental ini, subordinasi perempuan dan patriarki yang jelas di gereja telah bertahan hingga hari ini. Ini terutama karena kejatuhan manusia (Genesis 3, 1-7), di mana Hawa memetik buah terlarang dari pohon pengetahuan melalui kelicikan ular untuk diberikan kepada Adam. Dosa asal ini menyebabkan pengusiran dari surga dari kedua jenis kelamin, dan masih disalahkan pada wanita sampai hari ini, karena mereka dianggap penggoda besar untuk kejahatan.
Thomas Aquinas menggarisbawahi hal ini jauh lebih dalam dengan pernyataannya inferioritas fisik dan mental wanita bukan hanya akibat buruk dari Kejatuhan tetapi sudah diberikan oleh alam. Menurut Aquinas, supremasi dan subordinasi dari jenis kelamin sangat jelas dalam hubungan seksual, karena pria itu, sebagai prinsip aktif dan formatif, lebih unggul wanita, sebagai pasif dan prinsip murni materi. Subordinasi perempuan terhadap laki-laki dan kekuasaan mereka untuk membuang di banyak bidang kehidupan terlihat dalam Perjanjian Lama.
Demikianlah perempuan itu disebut sekaligus sebagai pelayan, pembantu, lembu dan keledai. Tuan dan tuan digunakan dalam Alkitab sebagai ungkapan untuk suami dan menjadi tuan untuk menikah. Namun demikian, baik laki-laki maupun perempuan dianggap sebagai gambar Tuhan, karena pada saat yang sama, Tuhan menciptakan manusia dengan cara yang berbeda sebagai laki-laki dan perempuan. Manusia ada dalam dua bentuk. Tidak satu pun mewakili keseluruhan manusia. Masing-masing tidak memiliki apa yang dimiliki yang lain. Hanya bersama-sama mereka adalah keseluruhan. Di sini gagasan ilahi tentang seksualitas pria dan wanita ditunjukkan dalam diferensiasi dan kesetaraan mereka.
Michel Foucault menggambarkan pandangan Freud sebagai hipotesis represi dan dengan keras mengkritiknya dalam karyanya The Will to Know, yang diterbitkan di Prancis pada tahun 1976. Foucault tidak mengorientasikan analisisnya pada represi, tetapi menanyakan tentang mekanisme kekuasaan yang membentuk wacana seksualitas.
Foucault menjelaskan perubahan dari penindasan yang dianggap berabad-abad lalu menjadi pembebasan seksual yang seharusnya lebih merupakan perubahan dalam mekanisme kontrol: Kontrol atas seksualitas individu tidak lagi menjadi kontrol dari luar, tetapi telah mengalami subjektivitas. Maksud dan konsekuensi dari larangan berbicara secara resmi bukanlah penindasan terhadap seksualitas, tetapi wacana yang intensif terhadapnya.
Jadi represi yang digambarkan oleh Freud tidak terbukti secara historis. Sebaliknya, bahkan pemeriksaan kritis terhadap penindasan seksualitas adalah bagian dari wacana yang dimaksudkan oleh kekuasaan. Selain itu, Foucault tidak memahami kekuasaan sebagai semata-mata represif, tetapi menerangi efek produktifnya.
Inti dari hipotesis represi Sigmund Freud adalah asumsi perkembangan budaya dan masyarakat hanya mungkin melalui penindasan seksualitas. Dengan demikian, fungsi penindasan adalah fungsi peradaban. Dia mengkonkretkan asumsi ini pada tingkat individu (sublimasi, superego) dan pada tingkat sosial (budaya).
Dengan demikian, seksualitas ditekan dalam masyarakat budaya sejalan dengan asumsi berikut:Di satu sisi, ia melakukan naturalisasi seksualitas, yang terbentuk dalam id yang dikendalikan oleh naluri. Di sisi lain, ia menggambarkan antagonisme antara seksualitas dan budaya : kemunculan dan keberadaan masyarakat hanya dimungkinkan melalui penindasan naluri. Ini membutuhkan penekanan seksualitas pada tingkat individu dan masyarakat.
Pada perannya sebagai lawan seksualitas, Freud menggambarkan budaya sebagai subjek akting yang mengejar kepentingannya sendiri.
Pada awal Kegelisahan dalam Budaya Freud mendedikasikan dirinya untuk religiusitas seperti yang dijelaskan oleh penulis Romain Rolland: sebagai perasaan dari sesuatu 'samudera' (Freud 1930). Kekuatan yang dijelaskan di sini dibentuk semata-mata oleh individu yang berjuang untuk kebahagiaan, dengan demikian merupakan kekuatan narsistik. Namun, dia hanya mengabdikan dirinya pada bentuk kekuatan ini di awal pekerjaannya. Berikut ini ia beralih ke konsep kekuasaan yang represif.