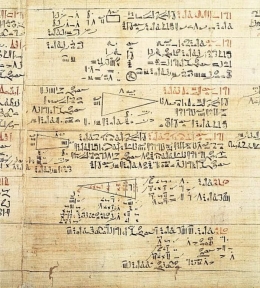Di saat usaha peningkatan kualitas literasi sedang digalakkan, kita kembali dikagetkan oleh sebuah tindakan yang sepatutnya tak lagi kita temui di saat sekarang ini: razia buku. Hanya karena buku itu menyajikan materi yang tidak sesuai dengan pemahaman -atau mungkin keinginan- kita, menyita dan menyembunyikan buku dari publik menjadi langkah taktis untuk menjaga serta melestarikan paham yang kita anut.
Sulit bagi saya pribadi membayangkan begitu lemahnya diri kita sehingga harus bersaing dengan buku. Begitu lemahnya diri kita sehingga hanya butuh sekadar kata-kata sebagai alasan untuk melampiaskan amarah. Apalagi perlakuan itu disiarkan secara sengaja entah untuk menarik simpati atau mencari pembenaran dari praduga publik yang terkadang berlebihan.
Ini patut saya sebut sebagai tragedi sehingga tidak bisa saya biarkan. Setidaknya, saya bisa mengajak kawan-kawan yang gemar merazia dan menyita buku untuk berdiskusi lewat tulisan ini. Sebab jika tidak, jangan sampai sejarah terulang kembali jika ini dianggap hal yang wajar.
Sejarah yang saya maksud adalah ketika Kaisar pertama yang menyatukan seluruh dataran China, Qin Shi Huang Di, memulai membakar buku yang dianggap tidak sesuai dengan pahamnya kemudian berakhir membakar penulis dan sarjana yang menulis buku-buku itu.
Contohnya seperti Ray Bradbury ilustrasikan dalam Fahrenheit 451, mengutip pujangga berkebangsaan Jerman Heinrich Heine bahwa mereka yang mulai membakar buku akan berakhir membakar sesamanya manusia.
Belakangan ini, buku-buku yang dianggap beraliran kiri (terutama yang membahas Marxisme dan Leninisme) menjadi target razia baik oleh aparat maupun organisasi masyarakat.
Saya tidak akan membahas argumen yang menyoalkan kebencian buta itu. Hal tersebut sudah dibahas secara komprehensif oleh banyak pihak. Di antaranya saudara Roy Murtadho di kolom IndoProgress dan saudara Roy Martin Simamora di kolom Geotimes. Keduanya saya rekomendasikan untuk dibaca sebagai pemandu sebab konteksnya lebih fokus dan argumen-argumennya lebih tajam.
Di sini, saya hanya ingin sedikit menyentil, atau paling tidak menyentuh, nurani kawan-kawan yang masih menjadikan razia dan penyitaan buku sebagai solusi positif. Saya masih berpegang teguh pada tesis bahwa setiap teks layak dibaca. Termasuk di antaranya buku. Jika pun apa yang disampaikan buku itu tidak berkenan, cukup dihiraukan saja. Boleh saja buku itu berguna setidaknya sebagai bahan kajian bagi yang lain.
Kalau dikhawatirkan buku itu menyampaikan paham yang bisa disalahgunakan maka yang patut ditanyai adalah pembacanya. Tidak serta merta buku yang dibaca akan dipraktekkan oleh pembacanya.
Sebagai contoh, jika kawan-kawan yang merazia buku kemarin itu membaca Al-Quran dengan utuh, sudah barang tentu mereka tidak akan melakukan hal demikian. Sebab perintah paling mendasar dalam Al-Quran adalah membaca dan terus belajar lewat aktivitas pembacaan. Tapi toh itu tetap terjadi.
Buku: Monumen Peradaban Manusia
Buku bukan sebatas rangkaian lembaran bertuliskan kata-kata. Buku adalah artefak dari peninggalan pengetahuan yang selama ini dihimpun dan dikembangkan umat manusia.
Tidak heran bila Geraldine Brooks, dalam novelnya People of the Book, menyamakan penyitaan buku sebagai kuburan massal hasil genosida umat manusia. Bahkan, hal itu disebut sebagai penistaan atas nama para leluhur. Lembaran buku dianggap sebagai monumen atau nisan bagi mereka yang menulis sehingga merobek dan membakar lembaran itu merupakan tindakan vandalisme atas monumen ingatan positif terhadap mereka.
Islam, seperti disebut Brooks dalam novelnya, justru pernah menjadi angin segar bagi peradaban barat ketika kaum Ortodoks Kristen mempersekusi kaum Yahudi di Eropa. Saat itu, Islam begitu menjanjikan dengan Sains dan Puisi di mana buku menjadi utusan ilahiah para pengkhotbah ketenteraman.
Bentang sejarah berdarah konflik umat manusia pun mencatat buku yang selalu selamat dari maha bencana itu. Sebab buku menandai sebuah komunitas yang toleran dan buku selalu menjadi penopang komunitas yang beradab dan mencintai peradaban.
Senada dengan itu, John Green mengandaikan lembaran buku pada The Fault In Our Stars-nya sebagai halaman hidup seseorang. Setiap kejadian diceritakan dengan penuh penghayatan; sesuatu yang sering diabaikan dalam perilaku sadar kita sehari-hari.
Buku memungkinkan kehidupan seseorang akan terus dibaca dan direnungkan meski kehidupan itu sendiri telah berakhir. Lembaran buku bukan hanya bentangan layar yang menggambarkan kehidupan namun juga menjadi cermin bagi setiap pembacanya.
Sang Pencuri Buku (The Book Thief) yang diilustrasikan oleh Markus Zusak pun dianggap begitu istimewa karena semangatnya begitu besar memeluk dunia yang pada kesehariannya tidak lebih dari mimpi menakutkan. Para penggenggam asa, di tengah konflik berdarah yang seperti sudah menjadi naluri bagi setiap orang, merupakan harapan baru untuk kehidupan yang nantinya akan kita wariskan.
Buku memiliki dunianya sendiri, dunia ideal yang dibayangkan oleh penulisnya. Baik maupun buruk semua dituntaskan lewat untaian kata. Sang Pencuri Buku dengan demikian merupakan pembawa obor yang mesti kita semua muluskan lintasannya.
Lucy Maud Montgomery pun lewat Anne of Green Gables-nya menyentil kita terhadap hal yang satu ini. Dalam novelnya itu, ia menuturkan bahwa Bunga Mawar, yang ditulis dengan rangkaian abjad berbeda di tiap bahasa, bau manisnya itu seakan dapat kita inderai begitu kita mendengar namanya. Namun mungkin juga hal itu karena tendensi kita menamai sesuatu yang kita sukai dengan nama indah dan cantik.
Andai saja nama Bunga Mawar itu kita ganti dengan nama lain Bangkai, misalnya, yang kita asosiasikan dengan sesuatu yang menyulut ingatan akan pengalaman buruk, tentu pengalaman pembacaan kita akan terasa berbeda.
Phobia Buku dan Ketakutan Kita Terhadap Nilai Kejujuran
Buku menyajikan suatu perspektif; cara kita memandang suatu peristiwa yang direkamnya. Dalam pertarungan ideologi, buku adalah amunisi mutlak.
Warisan cerita sejarah yang dituturkan oleh para tetua akan mudah dikalahkan oleh mereka yang menggenggam pena. Sebab tuturan mengharuskan sanad antar penutur dan pendengar. Hal itu dihiraukan oleh buku; tiap-tiap yang berkenan untuk mengulik lembarannya harus bersedia dilantik menjadi pewaris khazanah yang ditemukannya.
Temuan ini bersifat dinamis, sebab dalam perjumpaan masing-masing pembaca pada teks yang sama akan berujung pada dialog kognitif yang berbeda pula. Tentunya, hasil dari dialog itu pun beragam sesuai dengan niat, maksud, maupun tujuan dari pembacaannya.
Lewat pendekatan ini pula, buku menghadirkan pengadilan yang diputuskan oleh generasi pembaca berikutnya bagi mereka yang dahulu mengelak dari tuntutan akibat dosa dan perlakuan keji mereka terhadap sesama manusia maupun lingkungan.
Atas alasan itu, tidak heran jika kita menyaksikan banyak orang menginap phobia pada buku. Sebab ia telah didahului oleh kecemasan berlebihan sebelum memulai dialognya bersama buku. Mengapa hal itu bisa terjadi? Seperti yang diutarakan sebelumnya, buku menyajikan perspektif. Perspektif adalah cerminan dari apa yang kita sedang pikirkan.
Jangan-jangan, ketika membuka lembaran buku yang dicurigainya, seseorang dengan phobia tadi akan menemukan seluruh kebejatan yang selama ini ia coba hiraukan. Kita semua penuh dengan kehinaan dan buku selalu berupaya mengingatkan bahwa kehinaan itu adalah buah tangan kita sendiri. Bagi sebagian besar orang, hal ini terlampau berat untuk diterima.
Kejujuran merupakan sebuah nilai yang diagungkan hanya lewat khotbah belaka. Sebuah narasi luhur yang selalu ditampik dengan berbagai macam pengalih perhatian.
Buku yang menyajikan pemikirannya apa adanya, kadang ditanggapi terlalu serius terutama pada sisi di mana suatu perangai diceritakan dengan "terbuka" kepada pembacanya. Buku yang terlampau "terbuka" dengan kejujurannya ini menjadi momok bagi mereka yang masih belum siap menerima sisi lain dari dirinya. Ini membuat buku dibaca dan dipahami sebatas isi yang mendukung keinginan atau hasrat sang pembaca.
Di sisi lain, terkadang pula sebuah buku hanya dikenali lewat pembicaraan orang-orang; dikutip menurut kepentingan konteksnya namun tidak diberi kesempatan untuk membela dirinya sendiri. Nah, bagaimana pula buku yang pasif lewat diamnya itu bisa membela dirinya sendiri? Lewat bantuan kita, tentunya, dengan cara membacanya secara tuntas.
Kalau perlu mengangkatnya dalam diskusi bersama para pembaca lainnya sehingga kepingan mosaik penilaian kita terhadapnya menjadi lengkap dalam suatu gambaran utuh. Sebab buku yang tidak dibaca dengan tuntas hanya akan menuntun pada teks yang jalinan untaiannya terputus. Teks yang demikian tidak akan memberikan pemahaman selain praduga yang tidak tentu rujukannya.
Tiap lembaran buku yang kita baca pernah pula dibaca oleh orang lain sebelum atau bersamaan dengan kita. Kita tentu pernah pula merasakan bagaimana buku memainkan perasaan sehingga muncul anggapan bahwa buku tersebut ditulis secara khusus untuk kita. Ketertarikan aneh yang muncul ketika kita membaca sebuah buku dimulai dari beberapa serpihan pengalaman yang entah sengaja atau tidak seakan dikutip dari cerita kita menjalani kehidupan ini.
Semua hal itu menyiratkan satu hal; kita semua berbagi rasa yang sama, juga pengalaman yang sama. Yang membedakan hanyalah bagaimana kita menyikapi rasa dan pengalaman itu. Sehingga aku, kamu, dan mereka yang pernah membaca punya rasa dan cita yang dipertemukan lewat tulisan. Kita ternyata tidak begitu berbeda; lewat jalan inilah buku memahamkan kita akan pentingnya sikap toleran dan hidup harmoni.
Buku Sebagai Tonggak Peradaban Manusia
Sebelum era di mana imajinasi dituntun dan disajikan sedemikian rupa untuk kita seperti sekarang ini, buku adalah portal yang menuntun kita mengonstruksi dunia imajinasi sesuai keinginan kita. Selain sebagai sarana yang menyatukan pandangan seseorang; menghubungkan seseorang dengan orang lain dengan rasa serta cita yang sama, buku juga menyajikan pelarian.
Dahulu, sebelum media sosial mengganti peran buku, kejenuhan menanggapi kehidupan sehari-hari yang semakin tidak berpihak pada keinginan kita, buku hadir menemani dan menyuguhkan kebutuhan imajinatif kita. Buku membantu kita membangun ekspektasi ideal yang selama ini kita cita-citakan. Selain itu, buku membantu membangun laboratorium pikiran untuk menguji kualitas nalar kita.
Di era keemasan peradaban kuno sedang di puncak, perpustakaan berfungsi bukan hanya sebagai rumah buku namun juga sebagai rumah kebijaksanaan. Sadar akan usia manusia yang terbatas, perpustakaan dianggap sebagai virtual persona dari mereka yang sempat mendokumentasikan pengetahuannya. Musnahnya Perpustakaan Alexandria Kuno bahkan dianggap sebagai tragedi yang mengembalikan peradabaan manusia jauh ke belakang.
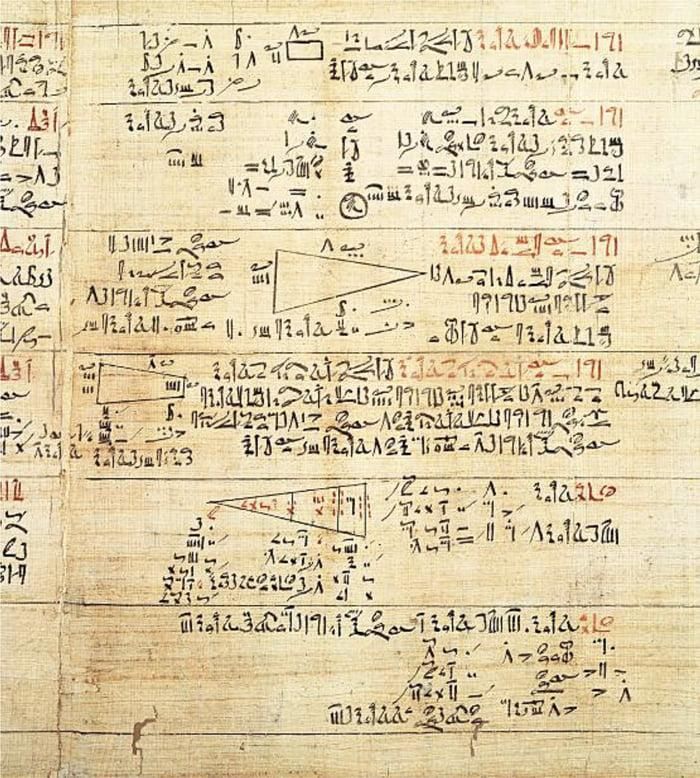
Mengapa tragedi itu disebut sebagai kemunduran peradaban? Sebab buku adalah markah yang menandai suatu pencapaian pengetahuan manusia. Dokumentasi pengetahuan yang dirangkum buku menjadi titik mula atau setidaknya sebagai inspirasi bagi yang ingin mengembangkan atau bahkan menganulir informasi yang terdapat di dalamnya.
Tanpa buku, seseorang ibaratnya kembali memulai membuka jalan sebab tidak lagi ada markah jalan yang menunjukkan arah yang harus dilaluinya. Sebagai misal, pengetahuan akan arsitektur kuno seperti Piramida, masih membingungkan para ahli di masa sekarang akibat hilangnya catatan utuh tentangnya ditelan sejarah.
Buku juga menandai suatu peristiwa penting dari proses pendewasaan kehidupan sosial manusia. Cerita-cerita tentang masyarakat masa lalu; bagaimana mereka membangun bangsa, mengatur interaksi sesama baik ke dalam maupun ke luar komunitasnya, hingga polemik dan konflik yang lahir dari interaksi itu. Semua itu banyak didokumentasikan ke dalam buku dan menunggu penilaian kita terhadapnya.
Banyak hal yang bisa kita pelajari darinya. Peradaban suatu bangsa muncul dan berakhir kita saksikan dalam pentas sejarah. Setidaknya kita tidak mengulang kesalahan yang berujung musnahnya seluruh sendi yang menopang perdaban mereka sehingga tidak tersisa dari peradaban tersebut selain artefak hasil galian arkeolog modern.
Buku juga menandai titik mula pemahaman kita akan kesetaraan hak. Mesin cetak buku yang diciptakan Johannes Gutenberg tidak hanya mendorong akselerasi pengetahuan dan ilmu namun juga menipiskan batas antara keistimewaan yang dahulu dimonopoli oleh kaum bangsawan. Pengetahuan dan ilmu tidak lagi menjadi spesialisasi para sarjana dan keluarga kerajaan.
Buku yang semakin mudah dicetak dan didistribusikan kemudian menjadi konsumsi masyarakat luas. Hak atas ilmu bukan lagi merujuk keistimewaan namun kemampuan untuk mengenali aksara. Buku yang lahir dari mesin cetak ini membawa masyarakat biasa menyuarakan aspirasinya di ruang publik dan ikut dalam urusan menentukan masa depan bangsa dan negaranya. Bisa dibilang, buku melahirkan demokrasi.
Mengapa Razia Buku Bukan Solusi
Buku, seperti yang diuraikan sebelumnya, merupakan monumen yang dibangun untuk mengenang penulisnya. Tindakan merazia atau menyita buku merupakan penistaan terhadap kenangan itu. Lebih luas, buku merupakan peninggalan yang menjadi markah pencapaian manusia atas peradaban yang terus disesuaikan. Tanpanya, kita bisa hilang arah.
Tindakan itu juga bisa menyulut kebencian. Ketidaksukaan atau ketidakpercayaan terhadap suatu hasil pikiran yang dituangkan ke dalam buku tentunya ditujukan kepada penulisnya. Hal ini yang bisa hilang kontrol. Ketika seseorang tidak lagi mampu membendung kebenciannya lewat representasi, dalam hal ini buku, maka ia akan melampiaskan langsung ke mereka yang menulis atau bersimpati pada buku tersebut.
Menyita buku juga bertentangan dengan prinsip demokrasi yang begitu dihargai bangsa ini. Buku melambangkan kebebasan mengutarakan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Menyita buku berarti merampas keistimewaan tersebut sekaligus merupakan pembangkangan terhadap ideologi bangsa.
Kalau toh alasannya karena buku itu memuat ideologi yang dilarang oleh konstitusi, perlu dipahami bahwa hal tersebut dalam rangka pergerakan yang ditujukan untuk menyerang ideologi dasar negara kesepakatan kita semua. Bukan cuma Marxisme atau Leninisme, ajaran apa pun yang melandasi suatu gerakan atau organisasi yang berseberangan dengan Pancasila dan UUD 1945, harus ditolak.
Kajian terhadap ideologi tersebut bukanlah bagian dari penerapan ideologi yang dimaksud. Sebab, secara tidak langsung, hal itu pun menyiratkan penghinaan terhadap institusi Perguruan Tinggi di negara ini yang terus berusaha menelurkan generasi yang tidak lagi berpikir picik terhadap hal semacam itu.
Sebagai bangsa dengan latar belakang peradaban tinggi, razia dan penyitaan buku bukanlah sesuatu yang wajar. Berilah kesempatan buku itu untuk membela dirinya sendiri dengan cara kita membacanya secara utuh. Jangan-jangan selama ini, kita hanya disetir oleh prasangka buta sehingga kebencian yang lahir karenanya sesungguhnya tidak berasalan.
Akhir kata, buku sebagai monumen peradaban manusia menjadi markah penunjuk arah ke mana peradaban ini akan dibawa. Razia dan penyitaan buku, dengan demikian, merupakan tindakan vandalisme atas monumen tersebut sekaligus menistakan peran mereka yang berusaha memberikan secuil kontribusinya untuk kebaikan kita bersama. Buku adalah warisan kekayaan peradaban yang patut kita lestarikan dan wariskan.
Mari membaca, mari jaga kewarasan kita!