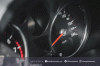Memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) di negeri ini ternyata bukan berbanding lurus dengan ketaatan berlalu-lintas. Rasanya pernyataan saya ini sudah menjadi rahasia umum.
Meski miris terdengar, tapi itulah faktanya. Suka atau tidak suka, ya c'est la vie di Tanah Air, khususnya di kota-kota besar. Skeptis? Mungkin iya. Pesimis? Hmm ... saya masih berusaha untuk optimis sih, makanya saya buat tulisan ini.
Saya masih menjaga untuk tetap bersikap optimis terhadap berbagai hal. Termasuk urusan etika berlalu lintas ketika mengarungi aspal dengan motor matic saya.
Setidaknya saya sendiri berusaha untuk tetap tertib di jalan. Meski, misalnya, saya sering diklaksoni oleh pengendara lain saat berhenti di belakang garis stop di lampu merah.
Atau berjalan lambat di sisi kiri saat macet. Atau saat saya selalu sendirian yang rajin memberi peringatan kepada pengendara motor yang lampu sen-kanannya masih kedap-kedip padahal ia berada di sisi kiri. Padahal saya tidak memiliki SIM C atau A!
Yes ... Anda tidak salah baca, saya tidak memiliki SIM C maupun A sudah bertahun-tahun. Saya sudah terlanjur skeptis dalam hal memiliki dua jenis SIM tersebut.
Saya sudah terlanjur berprinsip; selama tertb berlalu-lintas insha Allah aman. Kedua kartu SIM itu hanya berfungsi saat bertemu razia saja, ternyata.
Dan saya dengan pasrah menyerahkan STNK saya untuk ditilang tanpa berusaha 'berdamai'. Dan dengan sabar dan pasrah juga saya membayar denda di loket Kejaksaan (bukan pengadilan tatib LL).
Kenapa saya bersikap seperti itu? Karena saya pernah berusaha mengikuti prosedur memiliki kedua SIM tersebut dahulu kala.
Saya sudah belajar ujian teorinya. Dan berhasil lulus. Tapi ketika ujian praktek saya gagal. Saat itu saya melihat banyak peserta ujian yang gagal juga, tapi ternyata mereka 'diurus' oleh oknum dan mereka dengan mudah mendapatkan SIM.
Saat itulah saya mengatakan "percuma punya SIM". Ini sudah rahasia umum juga. Ya kan?
Tambahan lagi ketika melihat kelakuan pengendara kendaraan bermotor (baik motor maupun mobil) di jalan, saya makin berteriak dalam hati "percuma punya SIM".

Padahal, kalau melihat soal-soal ujian teori SIM saya berpikir seharusnya orang-orang yang lulus dan berhasil mendapatkan SIM itu adalah mereka yang taat dan tertib berlalu-lintas. Kenyataannya? Amburadul di jalan.
Jadi, sah saja kalau saya berpikir bahwa ada yang salah dengan proses ujian teori dan praktek SIM ini. Kesalahan yang struktural, massif dan sudah --maaf-- memborok.
Tambahan lagi, koordinasi antara polisi lalin dan DLLAJR dalam hal membuat peta lalu-lintas serta rambu-rambu plus tata kota yang juga abrakadabra, saya pikir kemacetan akan tak mudah teratasi dalam waktu dekat atau bahkan dalam jangka menengah. Saya tak ingin mengatakan dalam jangka panjang karena saya ingin tetap ada rasa optimis.
Meski salah-satu faktor kemacetan juga terletak pada pola bisnis industri otomatif yang kata beberapa pakar seharusnya untuk Jakarta dibelakukan morotarium (pengehentian sementara penjualan otomotif) atau pola cross-selling (beli mobil atau motor baru dengan terlebih dahulu beli yang tua untuk dibesituakan dan plat nomornya dipakai untuk yang baru) sehingga jumlah kendaraan tidak bertambah.
Rumit ya? Iya rumit kalau tidak diniatkan sih. Tapi kalau diniatkan mudah saja. Salah-satunya, menurut saya, perketat proses pemilikan SIM. Tidak boleh ada lagi kerjasama dengan 'oknum'.
Adakan ujian ulang untuk tiga atau lima tahun sekali. Karena waktu bisa mengubah perilaku orang kan. Ujian ulang ini diberlakukan juga bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat lalin. Dengan begitu saya optimis kondisi cerdas berlalu lintas akan tercapai.
Ini juga harusnya jadi pe-er untuk internal polisi dan dinas perhubungan (dalam hal ini DLLAJR). Dahulukan sikap preventif ketimbang reaktif.
Maksudnya, sering kita lihat polisi menunggu pengendara melanggar rambu lalin ketimbang membimbing agar tidak melanggar. Inilah yang sering dijuluki orang-orang polisi 'menjebak'.
Begitu juga dengan rambu-rambu lalin. Tidak jarang rambu-rambu diletakkan tidak pada posisi yang ideal sehingga pengendara merasa 'terjebak'.
Lampu pengatur lalin (lampu merah) pun seharusnya tidak perlu dobel-dobel yang membuat pengendara bisa berhenti jauh di depan garis berhenti karena mereka bisa melihat lampu merah kedua yang terletak beberapa meter di depan lampu merah utamanya yang tepat di garis stop.
Soal lampu merah ini saya pernah ngobrol dengan seorang kawan di kota Soe, NTT. Saya cerita soal lampu merah itu ketika saya takjub dengan ketaatan warga kota itu berhenti di belakang garis stop.
Dia bilang orang harus berhenti di belakang garis stop supaya bisa melihat lampu merahnya. Lalu dia merasa heran kenapa orang di Jakarta berhenti di depan garis stop. Saya ceritakan soal dobel lampu merah dobel. Dia pun tertawa sambil berkata, “Untuk apa dobel lampu merah?”
Program-program di televisi swasta yang selama ini sudah ada sebaiknya dioptimalkan untuk sosialisasi etika berlalin ketimbang hanya soal menghukum pelanggar lalin atau penangkapan para pelaku kriminal.
Kalau ada tindakan hukuman seharusnya ada tindakan penghargaan (reward). Sejauh ini saya belum melihat ada program reward terkonsep dengan baik dengan kata lain bukan yang sifatnya dadakan/sementara seperti selama ini.
Jadi panjang ya pe-ernya? Yes ... itulah sebabnya kemacetan masih panjaaaang sekali ... sama dengan pe-ernya.
Sekali lagi, apakah ini rumit? Tergantung seberapa kuat kita mau berbenah? Kalau enggan, ya sebaiknya tidak perlu repot-repot berkeluh-kesah, enjoy aja. Gitu aja kok repot ... hehe.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H