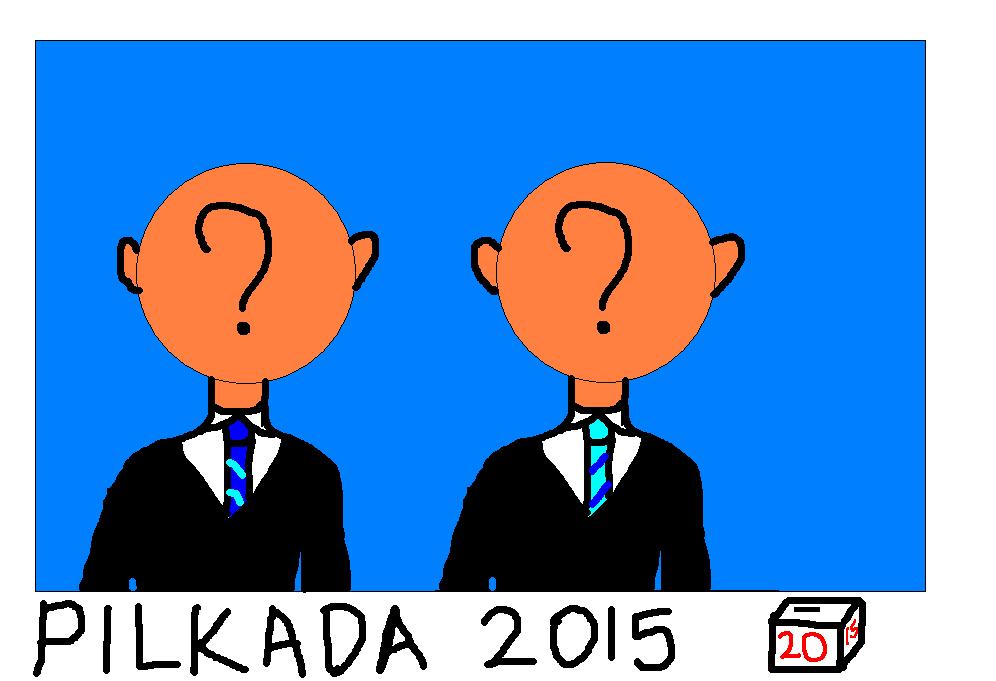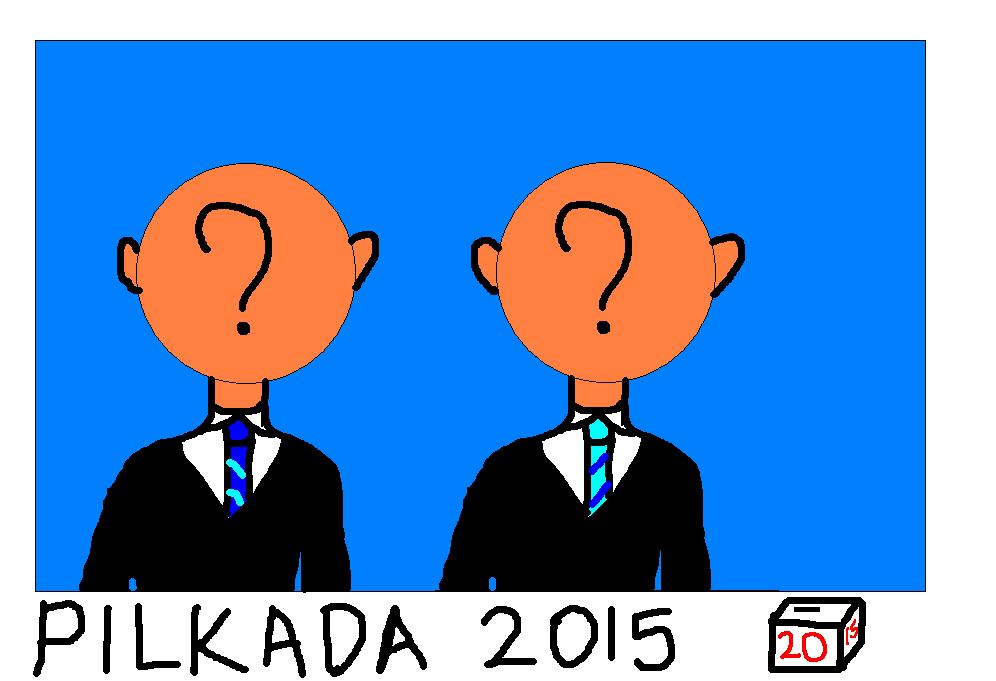Pertanyaannya kemudian, berapa banyak calon pemilih yang bisa meluangkan waktunya untuk menghadiri atau mengikuti perkembangan berita kampanye atau debat calon? Atau seberapa besarkah mereka calon pemilih mempunyai interest dan kepedulian untuk mengenali calon-calon pemimpinnya?
Disamping itu, calon-calon pemimpin bermental rendah yang berusaha memenangkan pilkada dengan segala cara juga sangat berperan besar mereduksi kualitas demokrasi itu sendiri. Politik uang adalah cara paling ampuh yang biasanya ditempuh. Kontestan pilkada butuh suara sedangkan calon pemilih juga tidak peduli atau tidak berkeberatan bila hak suaranya ditukar dengan sekian puluh ribu rupiah. Maka terjadilah praktik jual beli suara yang kotor itu.
Praktik kotor seperti itu jelas akan berdampak pada kinerja pemerintahan daerah yang terbentuk nantinya. Tingginya 'biaya politik' untuk mendukung pencalonan mereka -- termasuk biaya untuk membeli suara -- akan berusaha mereka tebus dalam masa pemerintahan yang mereka jalankan. Inilah lingkaran setan yang selalu mengungkung dan menghambat kemajuan bangsa kita.
Bila keadaan sudah seperti ini, bagaimana sebaiknya sikap kita? Sebagian masyarakat bahkan menjadi apatis karenanya. Memilih atau tidak memilih menurut mereka sama saja, yang tidak akan bisa mengubah keadaan. Bagi saya pribadi, keadaan seperti ini memang terasa dilematis. Namun saya menyadari, inilah konsekuensi sistem demokrasi yang kita anut. Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk memilih siapa. Bahkan sistem demokrasi tidak melarang seseorang untuk tidak memilih.
Pada akhirnya semua berpulang pada kita sebagai pemilih. Seberapa penting kita memandang kehadiran seorang pemimpin. Dan menurut kita, parameter-parameter minimal apa yang harus dimiliki seorang pemimpin. Semua ini tergantung pada nurani dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H