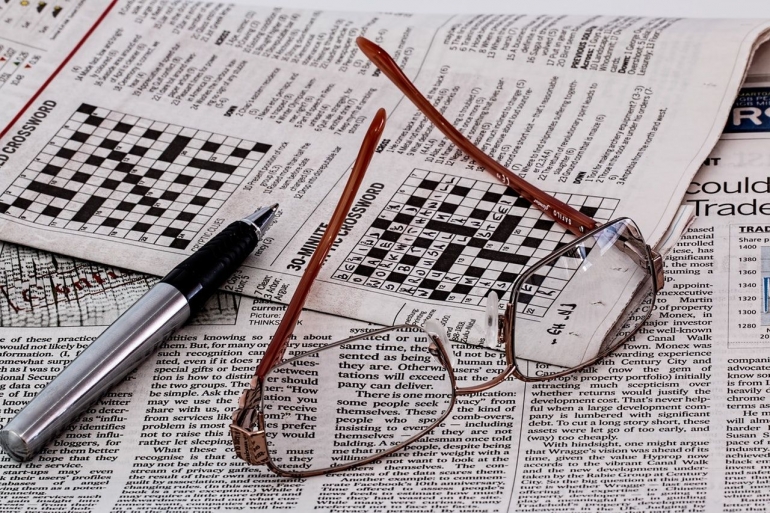Aku sendiri dan terkadang ilusi masa lalu mendarat begitu saja. Datang menyelusup pelan-pelan, parkir di cabang syaraf otak, menilang kesenanganku. Banyak sekali kejadian memilukan yang aku alami. Atau ini efek menahun dari kegilaanku? Suara simpang-siur mendekam.
Bau anyir berjatuhan di lantai kamar. Menggentayangi siapa saja yang tidur di ranjang itu. alarm pun menambah kesan mencekam. Kadang bunyi sendiri tanpa diatur. Aku kembali bangkit dan meraih kaki kursi di samping badanku. Aku menghuyung badanku agar terangkat dan duduk nyaman tanpa ingatan stress itu.
(2)
Aku bukan pecandu alkoholik. Semuanya tercipta gara-gara masa kecilku sedikit sepia dan suram. Aku tahu, semasa kecil aku diasuh nenek. Bapak-emak sedang tidak bisa mengasuh, kontrakan karir dengan gaji menggunduk besar membuat keduanya terpikat. Mereka ke kota pada akhirnya. Bapak menyuruh nenek agar aku kecil tinggal di kampung. Jangan di kota. Takut aku penasaran belum melihat gunung, sungai, sawah hijau segar bila kelak menetap di kota yang segar akan asap metropolitan. Kemelut.
Dialah nenek, beliau sosok wanita tegar meski usia direnggut ulat waktu. Saban hari usai bertani, beliau terbiasa duduk di bale bambu samping sawak milik almarhum kakek. Aku persis duduk di sisinya mendengar tiap ringkik jangkrik dan nafas terengah nenek saat berbicara.
Beliau kadang suka bercerita masa--masa penjajahan dulu. Seram. Adegan bunuh-bunuhan bukanlah adegan sensor lagi. Nyata di bola mata nenek. Sempat aku lihat, bayangan darah mengerang keras terlintas dalam kornea nenek. Bahkan lebih dramatis dan mengerikan. Nenek nangis saat itu. aku tidak bicara lebih dalam mengapa nenek menangis. Aku rasa gara-gara kue gula miliknya aku comot di piring saat di bale, ujung sore.
Nenek hanya mengintip sawah saja. Yang mengurus adalah tetangga sebelah yang kelihatan muda nan segar. Biasanya 3-4 pria pengangguran tidak jelas berjalan-jalan kecil menuju sawah nenek sambil memanggul cangkul. Itu suruhan nenek. Beliau upahi para pria pengangguran itu setara dengan lima kali makan nasi porsi keluarga (tiga kilogram), sekilo jagung, dua kilo umbi-umbian. Mereka nampak senang. Nenek pun melengkungkan kurva bibir yang tak semerah gincu.
Di masa sorenya, nenek ambil kesempatan lebih lama duduk bersamaku di bale bambu sambil memerhatikan pekerja sawah ayunkan cangkul. Nenek bercerita perihal masa mudanya; jalan panjang mengular dan berputar di diameter gunung. Gerobak-gerobak labu dan jagung diangkut dengan bantuan kuda ke arah gunung.
Danau biru berbau aroma kersen kian membundar dan iring-iringan bebek mengikuti induk. Anak-anak berlarian mengejar keong sawah, tangannya berlumpur, hasil tangkapan ditaruh dalam ember. Pulang ke rumah saat sore agak meradang gelap dengan perasaan senang. Aku menatap cerlak nenek seakan kembali ke masa muda. Nostalgia.Betapa bahagianya nenek ketika kicau burung itu setiba lintas di atas hamparan sawah. Mengingatkan kisah lampaunya.
Bapak-emak belum balik ke kampung. Sebenarnya bila aku sudah menginjak usia enam tahun, mereka akan mengajakku ke kota. Melihat sekitar kota dengan aktivitas liarnya; bajaj dan bis kota beradu kebut di jalan, gedung menjulang tinggi merobek atmosfer, tidak ada kelinci hutan disana apalagi keong sawah, yang ada hanya masakan pinggiran jalanan redup penuh lampion berkerlapan. Oseng-oseng makanan laut. Dan kepulan asap bakar sate macam-macam daging. Mereka ingin aku kelak bisa bersaing di kota yang rupanya peluang kerja dimana-mana padahal kurang apa-apa.
Sebelum aku meninggalkan tanah kampung, nenek merasa sedih dan rintik air terus menetes pelan. beliau usap pelan dengan kain dasternya dan mengelus kepalaku perlahan. Beliau merelakan kepergianku. Namun, ada yang pernah aku ingat ketika nenek pulang dari sawah di ujung sore.