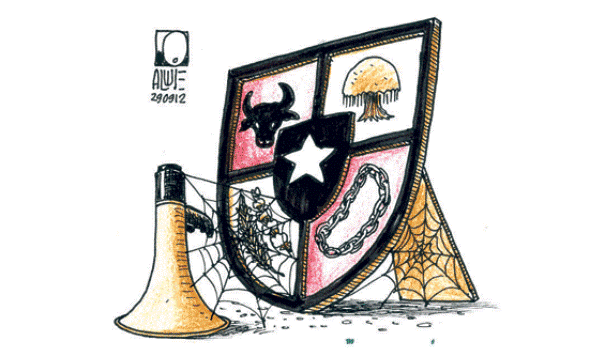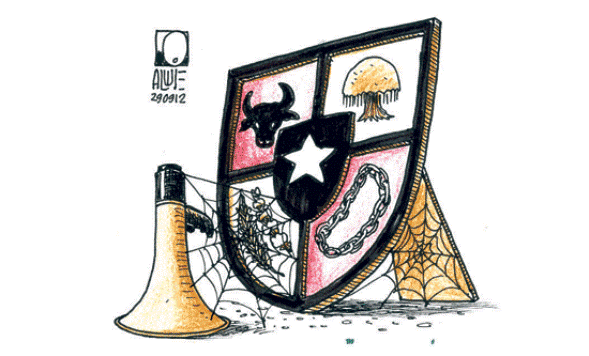Tiba-tiba ponsel Kepala Sekolah berbunyi. Ada telepon masuk. Ia meraih ponsel yang ada di saku celananya dan menerima panggilan itu. Tak sepatah kata pun terucap. Aku dan Guru Sejarah saling berpandangan.
“Baru saja sila kelima telepon. Dia bilang, jika kita ingin menemukannya, kita harus dengar dulu berita pagi ini,” kata Kepala Sekolah.
Ia pun menyalakan televisi yang ada di mejanya. Berita menyiarkan seorang ketua DPR yang mengundurkan diri karena kasus pencatutan nama presiden. Berikutnya, seorang hakim membuat pernyataan konyol dalam memutuskan perkara kebakaran hutan.
“Apa maksudnya?” tanya Guru Sejarah.
“Tidak mungkin hanya itu,” kataku.
“Maksudnya?” tanya Guru Sejarah lagi.
“Tidak hanya dua berita itu. Mungkin kita harus melihat ada petani dibunuh, sawah disulap jadi pabrik. Buruh dipaksa menjadi bahan cemoohan. Penguasa di sana pun juga sedang gemar bertikai. Harga BBM turun, tapi kelangkaan di mana-mana. Semua itu juga dibumbui oleh drama drop-out seorang ketua BEM sebuah universitas oleh rektornya. Masih banyak lagi,” jawabku.
“Ya. Aku tahu bahwa kita memiliki kisah pilu di masa silam. Penguasa tak hanya gemar bertikai, tapi mereka sendiri pun kerap menciptakan sejarah palsu. Kasus pembantaian massal masih ditutupi. Mereka itu membalikkan fakta. Pembunuh dipuji, korban dicaci,” ujar Guru Sejarah. “Jadi karena itu sila kelima pergi? Wajar saja ia merajuk.”
“Aku pikir, sila kelima memang sengaja dipergikan. Kalau ia merajuk, tak mungkin ia menelponku barusan. Ia masih berharap untuk ditemukan,” jawab Kepala Sekolah. Aku memandangi Kepala Sekolah. Ia terlihat cemas.
“Bapak yakin yang telepon tadi itu sila kelima?”
“Apa ada orang yang berani membajak sila kelima?” jawab Kepala Sekolah dengan pertanyaan. Sepertinya ia mulai gelisah.