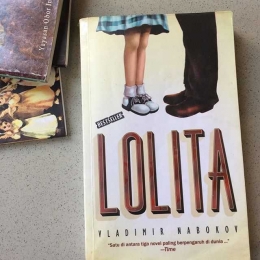Sewaktu kemarin mengantre di sebuah bank, tanpa sengaja, mata saya melirik televisi yang tergantung di dinding. Televisi itu menampilkan sebuah berita tentang Nafa Urbach yang murka lantaran menemukan adanya komentar bernuansa negatif dari netizen setelah mengunggah foto putrinya di instagram.
Di komentar tersebut terdapat sebutan "loli" dan "lolitan" yang dialamatkan kepada anaknya. Sewaktu menelusuri makna kata itu, Nafa berang. Dia kemudian menduga bahwa pemilik akun yang menulis komentar itu adalah kaum paedofil yang berusaha mengincar anaknya. Makanya, dia berupaya melacak si pemilik akun dan berniat melaporkannya ke pihak berwajib.
Sebutan "loli" dan "lolitan" yang disinggung di atas memang punya kesan negatif. Sebutan itu biasanya dipakai oleh kaum paedofil sewaktu akan mengincar korbannya. Sebutan itu sudah sedemikian umum di kalangan paedofil, layaknya sebuah "sandi" yang hanya dipahami oleh masing-masing anggota komunitas. Namun demikian, cuma sedikit yang mengetahui "sejarah" di balik sebutan tersebut.
Jika merunut sejarahnya, kita akan mendapati bahwa sebutan itu sebetulnya "diambil" dari novel Vladimir Nabokov, yaitu Lolita. Novel yang terbit pada tahun 1955 itu mengisahkan petualangan cinta yang "ganjil" antara Humbert Humbert dan Lolita.
Humbert Humbert (nama samaran) adalah seorang lelaki paruh baya yang jatuh cinta pada anak tirinya sendiri. Pertemuan awal mereka terjadi ketika Humbert berkenalan dengan Charlotte Haze. Charlotte Haze adalah seorang ibu dari Lolita, seorang single parent.
Charlotte sebetulnya jatuh hati pada Humbert. Tak lama kemudian, mereka pun menikah. Namun demikian, pernikahan mereka hanya berlangsung singkat. Suatu hari, Charlotte membaca diari suaminya dan menemukan suatu fakta bahwa suaminya mencintai putrinya yang masih berusia 12 tahun!
Setelah semua "aib" tersebut terkuak, Humbert membawa kabur Lorita selama dua tahun. Mereka pergi mengelilingi amerika, menginap dari satu hotel ke hotel lainnya, dan menjalani kisah cinta yang aneh.
Saya tak begitu ingat akhir dari novel itu lantaran saya membacanya bertahun-tahun yang lalu. Namun demikian, saya kemudian mengetahui bahwa novel itu menjadi "inspirasi" dari terbentuknya istilah baru dalam psikologi. Makanya, kemudian muncul sejumlah istilah, seperti "paedofil", "paedofilia", "loli", dan "lolitan".
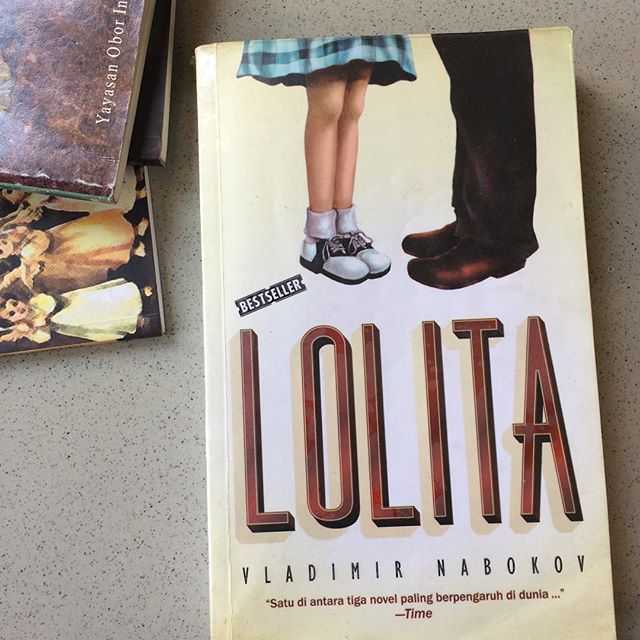
Namun, anehnya, semakin dilarang, semakin banyak pula orang yang penasaran ingin membacanya. Makanya, begitu diizinkan peredarannya kembali, novel itu berulang kali dicetak ulang.
Hal itu ternyata menarik minat sejumlah produser untuk memfilmkannya. Kemudian muncullah sejumlah film dengan judul yang sama, yaitu Lolita (1962) dan Lolita (1997).
Biarpun telah lama membacanya, saya tak pernah menyangka bahwa sejumlah elemen yang terdapat di dalam novel itu akan terkuak lagi pada masa kini. Apalagi, setelah muncul sejumlah kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum guru dan staf sebuah sekolah bertaraf internasional di Jakarta.
Dari situ kemudian terlihat "bayangan" dasar gunung es yang selama ini terbenam bahwa Indonesia disinyalir menjadi incaran kaum paedofil.
Pencegahan Berbasis Komunitas
Kasus tersebut jelas mengindikasikan bahwa media sosial sudah menjadi "lahan" yang dipakai oleh kaum paedofil untuk mengincar korbannya. Oleh sebab itu, orangtua harus proaktif membentengi anak-anaknya terhadap pengaruh media sosial demikian. Jangan sampai anaknya menjadi incaran para paedofil akibat kebablasan memakai media sosial.
Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah bisa orangtua terus mengawasi penggunaan medsos anaknya? Apakah orangtua mampu membatasi pemakaiannya pada zaman ketika jumlah medsos terus bertumbuh secara masif dari tahun ke tahun seperti saat ini?
Saya ragu bahwa orangtua dapat melakukannya. Agak sukar rasanya kalau orangtua mesti memantau medsos anaknya satu per satu. Jadi, apa yang mesti dilakukan agar si anak terhindar dari pengaruh negatif media sosial?
Pertanyaan itu sulit dijawab. Namun demikian, saya ingat pengalaman masa lalu yang mungkin saja bisa memberi sedikit jawaban. Sewaktu saya masih kecil, orangtua saya agak "longgar" dalam menetapkan peraturan yang harus dipatuhi. Orangtua saya juga tak terlalu mengekang kehidupan sosial saya. Orangtua saya membolehkan saya untuk bergaul dengan siapapun.
Makanya, saya kemudian bergaul dengan banyak orang tanpa pilih-pilih sama sekali. Namun, suatu ketika, orangtua saya tiba-tiba saja marah sewaktu mengetahui kalau saya sudah berteman dengan seorang anak. Sebut saja dia S. Saya sebetulnya sudah bersahabat cukup lama. Kami biasanya sering main sepakbola setiap sore di lapangan sebuah sekolah. Makanya, kemudian kami menjadi cukup akrab.
Sayangnya, pertemanan kami kemudian pupus lantaran orangtua saya tiba-tiba melarang saya bergaul dengannya. Alasannya agak aneh menurut saya. Mereka beralasan bahwa S tak berasal dari keluarga baik-baik. Sejak saat itu, saya berhenti berkomunikasi dengan S. Pun sebaliknya.
Bertahun-tahun kemudian, setelah lama tak berjumpa, saya kembali mendapat kabar soal S. Kali ini, yang datang justru kabar yang kurang enak didengar. S dikabarkan telah menghamili seorang gadis di luar nikah. Akibatnya, orangtua gadis itu memaksanya menikahi si gadis. Tak lama kemudian, mereka melangsungkan pernikahan dengan hanya dihadiri beberapa orang saja.
Saya agak kaget mendengar berita tersebut. Namun, dalam hati, saya bersyukur. Andaikan tetap nekad berteman dengan S, barangkali saya akan "terjebak" dalam pergaulan yang keliru seperti itu. Dari situ saya juga belajar bahwa orangtua ternyata perlu juga menyelidiki track record keluarga teman anaknya agar bisa mencegah sesuatu yang tak diinginkan pada kemudian hari.
Peristiwa itu telah terjadi bertahun-tahun yang lalu, jauh sebelum media sosial bertumbuh secara masif seperti saat ini, tetapi hikmah yang bisa diambil darinya masih terasa relevan, apalagi kalau kita menghubungkannya dengan kasus yang dialami oleh Nafa Urbach di atas.
Makanya, saya bisa menyimpulkan bahwa orangtua sebetulnya tak perlu repot-repot mengekang anaknya dalam menggunakan media sosial lantaran laju pertumbuhan medsos akan terus naik pada tahun-tahun berikutnya.
Namun demikian, orangtua wajib mengawasi dengan siapa saja anaknya bergaul. Orangtua harus mengetahui dengan jelas teman-teman dekat anaknya, agar lebih mudah memantaunya. Hal itu tentunya lebih mudah dilakukan daripada harus memeriksa setiap "status" atau chat yang ditulis anaknya.

Makanya, kalau bisa memberi perngaruh buruk bagi anak, seperti kasus yang dialami oleh Nafa Urbach di atas, kehadiran medsos seharusnya juga dapat "membendung" pengaruh tersebut.
Dengan terlibat aktif di media sosial dengan membentuk suatu komunitas, orangtua dapat bekerja sama dengan orangtua lainnya dalam mengawasi pemakaian media sosial anak-anaknya, tanpa perlu ribet memeriksa semua status yang dibuat anaknya di media sosial.
Salam.
Adica Wirawan, founder of Gerairasa.com
Referensi:
"Anak Nafa Urbach Diincar Paedofilia, Tanda Anak yang Jadi Korban," tempo.co, diakses pada tanggal 15 Agustus 2017.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H