Tahun 2016, waktu lulus kuliah teater, saya memutuskan untuk menjadi guru teater (intrakurikuler) di sekolah. Saya kira itu keputusan strategis karena di kurikulum pendidikan menengah pada pelajaran Seni Budaya terdapat materi teater, tetapi saya tidak temukan kampus besar pendidik(an) macam UPI atau UNJ yang memiliki Prodi Pendidikan Teater. Entah di kampus lain.
Maka, otomatis sekolah-sekolah pasti senang ada seorang lulusan teater yang mau menjadi guru teater, mengisi kekosongan guru teater yang mestinya tersedia menurut kurikulum seni budaya.
Lalu, ketika saya mulai mencari sekolah yang membutuhkan pengajar teater---saya mengira pasti banyak dan saya jadi rebutan, tapi ternyata saya salah besar banget. Hasilnya justru nol! Nihil! Tidak ada sekolah yang membutuhkan guru teater. Bahkan seorang staf sekolah bertanya, "Oh.. teater ya mas? yang belajar jadi kayak orang gila itu ya? Bagus tuh. Hahaha".
Karena bosan sudah berbulan-bulan jadi pengangguran, akhirnya saya membuka opsi untuk masuk ke dalam industri kreatif dengan melamar ke Stasiun TV, Rumah Produksi, Event Organizer dan sejenisnya. Ketika sudah ada beberapa respon dari industri tersebut, ada kabar dari seorang alumni teater bahwa Sekolah Madania (di Parung, Bogor) membutuhkan Guru Teater.
Secara spesifik disebutkan yang dibutuhkan adalah lulusan prodi teater dan akan mengajar mata pelajaran teater---bukan Seni Budaya---dari tingkat dasar sampai menengah. Ajaib! Ternyata ada sekolah umum yang punya pelajaran teater secara spesifik. Optimisme untuk masuk ke dunia pendidikan muncul lagi. Tanpa pikir panjang saya langsung meminang Sekolah Madania!
Pendidikan Teater Tidak Ada di Sekolah Umum
Pendidikan teater di Indonesia tingkat perguruan tinggi terdapat di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI), Institut Seni Indonesia (ISI), Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dan sejenisnya. Saya adalah salah satu produknya. Pendidikan tinggi tersebut dapat ditempuh seseorang yang sudah berusia di atas 17 tahun dan telah lulus dari tingkat SMA.
Jika ada anak yang berniat mendalami teater dengan berkuliah di perguruan tinggi seni, maka anak tersebut harus lulus SMA terlebih dahulu. Tetapi, kenapa harus seperti itu ya?
Apakah sekolah di tingkat SMA memberikan pengantar pelajaran teater bagi anak yang mau kuliah teater, sehingga jika belum lulus SMA, anak tersebut tidak akan mampu mengikuti pelajaran teater di perguruan tinggi? Padahal di Ibu Kota Jakarta saja tidak ada sekolah yang memiliki pelajaran teater secara spesifik. Kalaupun ada, saya yakin jari tangan saya akan lebih dari cukup jika digunakan untuk menghitung jumlahnya.
Saya jadi membayangkan jika tidak ada pelajaran matematika di SMA. Prinsip-prinsip matematika hanya ditemukan dari irisan pelajaran lain atau dari bias-bias kehidupan sehari-hari. Lalu ada anak yang punya minat besar terhadap matematika dan ingin mendalami matematika secara serius di perguruan tinggi.
Di sanalah ia pertama kali belajar matematika secara komprehensif. Karena belum pernah sama sekali belajar matematika, maka si anak akan bertanya: Bu/Pak, kenapa satu ditambah satu hasilnya lebih besar daripada satu dikali satu; padahal dua ditambah dua hasilnya sama dengan dua dikali dua? Saat itu ia akan berharap menemukan puisi dari pelajaran matematika.
Begitulah yang terjadi pada siswa di kelas teater. Setidaknya di kelas yang saya ajar tahun lalu. Banyak siswa yang berharap menemukan kepastian matematis dari seni (dalam hal ini teater).
Mereka mengira bahwa teater hanyalah matematika dari bahasa yang dilakukan. Mereka mengira bahwa semua yang terjadi di atas panggung dapat dihitung secara matematis: jumlah langkah kaki, ayunan tangan, arah hadap, level emosi, bahkan jumlah air mata yang menetes. Mereka mengira bahwa ada kepastian yang mutlak dalam teater. Tidak mengenal intuisi.
Bahkan jauh lebih rumit dari itu karena bias-bias teater yang ada dalam kehidupan sehari-hari begitu sporadis seperti belajar jadi kayak orang gila. Sampai di sini, saya jadi berpikir sulit betul jadi pengajar teater di perguruan tinggi seni. Karena selain mengajarkan teater betul-betul dari nol---bahkan dari minus, karena yang diketahui kerap keliru; mereka juga harus menjaga mahasiswanya agar tetap waras.
Belum Saya Temukan Kampus Pendidik(an) Teater
Menurut kurikulum 2013 di tingkat menengah, dalam pelajaran Seni Budaya terdapat empat cabang seni: Seni Rupa, Musik, Tari & Teater. Tetapi, sialnya tidak ada (baca: saya tidak tahu) pendidikan tinggi yang melahirkan guru teater.
Kalau kita mencari Sarjana Pendidikan Seni Rupa, Musik ataupun Tari, dengan mudah kita bisa temukan mereka di kampus pendidik(an) macam UPI, UNJ atau UNY. Tapi jika kita butuh Sarjana Pendidikan Teater, ada di manakah mereka? Adakah mereka? Saya belum pernah menemukannya.
Pada tingkat Pendidikan Tinggi, yang ada hanya Sekolah Seni seperti ISI, ISBI atau IKJ yang memiliki Prodi Teater. Bedanya apa? Dalam Prodi Teater, mahasiswa mempelajari teater dari sudut pandang teater; sudut pandang seni. Lulusannya diharapkan dapat menjadi seniman atau pelaku industri seni.
Sedangkan pendidikan teater di tingkat menengah dan dasar butuh perspektif lain, yakni perspektif pendidikan. Kampus pendidikan teater harus melahirkan pendidik teater untuk tingkat dasar ataupun menengah dengan asumsi teater dapat berkontribusi bagi pertumbuhan manusia dalam perspektif pendidikan.
Secara lugas, mungkin bedanya adalah prodi teater mempelajari materi teater lebih banyak dan murni sebagai seni; sedangkan prodi pendidikan teater mengurangi porsi materi teater dan diganti dengan materi tentang perspektif pendidikan dalam teater serta perspektif teater dalam pendidikan.
Tahun 2015 saya bersama teman-teman angkatan pernah mengadakan seminar teater berjudul "Dididik Teater[?]". Kurang lebih seminar tersebut membahas tentang peran teater dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tingkat SMA.
Salah satu pembicaranya adalah Deden Rengga. Beliau adalah dosen pendidikan seni tari di Universitas Negeri Jakarta. Kalau tidak salah, beliau juga salah satu perumus kurikulum teater di tingkat SMP dan/atau SMA. Saat itu beliau sedang mengambil program doktoral teater di Institut Seni Indonesia.
Dalam obrolan yang singkat, saya sempat bertanya pada beliau, mengapa kurikulum tingkat menengah (SMP/SMA) mengakomodir cabang seni teater, tetapi tidak ada kampus pendidikan yang melahirkan pendidik-pendidik teater.
Seingat saya, jawabannya adalah karena belum ada ahli di bidang tersebut; belum ada setingkat doktor/profesor yang menekuni bidang pendidikan teater. Karena untuk membuka sebuah prodi baru, harus ada beberapa orang ahli setingkat doktor/profesor yang sudah menekuni bidang tersebut.
Teater Sebagai Intrakurikuler
Di sekolah-sekolah umum, teater biasanya hanya ada sebagai ekstrakurikuler. Dibimbing oleh seorang pelatih, di luar jam sekolah dan 'hanya' sebagai pelengkap (baca: hiburan) yang dapat menjadi tempat penyaluran hobi siswa-siswi di sekolah. Karena umumnya sekolah hanya memberikan sedikit saja porsi untuk ekstrakurikuler. Dari segi waktu maupun dari segi finansial.
Meski begitu, di sisi lain, banyak juga pelatih-pelatih teater yang ngotot mencurahkan segenap energinya untuk serius membangun ekskul teater di sekolah. Merekalah sebetulnya yang sangat berjasa dalam menjaga---bahkan membuat---estafet pengalaman teater bagi pelajar untuk diteruskan di jenjang perguruan tinggi, maupun diteruskan sebagai seniman alam.
Namun, hal itu tidaklah cukup, karena ekstrakurikuler teater di sekolah-sekolah hanyalah tetap dianggap sebagai pelengkap. Ekskul teater yang maju, selalu saja karena energi berlebih pelatihnya, bukan karena dukungan sistem pendidikan.
Paling-paling yang menyuntikan semangat para pelatih tersebut adalah festival-festival teater remaja/pelajar, yang lagi-lagi diselenggarakan berdasarkan inisiatif kelompok independen. Bukan berasal dari sistem pendidikan. Oleh karena itu, menurut saya, eksistensi teater di ruang kelas; di dalam jam pelajaran; sebagai intrakurikuler, sangat penting adanya sebagai bentuk dukungan sistematis.
Pelajaran Seni Budaya dalam kurikulum sebetulnya memungkinkan teater eksis di dalam intrakurikuler. Namun, masalahnya itu tadi, bahwa tidak ada gurunya. Tidak ada sarjana pendidikan teater. Maka, mata pelajaran Seni Budaya hanya akan diisi oleh Seni Rupa, Musik & Tari. Karena apa? Karena ada gurunya.
Bukan salah mereka tidak memberikan ruang kepada teater, tetapi karena sistemnya sudah kadung seperti itu. Meski begitu beberapa Sarjana Seni (Teater) juga kebagian mengajar pada mata pelajaran Seni Budaya dan mereka boleh mengajarkan teater.
Secara formal, mereka memahami teater sebagai seni tanpa mempelajari perspektif pendidikan selama di perguruan tinggi. Meskipun tak menutup kemungkinan setelah mengajar, mereka belajar tentang perspektif pendidikan.
Beda Orientasi Teater di SMA dengan SMK Jurusan Teater
Memang betul, ada sekolah kejuruan yang spesifik memiliki jurusan teater, seperti SMKN 10 Bandung atau SMKN 13 Jakarta. Akan tetapi, tentu saja SMK memiliki orientasi yang berbeda dengan sekolah umum seperti SMA. Jika di SMA diajarkan seluruh materi secara mendasar, SMK mengharuskan pemberian materi secara lebih spesifik dan teknis.
Karena diasumsikan setelah lulus dari SMK, mereka bisa langsung bekerja; bisa langsung masuk ke dunia industri. Dalam hal teater, tak heran jika SMK Jurusan Teater menitikberatkan pada kemampuan teknis teater seperti akting, improvisasi, menari, bernyanyi, dsb. Serta SMK Jurusan Teater sudah pasti berfokus pada pembelajaran teater dan pembelajaran lain hanya sebagai penunjang.
Karena setelah lulus dari sana, diasumsikan mereka sudah mampu masuk ke dalam industri seni. Dalam hal ini, sangat cocok jika guru teater di sekolah kejuruan berasal dari perguruan tinggi seni seperti yang sudah disinggung di atas.
Berbeda dengan SMA, di mana siswa masih cenderung bebas memilih. Penjurusan IPA/IPS/Bahasa pun masih sangat umum. Di SMA mereka didesain untuk mencoba banyak hal, mempelajari banyak hal, untuk kelak menentukan akan melanjutkan studi ke bidang apa.
Oleh karena itu, setiap guru mata pelajaran harus sadar, bahwa mereka memberi bekal kepada orang yang belum tentu berminat mendalami mata pelajaran tersebut. Seorang guru matematika harus legowo jika ada siswa-siswi yang nilai matematikanya tidak bagus-bagus amat. Karena, siapa tahu, ia adalah calon aktor besar.
Pun sebaliknya, seorang guru teater tidak boleh terlalu ambisius untuk mencetak aktor-aktor di SMA, karena bisa jadi yang ada di hadapannya adalah ahli fisika abad ke-21.
Pertanyaannya adalah, seberapa penting matematika bagi seorang calon aktor? Pertanyaan ini mungkin tanggung jawab guru matematika. Pertanyaan selanjutnya: Seberapa penting teater bagi calon ahli fisika, pebisnis, politisi, teknokrat, dll?
Seberapa penting teater bagi pelajar yang bercita-cita di dalam masa depannya tidak akan ada teater? Dalam kondisi seperti ini, guru teater harus memahami perspektif pendidikan. Ini tantangan bagi lulusan perguruan tinggi seni yang mau terjun di dunia pendidikan sebagai guru.
Guru teater yang tidak memahami perspektif ini, mungkin akan sangat sulit beradaptasi di sekolah. Si guru pasti ingin memberikan pemahaman & kemampuan teknis sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada para siswa, meskipun para siswa tidak menyukainya bahkan tidak membutuhkan sebanyak itu. Si guru memiliki standar pendidikan teater yang tinggi; menyamakan standar dirinya di perguruan tinggi.
Guru teater yang seperti ini mungkin berambisi menyiapkan sebaik-baiknya calon seniman besar yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi seni. Padahal, dari satu angkatan saja, belum tentu ada yang mau kuliah teater.
Di titik ekstrem yang lain, jika seorang guru teater yang menyadari bahwa siswa-siswi di hadapannya tidak akan (baca: kemungkinan kecil) melanjutkan studi atau mendalami dunia teater/seni peran, maka, gaya mengajarnya akan serampangan.
Guru yang seperti ini akan lebih 'berbahaya'. Karena merasa dirinya yang paling tahu teater, dan mengasumsikan sangat sedikit sekali orang yang mengetahui tentang teater, maka ia akan seenaknya saja mengajar. Bahkan ia tidak akan mengajar teater. Ia hanya akan menghabiskan waktu dengan senda gurau, dan siswa-siswi menganggap menghabiskan waktu plus senda gurau adalah teater.
Lebih sial lagi, guru yang menyibukkan siswa-siswi dengan tugas-tugas teori nan ajaib. Siswa-siswi diberi tugas menghafal nama-nama kelompok teater, profil tokoh teater, sejarah teater, hingga menghafalkan secara redaksional definisi-definisi dari genre teater seperti realisme, surealisme, absurdisme dan sejenisnya. Tanpa pernah diajak melihat atau mengalami teater.
Materi Drama dalam Pelajaran Bahasa
Selain Pelajaran Seni Budaya, sebetulnya ada pelajaran lain yang memungkinkan siswa belajar teater, yakni pelajaran bahasa. Entah itu Bahasa Indonesia, Bahasa Lokal (seperti Sunda, Jawa, dsb.) atau Bahasa Asing (seperti Inggris, Mandarin, Korea, Thailand, dsb.).
Tetapi sebetulnya penekanannya akan berbeda. Dalam pelajaran bahasa, teater yang dipelajari lebih spesifik disebut sebagai drama. Di mana pertunjukannya berbasis teks sastra drama. Jadi, kurang lebih, konten utama pelajarannya adalah mentransformasi bahasa tulis menjadi bahasa lisan. Penekanannya ada pada bahasa lisan: dialek, pronunciation, dan sejenisnya.
Tetapi, jangan senang dulu. Ini hanya kemungkinan. Karena banyak juga guru bahasa yang tidak memilih jalan pertunjukan untuk mempelajari materi drama. Mereka lebih memilih jalan teori.
Mempelajari dramaturgi seperti menghafal definisi plot, kedudukan tokoh (antagonis, protagonis, dsb.), struktur dramatik (exposition, rising action, dst.) dan lain-lain. Ini pilihan saja, karena pelajaran bahasa memang lebih menekankan pada bahasa tulis dan bahasa lisan dalam penggunaannya di kehidupan. Bukan bahasa sebagai seni: susastra. Kalaupun ada, itu hanya sebagian kecil yang kadang tidak dipilih untuk dipelajari.
Sedangkan teater memiliki dimensi yang berbeda. Dimensi teater adalah seni pertunjukan (performing arts). Di mana, penekanannya ada pada laku-aksi di atas panggung pertunjukan. Bahkan, lebih jauh dari itu, meliputi komponen audio, visual & kinestetik yang ada di atas panggung. Pertunjukan drama juga perlu memperhatikan komponen-komponen tersebut.
Namun, bedanya adalah, drama didasari oleh bahasa tulis, sedangkan teater tidak. Sangat mungkin sebuah pertunjukan teater tanpa didasari bahasa tulis, bahkan tanpa menggunakan bahasa lisan. Misalnya pertunjukan pantomim. Media ungkap aktor pantomim adalah tubuhnya dan tidak menggunakan bahasa lisan sama sekali.
Jadi, pertunjukan drama adalah teater. Tapi, teater tidak hanya pertunjukan drama. Pertunjukan drama harus menggunakan teks tertulis (sastra drama) sebagai basis pertunjukan, sedangkan teater tidak harus menggunakan teks tertulis (sastra drama) sebagai basis pertunjukan. Pertunjukan drama adalah salah satu bentuk teater. Oleh karena perbedaan tersebut, penekanan dalam proses belajar juga akan berbeda.
Buat Apa Belajar Teater?
Setelah sampai pada paragraf ini, mungkin Kepala Sekolah atau pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan sudah merasa: Sok penting banget sih nih teater! Apa banget deh? Kecurigaan saya ini sangat mendasar karena saya terlalu percaya diri dengan teater, tetapi belum mampu menjelaskan: buat apa sih belajar teater di sekolah?
Sampai detik ini memang belum pernah saya temukan kajian yang komprehensif tentang teater dalam perspektif pendidikan. Entah karena memang belum ada atau karena memang referensi saya saja yang kurang. Tetapi, Deden Rengga saja tahun 2015 menyebutkan bahwa memang [saya: di Indonesia] belum ada ahli setingkat doktor/profesor yang menekuni bidang tersebut. Entah hari ini, lima tahun setelah 2015.
"Buat apa belajar teater?" adalah pertanyaan saya juga ketika pertama kali saya mengajar di sekolah. Kalau bagi mereka yang menyukai bahkan menginginkannya, mungkin tak perlu ditanya lagi. Tapi bagi mereka yang tidak menyukai, buat apa mereka belajar teater?
Pusing betul saya sama pertanyaan saya sendiri. Hingga kemudian, saya menemui Ki Hadjar Dewantara & Benjamin S. Bloom untuk meminta pencerahan.
Dari merekalah saya meyakini bahwa teater dapat memberi kontribusi pada pendidikan. Benjamin Bloom menyebutkan tujuan pendidikan dibagi ke dalam tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif & ranah psikomotor. Senada dengan itu, Ki Hadjar Dewantara menyebutkan penalaran, penghayatan dan pengalaman.
Saya merasa teater menyentuh ketiga ranah tersebut. Ranah kognitif sebagai ranah yang menekankan pada aspek intelektual. Ranah ini terjadi pada teater ketika melakukan analisis terhadap naskah drama atau membuat konsep pertunjukan hingga menilai pertunjukan (materi apresiasi teater). Pada intinya memahami teater secara kognitif.
Ranah kedua adalah ranah afektif yang menekankan aspek perasaan/emosi. Ranah ini tentu sangat dominan ketika seorang anak berlatih menjadi aktor. Di mana seorang aktor harus mampu berempati pada peran yang akan dibawakan. Bahkan membawakannya dengan merasakan apa yang harusnya dirasakan si tokoh yang dimainkan. Ranah ketiga adalah ranah psikomotor yang menekankan pada aspek psikomotorik.
Dalam teater, dikenal materi olah tubuh di mana seorang aktor harus melatih tubuhnya agar memiliki elastisitas yang baik dan fleksibel memerankan peran apapun. Rasanya, ranah psikomotorlah yang diolah oleh materi olah tubuh tersebut.

Sebetulnya ketiga ranah tersebut sudah dapat disentuh dengan pendekatan keaktoran. Seorang aktor harus memahami peran yang akan dibawakan (bahkan sampai melakukan riset), entah itu berasal dari naskah drama maupun konsep peran yang dibuatnya sendiri (kognitif).
Setelah itu, ia harus mampu berempati pada peran tersebut. Karena di atas panggung, aktor tidak boleh berpura-pura, ia harus benar-benar tulus, jujur, merasakan apa yang peran tersebut rasakan (afektif).
Secara fisik, aktor harus melatih perangkat fisik keaktorannya (baca: olah tubuh) dan mengaplikasikan apa yang telah ia ketahui (kognitif) dan ia rasakan (afektif) ke dalam laku-aksi tubuhnya (psikomotor).
Saya jadi teringat, Rukman Rosadi, aktor film & teater, dosen keaktoran ISI Yogyakarta, pernah menulis bahwa untuk menjadi aktor, seseorang harus melatih tiga aspek utama dalam dirinya, yakni pikiran, perasaan dan tubuh. Bahkan, Constantin Stanislavsky dalam buku Building a Character menyebutkan physical characterization, psychological characterization & psychophysical characterization. Banyak memiliki kesamaan bukan?

Tapi mungkin, ilustrasi di atas agak rumit jika diterapkan di tingkat sekolah dasar. Untuk soal ini, saya jadi ingat Ki Hadjar Dewantara mendirikan sebuah lembaga pendidikan dengan nama Taman Siswa, bukan tanpa alasan.
Dengan kata "taman" ia ingin sekolah itu menjadi tempat yang membahagiakan & menyenangkan. Ajaibnya, saya menemukan ini juga di teater. Iman Soleh, dosen keaktoran saya di ISBI Bandung selalu menggunakan metode bermain ketika mengajar.
Saya selalu merasa bahagia tiap kali bermain permainan-permainan yang dapat melatih perangkat keaktoran. Saat mondok di rumahnya, saya pernah bertanya tentang metode tersebut. Lalu, ia menunjukan sebuah buku Games for Actors and Non-Actors karya Augusto Boal. Ternyata ada juga buat anak SD. Bisa juga teater buat anak SD.
Salain itu, ada satu hal yang saya rasa sangat penting. Yaitu doktrin di dalam teater yang menyatakan bahwa aktor adalah tanah lempung [yang bernyawa]; tanah liat [yang bernyawa]. Kalau tidak salah, saya pertama kali membaca ini dari tulisan Suyatna Anirun.
Doktrin ini adalah doktrin jadul yang menyatakan bahwa menjadi aktor harus bisa menjadi apa saja. Oleh karena itu, seorang aktor harus mau dan mampu mempelajari apa saja. Aktor harus memiliki kesadaran aktif untuk mempelajari apapun sesuai dengan peran yang akan dimainkan. Awalnya, memang ada semacam formula untuk mempertanyakan atau melatih apa yang ingin diketahui dan dikuasai.
Tapi lama kelamaan formula tersebut sudah melekat pada aktor dan aktor akan mencari tahu segala macam hal tentang peran yang akan dibawakan; aktor akan mencoba, melatih dan memiliki kemampuan yang dimiliki oleh peran yang ia bawakan. Saya tidak tahu, apakah doktrin ini mirip-mirip dengan konsep Inquiry Based Learning yang dimiliki oleh kurikulum International Baccalaureate. Rasanya ada kemiripan.
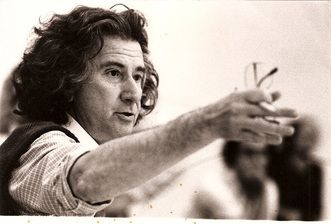
Saya Tutup dengan Menundukan Kepala
Semua yang sudah saya tuliskan sejak awal mungkin tidak betul-betul menggambarkan keadaan sebenarnya dari apa yang terjadi di sekolah maupun di teater.
Sebagai contoh misalnya, Sri Mulyani Budiantini, guru saya, mantan Kepala Jurusan Teater SMKN 13 Jakarta, mengatakan bahwa sekarang sudah ada prodi pendidikan teater di Semarang.
Meskipun ketika saya membaca buku Paradigma Pendidikan Seni yang ditulis oleh dosen & mahasiswa pascasarjana Universitas Negeri Semarang (editor: Deddy Irawan), saya mesti kecewa karena tidak ada tulisan tentang pendidikan teater. Selain itu, saya juga pernah dengar ada jurusan Sendratasik (Seni Drama Tari & Musik), mungkin ini senada dengan konsep Performing Arts Education di mana subjeknya adalah Performing Arts.
Gurunya berkelompok, terdiri dari guru musik, guru tari, guru seni rupa pertunjukan dan guru teater sebagai pemimpin (bertindak sebagai pelatih akting & sutradara).
Biasanya target pementasannya adalah drama musikal. Entah bagaimana konsep Sendratasik saya belum mengetahuinya. Mungkin saja, anggapan saya soal ketiadaan prodi pendidikan teater, hanya karena ketidaktahuan saya.
Selain itu, karena banyak variabel yang membuat sesuatu tidak dapat menjadi pasti/mutlak, maka anggapan saya tentang Sarjana Seni (S.Sn.) dan Sarjana Pendidikan Seni (S.Pd.) tentu saja dapat dibantah. Saya terlalu mempertajam perbedaan antara Sarjana Seni dengan Sarjana Pendidikan Seni.
Padahal tidak ada jaminan mutlak bahwa sarjana pendidikan sudah pasti lebih baik dalam mengajar dibanding sarjana seni, pun sebaliknya, tidak ada jaminan mutlak bahwa sarjana seni akan berkarya lebih bagus dibanding sarjana pendidikan seni. Bahkan boleh jadi orang yang tidak menyandang gelar sarjanapun mampu memberikan pendidikan yang baik dan/atau jadi seniman yang baik.
Dalam hal seni, banyak contoh tersebut terjadi di mana-mana. Ada variabel yang bersifat personal dan tak dapat dipukul rata. Secara substansial gelar memang tak penting, meskipun bisa jadi salah satu variabel.
Misal yang lain, adalah saya merasa terlalu percaya diri dengan teater. Padahal, kenyataannya, teater begitu rapuh tanpa bidang ilmu yang lain. Saya bahkan berani memberikan kesaksian bahwa orang yang unggul di teater, pasti memiliki keahlian/pemahaman mendalam di bidang lain. Tak jarang, orang teater menyukai bahkan mendalami bidang lain yang bukan spesifik teater seperti lukis, musik, tari atau bahkan hal lain di luar seni seperti sosiologi, psikologi, filsafat, sejarah bahkan matematika.
Misal yang lain lagi, selama saya mengajar di Sekolah Madania (2017-2019), saya mulai temukan satu persatu sekolah yang memiliki pelajaran teater (atau sejenisnya) seperti Sekolah Cikal (Performing Arts), Binus School (Performing Arts), Kharisma Bangsa (Drama), BPK Penabur (Seni Drama), Springfield School (Performing Arts), dan beberapa yang saya lupa. Perbedaan penggunaan istilah performing arts, drama atau teater adalah sesuatu yang menarik. Bahkan ada sekolah yang menamai kelasnya dengan lebih spesifik, yakni kelas akting/kelas seni peran. Saya lupa nama sekolahnya. Saya membayangkan ada keunikan dari penerapan definisi-definisi tersebut di lapangan. Ini yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut.
Oleh karena apa yang saya tulis ini tidak betul-betul menggambarkan apa yang terjadi di sekolah maupun di teater, siapapun boleh memberikan pandangan lain agar dugaan tentang sekolah & teater bisa lebih jernih serta menjadi diskusi yang menarik. Sampai jumpa di ruang diskusi.
Jakarta, 2-5 Mei 2020
Muhamad Habib Koesnady
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H









