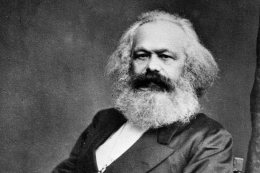Sulit mempercayai kalau pekerjaan besar sekelas pembuatan UU Cipta Kerja tidak dirancang dengan program komunikasi. Para pesona yang duduk di kursi Senayan itu bukan orang yang nemu ditepian jalan. Mereka dipilih dengan satu niat suci untuk dapat memperjuangkan nasib bangsa ini melalui produk legislasinya. Tapi itulah kenyataannya, entah iya dan tidak pembahasan RUU Cipta Kerja ini terkesan tertutup dan tidak melibatkan publik, padahal jelas-jelas peraturan ini akan berdampak bagi masyarakat.
Gelombang penolakan yang cenderung masif itu adalah gambaran bahwa telah terjadi sumbatan komunikasi dalam proses pembuatan UU Ciptaker tersebut. Publik khususnya pekerja harus tau sebagai pihak yang banyak dibicarakan di UU Sapujagat itu.
Bagi banyak orang, menyebut Omnibus Law pun terasa masih asing di ujung lidah, kononkah pula memahaminya? Oleh sebab itu perlu tahapan dan staging untuk mengkomunikasikannya dalam satu Cetak Biru Komunikasi dengan asas keterbukaan (disclosure) dan bisa diukur.
Mengingat khalayak sasarnya berada dalam demografis dan psykografis yang berbeda, dibutuhkan strategi dan taktik agar pesan tersebut sampai. Agenda besar ini tidak mudah - dibutuhkan waktu yang cukup karena perlu disampaikan secara berulang-ulang. Pada scene-scene selanjutnya jendela informasi dapat diproduksi melalui public hearing lewat pemanfaatan sarana teknologi komunikasi yang ada pada pemerintah. Semua tatanan ini dibuka seluas luasnya untuk masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan sekundernya sebagai bentuk layanan penguasa pada rakyatnya.
Kita dapat belajar dari teori Public Sphere Jurgen Hubermas (filsuf Jerman (1929) bahwa ruang publik sebagai konsep politik harus ditata sedemikian rupa sehingga merealisasikan kepentingan setiap orang untuk terlibat dengan seluruh kekhasannya.
Ruang Publik juga sebagai sebuah konsep politik harus mengusahakan komunikasi yang mampu menjembatani norma moral yang konkrit yang berlaku bagi setiap orang/kelompok. Konsep dan teori kritis ini sebenarnya sudah sejalan dengan aturan dan Tata Tertib DPR, baik pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP/Umum), maupun dalam sidang-sidang lainnya.
Mekanisme itu harus dijalankan sebagai esensi dari konsep ruang publik dimana publik diberi 'kebebasan' untuk mengikuti dan pada saatnya dapat memberikan masukan dan atau aspiranya. Kalau kemudian terjadi pelaksanaan diluar dari prosedur dengan dalih yang direkayasa, maka seyogyanya tidak menjadi penyebab terputusnya rantai komunikasi. Ini yang terjadi saat ini.
Menjaga Marwah
Penguasa dalam menjalankan Tupoksinya selalu dihadapkan pada suguhan kepantasan yang menguji moral. Sampai disini tak jarang menjadi statusquo, bertaruh di antara kepentingan kekuasaan atau kepentingan rakyat. UU Cipta Kerja adalah pemicu yang menyibak sesuatu yang tersembunyi selama ini.
Bagi penguasa reaksi penolakan publik, barangkali menjadi pilihan sulit atau malah tidak sama sekali. Nampaknya ada fenomena penguasa mulai belajar menggunakan konsep post-truth atau pasca-kebenaran yang dalam kamus Oxford, makna post-truth adalah dikaburkannya publik dari fakta-fakta objektif.
Kemelut UU Cipta Kerja menjadi bertambah kusut, ketika sadar bahwa kita sedang dihadapkan ancaman Covid-19 yang tak tau kapan akhirnya. Kalau saja mampu menakar setiap persoalan yang berpotensi menjadi konflik dengan timbangan hati, mungkin persoalannya akan menjadi lain. Ironi entah disadari atau tidak bahwa reaksi kegaduhan masyarakat dalam bentuk turun ke jalan, sudah dipastikan sulit untuk menjaga Protokol Kesehatan.
Peristiwa unjuk rasa penolakan Undang-Undang sebagai produk kerja DPR bersama Pemerintah, bukan kali pertama terjadi. Hal ini memberikan multifier effect yang serius salah satunya adalah terusik dan lunturnya sebuah Marwah Kekuasaan...