Seorang lelaki tua berdiri terpaku. Menyaksikan rumah beserta tanah warisan dari orangtua, yang dihuni sejak lahir, dihancurkan rata dengan tanah. Membiarkan istri dan anak-anaknya tergugu menatap barang yang berserakan di pinggir jalan.
Lelaki tua itu, tak perlu bertanya kepada warga sekitar, bahwa dia adalah pemilik rumah. Karena mereka adalah pendatang. Lelaki itu adalah orang tertua di kampung itu. Tak lagi ada orang yang bisa diajukan sebagai saksi.
Juga tak ada bukti, apatah secarik kertas, saat orangtuanya mewariskan rumah beserta tanah itu kepadanya. Semua saudaranya telah mati. Bahkan tak mungkin bertanya kepada kepala desa atau kantor pertanahan. Kantornya belum berdiri, dan pejabatnya saja belum lahir.
Percuma usaha berhari-hari bercerita tentang kenangan masa lalu, juga asal-usul berdirinya kampung yang sama persis dengan isi buku tentang sejarah berdirinya desa.
Satu-satunya kesalahan lelaki tua itu, adalah tak mampu menggantikan kebenaran cerita-cerita itu, dengan secarik kertas bukti kepemilikan. Sehingga memiliki kekuasaan untuk memperjuangkan kebenaran.
Satu-satunya pembuktian tentang kepemilikan itu adalah, orang-orang tahu, dia dan keluarganya mendiami rumah itu. Hanya itu. Tak ada pembuktian lain!
"Jika anda memiliki sekeranjang kebenaran. Maka itu tak akan berguna, tanpa segenggam kekuasaan."
Begitu dahsyatnya yang bernama kekuasaan. Secarik kertas yang berisi perintah pembongkaran rumah lelaki tua itu, lebih berkuasa untuk menghapus kebenaran-kebenaran sejarah yang dimiliki.
Secarik kertas yang bernama kekuasaan, bisa membungkam teriakan istri yang menunjuk satu kamar, sambil berkisah, bagaimana dulu berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan satu-persatu anaknya.
Segenggam kekuasan itu, mampu mengabaikan bekas jahitan luka di dahi anak tertua, setelah terjatuh dari pohon jambu di tanah kosong, yang sekarang sudah berganti mini market. Walau beberapa orang paruh baya membenarkan peristiwa itu.
Kekuasaan itu, menafikan cerita dari beberapa mantan kepala desa, tentang jasa lelaki tua itu membantu mereka menjalankan tugas sebagai pemimpin desa. Kebenaran-kebenaran dan kesaksian hanya sebagai bukti menghuni. Bukan memiliki.
***
Peristiwa pembongkaran paksa rumah itu, begitu membekas pada anak bungsu lelaki tua itu, belasan tahun kemudian. Satu-satunya pembelajaran penting dari peristiwa itu, bahwa kekuasaan lebih penting dari kebenaran.
Anak bungsu itu, berusaha melupakan perjuangan kedua orangtuanya. Harus pindah ke rumah kontrakan. Memaksa diri berjuang lebih keras untuk biaya sewa serta kehidupan keluarga. Orangtuanya mati, menyerah pada jemari kekuasaan.
Anak itu menertawakan nasib Socrates juga Galileo. Menjadi martir untuk suatu kebenaran, dan tersungkur di hadapan sebilah pedang kekuasaan.
Ia menatap kasihan kepada penjaja kebenaran yang setiap pagi, siang dan sore serta malam hari melontarkan hal itu, hingga ke pinggir-pinggir jalan. Ia meyakini, apapun kebenaran yang diperjuangkan, tanpa kekuasaan adalah kemustahilan.
Maka, tak perlu berpihak pada kebenaran bila muaranya adalah penderitaan dan kesengsaraan. Sebagaimana yang dialami orangtua dan keluarganya. Berpihak pada kekuasaan, berkuasa dan menjadi penguasa, satu-satunya cara memperjuangkan kebenaran.

Saat ini, ia berada di pusat kekuasaan. Tak hanya segenggam, namun bisa menentukan hitam dan putih masa depan. Tak cuma satu orang, tapi banyak orang. Namun kini ia telah berusia senja.
Setiap malam, ia mengalami pergulatan batin yang menggerogoti waktu tidur. Berfikir dan terus berfikir. Mencari dan terus mencari. Kepada siapa kekuasaan itu akan diserahkan.
Hadir kekhawatiran, jika kekuasaan itu diserahkan pada orang yang salah. Kisah masa lalu yang dialami orangtua serta keluarganya, akan terulang.
Tercipta kecemasan, menyaksikan kebenaran yang diperjuangkan dengan kekuasaan yang ia miliki, tanpa mampu dicegah, menjadi alat pembenaran bagi orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang berlindung dengan kekuasaan yang ia miliki.
Sesekali terdengar cerita, jika penjaga pintu di depan rumah lebih ditakuti dan disegani. Bukan karena keterampilan bela diri yang dimiliki atau sosok sangar dan tubuh besar.
Penjaga pintu itu memiliki posisi yang sangat penting. Mampu mengatur siapa yang berhak dan kapan serta berapa lama waktu untuk bisa berjumpa dengannya. Ia terpaksa membiarkan cerita itu, karena banyak hal besar yang harus dipikirkan.
Ia tak lagi memiliki banyak waktu untuk memutuskan. Siapa sosok yang tepat untuk mengambil alih kekuasaan yang puluhan tahun dipertahankan.
Sesungguhnya, tak hanya untuk sekedar mengambil alih kekuasaan. Tapi juga untuk menjaga harta benda yang dimiliki serta menjamin keselamatannya, dari lawan yang tampak dan tak tampak ketika ia berkuasa.
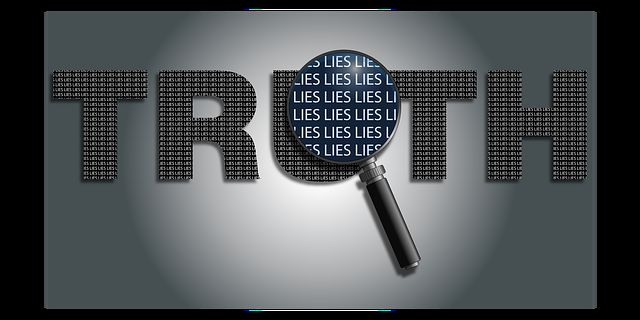
Lelaki itu, tiba-tiba merindukan anaknya. Menjadi ingat masih ada anaknya, sebagai generasi ketiga. Namun, ia tahu, anak itu tak pernah sepertinya. Tak pernah berfikir seperti pikirannya. Dia pun tak tahu, bagaimana kemampuan sebenarnya dari anaknya.
Ia menyesali, tak memiliki banyak waktu untuk bercengkrama dengan sang anak. Kecuali menikmati satu dua hari liburan keluarga. Sehingga tak mengenali anaknya.
Sesekali istrinya bercerita. Jika anaknya menyelesaikan pendidikan dengan baik. Memiliki tingkah laku yang baik. Dan sekarang ingin menikah dengan anak gadis yang baik dari keluarga baik-baik.
Ia pun sungkan bertanya setelah menerima jawaban ketus dari istrinya, karena berkali bertanya tentang nama calon menantu. Yang seingatnya, selalu berganti.
Malam ini, ia menikmati sepi. Merenungi kembali tentang kekuasaan dan kebenaran. Mungkinkah bercampur dengan pembenaran-pembenaran, yang tanpa sadar telah ia lakukan sejak dulu.
Saat ini, mungkin waktu yang tepat untuk sebuah diskusi kecil, dari hati ke hati dengan istri atau dengan anaknya sendiri. Sebagai ruang introspeksi dan refleksi diri.
Namun, ia sendiri tak tahu. Ada di mana, istri dan anaknya malam ini.
Curup, 24.07.2020
[ditulis untuk Kompasiana]
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H








