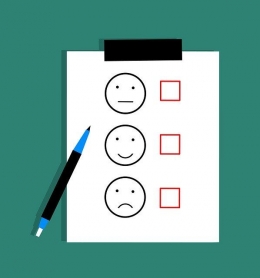Sama dengan poin kedua? Garis tipisnya pada pengaruh lingkungan dan kondisi sosial saat kritikan itu dilontarkan.
Keempat. Kritik sebagai Pendekatan Pragmatis
Yaitu kritik yang dipandang sebagai alat, media atau sarana untuk menyampaikan pesan atau tujuan tertentu. Alur ini, memiliki kecenderungan argumentasi yang bermuatan "menggeser atau bahkah menjatuhkan".
Semisal, yang dikritik bukan konten dan konteks dari kebijakan seseorang. Tapi isi kritikan melebar pada pribadi, orang terdekat bahkan masa lalu seseorang. Pernah membaca kritikan dengan argumentasi bernada seperti ini, kan?

Waktu jaman menulis skripsi dulu, aku diajari pakem teks yang mesti ada pada bab terakhir, "penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif, demi kesempurnaan penelitian ini." Ada yang pernah menulis kalimat seperti ini di skripsi?
Secara sadar dan "seenake dewe", kita mengharapkan kritik itu yang konstruktif (membangun). Walaupun kita tahu dan mengerti, kritik dan saran itu tak pernah ada. Kecuali di ruangan sidang skripsi. Setelah itu, berjilid skripsi terbiar disusun rapi dan berdebu. Hiks...
Nah, Alih-alih melakukan kritik secara adem seperti pakem yang diajarkan (Kukira, malah sejak Sekolah Dasar, tah?) dalam pendidikan moral dan pekerti. Letusan dan lontaran kritikan sekarang, pedas, tegas, cadas dan lebih disukai jika bernada lugas dan keras! Kata cerdas, tertinggal jauh di belakang.
Terus? Jika ternyata, setelah melontar kritik seperti itu, kemudian ternyata keliru? Pilihannya diam, atau mengajukan permintaan maaf dengan diam-diam, tah?
Balik lagi kepada dua baris puisi dari Taufik Ismail yang kukutip di atas. Mungkin, kita tak perlu lagi malu mengaku jadi orang Indonesia. Anggap saja, hal-hal aneh yang terjadi, sebagai kelucuan-kelucuan dalam dinamika berbangsa dan bernegara.
"Tekadang, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai "kelucuan" bangsanya!"