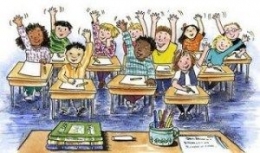"Buku adalah pengusung peradaban. Tanpa buku, sejarah diam. Sastra bungkam, sains lumpuh, pemikiran macet. Buku adalah mesin perubahan, jendela dunia dan mercusuar yang dipancang di samudera waktu" Barbara Tuchman (1989).
"Ayah! Bilang Ustazah, Uni diminta nulis puisi. Biar dibukukan!"
"Hebat!"
"Kakak juga, Yah!"
"Hah?"
Ini petikan percakapan di atas motor dua hari lalu. Saat menjemput kedua anakku pulang sekolah. Uni Tya kelas 6 dan Kakak Rizqy kelas 4 Sekolah Dasar. Si Uni, memang sudah mulai suka merangkai kata. Menulis puisi juga mengisi diary. Sejak kelas 3 SD, sudah 4 buku diary yang kubeli. Lah Kakak? Sependektahuku, boro-boro menulis. Diajak membaca saja susah! Haha..
Tenyata, ada program sekolah, siswa diminta menulis puisi dan diterbitkan berbentuk antologi puisi. Pada siswa dibebankan uang 40 ribu. Tentu saja aku gak punya pilihan jawaban selain setuju, kan? Anakku termotivasi dan bahagia. Gampang amat punya buku, ya? Dalam hati, si Ayah malah mikir dan berujar. Umur segini gak pernah terbitkan buku. Hiks...
Curhat? Galau? Merasa kalah dari anak? Bisa jadi! Aku jadi ingat diskusi belasan tahun lalu. Dari pertemuan "Membaca, Menulis dan Apresiasi Sastra" yang digawangi Horison dan Depdiknas (Sekarang Kementerian Pendidikan Nasional) pada pertengahan agustus 2004 di kawasan puncak Bogor.
Ada beberapa buku diberikan kepada semua peserta, langsung dari pengarangnya. Yang aku ingat, semisal O Amuk Kapak-nya Sutardji Chalzoum Bahri dan Malu Aku Jadi Orang Indonesia karya Taufiq Ismail. Plus beberapa buku non fiksi. Salah satunya Terbitan Universitas Yogyakarta tahun 2003.
Kenapa kegiatan itu dilakukan? Apa kaitannya dengan cerita anakku yang akan ikut dalam antologi puisi tersebut? Aih, Aku ceritakan saja, ya?

Yang Penting Itu Adalah Membaca Karya Sastra dan Mengarang!
"Saya mendapat berita pertama yang tidak sedap dicerna: sebagai bangsa, kita kabarnya rabun membaca dan pincang mengarang. Terdengar pula berita kedua yang lebih tidak enak, yaitu kontastasi bahwa kita sebagai anak bangsa malah sudah buta membaca dan lumpuh mengarang."
Kutipan di atas, kuambil dari buku kecil Pidato Penganugerahan Gelar kehormatan Doctor Honoris Causa di Bidang Pendidikan untuk Taufiq Ismail. Yang disajikan pada Rapat Terbuka Senat Universitas Negeri Yogyakarta 8 februari 2003.
Ada 35 butir persoalan yang diajukan Taufiq Ismail, kenapa fenomena "kabar" seperti tergambar di atas terjadi. Banyak, ya? Dengan jeda waktu 16 tahun sejak buku tersebut terbit. Keresahan dan refleksi Taufiq Ismail itu, Aku sajikan dalam empat ramuan besar, yang kuanggap masih terjadi hingga hari ini . Boleh, ya?
Pertama, merosotnya minat masyarakat membaca karya sastra. Terukur dari sepinya ulasan dan kritik karya sastra atau susutnya mutu karya sastra. juga kurangnya karya sastra dunia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Kedua, jarangnya penghargaan untuk karya sastra dan sastrawan, minimnya sayembara penulisan sastra plus ketersediaan ruang atau rubrik sastra dan apresiasi sastra di media massa.
Ketiga, keterbatasan lingkup ekspresi. Baik tentang penerbitan, pelarangan atau penyitaan karya, minimnya wadah dan pertemuan sastra rutin di daerah, kurang atau bahkan tak ada acara sastra atau pembicaraan tentang sastra di media cetak atau media elektronik.
Keempat, merosotnya wajib baca buku sastra, bimbingan mengarang dan pengajaran sastra di sekolah serta keterlibatan sastrawan dalam penyusunan kurikulum di ranah akademis.
3 poin pertama, bisa saja debatable, ya? Walaupun insidentil dan bersifat lokal, diam-diam kegiatan tersebut masih ada. Nah, aku sepakat dan tertarik menulis poin 4 sebagai salah satu penyebab. Sehingga anak bangsa mulai bergerak dari rabun membaca, pincang mengarang, menuju ke arah buta membaca dan lumpuh mengarang. Kok bisa?
Wawancara yang dilakukan Taufiq Ismail tahun 1997 pada 13 kota di 13 negara kepada tamatan SMA atau sederajat. Tentang buku sastra yang wajib dibaca. Hasilnya; Thailand (5 judul), Malaysia dan Singapura (6), Brunai Darussalam (7), Rusia (12), Canada (13) Jepang dan Swiss(15), Jerman (22), Perancis dan Belanda (30) serta AS (32). Dahsyat, kan?
Dalam pidatonya Taufiq Ismail menyajikan fakta. Pada tingkat SMA, Pengajaran Sastra tergusur ke pinggir dalam pelajaran Bahasa Indonesia, perbandingan antara Pengajaran Sastra dan Tata Bahasa pada rasio 10 -20% berbanding 90 -80%! Jika dibandingkan dengan kewajiban membaca karya sastra 25 buku dalam 3 tahun di Algemeene Middelbare School (AMS) masa Hindia Belanda dulu. Kini, terperosok jauh. Sekarang berapa? Aku sukar menjawabnya. Hiks

Mereka mulai membaca karya sastra sejak MULO-AMS dan mayoritas dari mereka memiliki kemampuan tinggi dalam menuliskan fikiran mereka, sebagai panen buah latihan mengarang di sekolah dahulu. Buku dan esai seperti anak sungai, terbit mengalir dari tangan mereka.
Ada 4 empat komponen keterampilan berbahasa, yaitu Menyimak, Berbicara, Membaca, dan Menulis. Yang termaktub dalam pelajaran bahasa Indonesia. Secara normatif, pelajaran sastra diakui memiliki peran penting dalam tujuan pendidikan nasional.
Pertanyaannya, seberapa banyak anak SMA yang masih mengenal buku "Salah Asuhan" karya Abdul Muis? "Di bawah Lindungan Ka'bah" karya Hamka, atau "Siti Nurbaya" dari Marah Rusli. Bukan hanya kisah percintaan, tapi juga konflik sosial bahkan konflik budaya antar bangsa?
Pada masa 36 minggu efektif belajar dalam satu tahun pelajaran, Berapa banyak Siswa kita membaca buku sastra? Yang punya anak masih sekolah, silahkan tanya. Pelajaran Bahasa Indonesia menjadi Kurikulum Nasional yang wajib ada dalam semua tingkatan pendidikan. Namun, mayoritas terjebak pada kajian struktur dan tata bahasa, tah?

"Pengunggulan secara berlebihan pada jurusan eksakta sudah harus ditanggalkan, bahwa peradaban bangsa ditentukan oleh penanaman literasi di sekolah yang dimulai lewat buku sastra." Taufiq Ismail.
Dalam sebuah Workshop Buku Bacaan Sastra, di Wisma Handayani Jakarta tahun 2002. Sapardi Djoko Damono bahkan berpendapat; "Pengetahuan tentang sastra agar dihapus dan tak lagi diajarkan di sekolah. Tapi diganti dengan membaca buku sastra dan mengarang. Kalau mau pengetahuan tentang sastra. Pelajari di perguruan tinggi!"
Idealnya, Pembelajaran sastra melalui bahasa dan budaya memberikan pengetahuan tentang bahasa sekaligus mengenal budaya bangsa. Sastra menjadi media yang dapat dimanfaatkan dalam mengenalkan budaya bangsa melalui bahasa tulis. Belajar sastra, bahasa dan budaya membangun cara berpikir yang lebih kritis terhadap lingkungan sekitar dan mampu bersosialisasi.
Sastra menjadi alat perekam berbagai sejarah yang dapat menggambarkan berbagai peristiwa yang dibangun oleh pengarang dengan bentuk cerita. Sastra adalah cerminan masyarakat yang digambarkan oleh pengarang dengan menanbahkan imajinasi. Sastra yang berupa imajinasi sekalipun pengarang tidak sepenuhnya sadar bahwa memasukan data yang menyangkut keadaan sosial.
Fenomena mutakhir yang menunjukkan gejala kemerosotan moral dan kenakalan remaja/siswa. Padahal dalam idealnya, karya sastra dapat memberikan pengertian yang dalam tentang manusia.
Bagaimana caranya? Ada 6 paradigma baru yang ditawarkan Taufiq Ismail dalam penyajian sastra di sekolah.
- Siswa dibimbing memasuki sastra secara asyik, nikmat dan gembira. Bukan menyampaikan pengetahuan sastra, tapi membuat asyik siswa membaca sastra dan membicarakan karya itu bersama-sama.
- Siswa membaca langsung karya sastra. Bukan ringkasan atau ikhtisar. Dan buku-buku yang ada di dalam kurikulum tersedia di perpustakaan sekolah.
- Adanya Kelas mengarang yang menyenangkan di sekolah untuk siswa dan guru.
- Menghargai ragam tafsir saat membicarakan dan membahas tentang karya sastra.
- Tata bahasa tak lagi diberikan secara teoritis. Namun di check dan dievaluasi saat siswa menggunakannya dalam karangan siswa.
- Pengajaran sastra sebaiknya menyemai dan merefleksikan nilai-nilai positif dari realitas kehidupan di sekitar siswa.
Jadi, Kukira ada baiknya setiap anak kembali didekatkan dengan karya sastra. Jika pun di sekolah masih pada kondisi minimalis. Tak ada salahnya usaha mandiri, tah? Jika masih sepakat, bahwa sastra itu adalah pelembut jiwa. Ahaaay...
Demikianlah, Hayuk salaman!
Curup, 24.08.2019
zaldychan
[ditulis untuk Kompasiana]
Taman Baca :
Agar Anak Bangsa Tak Rabun Mambaca tak pincang mengarang, Taufiq Ismail, UNY, 2003.
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ELIC/article/view/1230
http://jurnal.upi.edu/file/Hari_Sunaryo.pdf
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H