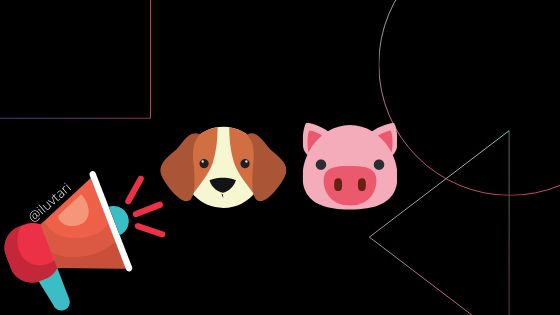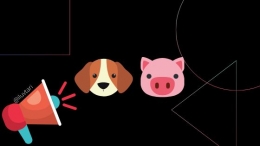Memilih Apa Adanya
Sejak anak-anak belum bisa bicara, setiap ketemu hewan, kuajari mereka nama-nama hewan tersebut. Bukan bunyinya. Itu kucing, itu anjing. Bukan meong dan guguk.
Enak kalau ketemunya kucing dan ayam, bisa ditiru. Kalau lihat buaya di kebun binatang? Masak aku harus bilang, "Hai cewek!"
Dengan mengubah nama hewan yang dianggap lebih halus, sebenarnya kita justru mengaburkan maksud perubahan nama itu. Apa bedanya orang memaki dengan menyebut anjing dengan coro (kecoak)? Sama-sama memaki kan.
Memangnya kecoak lebih sopan dari anjing?
Coba kita pakai kata kampret. Orang yang mendengar mungkin tersinggung, padahal kampret hanyalah kelelawar pemakan buah. Sekali lagi, memakinya yang salah. Bukan hewan/benda yang dipakai memaki.
Aku meyakini, menjelaskan sesuatu kepada anak-anak dengan lebih sederhana, membuat mereka masih punya ruang untuk hal lain yang memang rumit.
Seperti new normal. Ketika kata anjing dianggap kasar, orang mengubahnya menjadi anjir, anjay, ada pula anying. Alhasil lama kelamaan mengumpat dengan kata-kata tersebut dianggap biasa. Padahal tetap saja umpatan/makian.
Perbuatannya tetap dilakukan, padahal jelas salahnya. Seperti koruptor, korupsinya jalan terus, hanya ditambal-tambal dengan diksi dan narasi yang lebih ramah di telinga. Lebih kurang begitu.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H