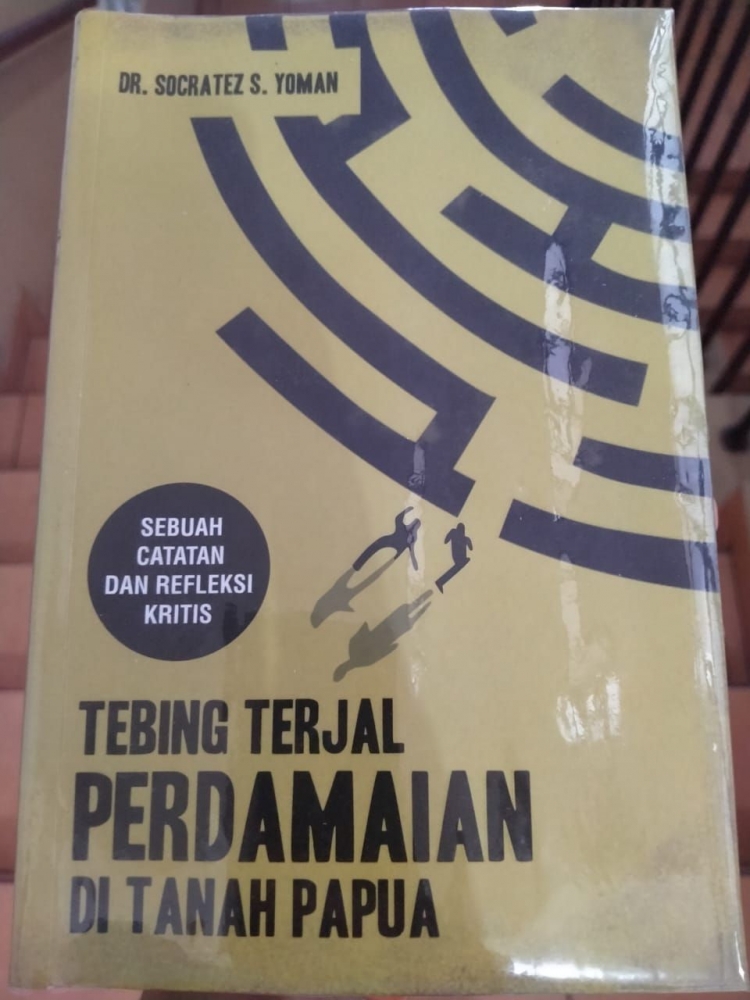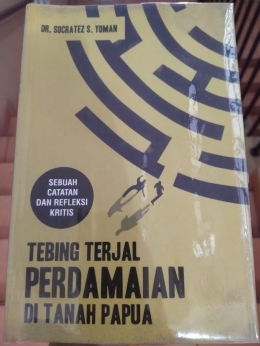Bertahun-tahun mengenyam bangku sekolah, baru aku tahu kenapa daratan timur Indonesia dipisah menjadi Papua Barat dan Papua New Guinea. Tak ada guru yang memberi tahu. Tak cukup nyali buat bertanya. Sejak abad ke-19 Inggris dan Belanda membelah Pulau Guinea menjadi dua menjadi New Guinea Barat dan Timur (Perjanjian London 1814). Garis itu tak berubah meski lebih dari dua abad berlalu.
Oleh satu rekanku, aku diperkenalkan kepada Dr. Socratez S. Yoman, nabi zaman now yang menyuarakan kesetaraan harkat dan martabat manusia di tanah Papua. Bagiku, beliau adalah pendeta, pemimpin, pelindung, pembela rakyat Papua yang terjajah di tanah sendiri. Pak Socratez lantang melawan ketidakadilan, namun mengayomi semua orang, termasuk yang berbeda etnis, keyakinan, maupun prinsip. Citra yang berbeda dengan pemimpin yang merasa kaya dan punya power.
Dalam kepicikanku, aku menganggap Papua dalam 5 tahun terakhir ini jauh lebih baik. Pertama kali dalam sejarah Indonesia Presiden Jokowi membangun jalan aspal membelah pegunungan dan hutan Papua. Itu suatu kemajuan besar!
Tapi, apa jadinya jika pembangunan aspal tidak dibutuhkan orang Papua?
Upaya mewujudkan perdamaian Papua masih menatap banyak persoalan, jika tidak dikatakan hampir mustahil diwujudkan. "Perdamaian", "kesejahteraan", "keadilan", dan "peradaban" merupakan akar persoalan di Papua yang belum dituntaskan hingga kini. (Dr. Adriana Elisabeth)
Tak hanya eksternal, tantangan yang dihadapi orang Papua juga berasal dari dalam. Banyak investor masuk ke Papua dengan iming-iming uang. Masayarakat adat terpecah menjadi kelompok yang mau menerima uang, dengan yang menolak demi kepentingan tanahnya. (Dr. Budi Hernawan)
Inikah citra manusia merdeka?
Sepenggal Fakta tentang OPM
Pada hakekatnya, orang Papua adalah rakyat yang berdaulat. OPM (Operasi Papua Merdeka) muncul ketika Papua "dipaksa" NKRI tahun 1961. OPM menjadi salah satu wadah bagi orang-orang Papua untuk mengembalikan jati diri Papua (jalur militer). Sedangkan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengambil diplomasi politik. Sangat kejam jika media, pemerintah dan kelompok tertentu melabeli Papua dengan "separatis", "KKB", "makar", dll.
Pak Socrates merekam beberapa kekerasan dan pembunuhan yang kesemuanya tidak memberikan sanksi bagi pelaku. Di manakah keadilan di negeri ini?
- 2003, di Kuyawagi dilakukan operasi militer, 10 orang anggota jemaat Gereja Baptis tertembak dan meninggal dunia
- 5 November 2003, sembilan pemuda ditembak aparat keamanan di kampung Yeleka, Kabupaten Jayawijaya, karena mencuri senjata
- 16 Agustus 2004, di Tingginambut, Puncak Jaya, pendeta Elisa Tabuni tewas, dibunuh anggota OPM (Namun Pak Socratez punya bukti, pembunuh adalah anggota Kopassus)
- 6 Februari 2008, seorang warga sipil ditembak anggota Batalyon 756
- 8 Desember 2014, empat siswa di Paniai ditembak, meninggal
- 19 Maret 2015, aktivis KNPB menggalang dana kemanusiaan untuk bencana alam di Vanuatu. Aparat keamanan tidak terima ada kerumunan, membubarkan dengan tembakan, tiga orang luka-luka, satu mati di tempat
- 19-23 Maret 2015, aparat gabungan tentara dan polisi melakukan operasi pengejaran aktivis KNPB, salah satu aktivis ditangkap, diadili, dijatuhi kurungan sebelas bulan penjara dengan tuduhan penghasutan dan makar
- Maret 2015, seorang pemuda menemukan cincin anggota intel, berusaha mengembalikan, namun ditangkap, diadili, ditahan dan baru dibebaskan Januari 2016 karena tak ada bukti
- 5 April 2016, gabungan aparat keamanan membubarkan acara doa ibadah KNPB di Timika
- 1 Desember 2015, empat orang di Serui ditembak mati, karena dituduh anggota OPM
- 16 Desember 2009, Kelly Kwalik dieksekusi oleh Detasemen Khusus 88
Bandingkan dengan, misalnya, kasus terbakarnya kios yang dijadikan Mushola di Tolikara (17 Juli 2015) menimbulkan tanggapan serentak pemerintah. Mulai presiden, Panglima TNI sampai Menteri Sosial. Tambahkan, sebelas orang menjadi korban, satu tewas, sepuluh lainnya luka-luka. Adakah perhatian pemerintah kepada korban? TIDAK.
KOMNAS HAM melaporkan dalam satu tahun kepemimpinan Jokowi, 700 kasus pelanggaran HAM di Papua seperti penangkapan, penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan. Dan, dari ratusan itu, tak satu pun tersentuh hukum!
Hendaknya pembaca berpikiran terbuka, tidak menilai tulisan ini dengan sekat sempit etnis atau agama. Lebih luas, ini tentang kemanusiaan.
Akibat dari pelanggaran sejak 2003 itu, kegiatan sekolah banyak terhenti. Guru-guru pergi karena trauma dan takut. Masa depan anak-anak pupus. Publik tentu tak lupa pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya bulan Agustus 2019 yang memicu keributan di banyak pihak. Tindak diskriminasi ini langgeng di negeri yang hampir 75 tahun merdeka.
Banyak pihak di Papua getol menurunkan Pak Socratez, bahkan tidak mengakui kepemimpinan beliau sebagai Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua. Salah satunya Dandim (Komandan Distrik Militer) Wamena. Beberapa pendeta, yang harusnya turut berjuang, bungkam atas nasib rakyat Papua. Pak Socratez yang jelas melawan kebatilan pemerintah menjadi ancaman. Lebih parah, semua pelanggaran HAM tersebut disahkan dengan alasan keamanan dan ketertiban nasional.
Ancaman pembunuhan
Sekelompok orang membuat siasat untuk membunuh Pak Socratez. Tiga orang di-setting memecahkan kaca gedung Sekolah Tinggi Theologi Baptis Papua, Kotaraja, Papua. Keributan terjadi. Situasi kacau. Tiga orang polisi melepas tembakan ke udara. Dalam kekacauan ini Pak Socratez diminta datang untuk menenangkan situasi. Diduga tiga polisi ini disiapkan untuk menembaknya. Tuhan menolong. Seorang perempuan yang mendengar rencana pembunuhan ini berlari dan memeluk Pak Socratez. Beliau diminta segera meninggalkan kampus.
Pencobaan pembunuhan kembali terjadi pada 16 Maret 2006. Pak Socratez berada di tengah kerumunan mahasiswa Universitas Cendrawasih. Beliau datang untuk menenangkan mahasiswa agar membuka jalan yang diblokir. Tiba-tiba kakaknya menelpon. Ia mendengar pembicaraan intel yang mencari cara untuk menembaknya. Pak Socratez segera keluar dari kelompok kerumunan menuju ke Sentani, Jayapura. Telepon selulernya berbunyi, pesan dari seorang intel yang bertugas di Polsek Abepura. Ia diminta kembali untuk memberikan arahan kepada massa. Menolak kembali, mobilnya dihancurkan anggota gabungan brimob dan tentara.
Ancaman lainnya terjadi di Makki, Lanny Jaya. Pada 20-22 November 2006 dilakukan pertemuan dengan gembala-gembala Baptis dengan agenda membahas sejarah gereja Baptis di Tanah Papua. Tiba-tiba sepasukan tentara dan polisi mendatangi lokasi. Mereka diperintahkan menangkap Pak Socratez atas laporan pertemuan tersebut membahas sejarah Papua Merdeka. Dengan sabar, Pak Socratez menjelaskan bahwa mereka memang membicarakan sejarah, tapi sejarah gereja-gereja Papua Barat, bukan sejarah Papua Merdeka. Ditunjukkannya spanduk di depan gereja dan di dalam gedung pertemuan.
Percakapan ditutup dengan makan siang bersama seluruh anggota tentara dan polisi. Antara malu dengan laporan palsu (hoaks) atau kecewa pulang dengan tangan hampa.
Penelitian LIPI
Para peneliti Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) telah melakukan penelitian selama 2004-2008 terkait akar-akar konflik dan persoalan antara Jakarta dan Papua. Hasilnya dibukukan dalam tulisan Papua Road Map.
Akar konflik yang terungkap adalah status politik, pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan, dan marjinalisasi penduduk asli Papua. Sayangnya, pemerintah tidak mencerna dengan baik persoalan Papua. Pemerintah justru keliru melakukan pendekatan dan mengambil kebijakan. Pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur tidak menjawab persoalan mendasar orang Papua.
Baca juga: Papua Bukan Tanah Kosong (George Saa)
Pemerintah Indonesia semestinya tahu bahwa satu-satunya provinsi di Indonesia yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia melalui mekanisme PBB adalah Privinsi Papua (Papua Barat). Sehingga persoalan Papua terkait dengan masyarakat internasional, bukan saja status politik dan sejarahnya, tetapi masalah kemanusiaan, keadilan dan perdamaian.
Merindukan 'Ndumma'
Dalam masyarakat adat tentu ada perselisihan yang bisa berujung perang. Yang namanya perang, kedua belah pihak dirugikan. Bedanya, orang Papua berperang dengan cara beradab, mengejar nilai-nilai kedamaian. Suku Lani, contohnya.
Apabila ada musuh datang untuk menyerang salah satu kelompok suku di kalangan suku Lani sendiri, kelompok yang diserang ini memotong daun pisang dan diletakkan daun ubi di atasnya dan ditunjukkan kepada kelompok penyerang. Potongan daun pisang dan daun ubi inilah simbol perdamaian. Ketika penyerang datang, walaupun dengan kekuatan besar dan penuh kemarahan, melihat simbol itu mereka sepakat menerima perdamaian. Mereka hidup kembali berdampingan.
Ketika telah sepakat hidup berdamai, pihak yang diserang harus memberikan beberapa ekor babi. (Babi merupakan hewan ternak yang banyak dipelihara orang Papua karena menjadi bagian upaya perdamaian, selain dari nilai ekonominya tinggi) Nilai-nilai luhur yang dimiliki orang Papua sejak dulu itu, kini justru direduksi oleh nilai-nilai yang dibawa oleh negara.
Dalam kehidupan suku Lani, ada sosok pemimpin yang dikenal sebagai 'Ndumma'. Ialah gelar yang diberikan kepada sosok pembawa damai, yang memberikan ketenangan, kesejukan, dan kebaikan bagi semua orang.
Di era globalisasi, masih adakah sosok Ndumma di bumi Papua?
Kini, nilai-nilai perdamaian di kalangan orang Lani telah hancur saat terjadi konflik dan kekerasan yang dilakukan pemerintah dan aparat keamanan. Kehadiran mereka justru merusak sosok-sosok pembawa perdamaian. Sosok Ndumma ini sangat dirindukan saat terjadi konflik. Orang Papua harus menempuh tebing terjal untuk mencapai perdamaian.
Salatiga, Maret 2020
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H