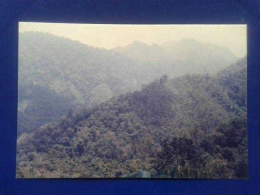(Gerilya 1949 dan pengalaman dimasa itu- artikel terdahulu).
Jangankan listrik, untuk lampu teplok saja tidak punya sebab, bagaimana mau pakai lampu teplok kalau minyak tanah saja tidak ada orang yang menjualnya di hutan itu. Tinggal di hutan itu sudah pasti serba primitifsemuanya.
Lalu, sebagai penggantinya terpaksa digunakan suluhyang terbuat dari getah rambung yang memang di beberapa tempat banyak tumbuh pohon karet yang ditanam warga setempat.
Getah rambung atau getah karet itu, selagi masih cair, dimasukkan ke dalam bambu yang ukurannya tidak terlalu besar. Lalu, bambu yang berisi cairan getah karet tersebut dijemur di panas matahari atau dikeringkan di para-para yag ada di atas tungku dapur. Seminggu saja getah karet tadi sudah membeku dan setelah bambunya dibuang jadilah lenteragetah rambung yang siap pakai.
Akan tetapi setelah bangun tidur dipagi hari kita harus cepat-cepat pergi ke sumur atau ke sungai untuk cuci muka sebab, muka kita hitam terkena jelagalampu getah karet tadi. Mandi di pagi hari tidak sanggup sebab, airnya terasa dingin. Tengah harilah baru berani mandi karena airnya sudah mulai terasa hangat.
Teh tidak ada dimasa itu. Kalau kopi masih bisa didapatkan asalkan saja mau memetik biji-biji kopi yang mudah kita jumpai di kebun-kebun kopi milik warga. Pemiliknya rela biji-biji kopinya diambil. Menggoreng dan menumbuknya menjadi pekerjaan rutin.
Kalau masa kini kopi luwak sudah populermaka dahulu hampir setiap hari kami minum kopi luwak itu sebab, di kebun-kebun kopi itu berserakan kotoran luwak tersebut yang banyak mengandung biji kopi. Tinggal kita membersihkannya serta memasaknya dan selanjutnya menumbuknya di dalam lesung. Jadi, deh !
Persoalannya sekarang bagaimana meminum kopi tersebut sedangkan gula pasir tidak ada pada masa itu. Sebagai gantinya digunakanlah gula arenyang memang pohon aren banyak tumbuh disekitar kampung-kampung itu.
Gula aren itu diiris halus-halus lalu, dimasukkan kedalam air kopi. Atau, gula aren itu dipatahkan dengan gigi lalu dikunyah-kunyah dan setelah halus barulah air kopinya diminum. Nikmatnya luar biasa dan cara minum kopi seperti itu kami sebut minum kopi ala Sipiongot, suatu nama kampung yang kini menjadi ibu kota Kec. Dolok.
Jika ingin minum teh kita tinggal memetik daun kopi yang belum tua benar lalu, daun kopi tadi di salai di atas para-para yang ada di dapur beberapa hari lamanya. Setelah itu daun kopi tersebut diseduh dengan air panas barulah diminum dengan gula aren.
Sabun cuci jangan harap ada di kampung-kampung itu dan kalau mau mencuci terpaksalah kita memakai daun serai atau daun alang-alang sebagai pengganti sabun. Pakaian bersih juga dibuatnya karena daun-daun itu mengandung getah.
Ikan ? Tinggal mancing saja di sungai-sungai dan sekali-sekali di Sei Bilah memancing ikan jurung. Ingin telur ayam ? Tinggal minta saja pada warga setempat sebab, mereka beternak ayam juga tetapi tak banyak karena ayamnya sering dimakan musang.
Ingin makan daging ? Daging sapi sulit didapat, yang banyak kerbau tetapi jarang sekali hewan itu disembelih karena kerbau itu andalan warga mengerjakan sawah. Sebagai penggantinya sekali-sekali berburu rusa ke hutan-hutan atau berburu ayam hutan.
Berburu rusa harus malam hari sebab, siang hari hewan itu bersembunyi. Memburu rusa dengan peluru tajam tetapi harus hati-hati karena selalu berebutan dengan si raja hutan, harimau. Manusia selalu tertipu dengan trik-trik jitu si harimau.
Begitulah sekelumit pengalaman sewaktu bergerilya di hutan-hutan hulu Sei. Bilah yang hulunya berasal dari Garoga yang berada di Kab. Tapanuli Utara. Tidak terlalu lama mengembara di hutan-hutan itu tetapi selama sepuluh bulan itu menyimpan segudang pengalaman yang sampai kini tak terlupakan.
Sekembali dari Sipiongotseluruh keluarga saya kembali lagi ke Sunutsetelah singgah sebentar di Pasar Simundoldan Padang Matinggi, dua kampung yang sebelumnya sudah diceritakan.
Rencana dari Sunutakan menuju ke Kampung Sibio-bio, suatu kampung yang cukup besar dan mungkin di sana bisa dijumpai seorang "dukun beranak". Akan tetapi perjalanan ke Sibio-bioini bukanlah mudah karena perjalanannya mendaki.
Dari Sunut kita menyeberang Sei. Bilah agar kita bisa sampai di Kampung Sipahonek, suatu kampung yang hanya bersebarangan dengan Sunut. Di kampung ini beristirahat beberapa hari lamanya karena harus mengumpulkan tenaga untuk perjalanan yang medannya cukup berat.
Dalam perjalanan dari Sipahonek menuju Kampung Gunting Bange jalannya masih mendatar, artinya tidak banyak mengalami kesulitan. Tetapi, sesudah Gunting Bange dan menuju Kampung Aek Pisang barulah disitu kita menempuh medan yang berat.
Karena dalam perjalanan ini kita harus mendaki Gunung Siatubang namanya, yang kemiringannya sampai 45 derjat, melalui jalan setapak yang agak licin, bisa saja kita jatuh ke jurang kalau tak hati-hati.

Tetapi, kalau menurun tidak terlalu berat namun, harus juga berhati-hati karena jalan agak licin. Jika slip, terlebih lagi di musim hujan, bisa saja maut menanti kita di dalam jurang. Itulah yang paling ditakuti pada saat mendaki dan menuruni gunung tersebut.

Saya dan adik-adik saya berada dibelakangnya menjaga jangan sampai dia tergelincir, sedangkan ayah saya menarik tangannya untuk mendaki. Kakak-kakak saya sibuk pula mengangkat barang bawaan yang juga dibantu warga Gunting Bange yang merasa iba melihat keadaan ibu saya seperti itu.
Belum sempat dua puluh meter berjalan ibu saya selalu minta istirahat karena dalam mendaki itu nafasnya sudah tersengal-sengal. Dalam pendakian tersebut entah berapa kali dia minta istirahat karena kecapekan dan perlu mengatur pernafasan.
Terasa berat baginya mendaki dengan kondisitubuhnya yang seperti itu. Berjalan saja sudah payah apalagi mendaki. Kandungannya itulah yang membuat dia harus begitu, kelelahan terasa sekali bagi dirinya. Disitu saya menangis melihat keadaan ibu saya seperti itu.
Begitulah penderitaan yang ditanggung didalam mempertahankan pemerintahan RI yang dilaksanakan berpindah-pindah. Pemerintahan mobileadalah konsekuensidari perjuangan Republik didalam mempertahankan eksistensinya.

Astaghfirullah ! Tega-teganya ia mengatakan demikian. Jangankan lima lemari, satu lemari pakaian saja pun tak sanggup kami membawanya karena harus melalui jalan setapak yang medannya cukup berat. Terkadang mendaki, terkadang menyeberang sungai, terkadang melalui jalan yang berlubang dan berlumpur yang ada lintahnya.
Mengapa tega sekali memfitnah kami yang sudah rela berkorban demi Republik ini. Banyak saksi, apakah kami sekeluarga memang ada membawa pakaian sebanyak itu dan bagaimana pula mengangkutnya sewaktu mendaki Gunung Siatubang.
Kami membawa pakaian secukupnya dan dibungkus dengan kain sarung dan kain panjang lalu, dijunjung diatas kepala. Alat-alat dapur seperlunya saja dan dimasukkan kedalam karung, juga dijunjung diatas kepala.
Mentang-mentang tinggal di Medan, yang selalu dibawah ketiak Belanda, yang tidak pernah susah, yang selalu beroti-roti, bermentega-mentega, berkeju-keju. Orang yang seperti itu pula yang memfitnah kami. Tuhan sajalah yang tahu !
Kami di hutan yang hanya bisa berubi-ubi, bertalas-talas, berjagung-jagung, tentu tak segagah orang Medan yang tak pernah capek. Lancar memfitnah, sedangkan kami hanya mampu pasrah menerima kenyataan dan keadaan. Ooiii..., manusia-manusia !
Disitulah nampaknya perbedaan antara orang-orang Republik yang berjuang dengan orang-orang yang menetap di kota-kota pendudukan Belanda sekalipun mengaku dirinya orang Republik.
Orang-orang yang berjuang terus di rimba raya adalah orang yang konsekuen pada Republik sementara, orang-orang yang tinggal di kota-kota yang diduduki Belanda banyak yang berjiwa kompromistissehingga bagi orang-orang yang mengaku dirinya Republik tidak lagi tulenjiwa republiknya. Itu sudah pasti !
Agak sore barulah kami sekeluarga sampai di Kampung Aek Pisang setelah hampir sehari penuh menempuh perjalanan. Yang lama itu ketika mendaki Gunung Siatubang yang ditempuh lebih dari tiga jam karena terlalu banyak istirahat dijalan.
Di Kampung Aek Pisang ini terpaksa istirahat sepuluh hari lamanya karena ibu saya sendiri sudah tidak kuat lagi berjalan untuk menuju Kampung Sibio-bio yang jaraknya tidak jauh lagi.

Disamping itu di kampung ini dihadapannya terbentang lembah yang sangat luas yang memberikan panorama alamyang cukup indah. Di lembah itu nampak dari kejauhan Sei. Bilah yang mengalir berlika-liku melalui hutan-hutan yang ada di lembah itu.
Tak jauh dari Kampung Aek Pisang tersebut terdapat sebuah air terjun yang bernama Siborpa. Air terjun ini bisa dicapai berjalan kaki selama dua jam perjalanan. Alamnya cukup indah dan sampai kini masih perawan. Mungkin air terjun ini bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik (PLTA).
Melihat alamnya yang begitu indah dan situasi di kampung itu begitu tenang rasanya mau saja tinggal disitu selamanya. Alangkah baiknya kalau di lokasiitu dijadikan tempat peristirahatan, atau tempat untuk mencari inspirasibaru bagi para penulis.
Di sebelah selatan dari Kampung Aek Pisang itu terdapat sebuah perbukitan yang tidak tinggi memanjang dari arah timur ke barat. Salah satu bagian dari bukit-bukit itu yang kebetulan tepat sejajar dengan Kampung Aek Pisang terdapat sebuah gua besar.
Konon kabarnya dahulu di gua besar itu pernah bertapaseekor ular raksasa, nagakata orang. Nagaini, kata orang, sangat sakti tetapi tak pernah mengganggu manusia. Hanya peliharaan dia jangan coba-coba diganggu, kontan ada akibatnya. Orang-orang di kampung itu selalu menasehati kita, jangan mengganggu ikan-ikan di sungai yang ada disekitar kampung itu. Nanti bisa berakibat fatal.
(Bersambung).
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H