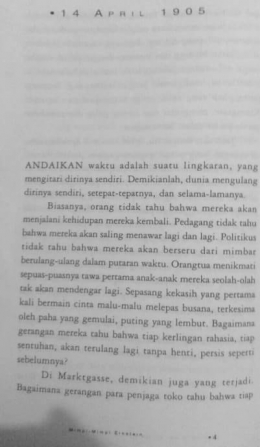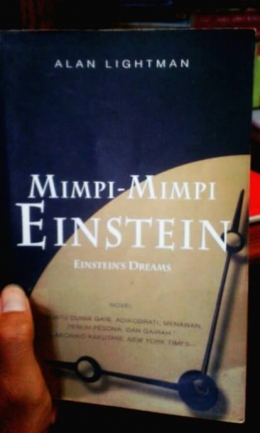JIKA MEMANG HARUS ada sebuah kenelangsaan di lembar terakhir kalender dan esok harus menggantinya dengan kalender hadiah toko sembako langganan dimana kita kasbon, seperti puisi-puisi murahan yang mesti ada frasa ‘senja’, ‘hujan’, dan farsa yang menyedihkan itu, maka itulah ketidakjodohan saya dengan buku Reuni karya Alan Lightman yang diterjemahkan penulis cermelang pemenang Khatulistiwa Literary Award (KLA) 2016, Yusi Avianto Paraenom, dan diterbitkan oleh penerbit asuhannya sendiri, BaNANA—dengan satu dan lain alasan, yang sebetulnya berpangkal pada nihilnya uang akhir tahun, begitulah....
Tampaknya, Reuni ialah buku, yang bila membaca potongan-potongan yang diser oleh Paman Yusi di akun Pesbuknya, sangat menjanjikan sebuah kesenangan. Silakan lihat kulit wajah buku tersebut. Apa yang berkelebatan di kepalamu melihat kulit wajah buku se-tampan itu, selain janji sebuah pengalaman-membaca yang menyenangkan?
Jika Anda masih beranggapan bahwa ‘melihat buku jangan dari cover-nya’, saya akan senang hati mendoakan Anda lekas sembuh dari penyakit kotok ayam dan dapat segera membedakan antara buku ‘asik dan perlu dibaca’ dengan buku yang pantas dijadikan bahan baku pembuat jalan raya.
Memang, tak semua ‘ingin’ lekas terpenuhi, seperti tak semua berahi tersalurkan, itulah mengapa Tuhan memperkenalkan masturbasi, terlebih perihal buku dan bacaan.

“Bagaimana gerangan mereka tahu bahwa tiap kerlingan rahasia, tiap sentuhan, akan terulang lagi tanpa henti, persis sebelumnya?” tulis Lightman. Sialnya, kalimat itu memburu saya tiapkali tergoda dengan kata ‘resolusi’ (mental).
Baiklah. Saya harus berdamai. Saya akan menyambut tahun baru dengan membaca Mimpi-mimpi Einsten, dan berdoa saya akan berjodoh dengan Reuni, kelak tentu saja, dan legowo bila resolusi yang saya susun melingkar bersama waktu.
Apa boleh bikin. Belum rezeki.
*
MOMEN PERTAMA SAYA membaca Mimpi-mimpi Einsten karya Alan Lightman ialah pada sebuah kereta-komuter dari stasiun Bekasi ke Cisauk, Tanggerang. Saya ingat, ketika itu saya membacanya dengan kondisi laiknya situasi transportasi umum negeri ini: berdesakan dan berhimpitan dengan penumpang dalam posisi berdiri, dan sesekali duduk ketika suasana gerbong lengang, dan kembali berdiri bila kiranya ada penumpang lain yang membutuhkan.
Anda tahu, kondisi itu mempengaruhi proses pembacaan saya. Cerita perenungan tentang waktu yang dikisahkan buku tersebut saya resapi dimana realitas di hadapan saya ialah manusia-manusia yang digerakkan oleh waktu mekaniknya—Lightman menjelaskan, waktu mekanik ialah waktu yang ‘kaku’ dan ‘serupa pendulum besi raksasa yang berayun maju-mundur’ (hlm. 16)—saya bisa mengatakan itu karena gerak-gerik mereka seperti diburu entah-oleh-apa, yang khas masyarakat urban, dan itu mengingatkan saya tentang karakteristik masyarakat Indonesia (modern yang masih terikat dengan tradisionalitasnya) menurut Saya Sasaki Shiraishi dalam Pahlawan-pahlawan Belia—memangada beberapa orang yang saya lihat mencoba mengalihkannya dengan sibuk pada gawai dan earphone yang menyumpal ke telinganya.
“Setiap orang berjalan sendiri, karena kehidupan masa silam tidak pernah bisa berbagi dengan masa kini. Setiap orang melekat pada satu waktu, melekat sendiri.” tulis Lightman (hlm. 47), dan saya membaca kalimat itu dengan realitas tersebut, dan saya juga bagian dari realitas itu, dan saya menghayatinya.
Saya sampai di Cisauk, dan bergumul dengan teman-teman, apa yang saya hayati tadi lamat-lamat di kepala saya.
Dan saya kembali ke Bekasi keesokan harinya, dan saya memanggil kembali yang lamat-lamat di kepala saya itu. Kini saya menikmati kalimat yang disusun buku itu, sungguh menakjubkan. Penuh kejutan dengan kalimat dan penggambaran yang dibangun. Bercerita tentang Swiss di awal tahun 1900-an dan hasrat seorang intelektual untuk memecah sebuah misteri kehidupan—misteri itu adalah waktu, dan terpendar melalui mimpi-mimpinya yang berkelebatan. Saya terbantun ke dalamnya, meski saya tetap awas terhadap situasi di mana saya membacanya: Jakarta abad ke-21 dan lebih tepatnya di lambung sebuah gerbong kereta-komuter.

Anda tahu, waktu di dalam lambung kereta-komuter ialah waktu yang bergegas ke depan. Mungkin frase ‘Hari esok adalah milik kita’ menggambarkan apa yang saya maksud. Saya tidak yakin. Kondisi tubuh yang lelah membuat sepanjang perjalanan—yang saya selingi dengan lelap karena kantuk—membuat saya kurang fokus dengan kalimat yang disusun mengejutkan, dan luput dengan simpul waktu dalam cerita tersebut.
Hingga, di jam-jam beralihnya tahun 2016 ke 2017, Anda tahu, saya kembali membaca Mimpi-mimpi Einsten—karena saya tidak berjodoh dengan Reuni Alan lightman yang tengah beredar itu.
“[...] jika membaca adalah perjalanan-tanpa-jalan-pulang, maka membaca-ulang sebuah buku yang pernah kita baca sebelumnya adalah sebuah perjalanan atas pengharapan cerita yang lain: seperti seorang flaneur yang berkelana di tempat yang sama pada waktu yang berbeda,” tulis saya tempo hari. “Saya harus katakan bahwa membaca-ulang, bagi saya, adalah sejenis permainan antara ingatan dan kenangan yang kerap melingkupi perjalanan literer saya: antara yang-di dalam buku/teks dan yang-di luar buku/teks.”
Jadi, sebagaimana saya tulis di atas, kondisi pembacaan selalu menentukan pembacaan itu sendiri. Itulah mengapa saya senang membaca-ulang sebuah buku.
Dalam hal Mimpi-mimpi Einsten, saya mencecap satu hal yang luput di pembacaan saya yang pertama. Yakni waktu yang melingkar.
Saya takjub dengan kalimat berikut: “Andaikan waktu adalah soal kualitas, dan bukan kuantitas, seperti cahaya malam yang menaungi pepohonan, saat bulan naik dan menyisiri garis-garis pohon. Waktu hadir, tetapi tidak bisa diukur.” (hlm. 93). Sehingga “Beberapa orang berusaha melakukan kuantifikasi terhadap waktu, demi mengurai waktu, membedah waktu. Mereka berubah menjadi batu.” (hlm. 96).
Olehnya keabadian adalah sebuah lelucon. Anda perlu menimpuk orang yang berujar ingin ‘Hidup seribu tahun lalu’ dengan sepatu boots. Anda tahu, “Tak seorang pun merdeka. Seiring waktu, orang berkeyakinan bahwa satu-satunya jalan agar dapat menempuh kehidupan milik sendiri adalah dengan kematian.” (hlm. 92).

Sial bagi saya, membaca ini di detik-detik pergantian tahun. Takhayal, membikin saya menyeret segala yang sudah saya lakukan selama satu tahun ini. Sebagai sebuah cermin untuk mengetahui diri sendiri sudah di pagan yang mana, dan akan ke pagan yang mana lagi sebagai capaian di tahun berikutnya. Orang-orang menyebut itu resolusi (mental)—Anda pun tahu, tidak sedikit orang yang akhirnya resolusi itu sebagai tisu cebok di akhir tahun nanti. Dan itu wajar saja, memang. Berapa banyak tenggat yang kita buat untuk akhirnya kita langgar juga? Biasa saja...
Yang tidak biasa buat saya ialah tiba-tiba ada yang menabrak saya. Bukan sesuatu-benda atau seseorang, bukan juga hal-hal gaib dan klenik. Tetapi sesuatu rasa yang memaksa saya untuk menuliskan catatan akhir tahun ini. Rasa yang membuat saya getun dan ingin mencium kaki dan mencuci telapak kaki ibu saya. Di titik ini saya senang dengan larik puisi GM di tahun 1971; “Tuhan, kenapa kita bisa bahagia?”
Selamat tahun baru.. semoga 2017 lekas klir apakah bumi itu datar atau persegi panjang… []
Jatikramat, akhir 2016.
*Tyo Prakoso, pembaca dan perajin tulisan. Berkegiatan di @gerakanaksara. Penjual buku yang ‘asik dan perlu dibaca’ di Kedai Buku Mahatma. Buku pertamanya berjudul Bussum dan Cerita-cerita yang Mencandra (2016).
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H