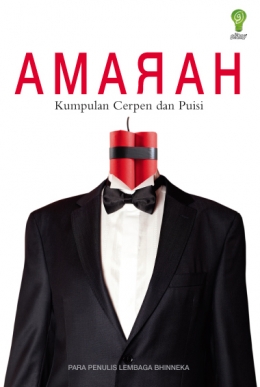[caption id="attachment_244493" align="aligncenter" width="380" caption="AMARAH (gramedia.com)"][/caption]
Oleh: Javid Deo
(Divisi Filsafat L’Nous Institute)
A N T A R A N
Sebuah toko buku, pada barisan buku-buku sastra. Ketika itu saya hendak mencari bacaan untuk sedikit berkontempelasi di waktu senggang. Dan buka demi buka, pencarian saya tertahan pada sebuah kumpulan cerpen dan puisi bersampul ‘manekin’ yang memakai setelan jas rapi dengan bentuk kepala serupa dinamit pada latar warna putih.
“AMARAH,” begitu nada judulnya, ditulis oleh Para Penulis Lembaga Bhinneka.
Bungkusannya saya buka (tentu saja dengan seizin penjaga). Lalu baca demi baca, sebuah cerpen berhasil mengaktifkan sensual pleasure of reading[Barthes] saya untuk terus melakukan pembacaan terhadapnya—tatkala saya menemukan banyak pengaruh filsafat dan bahasa simbol di dalamnya. Dalam situasi macam itu, saya merasa waktu dan ruang (di toko buku) tidak cukup untuk melakukan invenstigasi lebih jauh. Saya harus membawanya pulang. Saya putuskan untuk mengorbankan cokelat dan bunga valentine untuk pacar saya, dengan membeli buku itu.
Ruang kamar. Buku-buku filsafat sudah tersusun di atas meja. Saya duduk menghadap laptop, dan tangan saya menggenggam “AMARAH”.
Cerpen yang membuat saya bertapa di malam kasih-sayang itu adalah karya Haz Algebra, yang berani mengklaim isi ceritanya sebagai “Perjamuan Terindah Sepanjang Masa”. Tentu saja itu hanya klaim. Apalagi ketika Algebra menggunakan “tuhan” (di tulis dengan “t” kecil) sebagai tokoh utamanya. Karena saya yakin pula, bukan buku ini yang telah mendapatkan anugerah International Best Seller itu.
Baiklah. Saya menulis tulisan yang belum tulisan ini bukan sebagai resensi atas buku “AMARAH” yang dahsyat itu. Bukan pula niat saya untuk tujuan promotif—meskipun saya bukan pesulap yang harus berkata kepada Algebra, “Kita belum pernah kenal sebelumnya, kan?”—melainkan sekadar racauan (untuk tidak mengatakan ‘tafsir’) atas pembacaan saya terhadap cerpen Haz Algebra itu. Dan sebagai racauan, tentu saja tulisan ini berpotensi melemahkan muatan dalam cerpen itu, dan sebenarnya tak teramat dibutuhkan serta bisa dilewatkan.
R A C A U A N
Pada mulanya adalah teks. Ah, sudahlah. Saya memulai pembacaan saya pada bagaimana Algebra melakukan proses transisi metafora dari abstrak ke konkrit (the logic of concrete)[Strauss], yakni dari ide/gagasan/konsep ke dalam struktur teks (latar, alur, tokoh, dll) dalam cerpennya.
Sebagai salah satu cerpen yang terangkum dalam buku antologi hasil perlombaan, saya menemukan pada ilustrasi sampul belakang “AMARAH” bahwa ide dasar pembuatan semua karya dalam buku itu ialah amarah terhadap ke-bhinneka-an Indonesia yang tidak lagi tunggal-ika(?)
Dari situ akan muncul variasi perspektif ihwal diskriminasi, marginalisasi, kekerasan atas nama agama, cinta tapi beda dan berbagai ketimpangan-ketimpangan sosial lainnya dalam konteks masyarakat plural di Indonesia.
Algebra, dalam cerpennya tampak mengambil varian kekerasan atas nama agama sebagai ide dasarnya. Dan jika agama berafiliasi dengan Tuhan, dapatkah kita mengatakan bahwa tindak kekerasan atas nama agama tidak lain adalah tindak kekerasan atas nama Tuhan?[Armstrong]
Darinya Algebra menkonkritkan ide itu dengan (mengambil resiko) mempersonifikasi Tuhan sebagai tokoh utamanya. Namun itu sah-sah saja menurut saya, karena bukankah Tuhan telah mempersonifikasi diri-Nya sendiri secara dialogis dalam bahasa manusia (Kitab Suci) tatkala Ia memperkenalkan diri sebagai “Aku”?
Gagasan yang sangat klasik. Tapi untuk lebih menghidupkan gagasan itu, Algebra menciptakan latar dua dunia. Kita sebut saja, dengan meminjam istilah Plato: dunia idea dan dunia fisika; di mana Algebra menceritakan bagaimana kehidupan Tuhan di dunia idea dan bagaimana Tuhan dihidupkan di dunia fisika.
Sekilas tampak kontradiksi memang ketika proses mengkonkritkan ide dengan memakai latar dunia idea pula. Akan tetapi, di sinilah letak keunikannya ketika Algebra mereduksi deskripsi dunia idea Plato dengan narasi a la alam bawah sadar Freud yang sederhana tapi penuh intrik, antara tokoh “tuhan” dengan tokoh lain: “Para Penulis”.
Pada alur, cerita Algebra bermula dari dunia idea, yang ia sebutkan sebagai “Hari Keenam –yang bukan hari keenam kita–”. Alur tersebut terus maju membawa kita membaca alur penciptaan seperti dalam Bible pada Bab Kejadian, tapi dengan perspektif berbeda.
Dan ketika cerita sampai pada “Hari Ketujuh,” di mana cerita semakin menanjak mencapai klimaks, tiba-tiba terjadi patahan alur sebelum anti-klimaks. Algebra dengan cerdik mengejutkan kita dari dunia idea—seolah-olah menyadarkan kita dari mimpi-mimpi bawah sadar—untuk kembali melihat fakta di dunia fisika.
Ia, dengan nada sendu, mengajak kita untuk kembali pada “Hari Pertama,” yang tidak lain, katanya, adalah “–hari pertama kita.” Semacam nostalgia, tapi bukan.
Lalu makna. Seluruh struktur jalinan teks yang kering dan literal dalam cerpen Algebra membentuk semacam sistem tanda, maka tugas saya sebagai pembaca ialah melakukan investigasi terhadap deep structure-nya[Strauss]. Tapi cukupkah dengan mengatakan cerpen itu pada dasarnya hanya bercerita tentang kekerasan atas nama agama, lalu selesai?
Saya pikir tidak. Setiap karya yang berdimensi filsafat memiliki potensi pencerahan yang ingin menerangi pikiran dan menyapa hati para pembacanya. Dan untuk cerpen ini, saya berasumsi bahwa Algebra mencoba merumuskan makna pengalaman yang kerap terlampau pelik dan kompleks untuk dirumuskan—lewat simbol-simbol yang “asal-comot” sana-sini, seolah-olah ingin menyampaikan dengan tidak terus-terang tentang sebuah perspektif “campur tangan tuhan” dalam fenomena tindak kekerasan atas nama agama, bahkan barangkali, melampaui ihwal itu.
Saya berasumsi pula, cerpen ini lahir dari ruang privat yang penuh nuansa kontempelatif, sehingga dibutuhkan active power of reader[Barthes] untuk menggali kembali setiap lapisan-lapisan tak sadar di balik struktur bahasanya, yang melacak jejak makna purba di balik kata-kata dan dengan itu mengubah cara kita berpikir dan merasa.
Tengoklah tatkala Algebra menggambarkan karakter tokoh tuhan sebagai sosok multi-talenta yang “ambisius dan narsis,” lalu dikritik oleh tokoh Para Penulis dengan ungkapan “…terlalu. Huh!”[Rhoma?]
Ada pula istilah “roti dan anggur” yang dikambing-hitamkan sebagai penyebab kematian tuhan. Tapi kemudian Tuhan seolah hidup lagi dan ‘dituduh’ mengambil “daging dan darah” para korban pemboman di rumah-Nya sendiri.
Yang saya tidak habis pikir, kenapa pula tokoh tuhan harus dipertentangkan dengan Para Penulis? Siapakah yang dimaksud dengan Para Penulis itu, para Nabi-kah atau para Malaikat-kah? Tapi mengapa pula Para Penulis digambarkan “dengan setelan jas rapi juga safari”? Apa hubungannya antara berebut tulisan tuhan di dunia idea dengan peristiwa pemboman rumah ibadah di dunia fisika? Jika kedua dunia itu berhubungan, lalu siapa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya kerusakan di dunia fisika, tuhan-kah atau Para Penulis?
Oke. Mari kita coba racaumatiskan sistematiskan segala macam kekacauan ini. Begini: diceritakan pada “Hari Keenam,” tokoh tuhan sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi ‘penulis’ terkenal setelah di hari-hari sebelumnya ia sudah terkenal sebagai ‘pencipta,’ ‘pengatur,’ ‘penginspirasi,’ ‘pecontoh,’ dan ‘penyembuh’(?) Di sinilah kemudian tokoh Para Penulis muncul dengan amarahnya hingga berencana membunuh tuhan.
Pada bagian ini, tuhan digambarkan sebagai tokoh penuh ambisi yang ingin menguasai segalanya, sedangkan Para Penulis digambarkan sebagai pihak yang marah karena merasa terganggu dengan perilaku tuhan yang seenaknya saja itu. Tokoh tuhan semacam sosok totalitarian yang mapan (ia adalah segalanya, segalanya adalah ia), sementara Para Penulis terpahami sebagai “yang-lain,” yang ingin membela eksistensinya.
Pada bagian “Hari Keenam Malam,” pemahaman kita terhadap tokoh-tokoh akan berubah seratus delapan puluh derajat, di mana tuhan digambarkan sebagai sosok sederhana yang “tanpa alas kaki,” sedangkan Para Penulis sebagai sosok yang borjuis, “dengan setelan jas rapi juga safari”.
Jika kita menafsir “jas rapi juga safari” itu sebagai busana yang biasa dipakai oleh mereka yang duduk di pemerintahan (para penguasa), maka barangkali pertentangan tuhan vs Para Penulis sengaja dihadirkan untuk menggambarkan kuasa yang selalu tidak stabil. Bukankah ada istilah bahwa sejarah selalu ditulis oleh penguasa?[Marx]
Kita lewatkan dulu ihwal sejarah, sembari menghadirkannya sebagai historitas dalam teks. Sekarang timbul pertanyaan lagi, jadi di antara tokoh-tokoh itu, siapakah yang sebenarnya ingin mempertahankan eksistensinya? Apakah Para Penulis yang tak ingin ladangnya dikuasai? Ataukah tuhan yang ingin menuliskan sendiri “hikayat tentang dirinya ..,autobiografinya, karya-karyanya, sejarahnya dan segala yang melekat pada dirinya,” karena kecewa terhadap orang pilihannya yang berkhianat?
Tapi malam “Hari” itu, ketika rencana Para Penulis sedang dijalankan, pemahaman kita terhadap kedua tokoh itu kembali dijungkir-balikkan dengan penggambaran sosok tuhan yang sombong (seperti tampak dalam khotbahnya), sedangkan Para Penulis seolah tak sanggup berbuat apa-apa kecuali menunggu tuhan masuk dalam jebakan “racun” mereka.
Meskipun pada akhirnya rencana membunuh tuhan itu berhasil, akan tetapi tuhan tampak menang dari katanya: “Dasar pecundang. Jangan sebut aku tuhan jika aku tak tahu apa yang kalian pikirkan!”
Bahkan kematian tuhan (terlepas dari apa yang membunuhnya: panah, pisau, pistol atau racun) meninggalkan misteri pada secarik kertas yang bertuliskan: Terima kasih untuk roti dan anggur kalian.
Tokoh tuhan mati beberapa saat setelah khotbahnya diinterupsi, tepat di “Hari Ketujuh”. Kemudian adegan terus berlanjut dengan perkelahian di antara Para Penulis yang memperebutkan tulisan tuhan dan berakhir dengan saling bunuh membunuh.
Akan tetapi, ketika cerita tiba di bagian “Hari Pertama,” peristiwa saling bunuh juga terjadi, seolah baru saja dimulai, di mana Tuhan ‘kembali hidup’ dan ‘dituduh’ sebagai biang keladi peristiwa itu: “Tuhan, apa salah kami hingga Kau meminta daging dan darah kami?”
“Hari Keenam-Ketujuh” dan “Hari Pertama” adalah dua dunia yang berbeda—di mana yang satu bersifat universal/transendental sedang yang lain partikular/kasuistik—tapi berhubungan. Ketika di dunia idea Para Penulis marah dan membunuh tuhan, maka di dunia fisika setelahnya, Tuhan seolah marah dan kembali untuk melakukan ‘balas dendam imajiner’. Ketika dunia idea menandai kematian tuhan pada misteri “roti dan anggur,” maka pada dunia fisika kematian ditandai dengan jiwa-jiwa yang berlarian menanggalkan “daging dan darah.”
Dari sini, saya memahami bahwa kejadian dalam dunia idea adalah penyebab tragedi dalam dunia fisika. Sebagai sebab, “Hari Keenam-Ketujuh” menjadi sebuah masa lalu, dan “Hari Pertama” sebagai akibat menjadi masa kini atau masa depan dari masa lalu. Demikian halnya dengan metafora “roti dan anggur” yang bertransisi secara konkrit sebagai “daging dan darah.” Jadi, sebenarnya struktur cerpen Algebra itu membentuk sejarah kausalitas yang berdialektik[Hegel]; dan fenomena di dunia fisika adalah bayangan dari dunia idea[Plato].
Tapi muncul polemik baru ketika ternyata, struktur sejarah dalam cerpen itu tidak berjalan dalam garis lurus, melainkan tumpang-tindih, aforistik dan arbitrer. Cerpen itu tidak sepenuhnya menganut prinsip iluminasi Platonik maupun dialektika sejarah a la Hegelian, melainkan juga sejarah a la Derridian; meskipun “Hari Pertama” merupakan kelanjutan sejarah atau masa depan dari “Hari Keenam-Ketujuh,” tapi bukankah “Hari Pertama” juga merupakan masa lalu dari “Hari Keenam-Ketujuh”?
Derrida berkata, “Masa lalu menjadi the field of trace, sabana yang dipenuhi oleh tapak kaki, yang di dalamnya ketidakhadiran tersusun dalam sebuah jaringan kerja perbedaan dan penundaan (defferance)… Tak ada totalitas yang hadir dalam kekinian.”
Bukankah kekinian dan kesinian yang gelap pun ketika kita membayangkannya, merekonstruksinya, merepresentasikannya, ia dengan tiba-tiba menjadi masa lalu yang lain?
Dalam cerpen Algebra itu, masa lalu juga merupakan ruang, yang sama dengan masa kini maupun masa depan. Karena jika masa lalu bukan sebuah ruang, maka trace (dunia jejak-jejak) tak mungkin ada di dalamnya. Dan semisal jejak-jejak itu tersilapkan, itu berarti ia tidak ada, sebuah ketiadaan, sesuatu yang bukan apa-apa, yang tak berarti.
Itu akan mengakibatkan kefatalan: tokoh tuhan sebagai totalitas atau kepenuhan dari Yang Ada dalam cerita, pusat dari setiap lembar halaman, huruf dan kalimatnya, yang merupakan eksterioritasnya, luluh lantak; tokoh tuhan hanya akan menjadi masa lalu di “Hari Ketujuh”, menguap di kaca jendela dunia idea. Dan sebagai masa lalu, tuhan berada dalam sebuah labirin waktu yang gaib, ia hanya terartikulasikan oleh masa silam dan tertuliskan di dalamnya.
Akan tetapi, tuhan yang terkurung dalam simbol itu menjadi labirin sekaligus membentuk labirin yang di dalamnya termasuk keberadaannya sendiri, sebuah dunia tak bergaris. Dan ia ada, hadir, atau setidaknya ia pernah ada atau hadir meski kemudian terhapus atau tersilap.
Inilah yang menyebabkan meski tokoh tuhan dikatakan “mati” di “Hari Ketujuh,” namun ia (juga-sekaligus) ‘hidup’ di “Hari Pertama”.
Terdapat ‘tepian’ yang genting pada perpindahan alur dari “Hari Ketujuh” ke “Hari Pertama”; alur yang tidak bisa dikatakan maju, tidak bisa pula dibilang mundur.
“…‘Tepi’ bukanlah batas…‘Tepi’ mengandung sesuatu yang sepi, juga menunjukkan keadaan genting sebab siapa pun akan sendirian ketika ada pelbagai sisi yang dihadapi, ketika seseorang tak berada di di satu pusat yang mantap. Bukan saja karena terang dan gelap ada di mana-mana, tapi juga karena kedua-duanya mengandung bahaya.”[Goen: Tepi]
Saya menemukan adanya kemiripan deterministik antara tokoh tuhan dalam cerpen Perjamuan Terindah Sepanjang Masa itu dengan tokoh utama novel Ts’ui Pen dalam Taman Jalan Setapak Bercecabang karya Borges; pada Bab III, diceritakan Sang Tokoh mati, tetapi pada bab selanjutnya ia hidup seperti sedia kala, bukannya bangkit dari kematian, karena ia bahkan tak pernah menutup mata sebelumnya.
Sebagai pecandu Zarathustra, saya menemukan pula adanya pengaruh Nietzsche dalam prosesi pembunuhan tuhan dalam cerpen Algebra. Bedanya, jika Nietzsche secara tegas mengatakan “Tuhan telah mati!”, sedangkan Algebra hanya membunuh Tuhan yang sudah ‘dibonsai’.
“Mereka mengecam berhala. Mereka mengecam doa yang membayangkan Tuhan sebagai…bonsai. Berhala atau bonsai: sesuatu yang memikat justru karena diletakkan di sebuah kotak yang tetap, seakan-akan hidup, tapi sebenarnya hanya Tuhan yang diperkecil oleh manusia, sesembahan yang jauh dari hakikat Dia yang maha-agung.”[Goen: Allah]
Saya tidak pasti. Barangkali lebih jauh Algebra ingin menjelaskan ihwal konsep “tiada tuhan selain Tuhan”[Cak Nur] lewat alur ceritanya. Tetapi saya juga ragu. Jika itu menjadi solusinya, maka konsekuensinya adalah, Algebra telah menghadirkan Tuhan yang demikian harus diterima dengan kebesaran sikap: apakah “Tuhan akan lebih memunculkan kebaikan dari dalam kedurjanaan”[Augustinus] ketimbang mencegah kedurjanaan terjadi?
Saya menangkap semangat lain dari Algebra: Jika Tuhan kembali dibicarakan dalam kekinian “Hari Pertama,” bukan berarti Ia hadir setelah kematian, sebuah nostalgia narsisistik, atau ada setelah berakhir sebagai masa lalu “Hari Ketujuh,” karena keberakhiran itu hanyalah sebuah rekayasa pelupaan (oleh Para Penulis) terhadap Yang Ada dalam cerita.
Kembalinya pembicaraan tentang Tuhan bukanlah bentuk ilusi pengalaman yang penuh bahaya dan menegangkan, atau metafisika dari yang tiada. Melainkan sebuah operasi penjejakan kembali dari Yang Ada Yang Hadir ke Yang Ada Yang Tidak Hadir[Heidegger], dalam kekinian yang terus menerus, now and here[Derrida], dengan jalan menghadirkannya kembali, menampilkannya dari lipatan-lipatan, dan menyuarakannya dari kebisuan dan ketertindasannya dalam kurungan berhala konsep buatan manusia.
Penghadiran ini bukanlah dari ketidakhadiran karena ketiadaan, namun sebuah penyingkapan tabir, pembukaan pintu-pintu dalam labirin, penyalaan seberkas cahaya lilin dalam gelapnya relung kesadaran manusia.
Lebih lagi jika berhadapan dengan hasrat manusiawi yang selalu merindukan titik pusat yang stabil, sebuah jaminan, lewat pemahaman dan kejelasan. Kerinduan yang mengingatkan kembali bahwa dirinya tak lebih dari segumpal darah, mani yang kotor, Adam (tanah), pemenggalan terhadap Latah, Uzzah, Whatan, dan Shanam yang ia bangun dari api kesombongan.
Dengan demikian, alur seperti itu mengandung kritik bahwa proklamasi keberakhiran sejarah dan pembunuhan terhadap Tuhan hanyalah sebuah koar, yang terjadi kemudian adalah tak lebih dari penyangkalan Malin Kundang kepada Ibu-nya.
Stop!
Apakah pembacaan kita sudah selesai? Belum. Sistematika pembacaan yang berdekonstruksi dan sedikit melebar seperti ini ternyata tidak mampu memberi jawaban yang bisa dijadikan sandaran tentang bagaimana korelasi ‘kematian tuhan’ dengan ‘kematian orang-orang di Rumah Tuhan,’ dan seperti apa gerangan “campur tangan tuhan” itu terhadap fenomena sosial yang timpang. Maka saya harus membacanya kembali, kembali membacanya, dan lagi.
Buku demi buku mulai tak beraturan di atas meja. Saya akhirnya menemukan padanan (yang saya rasa cukup untuk mendekati) cerita Algebra dalam keping-keping Caping Kakek Tua Goen: Darah.
Barangkali “tuhan berlumuran darah,” “Para Penulis,” “jas rapi juga safari,” “roti dan anggur,” “daging dan darah,” adalah bentuk-bentuk kritik simbolik Algebra pada sistem yang mengatasnamakan dirinya “deliberative democracy”[Habermas] atau ‘demokrasi rembukan’.
Akan tetapi, di Negara yang mengalami banyak trauma semacam Indonesia, “Demokrasi Habermas (itu) hanya akan tampak seperti sebuah ruang sidang yang bersih dan rapi, jauh dari jalanan yang dihambat lubang dan reruntuhan.”
“...Dengan darah yang tumpah kemarin,” kata Kakek Tua Goen, “bagaimana kita bayangkan arena publik ini sebagai ‘demokrasi rembukan’..?” “...Dengan bekas luka yang masih nyeri, tiap rembukan akan dilihat sebagai sekedar siasat.”
Algebra seolah ingin menekankan “di sini,” bahwa di Negara ini, “konflik bukanlah sesuatu (yang terjadi) di luar proses, bukan (pula) ‘kecelakaan’ (yang serba kebetulan)”, melainkan keputusan dari suatu konsensus yang tidak pernah bulat.
“...Tidakkah kita harus selalu ingat bahwa ada hal-hal yang retak dan runtuh dan darah yang mungkin tumpah, ketika konsensus dibulatkan?”
Bukankah “Politik, dalam arti proses, prosedur, dan prasarana (yang) mengatur kehidupan bersama di sebuah negeri, tak selamanya hanya bersangkutan dengan negosiasi di sekitar ruang dan bahan (“tanah” dan “air”, “roti” dan “anggur”), melainkan juga dengan trauma (“daging” dan “darah”)”?
“…’Darah’ (memang) selalu menerbitkan imaji yang dramatis, apalagi darah yang ‘tumpah’. Kata itu dekat dengan nyawa dan tubuh. ‘Darah’ yang tumpah berasosiasi dengan luka, sengsara, resiko, bahaya, dan sengketa.”
Darah juga adalah keputusan. Dan “Keputusan:…, mengandung kata dasar ‘putus’ : sesuatu yang traumatis…saat manusia memutuskan adalah ‘saat kegilaan’.…Saat itu ‘gila’ karena meloncat ke dalam ketidakpastian. Ia subjek dari keputusannya, tapi juga objek yang dibentuk oleh keputusan itu.”[Goen: Yakin]
Persoalan yang mengganjal kemudian adalah, ketika merujuk pada sabda-sabda Kakek Tua Goen di atas, dan melahirkan pamahaman bahwa demokrasi kita tak terpisah dari yang namanya konspirasi, apakah kemudian fenomena “campur tangan tuhan” atas fakta kekerasan atas nama agama itu, tidak lain hanyalah sebuah alibi?
Memang benar bahwa Algebra bercerita tentang kekerasan atas nama agama, karena itulah yang menjadi ide dasarnya. Akan tetapi, sepanjang pembacaan yang berulang-ulang, saya tidak menemukan Algebra memvonis satu agama pun sebagai pelaku kekerasan, juga tidak mengatakan agama mana yang merupakan korban kekerasan.
Lihatlah tatkala Algebra menuliskan “Rumah Tuhan” yang dibom itu; sepintas barangkali kita sudah curiga bahwa yang dimaksud dengan Rumah Tuhan itu adalah Gereja, apalagi didukung oleh peristiwa itu terjadi pada “Hari Pertama” yang bisa saja ditafsir sebagai hari Minggu, hari di mana sebagaian besar umat Kristen beribadah. Akan tetapi, jika maksudnya seperti itu, benarkah orang-orang ketika beribadah di dalam Gereja, “Ada yang berdiri mengadah, ada yang duduk bersila, dan ada yang bersujud pasrah”?
Saya lalu teringat dengan cerita epiphany tentang: Yakub yang terbangun dan menyadari bahwa tanpa sadar dia telah bermalam di sebuah tempat suci di mana manusia bisa bercakap-cakap dengan tuhan mereka, “Betapa menakjubkan tempat ini! Ini tak lain adalah rumah Tuhan (beth El); inilah pintu gerbang surga.”[Armstrong]
Jadi, barangkali Rumah Tuhan yang dimaksudkan Algebra tidak hanya menunjuk pada Gereja sebagai Beth El (pintu gerbang surga, Bethlehem), tapi juga dalam terminologi Islam disebut Baitullah (Rumah Allah/masjid/tempat bersujud), maupun kuil-kuil Pagan dalam kebudayaan Babilonia yang disebut juga Bab-ili (Gerbang para dewa).
Sehingga dengan pemaknaan seperti itu, konteks Rumah Tuhan barangkali dapat dipertanggungjawabkan dalam hubungannya dengan orang-orang “yang berdiri mengadah, yang duduk bersila, yang bersujud pasrah.” Bahkan jika kata baitullah dan masjid (tempat bersujud) dielaborasi lebih jauh, maka kita akan menemukan keluasan bahwa Algebra tidaklah menunjuk suatu tempat ibadah tertentu, melainkan di mana saja di seluruh permukaan bumi (bumi tempat bersujud).
Demikian halnya dengan tuhan yang menjadi martir perebutan tulisan. Algebra tidak secara spesifik melukiskan konsep tuhan dari sebuah agama, tetapi karakter tuhan Algebra ini adalah perpaduan sedemikian rupa yang “comot-sana-sini” antara karakter tuhan dari berbagai agama dan orang-orang yang diteladani sepanjang masa. Di sana, jika jeli membaca tingkah dan proses dialognya, akan ketemu dengan beragam karakter tuhan mulai dari Kristen, Islam, Yahudi, sampai pada tokoh semacam Nabi Muhammad, (Isa Al Masih) dan Ali bin Abi Thalib.
Oleh karenanya, Algebra ingin mengatakan bahwa kekerasan atas nama agama bisa datang dari mana saja, oleh siapa saja, dengan korban yang beragam pula (tanpa memandang SARA, sekte, mazhab, aliran, dsb). Dan untuk itu, Algebra lebih menyalahkan sistem yang mengatur kehidupan bermasyarakat dalam sebuah Negara. Sistem yang telah membunuh kebenaran, hingga berakibat pada terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial semacam itu. Apakah Algebra sedang berbicara tentang ‘teologi pembebasan’?[Weber, Hannafi]
Lalu bagaimana dengan kata “perjamuan,” “ pengkhianat,” “panah,” “pisau,” “pistol,” “racun,” “tulisan tuhan,” “sastra terbaik sepanjang masa,” “khotbah Jumat,” “penulis senior,” “jiwa-jiwa yang terbang, berlarian dan telanjang”?
Huft…! Cerpen ini ibarat dunia yang telah menjadi sekedar kumpulan huruf-huruf, kata, kalimat; sebuah ruang yang ditengah-tengahnya berdiri cermin-cermin raksasa yang memantulkan masing-masing cermin itu secara tak berhingga, berjejal, hiruk pikuk, semrawut, dan cerai berai. Huruf, kata dan kalimat itu pun adalah bentuk dunia sendiri-sendiri, dimana “The Truth” sengaja diletakkan dalam tanda kurung dan garis silang, sementara saya sudah kelelahan dalam keasyikan menulis dan melantunkan kalimat-kalimat racauan.
Hal yang relatif pasti: begitu banyak paradoks, ambiguitas dan ambivalensi dalam pembacaan kilat terhadap cerpen Algebra itu, karena simbol-simbol yang dihadirkannya saling bersilang-singkarut, berhamburan, dan tak menetap pada satu titik makna.
Simbol demi simbol dalam ruang baca menjadi makna demi makna yang berubah-ubah seiring waktu pembacaan. Dari sini, pantaskah kita menuduh Algebra sebagai cerpenis yang menggunakan intellectual gimmick (tipu muslihat intelektual) yang tidak berisi selain permainan kata-kata?
Seluruh pertanyaan (yang tak terjawab dan tak) tersebut harus diajukan secara berhati-hati, sebab jika tidak, kita akan tergoda untuk menemukan sebuah jawaban, sebuah pharmakon, yang daya sembuhnya sama dengan kekuatan membunuhnya.
Akhirnya saya menyerah, meski pembacaan saya untuk membongkar “campur tangan tuhan” ini belum selesai. Karena pada awalnya, Algebra sudah mengingatkan saya bahwa “tuhan” pun“sedang duduk merenung memikirkan tulisannya yang belum selesai.”
Dan “Entah siapa yang menang, entah siapa yang kalah. Tak tau siapa yang bersedih, dan siapa yang bahagia.” Selalu saja tak ada makna definitif dalam sebuah cerita. Dan barangkali, saya tidak akan pernah memperoleh makna yang sama ketika membaca cerpen ini untuk kedua kalinya. Apalagi jika alasannya tak sederhana: “Bab terakhir telah sobek.”
S I M P U L A N ?
Membaca cerpen Haz Algebra ini seperti bertamasya tak henti-henti dengan kaki pincang di dalam taman jalan setapak bercecabang. Begitu banyak labirin yang harus dilalui, begitu sedikit rambu yang ia berikan. Kita seperti tak akan pernah sampai ke pusat makna dan maksudnya. Atau seperti kata Algebra sendiri dalam sebuah puisi: sebuah perbendaharaan tersembunyi di ujung labirin; ada pintu-pintu tak berujung yang menanti ketersesatan, ada bentangan sarang laba-laba yang terjalin halus namun rumit.
Barangkali banyak yang akan meragukan, banyak yang menyerah, dan banyak yang memalingkan wajah. Banyak pula yang menunda pemaknaan, bahkan banyak yang memuaskan diri lalu tenggelam dalam larutan kesadaran palsu, dan ada pula yang bisa jadi gila karenanya. Itu semua membuat kita tegang, tetapi asyik. Membuat kita minder dalam kebodohan, tetapi harus terus menerus menyelesaikan pemaknaan.
Pola nalar cerpen ini berada di tepian yang genting, yang selalu mondar-mandir di antara penalaran ketat konseptual-filosofis dan penggambaran naratif-imajerial dunia pengalaman, yang ambigu, senantiasa mengalir (flow logic) dan tak pernah sepenuhnya terumuskan. Dan Algebra mampu meramu kedalaman konseptual abstrak-nya dengan peristiwa-peristiwa kecil konkrit yang terus bermunculan; juga mampu memberi umpan pemikiran sekaligus menyentuh imaji dan perasaan.
Cerpen ini—meminjam kalimat Mas Bambang kepada Kakek Tua Goen—adalah kemanusiaan yang resah, yang terus menerus memperkarakan dirinya, yang terus menerus hendak melihat kompleksitas kehidupan, di hadapan kecamuk politik, agama, sains, budaya, atau apa pun juga; suara manusia yang kodratnya serba tak pasti, yang setiap kali berani menafsir ulang sejarahnya serta merelatifkan pemikirannya sendiri, terutama di saat “ajaran lama megap-megap tertimbun ribuan kata dan makna yang bergerak cepat, berubah cepat.”[Goen: Pengebom]
Dan barangkali klaim Algebra tak sepenuhnya salah, karena dalam cerpen ini, peristiwa-peristiwa konkrit lantas berfungsi sebagai lubang kecil untuk setiap kali mengintip persoalan-persoalan besar kemanusiaan sepanjang peradaban, persoalan yang kerap berulang, dan barangkali memang kekal sebagai Perjamuan Terindah Sepanjang Masa(?)
---JaDe---
Jakarta, 13022013/20022013
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

![[CERPEN] Umar Kolam sang Pendobrak Kejanggalan](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2024/11/07/01-672cb99b34777c0b9924b3e2.jpg?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)