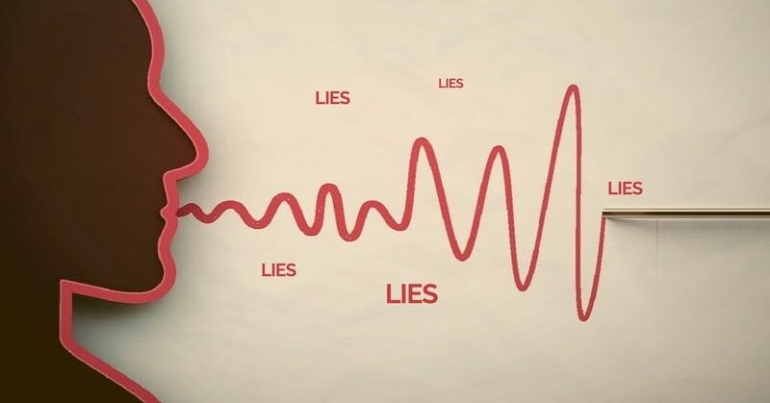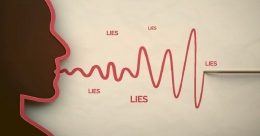"Berbohong itu hak, tapi menyiarkannya pada publik, kepada lebih dari satu orang, dapat dipidana," jawabku.
Anak sulungku bertanya, mengapa orang cuma berbohong saja kok bisa ditangkap Polisi? Kebetulan berita tentang penangkapan aktivis Ratna Sarumpaet sedang menghiasi layar kaca.
Logika anakku itu bisa jadi mewakili logika umum. Bahwa, adalah hal lazim berbohong dalam kehidupan sosial; masa iya boleh ditangkap Polisi.
Misalnya, berbohong sudah mandi (padahal belum), lagi senang (padahal sedih), tidak kentut (padahal kentut), mengaku hijrah (padahal lari dari proses hukum), dan seterusnya.
Kalau dipikir-pikir, memang iya, sih, negara seperti kurang kerjaan mengurusi orang berbohong apa tidak. Tapi itulah hukum, pada intinya agar masyarakat tertib. Hukum bisa bertindak bila suatu kebohongan merugikan orang lain atau merusak tertib sosial.
"Berarti, kalau aku menceritakan kepada teman-temanku bahwa aku sudah mandi, padahal belum, aku bisa ditangkap polisi dong, begitu ya pa?"
"Tentu tidak, karena tak merugikan orang lain atau berakibat keonaran di masyarakat."
Tafsirnya, secara subjektif, memang diserahkan ke aparat kepolisian. Tapi secara objektif dapat diuji melalui forum pengadilan. Ratna Sarumpaet, misalnya, dapat menggugat praperadilan untuk menguji langkah projustitia aparat penyidik kepolisian apakah sudah benar atau tidak.
Hoaks pada dasarnya merupakan kebohongan yang disebarluaskan. Tapi bukan kebohongan biasa, melainkan yang berdampak sosial, politik, atau ekonomi. Menyebarkan hoaks soal gempa jelas meresahkan masyarakat dan pelakunya layak dihukum.
Jujur dan bohong merupakan konsep moral paling tua dalam sejarah sosial homo sapiens. Iblis membohongi Adam dan adam memperdaya Hawa, sehingga mereka memakan buah quldi.
Qabil, anak Adam, memperdaya diri dan Tuhan saat diperintahkan berqorban. Jadi, kecenderungan berbohong sudah diwariskan dalam memori genetis dari generasi ke generasi.