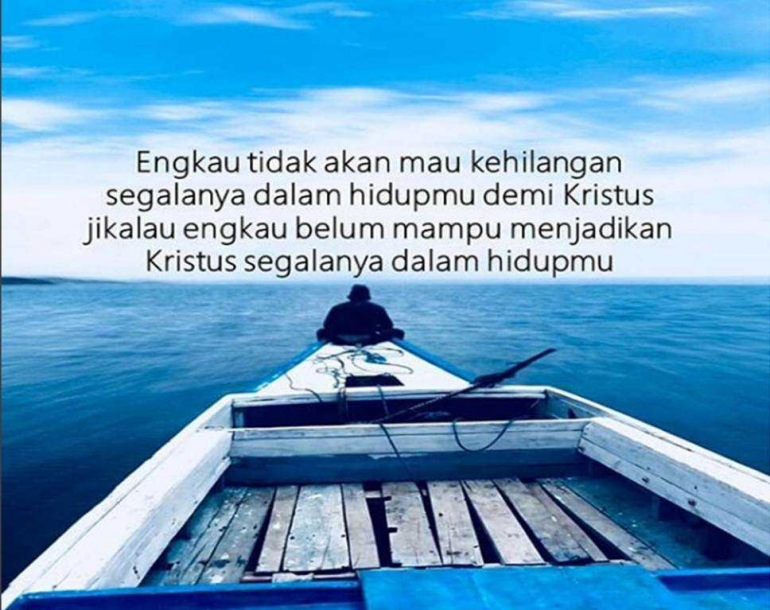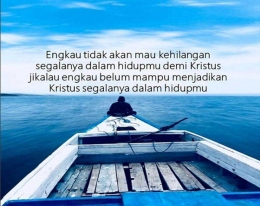Judul artikel ini mungkin sudah membuat kita mengasumsikan beberapa hal. Di kalangan orang-orang awam, teologi Reformed identik dengan lima semboyan yang sangat terkenal: (1) Sola Scriptura (2) Sola Gratia (3) Sola Fide (4) Solus Christus (5) Soli Deo Gloria. Teologi Reformed dikenal karena fokusnya pada Alkitab. Studi Alkitab yang mendalam dan mendetail menjadi ciri khas dan fokus pemberitaan John Calvin. Bahkan karya agung Calvin yang berjudul The Institutes of Christian Religion ditulis sebagai panduan untuk mengerti kitab suci.
Ciri khas ini sayangnya menjadi kabur di kalangan gereja-gereja Reformed di Indonesia. Khotbah yang filosofis dan doktrinal menjadi primadona. Tidak jarang, teks Alkitab hanya dibacakan di awal khotbah dan selanjutnya tidak diuraikan secara memadai. Sebagian orang bangga bisa mengutip perkataan dari tokoh-tokoh Reformed dunia, tetapi orang yang sama ternyata kurang menguasai kitab suci. Yang paling parah, ukuran kebenaran seringkali adalah tokoh tertentu, seolah-olah ada manusia super yang tidak mungkin keliru. Pandangan orang diterima tanpa ditelaah secara kritis bagaimana ketepatan argumen yang digunakan.
Dominasi kalangan intelektual dalam jemaat Reformed di Indonesia membuat penekanan teologi ini menjadi kental dengan nuansa doktrinal saja. Hal ini tidak berarti spiritualitas dan kerohanian tidak pernah disinggung sama sekali. Namun dari sekian banyak aspek yang ada dalam teologi Reformed, aspek yang paling dominan ditekankan adalah aspek intelektual. Karena itu dengan bersandar pada anugerah Tuhan yang sempurna, kali ini saya memberanikan diri membahas suatu topik yang mungkin di dalam konteks Reformed Indonesia sangat jarang dibicarakan: spiritualitas Reformed.
Membicarakan tentang spiritualitas Reformed merupakan tugas yang sangat tidak mudah. Kekayaan spiritualitas Reformed dapat diumpamakan seperti sebuah gelas bersisi banyak yang disinari beragam warna. Spiritualitas tidak hanya dibatasi pada ibadah, doa, mukjizat, atau moralitas belaka. Spiritualitas mencakup setiap detail kehidupan. Spiritualitas bukan hanya masalah praktis (doa, puasa, hidup baik), tetapi juga teologis (dasar spiritualitas yang teosentris).
Signifikansi: klarifikasi kekeliruan kerohanian
Kerancuan konsep seputar spiritualitas di dalam kalangan orang-orang Kristen membuat topik ini menjadi sangat relevan. Hal ini dapat ditinjau dari sejak peristiwa Reformasi gereja 500 tahun yang lalu. Apabila kita hidup sezaman atau sebelum zaman para reformator (Luther, Calvin, Zwingli, Knox), mungkin jawaban kita terkait spiritualitas akan berbeda dengan jawaban kita hari ini. Sakramen, liturgi, dan hal-hal yang sifatnya ritual adalah konsep spiritualitas yang berkembang pada waktu itu. Spiritual identik dengan ritual. Apabila kita ingin mengasah spiritualitas kita dalam pengertian pada zaman reformasi, maka kita tidak mungkin memisahkan diri dari hal-hal yang bersifat ritual, bukan doktrinal atau intelektual.
Penelusuran historis yang cermat ternyata memberikan penjelasan yang cukup memadai untuk memahami spiritualitas pada zaman reformasi. Berbeda dengan Alexander Agung yang memaksa penduduk di wilayah kekuasaannya untuk berbahasa dan berbudaya Yunani, pada waktu Kekaisaran Romawi berubah menjadi Kekaisaran Kristen sejak zaman Kaisar Kontantinus di awal abad ke-4, mereka tidak memiliki kebijakan semacam itu. Sehingga ketika mereka menguasai berbagai macam tempat yang mengakibatkan kekristenan merangsek ke banyak daerah, alih-alih memaksa penduduknya berbahasa lain, bahasa dan budaya setempat tetap dipertahankan.
Dimulai oleh bapa gereja yang bernama Jerome (abad ke-4) dari Kota Betlehem, Alkitab mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dengan kata lain, kekristenan di masa pra-reformasi gereja adalah kekristenan dengan Alkitab dalam bahasa Latin (Vulgata). Ini adalah satu-satunya Alkitab yang beredar dengan otoritas hukum dari gereja. Orang-orang Kristen tidak bisa dan tidak diperbolehkan membaca dan menafsirkan Alkitab sendiri. Sedangkan banyak dari antara mereka yang tidak bisa berbahasa Latin. Sehingga bisa dibayangkan ada banyak sekali orang Kristen - pada waktu itu kekristenan menjadi agama resmi negara - yang pergi ke gereja tanpa mengetahui apa yang sedang mereka baca.
Kendati demikian, kita tidak bisa menafikan bahwa ada orang-orang Kristen tertentu yang bisa membaca Alkitab edisi Vulgata. Persoalan tidak tuntas sampai di sini. Bisa membaca belum tentu diperbolehkan membaca. Para pemimpin gereja membuat aturan bahwa yang berhak untuk menafsirkan Alkitab hanyalah gereja. Kekeliruan dianggap mustahil jika penafsiran dilakukan oleh gereja. Individu Kristen tidak boleh menafsirkan Alkitab secara independen. Semua harus mengikuti gereja. Gereja adalah jawaban dari semua pertanyaan. Apapun pertanyaannya, sumber dari kebenaran hanyalah jawaban dari gereja.
Pendeknya, spiritualitas pra-reformasi adalah segala hal yang berbau ritual. Di luar itu, hampir tidak ada pembicaraan yang bermakna tentang spiritualitas. Karena itu ucapan syukur harus dinaikkan setinggi-tingginya kepada Tuhan jika kita bisa mulai memahami persoalan ini di dalam konteks dan situasi yang baru.
Konsep modern tentang spiritualitas atau kerohanian biasanya berkutat pada karakteristik berikut ini: (1) dekat dengan Tuhan (2) sering berdoa (3) membaca Alkitab setiap hari (4) banyak pelayanan (5) ramah. Tentunya lima hal tersebut tidak mewakili pendapat seluruh orang Kristen tentang spiritualitas. Namun, pembahasan terhadap ciri-ciri kerohanian seseorang mutlak ditempatkan di awal bersamaan dengan pembahasan teks Alkitab yang akan mendasari artikel ini (Matius 6:1-18 dan Kolose 2:20-23) supaya kita bisa memikirkan ulang karakteristik kerohanian yang kita asumsikan dengan apa yang dikatakan teks-teks tersebut mengenai kerohanian yang sejati.
Matius 6:1-4 menunjukkan kesungguhan orang Yahudi dalam memberikan sedekah. Untuk diketahui, sedekah berbeda dengan persepuluhan. Kewajiban mereka adalah memberikan persepuluhan, bukan memberikan sedekah. Sekilas, tindakan ini tampak sangat kental dengan nuansa kemurahhatian. Penelitian awal mungkin menunjukkan bahwa tindakan ini patut diapresiasi sebagai tanda kerohanian. Tidak semua orang Kristen membayar persepuluhan, apalagi berkomitmen untuk menyisihkan hartanya bagi kebutuhan orang lain (bersedekah).
Penyelidikan lebih lanjut terhadap perikop ini ternyata mengarahkan kita pada kesimpulan yang berbeda. Bersedekah belum tentu menjamin kualitas kerohanian seseorang. Dalam perikop ini, pujian dari orang lain ternyata menjadi tujuan dari pemberian sedekah.
Perikop setelahnya menunjukkan kesungguhan orang Yahudi dalam berdoa (ay. 5-7). Mereka memang memiliki aturan yang sangat ketat tentang rutinitas berdoa. Aturan ini dijalani juga dengan sangat ketat, tanpa memandang tempat, tanpa pernah melewatkan kesempatan. Beberapa penafsir Alkitab bahkan menjelaskan bagaimana mereka mengatur waktu ketika dalam perjalanan. Ketika tiba waktunya berdoa, mereka berada di pusat keramaian. Sekilas, tindakan ini mungkin mengecoh penilaian kita terhadap kualitas kerohanian seseorang. Apalagi ditambah dengan realita bahwa kita sering kali bersikap ogah-ogahan untuk mencari gereja pada saat sedang berpergian ke luar kota/luar negeri. Bahkan ketika usaha pencarian gereja menemui kebuntuan, kita juga kerap mengabaikan ibadah bersama dengan keluarga di hari Minggu.
Ketekunan orang-orang dalam perikop ini untuk menaati aturan-aturan keagamaannya - secara khusus terlihat dari konsep berdoa mereka - ternyata tidak menghasilkan kualitas kerohanian seperti yang diharapkan. Apa yang terjadi dengan orang-orang di Matius 6:7 sebetulnya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Fenomena yang sama sedang dialami oleh orang-orang Kristen. Kalimat yang indah dan jumlah kata yang banyak dianggap menambah khasiat kemanjuran sebuah doa. Kesan meyakinkan ditampilkan melalui suara yang diucapkan. Doa yang sederhana dipandang tidak berkuasa. Menariknya, beberapa orang Kristen menentukan kualitas kerohanian seseorang hanya dari cara ia berdoa. Ternyata, konsep doa yang keliru membuat semua tindakan doa kita tidak ada artinya bagi kesalehan hidup kita.
Perikop setelahnya menunjukkan kesungguhan orang-orang Yahudi dalam berpuasa (ay. 16-18). Orang Farisi berpuasa dua kali dalam seminggu (bdk. Luk. 18:12). Hukum Taurat hanya memerintahkan puasa wajib sebanyak sekali dalam setahun, yaitu pada saat Hari Raya Pendamaian (Im. 16:29- 31; Bil. 29:7). Ada beberapa puasa tambahan yang dicatat dalam Alkitab, tetapi hal itu hanya dilakukan dalam situasi-situasi khusus saja (2Sam. 12:21-22; 1Raj. 21:27; Neh. 1:4; Zak. 8:19). Berpuasa secara rutin dua kali dalam seminggu jelas bukan pencapaian yang biasa. Dibutuhkan kemauan dan kedisiplinan yang besar.
Alih-alih mengerti konsep berpuasa yang benar, kekristenan modern jarang sekali menekankan kesalehan dalam bentuk puasa. Jumat Agung adalah satu-satunya waktu berpuasa bagi beberapa orang. Dengan fakta semacam ini, mungkin kita merasa minder dengan kerohanian yang ditunjukkan orang-orang Yahudi.
Penyelidikan lebih lanjut terhadap perikop ini ternyata mengarahkan kita pada kesimpulan yang berbeda. Kuantitas berpuasa belum tentu menjamin kualitas kerohanian seseorang. Dalam perikop ini, pujian dari orang lain ternyata menjadi tujuan dari tindakan berpuasa.
Dengan kata lain, hal-hal yang selama ini kita pandang sebagai kerohanian ternyata belum tentu diperkenan Tuhan. Orang yang banyak memberi belum tentu termasuk orang yang rohani. Orang yang sering berdoa belum tentu termasuk orang yang rohani. Orang yang sering berpuasa belum tentu termasuk orang yang rohani. Tetapi orang yang rohani pasti sering melakukan ketiganya.
Tinjauan lain mengenai spiritualitas datang dari Kolose 2:20-23. Upaya melarikan diri dari dunia ini tampaknya dipandang sebagai sesuatu yang baik bagi beberapa orang. Ketaatan terhadap peraturan yang merinci tentang ini dan itu dianggap sebagai tanda kerohanian. Tugas orang Kristen pun dipersempit menjadi hanya memelihara relasi yang baik dengan Allah dalam doa, pembacaan Alkitab, dan melayani orang lain. Pengamatan yang komprehensif terhadap situasi semacam ini menunjukkan bahwa upaya menyiksa diri belum tentu menjamin kerohanian seseorang.
Melalui beberapa klarifikasi di atas, saya ingin menandaskan bahwa kesalehan tanpa kebenaran adalah sebuah kesalahan. Tidak adanya kebenaran Kristus dalam tiap kesalehan kita adalah tanda bahwa kesalehan kita hanyalah kumpulan kesalahan yang terakumulasi.
Dalih yang mungkin berdatangan adalah mengenai kesungguhan. Kesalehan yang salah dipandang bisa ditolerir dengan sikap yang sungguh-sungguh. Salah tidak apa-apa, yang penting sungguh-sungguh. Banyak hal yang bodoh dan salah dibenarkan karena dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pandangan semacam ini hanya berujung pada kekeliruan yang lain. Orang yang sungguh-sungguh dalam kesalahannya adalah orang yang sungguh-sungguh salah. Pengujian yang sesungguhnya bukan hanya terletak pada kesungguhan dan ketulusan, tetapi juga pada kebenaran. Kesalehan yang sejati adalah perpaduan antara kebenaran, kesungguhan, dan ketulusan.
Namun, kebenaran tanpa kesalehan hanya menghasilkan kesombongan dan kekeringan spiritual. Fenomena semacam ini sering terjadi terutama di kalangan Reformed. Kebenaran tidak didaratkan menjadi kesalehan. Hanya menempel di kepala tanpa pernah mengubahkan hidup. Kebenaran teologis tidak cocok dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh konkret terhadap persoalan ini adalah sikap seseorang yang bersandar pada kedaulatan dan anugerah Allah (salah satu ciri khas teologi Reformed) untuk membenarkan perasaan cintanya terhadap seorang perempuan yang sebetulnya berada di ranah abu-abu dalam etika pelayanan.
Di mata orang-orang awam, orang-orang Reformed identik dengan sikap sombong, lekas marah, dan sulit menyapa orang lain terlebih dahulu. Kita dianggap sebagai orang yang merasa diri paling benar; sangat pintar untuk melihat kelemahan orang lain namun mengalami kesulitan saat melihat kelemahan diri sendiri. Ungkapan kebenaran dari orang Reformed biasanya tanpa disertai rasa takut dan dipenuhi dengan kalimat yang kasar dan ofensif. Tangisan adalah sesuatu yang tampaknya bermusuhan dengan kehidupan spiritual orang Reformed. Namun, orang Reformed paling ahli dalam membuat orang lain menangis.
Kritik terhadap kekeliruan ini seharusnya didorong oleh kepedulian terhadap teologi kita sendiri. Teologi Reformed juga mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kebenaran. Semua tindakan di atas adalah tindakan yang sangat tidak Reformed.
Tantangan kontemporer: Gerakan Zaman Baru dan Postmodernisme
Pada paruh pertama abad ke-20 terjadi perubahan signifikan berupa sinkretisme budaya/filsafat Timur dan Barat. Kalau sebelumnya dua kutub ini dianggap tidak mungkin disatukan (Rudyard Kliping), pada masa itu keduanya justru bersinergi. Filsafat Timur yang sangat mistis dan pragmatis ternyata mendapat sambutan yang luar biasa di Barat. Kendaraan utama yang dipakai untuk mempercepat proses sinkretisme ini disebuta dengan istilah Gerakan Zaman Baru (selanjutnya disingkat GZB). Gerakan ini memiliki banyak bentuk, seperti The Human Potential Movement, The Third Force, The Aquarian Conspiracy, Cosmic Consciousness maupun Cosmic Humanism.
Mendefinisikan GZB bukanlah hal yang mudah. Ada dua faktor yang membuat tugas ini menjadi sulit. Pertama, GZB bersifat eklektik dan beragam. Sifat eklektik dari GZB tercermin dalam tindakannya mengadopsi banyak sumber/aliran dalam filsafat Timur. Sifat beragam dari GZB dapat juga disebut tidak kohesif, tetapi sebaliknya memiliki komposisi dan ideologi yang berbeda-beda. Sifat yang eklektik dan beragam ini memberikan kesulitan untuk mencari suatu definisi yang dapat mencakup semua keberagaman dalam GZB.
Faktor kedua yang membuat definisi GZB sulit dicapai adalah sifatnya yang berubah-ubah. GZB sangat menekankan dan mendorong terjadinya perubahan yang terus-menerus. Sikap ini sangat mudah dipahami, karena sifat GZB yang sinkretis. Dia berusaha membaur dengan apa saja yang baru, sejauh percampuran tersebut tetap memiliki ideologi dasar yang sesuai. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan kita sulit untuk menemukan suatu definisi yang mampu mewakili atau mengantisipasi perubahan yang akan terjadi.
Walaupun suatu definisi yang tepat sangat sulit dicapai, namun hal itu bukan berarti tidak ada penjelasan yang memadai tentang GZB. Kita masih dapat memahami GZB berdasarkan salah satu keyakinan utama yang dipegang oleh para penganutnya, yakni pantheisme. Pantheisme berasal dari kata Yunani “pan” yang berarti “semua” dan “theos” yang berarti “allah”. Pantheisme berarti kepercayaan bahwa segala sesuatu adalah allah. Semua ciptaan mengambil bagian dalam natur/hakikat ilahi.
Gagasan tentang “allah” telah direduksi sedemikian rupa. Allah yang berpribadi telah diganti dengan energi kekuatan atau kesadaran yang tidak berpribadi. Studi komprehensif terhadap banyak literatur GZB menunjukkan bahwa mereka memahami adanya sebuah keberadaan ilahi yang tidak berpribadi, yaitu Brahman. Ia dipahami sebagai realitas tertinggi (impersonal divine being) yang memercikkan/mengemanasikan dirinya ke dalam segala sesuatu. Masing-masing percikkan itu mengandung hakikat ilahi. Segala yang ada di alam semesta merupakan percikan dari keilahian.
GZB merupakan masalah yang sangat serius. Pengaruhnya tidak dapat diabaikan begitu saja. Media propaganda yang dipakai juga sangat bervariasi dan efektif. Banyak bidang telah dipengaruhi oleh pemikiran GZB. Akibatnya, walaupun banyak orang tidak mengenal istilah “Gerakan Zaman Baru”, namun mereka secara tidak sadar telah mengadopsi dan mempraktikkan wawasan dunia GZB.
Yang paling menyedihkan dan berbahaya, pengaruh GZB telah merambah sampai ke dunia kekristenan. Tinjauan historis terhadap spiritisme di dunia barat adalah langkah awal yang tepat untuk pembahasan lebih lanjut mengenai GZB dan pengaruhnya bagi kekristenan. Sebelum GZB menginvasi masyarakat Barat, budaya Barat ditandai dengan rasionalisme yang menekankan kebenaran objektif dan pengagungan rasio. Seiring dengan kegagalan rasionalisme dan masuknya filsafat Timur melalui jalan yang dibuka oleh GZB, semakin banyak masyarakat Barat yang bersikap mistis dan pragmatis. Mereka telah memasuki suatu zaman yang baru sebagai pengganti rasionalisme, yaitu spiritisme. Zaman yang baru ini secara cepat meresap dalam seluruh bidang kehidupan, termasuk kekristenan.
GZB secara eksplisit mengajarkan pengalaman-pengalaman mistis yang dapat dikategorikan sebagai okultisme (berkaitan dengan roh-roh jahat). Para pengikut meditasi transendental dilatih untuk bermeditasi sampai mereka tidak bisa terbang, tidak dapat dilihat oleh mata biasa, bahkan hingga rohnya dapat berkelana meninggalkan tubuh. Sebagian yang lain mengalami kesurupan dan menjadi media komunikasi bagi roh-roh tertentu yang mengajarkan berbagai hal tentang allah, manusia, dan dunia. Beberapa orang mengaku mengalami perjumpaan dengan dewa tertentu ketika mereka meleburkan diri dengan alam semesta.
Bidang psikologi GZB juga memengaruhi beberapa orang Kristen. Humanisme, sekularisasi, dan gaya hidup individualistik telah menjadi tanah yang subur bagi psikologi yang antrposentris. Teori psikoanalisa Sigmund Freud sampai teori motivasi dan kepribadian yang dikembangkan Abraham Maslow merupakan jalan masuk bagi penyambutan GZB. Pikiran kita dianggap memiliki kekuatan yang tanpa batas. Banyak hal dapat dihasilkan melalui pola pikir yang positif dan melampauin kebiasaan. Salah satu produk terkenal dari pengaruh ini adalah Human Potential Movement yang mendorong manusia untuk memercayai diri sendiri dan menyangkali semua keterbatasan yang ada.
Fenomena serupa sedang melanda gereja-gereja kalangan tertentu. Tuhan adalah alat pemuas kebutuhan. Percaya dapat pasti dapat. Keraguan adalah tanda iman yang lemah. Sugesti yang berlebihan dipandang cocok untuk menggantikan kebenaran Alkitab. Tangisan menjadi tolok ukur kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Keutuhan Injil Yesus Kristus tidak lebih penting daripada pertunjukan bahasa roh yang tidak karuan (tidak disertai penafsirannya). Hal-hal yang anti-rasional mendapat posisi penting dalam ibadah. Kegemaran banyak gereja terhadap peristiwa tumbang dalam roh atau pengalaman ekstase lainnya merupakan bukti nyata bahwa gereja-gereja modern terikat oleh pengaruh GZB.
Tantangan selanjutnya datang dari postmodernisme. Tantangan ini muncul hampir bersamaan dengan GZB. Keduanya bahkan saling memengaruhi. Pola pikir postmodern sudah sedemikian akrab bagi banyak orang, sehingga - disadari atau tidak - mereka telah diliputi oleh pola pikir ini. Semua bidang sudah disentuh oleh postmodernisme. Dalam kaitan dengan pembahasan kali ini, fokus kita hanya tertuju pada spiritualitas postmodern.
Spiritualitas Reformed dan postmodernisme akan coba dilihat secara bersamaan, walaupun ini bukanlah sebuah studi komparasi. Artikel ini ditulis untuk menolong pembacanya melihat kekayaan spiritualitas Reformed dan bagaimana kekayaan itu dapat memperkaya orang-orang Kristen yang hidup di zaman postmodern. Melalui artikel ini diharapkan muncul sebuah pemahaman yang lebih komprehensif seputar spiritualitas Reformed dan bagaimana spiritualitas tersebut dapat menjawab tantangan di era postmodern.
Postmodernisme didasarkan pada satu filosofi: relativisme. Paham ini mengajarkan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak (absolut). Segala sesuatu adalah relatif, subjektif, dan personal. Benar bagiku belum tentu benar bagimu. Biarkan saja semuanya mengalir seperti air. Tidak perlu bertengkar. Dua kebenaran yang saling berkontradiksi pun dianggap dapat disandingkan bersama tanpa harus memilih salah satu dan membuang yang lain. Walaupun secara logis pandangan ini tidak bisa dibenarkan, namun para penganut postmodern tetap memegang teguh paham ini karena pada dasarnya mereka lebih cenderung mengutamakan pemikiran pragmatis ketimbang logis.
Pengaruh yang dibawa oleh relativisme tidak bisa dipandang sebelah mata. Hukum, politik, seni, pendidikan, filsafat, teologi, gereja, hanyalah sebagian kecil dari merebaknya pengaruh relativisme dalam masyarakat modern. Pengaruh ini pun dapat dengan mudah ditemukan dalam bidang spiritualitas. Sayangnya, spiritualitas Kristen pun ikut teracuni oleh relativisme. Apa saja bentuk spiritualitas postmodern yang relativis ini?
Pertama, spiritualitas yang tidak memiliki dasar kebenaran mutlak. Akibat dari relativisme adalah penolakan terhadap suatu dasar kebenaran yang mutlak, termasuk dalam hal spiritualitas. Ketika dasar kebenaran ditolak, maka yang disorot hanyalah bentuk luar dari spiritualitas. Hal ini bisa dipahami karena bentuk luar dari agama-agama yang ada cenderung sama sehingga bentuk luar inilah yang dijadikan “alat pemersatu”. Semua agama mengajarkan perbuatan baik; dan itu dirasa sudah cukup. Demikianlah kira-kira cara pandang orang postmodern. Dengan demikian, spiritualitas dalam era postmodern telah direduksi menjadi sekadar moralitas belaka.
Beberapa fenomena secara jelas mengarah ke sana. Berkembangnya SQ (Spiritual Quotient) merupakan salah satunya. Banyak orang membicarakan spiritualitas versi SQ yang - jika dilihat dari perspektif Alkitab - tidak lebih daripada moralitas. Tidak jarang dalam diskusi yang dilakukan orang Kristen tentang SQ pun pembahasannya sama persis dengan SQ versi lain.
Fenomena lain adalah merebaknya kata-kata motivasi. Para motivator sekarang mulai naik daun. Dengan sejuta janji mereka meyakinkan banyak orang tentang kepastian keberhasilan dalam hidup yang biasanya dipahami semata-mata secara material. Sayangnya, para motivator Kristen lupa untuk menggarami wilayah baru ini dengan prinsip teologi Kristen. Apa yang disampaikan tidak ada bedanya dengan kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang non-Kristen. Radio Kristen tidak ketinggalan memberi ruang khusus bagi hal ini, walaupun banyak kata-kata motivasi yang muncul sebenarnya tidak memiliki nuansa kekristenan yang unik. Tanpa bermaksud mengabaikan prinsip “segala kebenaran adalah kebenaran Allah”, fenomenda maraknya kata-kata motivasi ini paling tidak menjadi salah satu bukti betapa spiritualitas Kristen dalam banyak hal sudah teracuni dengan filosofi postmodern.
Situasi di atas diperparah dengan gerakan ekumenikal yang berusaha untuk mengingkari perbedaan esensial antar agama. Keunikan masing-masing agama coba untuk diminimalisasi (jika perlu dihilangkan sama sekali), padahal secara logis toleransi tanpa batas merupakan sebuah mitos, bahkan utopia. Kebersamaan bagi mereka dipahami sebagai kesamaan. Kesatuan dibatasi pada keragaman. Tidak heran, ketika mereka mencari alat pemersatu antar agama, mereka menemukan perbuatan baik (moralitas) sebagai media yang tepat. Perbedaan esensial dalam taraf motivasi atau dasar moralitas diabaikan supaya kesamaan terlihat lebih mengemuka.
Kedua, spiritualitas yang bersifat subjektif dan pragmatis. Konsekuensi tak terelakkan dari relativisme di bidang agama adalah munculnya rasa keagamaan yang lebih didominasi oleh perasaan seseorang. Masyarakat postmodern tidak terlalu mempedulikan kebenaran dari suatu ajaran. Yang penting bagi mereka adalah ajaran tersebut mendatangkan perasaan nyaman dan kepuasan psikologis. “Today religion is not seen as a set of beliefs about what is real and what is not. Rather, religion is seen as a preference, a choice. We believe in what we like. We believe what we want to believe.”
Pola pikir yang pragmatis juga mengondisikan banyak orang untuk mementingkan hasil praktis dan instan dari ajaran yang mereka yakini: yang penting ada hasilnya. Kebenaran suatu ajaran diukur berdasarkan “buah” dari ajaran tersebut. Celakanya, yang dimaksud “buah” di sini sering kali hanya dibatasi pada kriteria-kriteria keberhasilan yang semu: jumlah pengikut, perasaan nyaman dari pengikut, keberhasilan materi, popularitas yang menanjak, dan lain sebagainya.
Sebagai contoh di sekitar kita adalah pertobatan dari orang-orang yang mendengarkan pengalaman-pengalaman rohani pendeta-pendeta yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Banyak orang yang menyesali dosanya setelah mengetahui apa yang terjadi di surga dan neraka. Kekeliruan semacam ini berangkat dari kerancuan yang umum: kebenaran suatu ajaran dinilai dari jumlah pengikut yang banyak.
Spiritualitas postmodern di atas sekaligus berfungsi sebagai penjelasan mengapa dalam kekristenan sendiri aliran karismatik (yang mementingkan kepuasan dan emosi) dan ekumenikal (yang meniadakan perbedaan esensial dan keunikan kekristenan) semakin mendapat tempat di hati banyak orang. Dua aliran ini dianggap mampu memenuhi kebutuhan spiritualitas masyarakat postmodern. Tantangan kontemporer semacam ini sangat berbahaya bagi spiritualitas Reformed.
Apa yang salah dengan spiritualitas Reformed?
Apa yang sudah dipaparkan sebelumnya jelas memberikan ancaman bagi spiritualitas yang sejati. Spiritualitas semu tampak lebih dominan dan diminati banyak orang. Tanpa bermaksud mengingkari kerusakan natur manusia yang cenderung melawan kebenaran (Rm. 1:18) maupun mengikuti gaya hidup guru palsu yang “menyenangkan telinga orang” (2Tim. 4:2), sudah sepantasnya orang-orang Reformed bertanya pada diri sendiri: mengapa spiritualitas yang didasarkan pada teologi yang begitu konsisten dengan Alkitab justru kurang dinikmati? Mengapa spiritualitas sejati selama ini tidak mampu menunjukkan dirinya secara penuh dan dengan demikian akan menjadi alternatif kuat bagi masyarakat postmodern? Apa saja kekurangan spiritualitas dalam tradisi Reformed sehingga terkesan tidak mampu mengimbangi perkembangan spiritualitas yang semu?
Kurangnya relevansi kekristenan
Salah satu kekurangan spiritualitas Reformed (juga kalangan injili secara umum) terletak pada relevansi. Orang-orang Reformed cenderung terjebak pada diskusi logis-filosofis daripada isu-isu praktis yang sedang digumulkan banyak orang. Fokus perhatian diarahkan pada hal-hal metafisik yang kurang membumi. Relasi yang personal dengan Allah cenderung dibatasi pada pergumulan intelektual belaka. Ruang untuk pertemuan pribadi dan subjektif dengan Allah makin lama makin sempit. Alister McGrath mengatakan, “And what has attracted these people away from evangelicalism?... they felt that evangelicalism offered relatively little help to those who were trying to deepen their understanding of God and to develop approaches to prayer and meditation that would enrich their faith and sustain them in Christian life.”
Spiritualitas memang harus berkaitan dengan doktrin. Namun jika pembahasan doktrin hanya dilakukan secara kering, teoritis, dan abstrak tanpa menyentuh kehidupan personal kita, maka jangan heran jika banyak orang mulai mengabaikan doktrin yang solid secara biblika. Relevansi doktrin mulai diragukan dalam kehidupan sehari-hari. Katekismus Westminster dan Heidelberg hanya dihafal dan dipahami secara teoritis. Semua ini adalah kesalahan kita yang gagal menemukan relevansi antara doktrin dan kehidupan sehari-hari. Kegagalan kita dalam membuat orang lain tertarik dengan doktrin adalah karena hidup kita tidak diwarnai oleh doktrin.
Sebagai contoh adalah banyaknya orang Kristen yang tidak memahami apa hubungannya penebusan Kristus dengan membuang sampah pada tempatnya. Banyak orang Kristen tidak memahami kaitan antara salib Yesus Kristus dengan membuang kebiasaan berkata kasar. Belum lagi isu-isu seperti berpacaran, pergi ke diskotik, berolahraga, pola hidup sehat, cara bermedia sosial, budaya konsumerisme, dan lain sebagainya. Injil Yesus Kristus akan semakin sulit menembus kehidupan praktis jika kita terjebak pada doktrin yang tidak membumi.
Gejala intelektualisme
Kekurangan yang lain adalah gejala intelektualisme. Sebagian orang Reformed mengukur spiritualitas berdasarkan tingkat pengetahuan seseorang tentang doktrin maupun Alkitab. Kriteria ini diperlakukan sebagai kriteria utama. Tidak jarang pengetahuan doktrinal yang begitu banyak dipakai sebagai perisai untuk menutupi kehidupan rohani yang kering.
Kecenderungan di atas sebenarnya dapat dipahami. Walaupun kecenderungan tersebut tetap merupakan sebuah kesalahan fatal. Teologi Reformed memang satu-satunya teologi yang memberikan jawaban logis dalam banyak hal. Teologi ini adalah yang paling dekat dengan Alkitab, paling konsisten dengan logika, dan paling koheren dengan realita. James M. Boice, salah seorang teolog Reformed kontemporer pernah menerangkan hal ini sebagai berikut, “The very nature of the Reformed system of doctrine, which tends to put reality together and thus make sense of life as other systems of theology do not, tends to produce lovers of theology for its own sake and thus persons detached from life and perhaps even detached from vital fellowship with the God they speak about theologically...it is not without justification that many Reformed people are seen as dry, ivory-tower intellectuals (or pseudo-intellectuals) out of touch with contemporary needs.”
Berpikir secara intelektual adalah hal yang sejalan dengan natur manusia sebagai makhluk rasional. Kekeliruan muncul ketika kita terjebak pada intelektualisme saat mempelajari teologi Reformed yang memang sangat solid secara intelektual. Ini adalah sebuah kombinasi yang sangat membahayakan. Kita mencintai teologi, tetapi tidak benar-benar mencintai Allah. Membaca buku yang ditulis oleh teolog-teolog Reformed lebih diutamakan ketimbang membaca Alkitab.
Mengingat kekristenan Reformed menawarkan apa yang disebut Cornelius Van Til sebagai “an absolutely comprehensive interpretation of human experience...the only true interpretation of human experience,” maka tidak heran para peminat teologi ini memang adalah orang-orang yang mumpuni secara intelektual. Dari awal, ketertarikan mereka terhadap teologi Reformed memang dimulai dari ketertarikan secara intelektual. Akhirnya jika tidak diwaspadai, kelebihan ini justru menjadi kelemahan dalam tradisi Reformed.
Peluang: menjembatani jurang yang ada
Kekuatan teologi Reformed terletak pada konsistensi dan ketahanan terhadap berbagai macam ujian. Dari para rasul, bapa-bapa gereja awal (terutama Agustinus), Calvin, Puritan, bahkan sampai sekarang, teologi ini tetap tidak lekang oleh zaman. Bagaimanapun, kekuatan ini jangan sampai menjadi titik kelemahan. Para penganut teologi Reformed sering membanggakan diri dengan teologi yang tidak lekang oleh zaman. Kebanggan ini di satu sisi memang benar. Namun anggapan semacam ini menimbulkan akibat yang fatal. Teologi yang dianggap tidak lekang oleh zaman ternyata tidak peka terhadap zaman dan tidak pernah menangisi zaman. Apakah kita pernah menangisi dunia ini dengan semua degradasi moral yang jauh dari kebenaran Allah? Apakah kita pernah dengan sungguh-sungguh berdoa memohon datangnya Kerajaan Allah? Apakah lagu “Dalam Dunia Penuh Kerusuhan” termasuk sering dinyanyikan dalam gereja dan persekutuan? Ataukah kita hanya sering menangisi masalah-masalah pribadi kita saja? Sadarkah kita ke arah mana dunia ini akan menuju?
Tidak lekang oleh zaman tidak berarti harus tidak peka terhadap zaman. Sebuah peringatan indah yang perlu disimak datang dari Richard Middleton dan Brian J. Walsh, “But any faith which claims to be timeless is simply unaware of its own contextual character, and in seeking to transcend (even escape) the problems of the present many Christians simply enshrine and absolutize some supposed golden age in the historical past.”
Masing-masing orang memang memiliki kebanggan terhadap zamannya. Orang-orang dewasa sering kali membandingkan zamannya dengan anak-anaknya. Demikian pula sebaliknya. Hal yang sama juga dialami oleh teologi Reformed. Sesuatu yang dibanggakan sebagai yang tidak lekang oleh zaman jangan sampai justru ketinggalan zaman. Jika teologi kita sudah tidak relevan, apakah kita hanya bisa menyalahkan zaman dan mengenang masa jaya yang sudah lampau? (bandingkan lagu “Gereja Bagai Bahtera” bait ke-2).
Sebagai contoh praktis adalah upaya kita untuk mengembalikan relevansi reformasi gereja pada masa kini. Kita tidak boleh terlena dengan zaman kejayaan reformasi gereja. Kepekaan terhadap zaman seharusnya memberi kita kesimpulan bahwa zaman ini masih membutuhkan reformasi. Teologi Reformed harus terus-menerus dipikirkan untuk bisa menjadi relevan menjawab permasalahan kontemporer. Spiritualitas Reformed harus bisa menjawab kebutuhan mendasar dari umat manusia. Jika Reformed tidak bisa menjawab, maka jawaban akan datang dari wawasan dunia yang lain. Bagaimanapun, semua jawaban di luar Alkitab hanya berujung pada kesia-siaan.
Dalam konteks postmodernisme yang sangat pragmatis, orang-orang Reformed perlu memberikan perhatian yang lebih memadai terhadap aspek spiritualitas personal. Relevansi kekristenan harus mendapat pengamatan yang lebih serius. Jika Alkitab adalah firman Allah untuk sepanjang zaman, maka pada dirinya sendiri Alkitab sudah pasti relevan. Tugas orang Kristen hanyalah mengedepankan hal itu supaya tidak tertutupi oleh hal-hal lain yang justru kurang esensial. McGrath memberi nasihat bijaksana sebagai berikut, “No longer was it adequate to define Christian faith and practice in purely external terms, such as attending church and receiving sacraments. Instead, faith must be made relevant and real to the private experiential world of individuals. The subject reality of faith became popular issue, as it never had before.”
Sebagai akibat buruk dari zaman pencerahan, pembicaraan tentang iman selalu diletakkan pada domain yang lain. Iman mulai dikunci pada laci yang tertutup. Hanya dibuka pada hari Minggu. Semua pembicaraan yang kental dengan nuansa akademis tidak boleh diganggu dengan iman. Kita harus berani membawa iman keluar dari tempurungnya dan mengatakan bahwa iman kita masih relevan dengan dunia ini. Iman Kristen harus menjadi pembicaraan sehari-hari. Ajaran Alkitab harus dibawa ke semua bidang kehidupan, termasuk medis, bisnis, politik, pendidikan, pertahanan, agraria, dan lain sebagainya. Jawaban dari Alkitab pasti lebih rasional daripada yang lain. Kekristenan bukan hal yang kuno!
Kita tidak perlu takut dengan tantangan-tantangan yang sudah dipaparkan di atas karena beberapa hal berikut ini. Pertama, manusia memiliki kebutuhan yang besar terhadap spiritualitas. Manusia diciptakan Allah dengan jiwa yang terus mencari Dia. Tindakan Allah yang menghembuskan nafas kepada Adam (Kej. 2:7) bukan hanya menjadikannya sebagai makhluk yang hidup, melainkan juga bahwa untuk menjadi utuh, manusia akan selalu mencari Penciptanya. Penafsiran ini didukung oleh teks Alkitab yang lain terutama Kitab Pengkhotbah (Pkt. 3:11).
Dalam diri manusia terdapat kerinduan yang sangat mendalam terhadap perjumpaan pribadi dengan Allah sebagai Pencipta. McGrath dalam bukunya yang lain menulis demikian, “We are made in the image of God. We have an inbuilt capacity - indeed, an inbuilt need - to relate to God. Nothing that is transitory can ever fill this need. To fail to relate to God is to fail to be completely human. To be filled is to be filled by God. Nothing that is not God can ever hope to take the place of God. And yet, because of the fallenness of human nature, there is a natural tendency to try to make other things fulfill this need. Created things are substituted for God, and they do not satisfy.”
Salah satu filsuf yang paling anti terhadap kekristenan, Fredrich Nietzsche, pernah mengatakan bahwa akan terjadi The Death of God suatu saat kelak ketika ilmu pengetahuan semakin berkembang. Tidak akan ada lagi diskusi tentang Allah, demikian pemikirannya. Kenyataannya, Islam menjadi agama yang paling cepat berkembang. Saksi Yehova dan Mormon memiliki pengikut yang semakin banyak. Dengan demikian, dimensi religius menjadi salah satu hal yang paling banyak dicari oleh manusia.
Dalam beberapa dekade ke depan, ketika semua orang masuk dalam budaya digital yang sifatnya impersonal (tatap muka seminimal mungkin), maka kekosongan secara rohani akan menjadi semakin kentara dan besar. Pencarian akan kerohanian menjadi semakin dibutuhkan oleh manusia. Kesungguhan terhadap hal-hal yang bersifat spiritual akan semakin dicari oleh banyak orang.
Budaya konsumerisme dan materialisme telah meninggalkan kekosongan dalam diri manusia. Banyak orang lebih puas untuk membagi uang ketimbang memiliki uang. Membeli hal-hal yang sifatnya non-material (liburan, pengalaman, dsb.) jauh lebih disukai banyak orang ketimbang menghabiskan uang untuk hal-hal yang bersifat material.
Adam menjadi makhluk yang terus mencari Allah sebab Ia menghembuskan nafas-Nya ke dalam diri Adam. Ini adalah apa yang disebut John Calvin sebagai “divinitatis sensus” atau benih keagamaan. Walaupun ini bukan inti dari teologinya, tetapi ia banyak menyinggung tentang sense of divinity. Salah satu hal menarik adalah keinginannya untuk mendaratkan teologi sebagai jawaban dari kebutuhan manusia. Kekosongan rohani mendapat perhatian yang serius dalam teologi Calvin.
Setelah menjelaskan relasi antara pengetahuan Allah dan manusia (Institutio I pasal 1) maupun hakikat dari pengetahuan tentang Allah ini (Institutio I pasal 2), Calvin selanjutnya meletakkan kekosongan rohani ini di bagian paling awal sebagai salah satu cara manusia dapat mengenal Allah. Cara pengungkapannya pun sangat tegas, demikian tulisnya: “That there exists in the human minds and indeed by natural instinct, some sense of deity, we hold to be beyond dispute, since God himself, to prevent any man from pretending ignorance, has endued all men with some idea of hid Godhead, the memory of which he constantly renews and occasionally enlarges, that all to a man being aware that there is a God, and that he is their Maker, may be condemned by their own conscience when they neither worship him nor consecrate their lives to his service”.
Sebagian orang Reformed kurang menekankan hal ini karena khawatir bahwa konsep ini terlalu berbau skolastik. Kekhawatiran ini sangat disayangkan karena penekanan Calvin berbeda dengan teolog skolastik. Calvin lebih menyoroti aspek praktis dari apa yang ia sebut sebagai sensus divinitatis. “Calvin’s interest in the divinitatis sensus are not primarily scholastic. Instead of exploring what this innate sense is, he is going to focus on what it does or what functions it serves. Calvin thus remains consistent with his previous disavowal of all theologically specualtive enterprise.” Itulah sebabnya semua orang akan mencari Allah. Persoalannya, tidak semua orang menemukan Allah yang benar.
Sinyal peluang yang lain datang dari fakta bahwa manusia memang butuh disentuh secara emosional. Sebagai contoh adalah apa yang terjadi pada ibadah-ibadah kontemporer. Meskipun tidak semua ibadah kontemporer keliru, tidak semuanya juga dapat dibenarkan. Banyak ibadah kontemporer yang menawarkan hiburan. Penyembahan diekspresikan melalui gerakan melompat dan menari. Begitu sang pendeta mulai berkhotbah, mayoritas jemaatnya asyik bermain handphone. Orang-orang semacam ini sebetulnya hanya menunjukkan kekosongan jiwanya yang tidak terisi oleh Tuhan.
Semangat zaman postmodern yang sangat menekankan pengalaman subjektif dengan apa yang disebut “Allah” sebenarnya tidak terlalu negatif seperti yang dipikirkan banyak orang. Poin ini justru memberikan peluang bagi orang-orang Reformed. Fenomena tersebut memberikan petunjuk yang jelas bahwa mereka merasakan kekosongan dalam hatinya. Kekosongan dalam hati manusia adalah peluang yang besar bagi relevansi spiritualitas. “Central to the intensity of contemporary interest in the spiritual life is the desire for personal religious experience. Many people have become serious in their search for a living and vital relationship with God because they feel empty.”
Contoh paling terkenal tentang hal ini adalah bapa gereja Agustinus. Ia telah mencoba berbagai cara untuk mencapai kebahagiaan sejati. Ia mencoba ilmu retorika yang waktu itu menjadi primadona ilmu. Tidak ketinggalan, ia pun mencari kepuasan dalam filsafat mistis Manikheanisme. Kehidupan bebas pun ia jalani hanya demi mengisi kekosongan dalam dirinya. Di akhir pergumulan ini ia mengutarakan sebuah ungkapan yang sekarang menjadi sangat terkenal, “You have made us for yourself, and our hearts are restless until they rest in you.”
Dari semua penjelasan di atas terlihat bahwa postmodernisme tidaklah seburuk yang diduga banyak orang. Seolah-olah Allah tidak sanggup lagi mengontrol semua kebusukan yang sedang berlangsung. Allah tetap mengatur setiap zaman dan mengerjakan kebaikan di dalamnya (Rm. 8:28). Apa yang terjadi justru menunjukkan kebenaran Alkitab. Manusia postmodern sedang berusaha mengisi kekosongan dengan hal-hal yang semu dan tidak mungkin memuaskan mereka. Manipulasi psikologis, motivasi emosional, dan meditasi panteistik justru dapat dipakai Allah untuk menawan mereka dengan kekosongan supaya hati mereka disiapkan bagi Injil yang mengubahkan dan memberi damai sejahtera.
Apakah spiritualitas Reformed mampu menawarkan spiritualitas yang relevan dengan situasi di atas? Apakah teologi Reformed hanya melulu sebuah pergumulan intelektual yang teoritis tentang hal-hal yang abstrak dan metafisik? Sama sekali tidak! Dalam pembahasan selanjutnya, kita akan melihat sisi praktis dari spiritualitas Reformed.
Spiritualitas Reformed: aspek eksistensial
Istilah “eksistensial” memiliki beragam arti dan dipahami dalam banyak cara. Tidak jarang makna yang dipetik dari istilah ini cenderung negatif. Kecenderungan ini diidentikkan dengan para teolog eksistensial di era Pencerahan yang mengedepankan otonomi manusia maupun pengalaman subjektif manusia yang tidak terkontrol oleh kebenaran yang objektif. Dalam artikel ini istilah “eksistensial” dipahami secara netral dalam kaitan dengan pengalaman seseorang bersama Allah.
Bagian ini akan menunjukkan bahwa spiritualitas Reformed seharusnya tidak kering seperti yang dituduhkan banyak orang. Spiritualitas Reformed lebih dari sekadar kumpulan proposisi teologis-filosofis tentang Allah. Dalam tradisi Reformed, spiritualitas tidak boleh diidentikkan dengan pengetahuan teoritis. Kenyataannya, salah satu karakteristik dari teologi Reformed bahkan adalah “theology as a practical science.”
Memaparkan spiritualitas Reformed secara komprehensif merupakan tugas yang sangat berat bagi siapapun juga. Beranjak dari pertimbangan ini, maka pembahasan aspek eksistensial dalam spiritualitas Reformed hanya akan dilihat dari tiga perwakilan saja: John Calvin, Katekismus Heidelberg, dan J. I. Packer. Pembatasan ini tidak berarti pengabaian terhadap tokoh atau dokumen yang lain. Bagaimanapun, dalam ruang yang terbatas ini seleksi tetap harus dilakukan dan semoga pemilihan ini tidak mengecewakan.
Beberapa orang terhalang untuk berjumpa dengan Tuhan karena hambatan intelektual. John Calvin menuliskan buku Institutes of Christian Religion dengan tujuan agar pembacanya bisa membaca Kitab Suci dengan baik. Pada saat ia mengajarkan tentang apapun, logika selalu ditempatkan setelah apa yang ditulis di dalam Alkitab. Penjelasan logis terhadap sebuah ayat akan ia berikan setelah mempelajari sampai ke teks aslinya. Demikian pula ketika ia hendak menyanggah pandangan orang lain. Pendeknya, ia adalah seorang ahli biblika yang brilian.
Lebih dari sekadar ahli biblika dan penulis sistematika teologi, Calvin sebenarnya sangat menekankan aspek praktis dari pengajarannya. Sesuatu yang luar biasa dituliskan oleh John T. McNeill mengenai teologi Calvin, “His piety described at length” (bdk. 1Pet. 1:16). Bagi Calvin, Alkitab adalah dasar dari spiritualitas yang benar.
Bahkan salah satu biografi tentang John Calvin menuliskan bahwa ia tidak mau diganggu sedikitpun saat sedang belajar. Sampai suatu ketika ada seseorang yang memiliki kebutuhan mendesak untuk bertemu dengan Calvin. Ketika ia masuk ke ruang belajarnya, Calvin tidak marah. Jawaban Calvin adalah, “Let us find out why God sends you here.” Ini adalah salah satu bentuk penerapan doktrin kedaulatan Allah yang nyata dalam kehidupan Calvin.
Dalam tulisan John Calvin, spiritualitas lebih mengarah pada relasi dengan Allah daripada pengetahuan teoritis tentang Dia. Menguasai teologi sangat berbeda dengan mengenal Allah secara pribadi. Walaupun Calvin diakui sepanjang zaman sebagai seorang teolog yang sangat brilian, tetapi ia tetap meletakkan relasi dengan Tuhan sebagai prioritas tertinggi. Francois Wendel, salah seorang pakar terkemuka dalam studi tentang Calvin menulis demikian, “What interests Calvin is not an abstract knowledge of God such as we might deduce from philosophy; on the contrary, it is a knowledge of what he is in relation to ourselves, the knowledge which, as Luther also taught, brings us to love and fear God and render him thanks for his benefits.”
Allah menyatakan diri-Nya hanya dalam konteks membangun relasi dengan kita. Allah tidak pernah menyatakan diri-Nya hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia. Itulah sebabnnya setiap doktrin yang kita percayai dan pahami harus benar-benar dilakukan secara serius. Biarlah hidup kita dikuasai oleh teologi kita.
Konsep di atas diungkapkan secara eksplisit oleh Calvin dalam karya monumentalnya, Institutes of the Christian Religion. Di bagian pengantar buku ini yang ditujukan kepada Raja Francis I, ia menjelaskan tujuan penulisan karyanya sebagai berikut, “My intention was only to furnish a kind of rudiments, by which those who feel some interest in religion might be trained to true godliness.”
Walaupun Calvin sangat menekankan aspek praktis dalam spiritualitas, namun ia sangat berbeda dengan para penganut spiritualitas postmodern yang sangat subjektif dan tidak memiliki dasar objektif yang mutlak. Kesalehan (pietas) menurut Calvin didasarkan pada kebenaran objektif yang sangat esensial. Spiritualitas bukanlah bersumber dari praktik-praktik keagamaan yang superfisial. Kerohanian bukanlah mengikuti tatanan moralitas tertentu. Dasar dari segala kerohanian sejati adalah persekutuan mistis (mystical union) dengan Kristus. “Not only does he cleave to us by an indivisible bond of fellowship, but with a wonderful communion, day by day, he grows more and more into one body with us, until he becomes completely one with us.” (Institutes III.2.24) à bdk. Gal. 2:20; Flp. 1:21a.
Secara historis, persekutuan mistis (mystical union) dengan Kristus sudah terjadi sejak kekekalan di mana Allah sudah merancangkan penebusan dengan tujuan supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya (Rm. 8:29; 2Kor. 3:18; Kol. 3:10). Dengan kata lain, kerohanian sejatinya adalah perjalanan menjadi serupa dengan Kristus. Konsep kerohanian seperti ini sangat berpusatkan kepada Kristus. Kerohanian yang dipisahkan dari Kristus bukanlah kerohanian ala Reformed.
Segala sesuatu yang kita lakukan harus berkaitan dengan Kristus. Setiap aspek hidup kita harus berpusatkan kepada Kristus. Tidak heran, Paulus berani menuliskan kalimat yang sangat terkenal sekali dalam 1 Korintus 10:31. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan bahkan dalam hal-hal yang dipandang sepele sekalipun (bandingkan artikel berikut ini).
Abraham Kuyper, seorang teolog Reformed yang sangat disegani pernah menuliskan hal senada dalam salah satu bukunya, “There is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is Sovereign over all, does not cry, Mine!” Dengan kata lain, Kristus berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kita. Dialah yang menggerakkan seluruh kehidupan kita.
Perenungan mendalam terhadap doktrin ini membuat kita terkagum-kagum akan relevansinya. Tujuan hidup kita adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan ini tidak mungkin dicapai jika Dia tidak melakukan segalanya untuk kita. Dia mati untuk menyelesaikan persoalan kita yang terbesar yaitu dosa. Dia bangkit untuk mengalahkan ketakutan kita yang terbesar yaitu maut. Dia memberi kita kuasa untuk hidup terus semakin serupa dengan Dia dalam pengudusan seumur hidup. Doktrin ini seharusnya membuat kita terus memikirkan segala sesuatu yang kita lakukan dalam terang Injil Yesus Kristus. Segala keputusan dan pilihan yang kita buat harus berkaitan dengan penebusan Kristus dan Kerajaan Allah di muka bumi. Apa yang kita pilih dan lakukan dalam hidup ini tidak boleh menjadi penghambat bagi kepentingan Kristus dan pembangunan Kerajaan Allah di dunia. Studi kita, pekerjaan kita, cara kita berumah tangga, bahkan cara kita berhubungan seksual harus menjadi fasilitator bagi kepentingan Injil Yesus Kristus dan pembangunan Kerajaan Allah di dunia.
Ini merupakan akar dari spiritualitas Reformed. Seluruh orang percaya telah dipersatukan begitu rupa dengan Kristus sehingga apa yang Ia lakukan dapat dinikmati oleh orang percaya. David Willis-Watkins, seperti dikutip oleh Joel R. Beeke menandaskan pentingnya kesatuan ini dalam ungkapan berikut, “Calvin’s doctrine of union with Christ is one of the most consistently influential features of his theology and ethics, if not the single most important teaching that animates the whole of his thought and his personal life.”
Tujuan dari kesalehan yang sejati adalah kemuliaan Allah (Soli Deo Gloria). Dalam Institutio III.7.1 Calvin menulis, We are God’s: let us therefore live for him and die for him. We are God’s: let his wisdom and will therefore rule all our actions. We are God’s: let all the parts of our life accordingly strive toward him as only lawful goal” (bdk. Luk. 17:10; Rm. 3:36). Semua persoalan kita bersumber dari fokus dan tujuan hidup yang keliru. Tujuan hidup yang benar akan menghindarkan kita dari banyak masalah. Mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas alam semesta memang mudah, namun akan menjadi sebuah hal yang sulit untuk melakukan hal yang sama atas hidup kita. Kesalehan semacam ini ditunjukkan Ayub dalam akhir pergumulannya bersama Allah (Ay. 42:2). Allah berhak melakukan apa saja dalam hidup kita demi kemuliaan-Nya.
Dalam perkembangan selanjutnya aspek eksistensial dalam spiritualitas Reformed tetap dipertahankan. Yang menarik adalah cara Katekismus Heidelberg dimulai. Dalam diskusi teologi di tradisi Reformed, topik pertama yang sering diulas biasanya adalah tentang Allah atau Alkitab. Hal berbeda dapat ditemukan dalam Katekismus Heidelberg. Katekismus ini dimulai dengan topik yang berkaitan dengan manusia dan langsung menyentuh kebutuhan terbesar dalam hidup manusia. Pertanyaan pertama berhubungan dengan penghiburan satu-satunya bagi manusia selama hidup di dunia ini dan yang akan datang.
Keputusan untuk memulai katekismus dengan cara seperti ini jelas bukan suatu kebetulan. Posisi pertanyaan ini menyiratkan bahwa para perumus Katekismus Heidelberg memandang teologi sebagai sentuhan praktis bagi kebutuhan riil manusia. Katekismus ini bukan hanya berusaha menyampaikan suatu pengetauan, tetapi memenuhi sebuah kebutuhan. Herman Hoeksema dalam tafsiran klasiknya tentang Katekismus Heidelberg menulis demikian, “Man is more intellect, mind or reason. He is also volitional being. He has a will, emotions, desires, imangination, feelings. He is a being with ‘heart and mind and soul and strength’. And comfort concerns the whole man...faith is more than knowledge, it is also confidence. Religion is more than doctrine, it is life and joy. And comfort is more than a mere decision of the mind, it is also a determination of the will, affecting all the desires and emotions.”
Spiritualitas yang hanya dilekatkan pada aspek intelektual akan membuat kita kehilangan banyak hal. Sebab manusia bukan hanya makhluk rasional, tetapi juga makhluk emosional. Semuanya itu harus disentuh di dalam ibadah Reformed. Ibadah kita seharusnya adalah ibadah yang bebas; bukan berarti kita bisa berbuat apapun semaunya. Ruang bagi pekerjaan Roh Kudus harus disediakan lebih luas untuk menyentuh diri kita sebagai manusia seutuhnya. Ekspresi yang sopan dan teratur harus diterima dengan tangan terbuka. Sentuhan yang diberikan bukan hanya terpaku pada aspek intelektual, melainkan juga mulai bermain di ranah imajinasi dan perasaan emosional.
Pada zaman modern ini spiritualitas Reformed yang membumi tetap mendapat perhatian utama. Salah satunya diungkapkan oleh J. I. Packer, seorang tokoh Reformed modern dalam bukunya yang sangat terkenal yang berjudul Knowing God. Dalam karyanya ini Packer menegaskan keterkaitan yang tepat antara doktrin dan spiritualitas. Menuturnya, spiritualitas tidak dapat dibatasi atau diidentikkan dengan pengetahuan teologi yang mendalam, walaupun pengetahuan doktrinal tetap diperlukan bagi spiritualitas yang sejati. Ia mengungkapkan, “There can be no spiritual health without doctrinal knowledge; but it is equally true that there can be no spiritual health with it, if it sought for the wrong purpoe and valued by the wrong standard. In this way, doctrinal study really can become a danger to spiritual life.”
Harus diakui, tidak mungkin ada kerohanian yang sehat tanpa doktrin yang benar. Namun sering kali doktrin yang benar tidak secara otomatis menghasilkan kerohanian yang sehat. Doktrin sering kali menjadi bahaya bagi kerohanian. Hal ini mungkin disebabkan oleh upaya pembelajaran doktrin dengan tujuan yang keliru. Sebagai contoh adalah orang-orang yang bertanya kepada saya hanya untuk mencari pembenaran atas konsep dan tindakannya, bukan secara serius mencari tahu mana yang benar. Memuaskan rasa ingin tahu, meraih kemenangan dalam perdebatan, hanyalah contoh lain dari motivasi yang keliru terhadap pembelajaran doktrin. Teologi seharusnya berujung pada doksologi.
Jika kita tidak melakukan kebenaran, kita hanya bisa menunjukkan orang lain salah, tetapi tidak akan pernah bisa membimbing orang itu ke dalam kebenaran. Hal ini disebabkan karena kita tidak memiliki kesaksian hidup yang persuasif. Pendeknya, teologi yang benar harus berkaitan erat dengan spiritualitas.
Di bagian selanjutnya Packer juga memberikan nasihat praktis tentang bagaimana orang Kristen dapat meningkatkan spiritualitas mereka. Dari sekadar tahu tentang Allah menjadi benar-benar mengalami Allah secara pribadi. Dari sebuah pengetahuan teologis yang teoritis menjadi devosi praktis yang mendekatkan orang percaya dengan Allah. “It is that we turn each truth that we learn about God into matter of for meditation before God, leading to prayer and praise to God”. Jika ini dilakukan secara konsisten, maka orang-orang Reformed akan terhindar dari gejala intelektualisme.
Selama teologi kita tidak membuat kita mengenal dan memuji Dia, maka teologi kita menjadi teologi yang keliru. Buku “The Holiness of God” karya R. C. Sproul sangat membantu kita dalam mengaitkan doktrin dengan spiritualitas.
Konklusi
Tanpa bermaksud menjadikan aliran karismatik sebagai seteru dalam Kerajaan Allah, aliran Reformed seharusnya bisa melakukan lebih banyak hal lagi dibandingkan aliran karismatik. Kalau mereka mencoba menjangkau dan mengisi kekosongan jiwa orang-orang postmodern dengan menawarkan spiritualitas yang sangat praktis tetapi kurang mendasar, maka tradisi Reformed seyogianya mampu menawarkan kedua hal tersebut.
Bukankah seharusnya Injil Yesus Kristus yang benar – kematian-Nya, kebangkitan-Nya, dan kenaikan-Nya ke surga – yang lebih sering diberitakan? Bukankah khotbah yang Alkitabiah – sesuai dengan maksud penulis Alkitab, berfokus pada teks, dan mendalam – yang lebih dijadikan fokus dalam ibadah? Bukankah khotbah yang benar - tentang dosa dan kesucian hidup - yang lebih sering diperdengarkan daripada hiburan kosong tentang kesembuhan, kemakmuran, mukjizat, dan kesuksesan?
Problem yang dihadapi orang-orang Reformed bukanlah kekeliruan atau keseimbangan. Kelemahan terbesar hanya terletak pada upaya relevansi yang kurang optimal. Orang-orang Reformed terlalu terkungkung dengan mainan baru berupa pergumulan intelektual yang mendalam. Kita lupa melihat sesuatu yang esensial di balik semua diskusi logis tersebut: spiritualitas yang membumi. Kehidupan doa yang teratur, ibadah yang menekankan perjumpaan pribadi dengan Allah, firman Tuhan yang mampu menjawab kebutuhan zaman, dan sentuhan-sentuhan emosi yang wajar dan tepat merupakan hal-hal yang perlu digali ulang dari warisan teologi Reformed yang sangat konsisten dan seimbang.
Karakteristik spiritualitas Reformed bahkan dapat dikatakan sangat biblikal. Kita harus kritis melihat segala sesuatu dari perspektif Alkitab. Penafsiran Alkitab yang benar dan bertanggung jawab mutlak diperlukan dalam memahami segala sesuatu. Jangan sungkan berbeda pendapat dengan pendeta manapun. Jangan sungkan untuk mempertanyakan materi seminar dari pembicara manapun. Pendeta Reformed bukan standar kebenaran. Diri kita sendiri juga bukan standar kebenaran. Firman Tuhan adalah standar kebenaran. Jangan bangga kalau kita lebih banyak tahu kalimat-kalimat terkenal dari tokoh Reformed sekaliber Augustine, John Calvin, Abraham Kuyper, Cornelius Van Til, J. I. Packer, Michael Horton, Richard Pratt, Ravi Zacharias, Steven Lawson, John Piper, Timothy Keller, bahkan Stephen Tong. Semua kutipan dari mereka harus diuji kebenarannya melalui firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab harus ditolak. Inilah yang dilakukan para reformator pada waktu mendirikan gerakan Protestan.
Karakteristik spiritualitas Reformed yang lain adalah teosentris. Allah adalah motor penggerak hidup kita. Allah bukan salah satu yang terutama, tetapi satu-satunya! Ia tidak ada bandingannya. Jika kita menempatkan Allah pada urutan pertama dalam prioritas hidup, maka kita telah merendahkan Dia. Sebab Ia masih kita tempatkan dalam kategori yang sama dengan ciptaan-Nya.
Selain itu, karakteristik yang lain adalah kristo-sentris (berpusat kepada Kristus). Nasihat Schaeffer patut diperdengarkan kembali bagi gereja-gereja Reformed saat ini, “The first point that we must make is that it is impossible even to begin living the Christian life, or to know anything of true spirituality, before one is a Christian. And the only way to become a Christian is neither by trying to live some sort of a Christian life nor by hoping for some sort of religious experience, but rather by accepting Christ as Savior.” Spiritualitas selalu berkaitan dengan status kita sebagai orang Kristen.
Salib Kristus dan kubur yang kosong harus senantiasa menguasai pemikiran dan gaya hidup kita. Selama kita tidak mampu mengaitkan apapun yang kita lakukan dengan Injil Yesus Kristus, maka kita tidak sedang berada dalam spiritualitas ala Reformed. Apa yang Yesus lakukan dalam karya penebusan-Nya yang sempurna itulah yang menjadikan hidup kita penuh arti. Jika kita tidak tahu apa makna, nilai, dan tujuan hidup kita di dalam Kristus, we are merely existing rather than living.
Spiritualitas tidak selalu hanya berkaitan antara Tuhan dengan kita saja. Relasi kita dengan sesama dan alam juga patut mendapat perhatian. Allah menciptakan kita secara utuh. Ia memberikan mandat untuk menguasai seluruh bumi. Teologi Reformed selalu didasarkan pada wawasan dunia Kristen (penciptaan, kejatuhan, penebusan, pemulihan segala sesuatu). Topik apapun yang kita bicarakan harus berangkat dari pemahaman ini. Apa yang ada dalam penciptaan? Apa yang hilang dan rusak di dalam kejatuhan? Bagaimana penebusan Kristus memulihkan itu semua? Dan bagaimana semuanya akan berakhir dengan harapan yang berujung pada kemenangan? Inilah kerohanian Reformed yang utuh.
Spiritualitas Reformed juga berkaitan erat dengan keunikan, superioritas, dan relevansi kekristenan dengan wawasan dunia yang lain. Setiap wawasan dunia menjelaskan akar persoalan terbesar yang terjadi di dunia ini, beserta dengan solusi yang mereka tawarkan sampai dengan tujuan akhirnya. Kekristenan memenuhi kebutuhan mendasar umat manusia (yaitu relasi kasih) dengan sangat tepat. Ditinjau dari sisi manapun, jawaban (baca: kebenaran) yang disediakan kekristenan jauh lebih baik, masuk akal, dan relevan dibandingkan dengan alternatif lain yang disediakan manusia. Spiritualitas yang sehat dicirikan dengan ketertarikan yang kuat untuk menghubungkan Injil Yesus Kristus dengan kebutuhan mendasar umat manusia. Di luar itu, tidak ada spiritualitas yang bisa memuaskan kita secara utuh. Solusi dan kemenangan sudah ditemukan dalam Injil Yesus Kristus. Kiranya spiritualitas kita selalu berujung pada persembahan hidup yang olehnya Allah dimuliakan dan Kerajaan-Nya terus dikembangkan.
Bacaan penting :
- Alister E. McGrath, Spirituality in An Age of Change.
- James Montgomery Boice, The Future of Reformed Theology.
- Cornelius Van Til, Defense of The Faith.
- J. Richard Middleton & Brian J. Walsh, Truth Is Stranger Than It Used To Be: Biblical Faith in a Postmodern Age (Downers Grove: InterVarsityPress, 1995)
- Alister E. McGrath, Intellectuals Don’t Need God & Other Modern Myths.
- David Tacey, The Spirituality Revolution.
- John T. McNeill, The History and Character of Calvinism (New York: Oxford University Press, 1954).
- John Calvin, Institutes of Christian Religion, ed. John T McNeill, trans. Ford Lewis Battles, vol. 20 of The Library of Christian Classics (Philadelphia: Westminster, 1960).
- Augustine of Hippo, Confessions.
- Serene Jones, Calvin & The Rhetoric of Piety.
- Howard L. Rice, Reformed Spirituality: An Introduction for Believers.
- Francois Wendel, Calvin: Origins and Development of His Religious Thought, translated by Philip Maier (Durham: The Labyrinth Press, 1963).
- Joel Beeke, Calvin for Today, (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2010).
- Abraham Kuyper, “Sphere Sovereignty,” in Abraham Kuyper: A Centennial Reader, ed. James D. Bratt (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1998).
- Herman Hoeksema, The Heidelberg Catechism (An Expositional): Triple Knowledge, In the Midst of Death [Grand Rapids: Eerdmans, 1943].
- J. I. Packer, Knowing God (Downers Grove: InterVarsityPress, 1973).
- R. C. Sproul, The Holiness of God (Tyndale Momentum; 2nd Revised, Expanded ed. edition, July 1, 2000).
- Francis A. Schaeffer, True Spirituality (Wheaton, III.: Tyndale House Publishers, 1971, 2001).