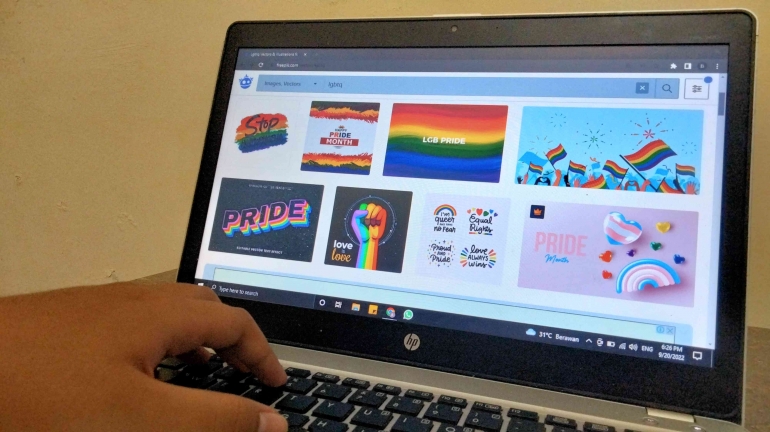SEMARANG (23/09/2022) - Universitas sejatinya menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mencari jati diri, mengasah skill, melatih kemampuan bersosialisasi, dan mengembangkan value diri. Namun, mahasiswa yang tergabung dalam komunitas LGBTQIA+ dan menunjukkan ekspresi gender yang berbeda dari norma serta nilai yang ada di masyarakat, masih sering mendapat persekusi di lingkungan akademik ketika identitas mereka terkuak.
Alex (bukan nama asli) merupakan seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) yang mengaku memiliki orientasi seksual gay. Meski begitu, ia menekankan ekspresi gender yang dimilikinya adalah cis man. “Selama ini aku tetap berperilaku sebagai laki-laki dan aku mengidentifikasi diriku sebagai laki-laki normal pada umumnya. Style ku normal, cara bicaraku normal, sikapku normal, aku tetap laki-laki,” tutur pemuda berdomisili Jakarta ini.
Dia menerima jati dirinya sebagai seseorang yang memiliki orientasi seksual gay ketika berada di tingkat dua bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Tidak ada penolakan (denial) yang ia rasakan ketika menyadari hal tersebut, dia mengatakan justru ia merasa lega karena tahap eksplor jati diri telah ia lalui, jawaban atas segala pertanyaannya telah terjawab.
“Waktu SMP aku pernah kena bully, karena kata mereka aku lekong. Padahal aku merasa biasa-biasa aja. Aku sempat punya curiosity, apa benar aku berbeda? Waktu tau jawabannya kalau aku gay rasanya lega, karena memang jawaban itu yang aku cari,” terangnya.
Meski begitu, ia belum siap ketika identias seksualnya tersebar secara luas. Di lingkup perkuliahan, orientasi seksualnya mulai terbongkar ketika ia memutuskan untuk bercerita kepada beberapa teman yang dipercayai. Namun, ia tak menyangka seksualitasnya dapat menyebar dalam hitungan bulan. Akibatnya, ia mendapatkan persekusi yang cukup ekstrim hingga membuatnya merasa takut, tidak aman, dan sempat kehilangan motivasi untuk mengikuti perkuliahan. Persekusi ekstrim ini justru datang dari lingkup teman sebaya.
“Masa terberat yang aku lalui ada di semester dua sampai tiga, karena aku mulai merasa dijauhi dan teman-teman gosipin aku yang buruk-buruk di belakang,” ujarnya.
Persekusi yang paling menyakitkan ia rasakan ketika dalam suatu mata kuliah terdapat tugas kelompok. Ia sering ditolak ketika mengajukan diri menjadi anggota kelompok, mahasiswa dalam kelas tersebut enggan bekerja sama dengan Alex tanpa alasan yang jelas.
“Aku malas kalau ada tugas kelompok. Waktu semester dua atau tiga itu parah banget. Aku sampai merasa apakah value diriku hanya sebatas orientasi seksual? Padahal aku bisa berkontribusi lebih,” ungkapnya.
Persekusi lain yang membuatnya sempat merasa down terjadi ketika ia bergabung dalam sebuah kepanitiaan mahasiswa. Mahasiswa yang tergabung dalam kepanitiaan tersebut seringkali bergosip, mencemooh, dan mengolok-olok Alex terkait orientasi seksual dan ekspresi gendernya.
“Waktu rapat kepanitiaan mereka ngomongin orientasi seksualku di belakang. Aku kecewa banget karena orang yang aku percayai malah menyebarkan seksualitasku dan khianatin kepercayaanku,”

Tidak mudah bagi orang seperti Alex untuk coming out mengenai orientasi seksual yang dimiliki, norma dan nilai yang tertanam di masyarakat tentunya menentang “penyimpangan” ini. Alex mengatakan di lingkup Undip cukup banyak mahasiswa yang tergabung dalam komunitas LGBTQIA+. Rata-rata dari mereka berkomunikasi serta membuka jati diri melalui media sosial dan group chatting khusus.
Mereka membangun kepercayaan satu sama lain karena berada dalam komunitas yang sama, dan merasakan perasaan yang sama. Interaksi yang mereka lakukan di lingkup universitas bersifat professional dengan sebisa mungkin menghindari pembahasan mengenai orientasi seksual dan ekspresi gender yang mereka miliki.
“Walaupun aku tau kalau dia ‘sama’ seperti aku lewat gay radar, aku nggak akan serta-merta tanya orientasi seksualnya, karena aku tau gimana rasa unsafe waktu orang lain tiba-tiba tanya orientasi seksualku. Cukup sekedar tau, kalau interaksi paling lewat media sosial,” jelas Alex.
Sementara itu, Kei (bukan nama asli), seorang mahasiswi FISIP Undip angkatan 2019 berdomisili di Semarang, mengatakan selama ini ia tidak pernah mendapatkan diskriminasi yang terlampau ekstrim baik di lingkup pertemanan maupun akademik terkait orientasi seksualnya (bisexual). Cemoohan yang ia dapat justru berasal dari ekspresi gender yang dimiliki, Kei mengaku dirinya androgyny atau biasa disebut tomboy.
“Kalau orientasi seksual aku sangat merahasiakannya, aku belum merasa aman, jadi nggak banyak yang tau. Kalau soal ekspresi gender, penampilan, sering dikomentari ‘cewek kok bajunya gitu, cewek kok tingkahnya gitu’ tapi yaudahlah aku cuek,” ucap gadis berusia 21 tahun itu.
Hal serupa diungkapkan oleh Blank (bukan nama asli), seorang mahasiswi Undip angkatan 2020 yang berdomisili di Semarang. Blank mengungkap bahwa sebenarnya mahasiswi yang tergabung dalam komunitas LGBTQIA+ memiliki resiko terungkap yang lebih rendah, karena Blank merasa perempuan dapat menyembunyikan identitas orientasi seksualnya dengan lebih mudah, selain itu perempuan dapat ‘berkamuflase’ dengan lebih baik.
“Kalau aku biasanya pura-pura idolain cowok atau pura-pura kelihatan suka sama cowok buat kamuflase. Lagipula, walaupun kami ini tergabung dalam komunitas LGBTQIA+ kami nggak sembarangan naksir sama orang. Kami punya kriteria juga seperi cishet (cis-hetero) man or woman. Atleast, kami nggak akan naksir mereka yang orientasi seksualnya straight,” jelas mahasisiwi berusia 20 tahun itu.
Mereka yang tergabung dalam kelompok minoritas LGBTQIA+ di Undip masih merasa tidak aman dan menyembunyikan seksualitas yang dimilikinya. Selain itu, mereka ingin dilihat sebagai human being yang memiliki value berdasarkan kemampuan yang dimiliki, mereka ingin dilihat seperti manusia pada umumnya dan tidak dinilai sebelah mata hanya karena orientasi seksualnya.

Menanggapi adanya cerita diskriminasi serta persekusi ekstrim yang didapatkan mahasiswa FISIP terkait orientasi seksualnya, Luthfi Maulana Adhari (20), Pemimpin Redaksi (Pemred) Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) OPINI mengatakan bahwa OPINI bersedia menampung cerita-cerita teman mahasiswa dan menjamin kerahasiaan identitas mereka.
“Sebagai lembaga pers, kami sangat terbuka dengan isu kelompok minoritas, termasuk LGBTQIA+. Kebetulan kami juga lagi fokus dengan isu-isu seperti ini.”
Mengenai kasus pembatalan diskusi Ngopi 6 “Ngobrol Pintar” dengan tema Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) LPM Gema Keadilan (LPM Fakultas Hukum) 2015 silam, LPM OPINI berani menjamin hal serupa tidak akan terjadi. LPM OPINI mengakomodasi melalui liputan-liputan dan bukan diskusi umum terbuka.
“Kalau diskusi terbuka banyak resiko, bukannya membantu mereka malah sebaliknya,” terangnya. Ia menambahkan, sudah menjadi tugas jurnalis untuk melindungi segala identitas yang tidak ingin ditunjukkan oleh narasumber, serta membantu kelompok minoritas untuk menyuarakan aspirasinya dalam bentuk tulisan. (Fan/Fan)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H