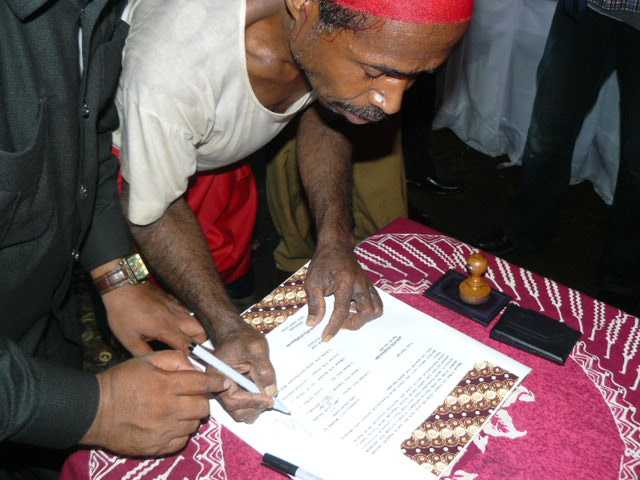kami cuma tulang-tulang berseraka...
...jiwa kami melayang untuk kemerdekaan
kemenangan dan harapan atau tidak untuk apa-apa ---Chairil Anwar, Sajak Kerawang Bekasi
Di tubuh surat ini, kunyatakan segala kekaguman milikmu. Kau yang tulangmu berseraka, adalah Manusia Ideal. Tanpa keraguan sedikitpun, tentang kataku. Kesadaran penuh, kau bangkit merubah keadaan. Dengan nyawa ataupun kematian kau membayarnya, lunas. Sungguh! kaulah manusia pilihan, hidup di tengah-tengah "manusia kebanyakan". Di waktu nun singkat, tunai sudah tanggungjawabmu sebagai manusia. Satu daritugas mulia, harap langit.
Kepahlawanan adalah bukti kecintaan. Chairil Anwar, memapar dalam puisinya; "Kami cuma tulang-tulang berseraka, jiwa kami melayang untuk kemerdekaan. Sudah barangtentu, membincang cinta, sama halnya membincang kesetiaan pengorbanan. "Cinta adalah perihal memberi, bukan mengambil ataupun merampas.
Cinta memilih dirinya mati, agar yang lain hidup. Agar suatu cita-cita menang, agar suatu impian menjadi kenyataan." Kira-kira begitulah pendakuan Ali Syarati, Sosolog dan arsitek revolusi Islam Iran. Di makam ini, pahlawan adalah pecinta sejati.
Dapat dipasti, bahwa, tatkala dahaga, lapar, haus, perih, dan luka melebur menjadi satu di tubuh, kalian memilih bungkam, sembunyi pelbagai sakit. Tenimbang mengumbar, pangkalnya menghimpun iba, atas diri. Tentu, bukanlah ciri seorang pahlawan. Semua ini, hanya satu harap menguat baja---kelak, taklagi ada airmata ataupun darah, melainkan bersemayam senyum di angkasa Nusantara.
Dari Sabang sampai Merauke, entah berapa banyak pusaramu---pahlawan? Selayaknya, di hari sepuluh, bulan November, meski disepakati sebagai ritus yang dikultus. Tentang nilai, perjuangan, kesetiaan, cinta, dan pengorbanan---dengannya kami petik, jadilah lakon hidup dan tindak. Taklagi ada pijakan ketauladanan di negeri ini, selain pada dirimu."...Kemenangan dan harapan atau tidak untuk apa-apa".
Adalah setumpuk ciri yang mengakar. Pahlawan, seorang yang rela mengorbankan jiwa serta raganya. Jelas bahwa, sejarah telah mengajarkan kepada kita; bahwa di masa silam, siapa pahlawan? Siapa pecundang? Sejarah merekam track record orang besar, penutur di masa datang, tentang kebenaran di masa silam. Kelak sejarah dipolitisasi, mereka yang rendah secara pengetahuan dan moral.
Maka tugas kita, kembali menjernikan sejarah yang telah tercemar. Sebab, sebaik-baiknya generasi, menurut pendakuan Maxim Gorki; The people must know their history---setiap orang harus tahu tentang sejarahnya.
Kutulis surat ini, hendak bermaksud, pengganti ziarahku. Apalah daya, jarak merentang, menentang sua. Wahai yang mengorban jiwanya, kuingin surat---sesari doa, sampai ke pusaramu, sebelum pagi membuka mata. Ataupun, para pejabat negeri datang berziarah, yang sesungguhnya, memanjatkan doa-doa paling sial.
Mulutnya bau kebohongan, doa yang ditumbuh kembangkan adalah gugusan kutukan yang abadi. Begitujuga, tangan mereka yang zalim menabur bunga. Sepenuhnya beraroma keringat, airmata, dan darah rakyatnya sendiri. Jika tidak berlebihan, "pejabat negeri ini, taklebih dari kumpulan orang-orang pendir yang lalai. Semeskinya dilihat sebagai pelaku tindak kriminal,"---perihal ini yang meski kukabarkan, di tubuh surat ini.
Satu dari sekian kekhawatiranmu, yaitu kehidupan orang Desa, kelak. Orang Desa absen dari nalar pejabat negeri ini. Padahal, orang Desa adalah museum leluhur. Perjuangan membebaskan orang Desa dari penjajahan, penindasan, dan eksploitasi adalah buah dari sejarah perjuangan bangsa. Menilik sejarah orang Desa adalah sejarah pemerasan.
Seolah-olah potret orang Desa tersaji dari pemerasan airmata dan darah. Apakah tanpa pemerasan airmata dan darah, sejarah tidak lahir? Apa benar, "Hidup adalah kesengsaraan dan manusia tidak dapat menghindarinya?" kata sang Budha.
Saya tumbuh besar di desa, dalam peluk hangat orang Desa. Ayahku kerap berkata: "Orang Desa tersenyum, kala leluhur negeri ini masih hidup. Kini mereka telah tiada. Senyum orang Desa pun memudar. Orang Desa tak sanggup bermimpi. Entah, kepada siapa mimpi itu, diharap? Pejabat negeri ini, bungkam dengan jeritan orang Desa.
Bungkam dengan jeritan pohon-pohon, yang takhenti dari gemuruh gergaji. Bungkam dengan jeritan lahan-lahan yang telah dibabat habis. Demi nasib perkebunan dan industrialis kaum kapitalis. Bungkam dengan jeritan suara burung kakatua, cendrawasih, krisis akan huniannya. Bungkam dengan jeritan nasib tanah adat, cagar budaya, cagar alam, hutan konservasi, hutan produksi, tak tahu wujudnya di lembaran hukum agraria. Bungkam dengan jeritan para nelayan.
Barangkali perubahan hanya milik orang Kota? Yang kehidupannya serba-serbi lengkap; elit, pejabat, pengusaha, cendikiawan, aktivis, dokter, dan guru. Semuanya tinggal di kota. Pembangunan pun masih difokuskan di kota. Padahal kehidupan mereka jauh lebih baik. Sungguh miris, di desa terpencil, guru, dokter, takut bermukim di desa.
Rumah sakit dan sekolah, jauh dari kata spesialis menyembuhkan dan mendidik. Apakah pejabat negeri ini lupa dengan kami yang tinggal di desa? Ataukah mereka sibuk dengan akumulasi kekayaan alam desa? Segala kekayaan; emas,minyak bumi, nikel, batubara, dan gas. Semuanya dirampas dari desa kami.
Pejabat negeri ini, semeskinya bertanggung jawab dihadapan Tuhan, leluhur negeri, dan generasi mendatang. Saatnya pula, mereka belajar mencintai dan belajar melindungi rakyat kecil, tanpa embel-embel ideologis. Apalagi politik. Belajar dan menggali lebih dalam tentang Pancasila, satu dariwarisan leluhur negeri. Adalah Pancasila---representasi nilai-nilai kehidupan, digali dari kebiasaan hidup orang Desa. Dari merekalah, Nusantara disatu. Meski berbeda secara budaya, etnis, bahasa, dan agama.
Namun, sebuah firasat besar mendobrak: " Bhinneka Tunggal Ika" semacam simpul pemersatu. Akhirnya, Bangsa ini dibentuk bukan lagi melindungi mayoritas atau melindungi minoritas. Tetapi, melindungi seluruh segenap bangsa Indonesia.
Syahdan. Di akhir surat ini, kukirimkan dikau puisi---sesari doa-doa orang desa:
Tujuh puluh dua tahun,
silam serpihan peluru dengan riang menggali luka, di dadamu
safarimu lusuh, koyak. Mengalir darah, airmata, membentuk parit kecil, amis.
Demi kemerdekaan desa, bangsaku nyawamu satu dikorban.
Entahlah, kau milik siapa?
Di hari ini, perjuangan dan buah gagasmu, lenyap bersama kematianmu.
Adalah kebesaran selalu-seiring dengan kematian.
Dikau menegas muasal, pancasilalah wasiatmu serupa museum lengah, pancasila sepi dilaku dan tindak.
Barangkali pancasila sekadar burung murung, terbang dari negeri Etopia, kemudian tersesat di angkasa Nusantara?
generasiku, ataupun di mulut pejabat, pancasila gagap dalam wicara dan wacana.
Pancasila taklebih dari sehimpun gagasan liar, binal, dan banal.
Bagitu miris, nurani terpojok, terperosok pancasila taklagi museum---gubuk etis, etos, dan walas asih.
sekarang
nanti
Salam sejahtra bagimu---para jejiwa suci di alam malakut!
Damailah dalam keabadianNya.
Negeri Adat Kiandarat, 5 November 2017
Ishak R. Boufakar
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H





![[Yang Terlewatkan dari Bulan Bahasa] Menulis Surat Cinta untuk Orangtua](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2024/11/06/https-asset-kgnewsroom-com-photo-pre-2023-02-02-0c2eaefc-18b8-4db8-9e02-594d7b3da918-jpg-672ae6e334777c22611d09e2.jpg?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)