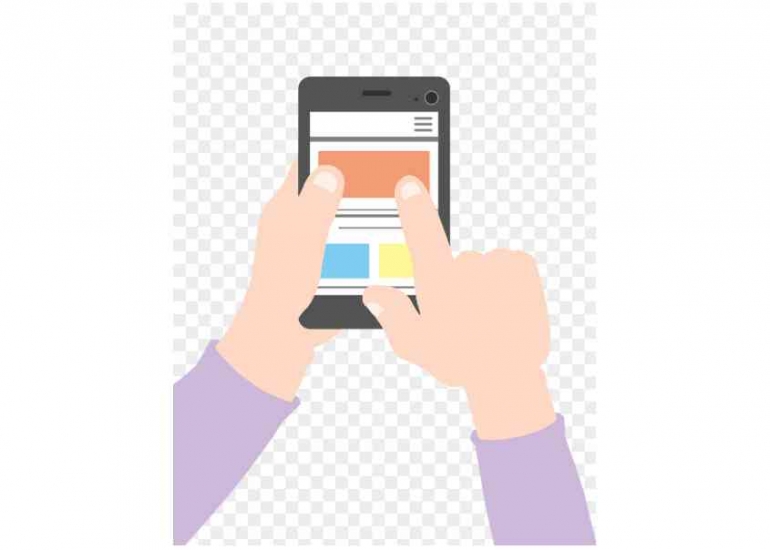Sepasang sahabat, seekor anjing darat dan seekor anjing laut, suatu ketika hendak bersenang-senang dengan melakukan balapan lari di tepi laut. Awalnya, mereka menikmati perlombaan lari tersebut, tetapi lama kelamaan anjing laut mengeluh kalau badannya sakit akibat tergores pasir pantai sehingga tidak dapat berlari lagi. Jadi, yang anjing darat lakukan kemudian, ia mengizinkan anjing laut untuk segera masuk ke air dan mereka pun tetap bisa berlomba selamanya---satu di darat dan satu lagi di air.
Ketika membaca cerita fabel tersebut, kebanyakan dari kita akan memiliki sentimen yang berbeda-beda. Entah siapa yang disalahkan sejak awal, apakah anjing darat yang terlalu egois atau anjing laut yang begitu bodoh, meski akhirnya keduanya menyadari kalau mereka tidak sepantasnya seperti itu sehingga kemudian menjalani koridor hidup yang sudah ditentukan untuk kebaikan bersama.
Meskipun sekilas tampak seperti dongeng belaka, sebenarnya ada banyak hal yang dapat dipelajari dari cerita awal di atas, seperti persahabatan, kerja sama, dan kesetaraan.
Dulu, cerita-cerita seperti itu merasuki budaya masyarakat kita sejak kecil hingga tua. Namun, kisah-kisah yang mengajarkan tentang rasa kebersamaan, kini hanya sebatas dongeng anak-anak dan tidak lagi beredar sebagai budaya seiring bertambahnya usia. Dunia telah banyak berubah sejak manusia menjadi sosok individual yang makin hedonisme.
Jika dulu tugas untuk menyampaikan kebaikan, keterampilan hidup, sejarah, dan informasi lainnya merupakan upaya kolektif yang dilakukan di lingkungan rumah, masyarakat, ataupun sekolah, saat ini semua kewenangan tersebut tampaknya telah diberikan kepada media komersial---seiring globalisasi internet memunculkan media-media daring yang dapat diakses oleh siapa pun.
Hal tersebut seakan-akan membenarkan adanya anggapan bahwa media komersial tak pelak seperti telah melampaui agama, seni, tradisi lisan, dan bahkan bertindak sebagai mesin penyampaian cerita yang hebat di zaman sekarang, yang artinya, siapa yang menceritakan kisah-kisah tradisi budaya akan dapat mengatur perilaku manusia ke depan.
Dari situlah letak permasalahan terbesarnya. Semua aplikasi dan situs berita yang berbeda, termasuk juga aplikasi jejaring sosial seperti Twitter (yang sekarang berganti X), You Tube, Facebook, Tik-Tok, akan terus berlomba-lomba menampilkan berbagai informasi yang baik maupun buruk, apalagi rata-rata masyarakat kita cenderung betah memeriksa berita di ponsel berjam-jam dan berkali-kali dalam satu hari.
Pada masa lalu, dibutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk mendengar kabar dari belahan dunia mana pun. Namun saat ini, kita seolah-olah memiliki segalanya di ujung jari. Berita yang bermunculan silih berganti dan rasanya tidak terhindarkan.
Ironisnya, kecenderungan orang-orang lebih memperhatikan dan mengingat berita-berita negatif daripada berita positif. Hampir setiap hari mereka akan terus menikmati pemberitaan dari media-media yang seolah-olah seragam menampilkan berita terkait kekacauan bangsa, termasuk pemberitaan buruk mengenai instrumen-instrumen yang ada di dalam negeri---katakanlah Indonesia. Mereka pun sepertinya terus-menerus terjebak ke dalam arus informasi negatif di semua platform dan dari setiap outlet berita dengan pesan yang selalu sama.
Berita buruk yang senantiasa tersaji, sesuatu yang mempermainkan emosi dan menanamkan rasa takut di dalam hati dengan memperingatkan mereka terhadap keadaan yang penuh dengan orang-orang yang ingin merusak, ideologi yang mengancam, dan kejadian tak terduga, dimaksudkan untuk membuat mereka tetap waspada. Namun, apakah dunia ini benar-benar seburuk yang media massa ingin orang-orang yakini atau apakah mereka menderita "sindrom dunia yang kejam"?
Istilah "sindrom dunia yang kejam" atau "mean world syndrome" yang pertama kali dicetuskan oleh Dr. George Gerbner pada tahun 1970, saat sedang melakukan penelitian tentang dampak konten terkait kekerasan terhadap pandangan orang-orang terhadap dunia, menunjukkan bahwa banyaknya kekerasan, baik melalui hiburan atau berita, dapat menyebabkan semacam bias kognitif yang membuat sebagian besar kita menganggap dunia lebih berbahaya daripada yang sebenarnya.
Hal yang paling menarik dari istilah ini (tidak peduli apakah masyarakat mengetahui konten yang dikonsumsi mereka merupakan konten faktual, seperti laporan berita, atau fiksi, seperti film) adalah efeknya tetap sama. Ketika terus-terusan dibombardir dengan informasi negatif, mereka mulai mengembangkan pandangan kehidupan yang sangat skeptis, curiga dan pesimis.
Jika hanya hal itu satu-satunya masalah media, mungkin masalahnya tidak terlalu buruk. Yang justru akan membuat kita merinding adalah orang-orang bodoh akan lebih bergantung, lebih mudah dimanipulasi atau dikendalikan, dan lebih rentan terhadap tindakan yang tampak sederhana, padahal justru memberi pengaruh garis keras terhadap pola pikir mereka.
Mungkinkah media dirancang untuk menyajikan berita terburuk kepada masyarakat untuk menanamkan rasa takut pada diri mereka sehingga mereka dapat lebih mudah dikendalikan oleh penguasa? Hal ini menjadi lebih masuk akal jika kita mempertimbangkan fakta bahwa sebagian besar media dikendalikan hanya oleh kaum kapitalis yang mengambil alih sebagian besar berita yang kemudian disebarkan ke seluruh penjuru wilayah masyarakat.
Katakanlah situasinya tidak seburuk itu, dan masyarakat kita tidak dikendalikan secara subversif oleh beberapa dalang pembuat ide berita, paling tidak semua media menginginkan satu hal yang sama, yaitu perhatian masyarakat---dan beberapa dari media-media itu akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Kelompok media mengetahui bahwa orang-orang lebih cenderung memperhatikan dan mengingat hal-hal negatif. Itulah sebabnya sebagian besar yang menyukainya akan menemukan lebih banyak berita negatif daripada berita positif di lapak platformnya.
Hal tersebut merupakan wujud polarisasi yang menarik dan membuat orang-orang terpaku pada layar digital yang pada gilirannya menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi pengiklan yang berperan mengalihkan perhatian (dalam hal ini lebih diuntungkan). Begitu orang-orang mulai menaruh perhatian, algoritma media sosial mengambil alih dan tiba-tiba mereka terus-menerus diberi berita yang menegaskan keyakinan mereka dan makin memperkuat pandangan mereka yang sudah menyimpang.
Bukan rahasia lagi bahwa konten kontroversial atau konten yang memicu respons emosional merupakan konten yang memiliki performa terbaik, paling banyak dibagikan, dan paling lama beredar. Jadi, suka atau tidak suka, masyarakat dibombardir dengan konten polarisasi yang tidak ada habisnya yang hanya membuat mereka semakin skeptis terhadap kondisi di sekitar mereka dan curiga terhadap siapa pun yang tidak memiliki keyakinan yang sama dengan mereka.
Masyarakat pada akhirnya malah terpecah belah dan bukannya bersatu seperti cerita-cerita di masa lalu. Kenyataan yang menyedihkan adalah, entah keadaan negeri makin buruk atau tidak, media hampir selalu membuat orang-orang berpikir demikian, hanya karena hal tersebut baik untuk bisnis.
Kebenaran yang seharusnya merupakan representasi fakta yang tidak memihak, tidak lagi menjadi inti pemberitaan. Cerita menjadi jauh lebih penting dan cerita yang menimbulkan emosi negatif sering kali mendapat lebih banyak perhatian, reaksi, dan pendapatan iklan.
Akibatnya, permasalahan yang terus-menerus digambarkan dalam film, media berita, dan media sosial, selalu dilebih-lebihkan hingga pada titik di mana masyarakat mungkin merasa tidak ada lagi harapan untuk melakukan apa pun untuk mengatasinya. Yang lebih buruk lagi adalah paparan terus-menerus terhadap informasi negatif yang tanpa henti didorong oleh algoritma obsesif dapat membingungkan otak sehingga hampir mustahil bisa membedakan antara fakta menarik dan fiksi yang mendebarkan.
Fakta bahwa berita palsu menyebar di media sosial jauh lebih cepat, lebih jauh, dan lebih dalam dibandingkan kebenarannya, juga ditemukan bahwa kesalahan informasi itu tidak disebarkan melalui bot, namun oleh tangan manusia dalam arti yang sebenarnya, yang turut menyebarkan. Sama seperti algoritma ini, otak manusia mengenali bahwa informasi yang paling memolarisasi, benar atau tidak, adalah informasi yang akan menjadi mewabah (viral) dan menimbulkan respons paling emosional dari masyarakat luas tanpa terlebih dahulu memverifikasi apakah informasi yang tersebar itu akurat.
Alasan lain mengapa dunia tampak jauh lebih buruk daripada yang orang-orang lihat adalah karena berita berbicara tentang hal-hal yang benar-benar terjadi dan bukan hal-hal yang tidak terjadi. Orang-orang tidak mendengar tentang kekacauan politik, misalnya, yang tidak pernah dimulai karena situasi yang baik-baik saja, sebab pasti ada faktor pemicunya.
Masyarakat akhirnya jarang mendengar berita baik karena sekali lagi, ini tidak semenarik berita buruk. Sedihnya, selama hal-hal buruk terus terjadi di muka bumi, ini akan selalu ada cukup banyak laporan negatif untuk mengisi berita, terutama dengan ponsel pintar yang kini memungkinkan orang secara pribadi menjadi reporter amatir dan penyelidik kejahatan. Sindrom dunia yang kejam berbicara langsung tentang ketakutan bawaan manusia yang kemudian memicu naluri masyarakat untuk melawan atau lari.
Meskipun karakteristik kelangsungan hidup ini sangat penting pada masa sekarang, saat ini yang media lakukan hanyalah menimbulkan kecemasan, stres, bahkan trauma. Namun, dunia ini tidak seburuk yang dikira, yang ada hanya cerita saja. Inilah sebabnya untuk memerangi sindrom dunia yang kejam, masyarakat harus mengambil kembali cara mereka berpikir, merasakan, dan bereaksi terhadap berita-berita negatif atau kekerasan yang terus menerus muncul di sekitar mereka.
Meski masih ada konflik di banyak tempat di negeri ini, masalah politik yang harus berujung, masalah sosial yang harus dipangkas, masalah hak asasi manusia yang perlu semua atasi, masalah perubahan iklim yang perlu diperbaiki, tetapi dunia belum pernah sebaik sekarang ini---setidaknya bagi sebagian besar masyarakat. Dalam skala global dan pribadi, masyarakat menghadapi kenyataan pahit hampir setiap hari, tetapi karena tragedi seolah-olah ditampilkan sebagai hal yang biasa dan bukan hal yang asing, wajar saja jika masyarakat merasa marah atau takut.
Jadi, kita perlu memilih sumber informasi dengan hati-hati dan tidak membiarkan algoritma media sosial yang obsesif mendominasi persepsi kita tentang dunia. Kita harus sadar akan pendekatan terhadap berita supaya dapat mengubah cara berpikir kita.
Ketika menelusuri laman jejaring sosial, atau lapak daring, dan menemukan berbagai berita yang meresahkan, kita secara cerdas akan bertanya, apakah itu fakta atau fiksi? Apa bukti nyata kejadiannya? Apa konteksnya? Atau apakah kita hanya dimanipulasi sehingga timbul perasaan takut dan curiga tertentu? Jika menemukan platform media sosial menyajikan jenis konten yang sama, kita akan terpicu untuk mewaspadainya sehingga akhirnya mendiversifikasi umpan berita mereka dengan memasukkan hal-hal positif untuk menyeimbangi hal-hal negatif.
Pada akhirnya, sebagai bagian dari masyarakat, kita adalah spesies yang suka bercerita dan jika belajar sesuatu dari sejarah, maka narasi yang kita bagikan satu sama lain adalah hal yang paling penting, kisah-kisah yang kita ceritakan sekarang memiliki pengaruh besar dalam membentuk budaya dan masyarakat kita.
Mungkin saatnya kita kembali bercerita seperti anjing darat dan anjing laut. Mungkin jika kita melakukannya, kita dapat menimbulkan nilai-nilai yang benar-benar menjadikan kita manusia yang peduIi satu sama lain, berbelas kasih, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Dunia ini tidak sekejam yang media ingin kita percayai. Sudah waktunya kita berhenti membiarkan mereka berbohong kepada kita.
---
-Shyants Eleftheria, Salam Cerdas Literasi-
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H