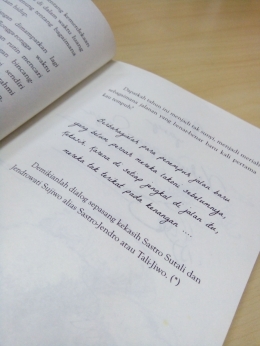Sudah berapa lama kau terjebak dengan beragam kesibukan yang tak habis-habis itu? Berhentilah berbusa-busa tentang kemerdekaan bila ternyata kau sendiri tak punya waktu luang.
Padahal, hanya di dalam waktu luang manusia bisa berpikir dan merenung tentang bagaimana seyogianya mengisi kemerdekaan hidup.
Maka, waktu luang itu jangan dimampatkan lagi dengan melulu main gadget. Berbincanglah bersamaku. Duduklah di sampingku dan buka ruang imajinasimu. Bersama-sama kita akan larut dalam suara-suara Talijiwo. Mungkin kau akan semakin gelisah, marah, atau justru lupa pada beban dunia. Mari bersama-sama merdeka. Meski kita tetap tak bisa merdeka dari kenangan.
Itulah sepenggal kutipan yang menurut saya sedikit agak "menyindir", yang pada akhirnya membuat saya membeli novel "Talijiwo" di bulan Juni 2019 lalu.
Yup, bagi saya penggalan kutipan tersebut sangat berjalan lurus dengan fenomena yang terjadi saat ini. Di mana, kita terlalu sibuk untuk berteman dengan gadget, meluapkan segala keresahan dan kelelahan hidup yang kita alami selalu lewat sosial media, sehingga terkadang membuat kita lupa bahwa sebenarnya kita masih punya seseorang yang mau mendengarkan segala keluh kesah hidup yang kita rasakan.
Bagi manusia-manusia yang tidak pernah peka atau memiliki masalah yang sama, saya rasa "Talijiwo" dengan 35 cerita pendeknya tersebut dapat mengajak pembaca untuk menyelam lalu merenungi setiap persoalan yang terjadi di dalam dunia ini.
Ya mungkin sebagian pembaca akan merasa "tersindir", tapi apa salahnya jika sindiran tersebut membuat kita pada akhirnya peka?
Beberapa cerita yang saya sukai

Suatu ketika, keluarga kecil tersebut sudah janjian akan makan di restoran Padang di Mojokerto, namun karena kerjaan si bapak alias Nunuk belum kelar, alhasil si Ninik manyun karena hari itu merupakan hari terakhir restoran tersebut mempertahankan keasliannya, sebab esok-esok karyawan Minang bisa terhitung dengan jari dan selebihnya mereka adalah orang Madura, Bugis, Batak dan Manggarai.
Dari cerita pendek "Puasa" tersebut diceritakan bahwa pemilik warung Padang tersebut menerapkan kebijakan pluralisme tersebut karena terinsiprasi bakso Malang dan Siomay Bandung yang para penjualnya belum tentu asli Priangan atau asli Malang. Iya toh?
Dalam cerita "Puasa" juga menceritakan kisah bosnya Nono yang sangat teratur dalam bekerja dan taat dalam menjalankan ibadah puasa. Namun sayangnya, ibadahnya rajin tidak seirama dengan perlakuan dia terhadap sesama manusia, yang mana karyawan yang tidak berpuasa jadi terkena imbasnya.
Mereka merasakan lapar karena tidak ada jadwal makan, padahal bukannya sudah seharusnya manusia harus saling menghargai dan berbagi?
Selanjutnya, selain cerita tentang "Puasa", saya suka dengan cerita "Arus Balik". Menurut saya, cerita "Arus Balik" sangat menggambarkan betapa ketergantungannya manusia dengan GPS ketimbang bertanya dengan penduduk setempat ketika akan mengunjungi suatu tempat baru yang belum pernah dikunjungi sebelumnya.
Nah di cerita "Arus Balik" ini menceritakan tentang kakak beradik yang akan mengunjungi pesantren Sastrojendro saat arus balik ke perantauan.
Di tengah jalan, sang kakak bernama Sastro sudah mewanti-wanti agar jangan keblabasan mengimani GPS dan alangkah baiknya untuk bertanya dengan penduduk setempat yang mereka temui.
Cerita tersebut jikalau dilihat memang sangat merefleksikan manusia zaman sekarang yang sangat bergantung sekali dengan GPS dan gadget. Toh, tidak selamanya GPS itu membawa pada jalan kebenaran, dan pernahkah kamu merasakan risih jika lama-lama mendengar suara "mbak-mbak" dalam navigator yang suaranya datar tanpa ekspresi?
Dan benar apa yang ada dalam Talijiwo, "Bahkan sampai meskipun jalan yang diarahkan benar maupun sesat, yaa toh tetap saja suara mbak-mbak navigator layaknya ransum nasi kotakan. Pedas tidak, asin pun tidak juga. Bahkan hambar juga ndak (hal.25)"
Iya toh?
Selain dua cerita di atas, ada cerita yang mengingatkan saya akan dunia kampus, yang "mungkin" dulu pembaca juga pernah alami, yaitu perihal "titip absen" kepada teman sekelas. Nah di kisah "Membaca Novel", pembaca akan dibawa ke dalam kisah sepasang kekasih, yaitu Parwati dan Buchori.
Dikisahkan suatu hari saat kamis pon bulan Rajab, Parwati, kekasih Buchori tidak masuk sekolah karena sakit. Karena mereka pacaran, atas inisiatif sendiri, Buchori menandatangani kolom kehadiran Parwati.
Buchori tak menyangka bahwa di hari itu dosennya, si Pak Gemuk menghitung presensi daftar hadir dengan teliti. Sontak, ia teringat kisah seniornya yang dihukum satu kelas karena menyalahgunakan absen.
"Kalau tidak ada yang mengaku, yo wis," tukas pak Gemuk. "Saya Cuma berharap, jangan ulangi modus tanda tangan oplosan begini. Salam buat Parwati."
Diperlakukan seperti itu, Buchori merasa tak enak dan akhirnya ingin mengakui perbuatannya. Namun setelah ia bercerita dengan Parwati, Parwati tidak memperbolehkannya, sebab Buchori itu laki dan biasanya "lakik itu pengapesannya mahasiswi."
Dan setelah pengakuan atas "tanda tangan oplosan" tersebut, Parwati dihukum membuat rangkuman yang ia berhasil selesaikan selama 3 hari.
Selain kisah "titip absen", perihal kelakukan mahasiswa ketika di kampus memang tidak ada habis-habisnya. Mungkin pembaca juga pernah menunggu dosen yang datang ke kelas telat, lalu karena dosen tak kunjung datang, seluruh mahasiswa sepakat untuk meninggalkan kelas dan hanya sedikit yang tetap menunggu di dalam kelas.
Yaa begitulah kehidupan perkuliahan, terkadang bisa dihitung jumlah mahasiswa yang setia dengan dosennya layaknya pasangan Parwati dan Buchori.
Dari cerita "Membaca Novel" yang membahas kehidupan perkuliahan. Talijiwo juga mengajak pembaca untuk merenung sejenak ke cerita tentang "Sampah".
"Sampah" merupakan bagian cerita yang dirasa mampu menyentil pembaca. Bagi saya, ini merupakan kejadian sehari-hari, yang pasti sering terjadi kepada seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak yang jarang membantu orangtua dalam pekerjaan rumah.
Cerita ini mengajak pembaca untuk belajar meresapi bagaimana lelahnya seorang ibu bernama Bu Sastro, ibu rumah tangga yang memiliki dua putri. Putri sulung bekerja sebagai pegawai honorer di DPR sedangkan si sulung merupakan siswi SMA.
Sejatinya, harapan seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua putri, meskipun kerja dan belajar itu membuat lelah, mestinya kedua putrinya bisa membantu ibunya walau hanya sekadang nyapu dan membuang sampah. Bahkan, dalam cerita tersebut, urusan tempat tidur tetap saja urusan ibu yang memebereskannya.
Bu Sastro menjadi perempuan pada umumnya yang menyanjung janji...menyangga matahari...menanggung suka dan duka...menuai tingkah laku anak sendiri...menua sendiri...
Itulah ironi yang mungkin dirasakan oleh ibu rumah tangga yang memiliki anak yang sudah dewasa, namun tidak membantu ibunya.
Pada akhirnya, dari cerita "Sampah", di dunia ini terdapat dua tipe ibu-ibu di kehidupan bermasyakat. Pertama,ngedumel dan yang kedua, mengelus dada (karena tak bisa ikutan ngedumel) saat tetangganya bilang "Duh bahagianya punya anak. Punya teman. Ada yang membantu-bantu untuk berberes."
Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari cerita-cerita dalam novel "Talijiwo", entah itu mengenai kehidupan dengan keluarga, dengan kekasih bahkan hingga masalah politik. Seperti dalam kisah "karaoke" yang menceritakakan kisah bu Jendro dan anak-anaknya yang baru saja mengajak Pak Jujur ke tempat karaoke.
Saat menjelang tidur, Pak Sastro mengulang-ngulang rasa terima kasihnya atas karaokeannya tadi. Bu Jendro senang bukan main dipuji oleh suaminya.
Obrolan di karaoke menjadi obrolan pengantar tidur mereka. Namun, saat mereka sudah kehabisan cerita, mereka pun tak dapat tidur.
Pak Sastro pun akhirnya memulai topik baru terkait Pilkada. Dalam pembahasan malam itu, Pak Sastro mengutuk siapa saja yang menerima serangan fajar.
Bu Jendro pun tak jadi tidur, resah, terngiang-ngiang kata kata suaminya. Sebab, duit yang dipakai untuk membayar karaoke tadi siang adalah duit dari hasil serangan fajar.
Sebagai penutup yang manis tapi tidak seratus persen manis. Saya juga suka dengan cerita berjudul "Calon", mungkin pernah dirasakan juga oleh sebagian pembaca.
Kini kita ketahui bahwa urusan pasangan itu cocok atau tidak buat kita, bukan hanya datang dari restu orangtua, namun sekarang melibatkan restu "bulek atau bule", bukan begitu?
"Bapak dan Ibumu ndak setuju ama calonmu? Tenang! Selama bulek atau budekmu setuju, jalan terus. Percayalah pada the power of Bulek atau bude." (Hal.114)
Bagi pasangan yang sudah menjalani hubungan atau baru menemukan tambatan hati dan ingin menikahi mereka, tentu meminta izin hanya kepada orangtua tidaklah cukup.
Terkadang, perlu juga meminta restu dari orang luar (keluarga layaknya tante atau om). Namun, apa jadinya, jika keputusan dari bulek dan bude sudah melebihi batasnya restu orangtuamu? Alih-alih, mengharapkan dukungan eh malah berakhir konflik batin? Hadeuh....
Nah, permasalahan tersebut diceritakan secara gamblang melalui hubungan Sastro dan kekasihnya yang bernama Jendro Wardhani. Mereka dipertemukan Tuhan secara tak sengaja, saat Sastro sedang mancing ikan di Rawa Pening.
Dari tempat pemancingan, akhirnya benih-benih cinta tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan, diceritakan hubungan mereka disenangi oleh bulek dan budenya Sastro. Namun, rasa senangnya mereka kepada Jendro hanya sebatas pacar, tidak lebih alias jangan harap untuk menjadi pendamping hidup.
Maka, dari situ, terjadilah perang batin di dada Sastro, dia sedih. Mengapa Negara demokrasi namun manusianya tidak demokratif? Mengapa perihal pendamping hidup masih dihubung-hubungkan dengan status orangtuanya? Ah cinta memang complicated.
".....Bagaimanapun kamu masih beruntung. Keluarga besarmu ndak setuju ma calonmu. Orang-orang lain itu...coba lihat. Mereka nasibnya lebih sial. Keluarga besar semua setuju. Yang tak setuju malah calonnya." (Hal.117)
Begitulah Sujiwo Tejo mengambarkan fenomena dan kondisi sosial masyarakat saat ini melalui "Talijiwo".
Bagi saya, kumpulan cerita dalam "Talijiwo", mampu menggelitik dan menyindir pembaca agar lebih peka dalam menjalani hidup bermasyarakat.
Terakhir, yang membuat kumpulan cerpen ini menjadi manis dan membawa pada perenungan ialah quote yang sederhana namun mampu memikat hati para pembaca.
"Berbahagialah para penempuh jalan baru yang belum pernah mereka lakoni sebelumnya, Kekasih. Karena setiap jengkal di jalan itu, mereka tak terikat pada kenangan...."
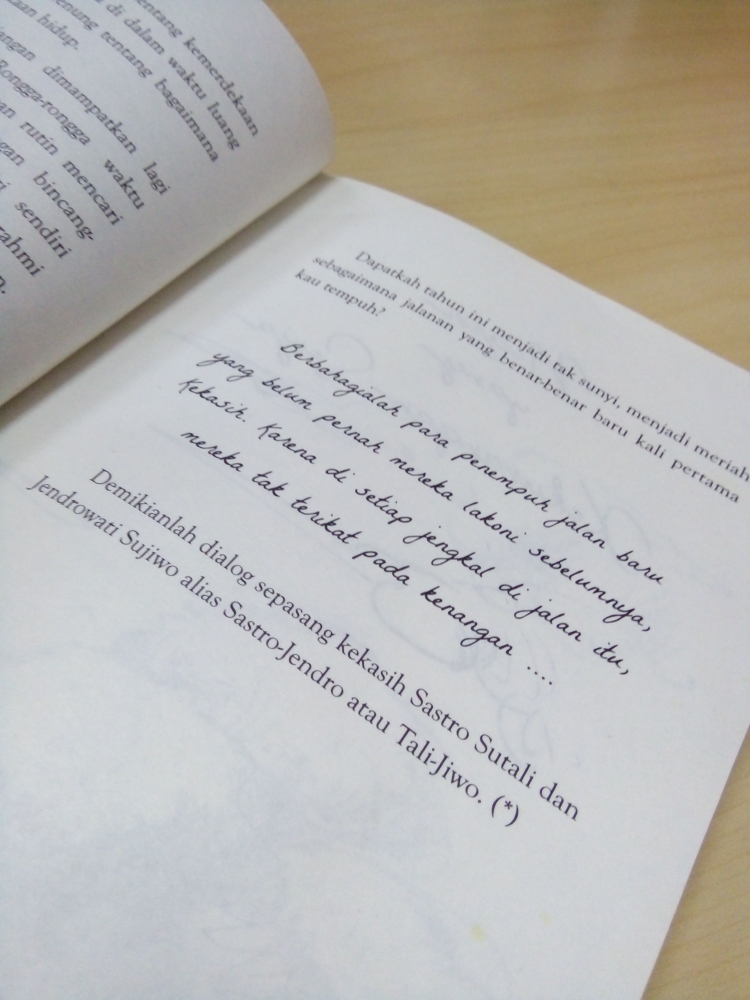
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H