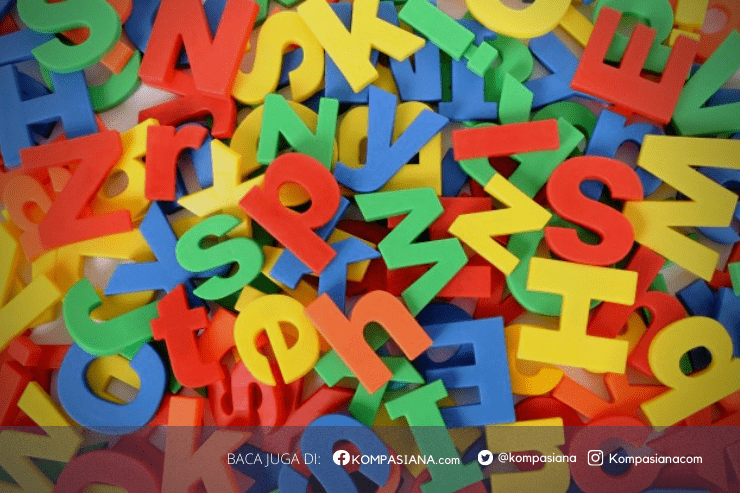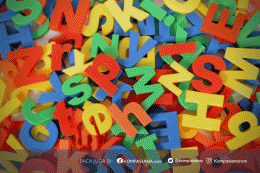Bahasa adalah salah satu identitas bangsa yang paling fundamental. Di Indonesia, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol persatuan dari keberagaman budaya. Namun, di era digital yang semakin berkembang pesat, bahasa Indonesia mulai menghadapi tantangan baru: privatisasi oleh perusahaan teknologi yang beroperasi di ranah kecerdasan buatan atau yang kini marak disebut dengan AI atau Artificial intelligence.
Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi digital, bahasa ini semakin diposisikan sebagai komoditas. Fenomena ini tidak hanya menciptakan peluang baru bagi penutur bahasa Indonesia untuk terlibat dalam ekonomi digital global, tetapi juga membawa risiko privatisasi yang signifikan.
Dalam era digital saat ini, banyak platform online yang menggunakan bahasa Indonesia untuk menjangkau pengguna di seluruh dunia. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter telah mengadopsi bahasa ini sebagai salah satu cara untuk berinteraksi dengan pengguna. Selain itu, aplikasi komunikasi seperti WhatsApp dan Telegram juga menyediakan antarmuka dalam bahasa Indonesia. Hal ini menciptakan peluang bagi penutur bahasa Indonesia untuk terlibat dalam ekonomi digital global.
Namun, penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks komersial sering kali tidak memperhatikan nilai-nilai budaya dan linguistik yang melekat pada bahasa tersebut. Menurut (Kurniawan, M. A. 2018) mengatakan penggunaan bahasa dalam platform digital sering kali diarahkan oleh kepentingan bisnis daripada pelestarian budaya. Banyak perusahaan teknologi besar lebih memilih untuk mengadaptasi konten mereka ke dalam format yang paling menguntungkan secara finansial tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan bahasa dan budaya lokal.
Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan privatisasi sebagai proses, cara, perbuatan dari milik negara menjadi milik perseorangan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa telah berkembang menjadi elemen penting dalam interaksi sosial, pendidikan, dan komunikasi publik. Namun, di era digital, bahasa ini menghadapi tantangan baru berupa komodifikasi, yakni proses di mana bahasa dijadikan aset ekonomi yang dapat diperjualbelikan. Privatisasi bahasa Indonesia dalam konteks ini melibatkan penguasaan elemen-elemen bahasa oleh perusahaan teknologi atau entitas komersial, yang dapat berujung pada berbagai risiko, termasuk eksklusivitas akses, manipulasi data linguistik, dan hilangnya kedaulatan budaya.
Menurut (Cameron D. 1998) seorang pakar linguistik dari Universitas Oxford, komodifikasi bahasa adalah gejala global di mana bahasa dianggap sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi untuk keuntungan ekonomi. Hal ini terlihat jelas pada perkembangan teknologi seperti mesin penerjemah, asisten virtual, dan sistem pengenalan suara, di mana data linguistik menjadi komponen utama. Dalam konteks bahasa Indonesia, privatisasi dapat terjadi ketika perusahaan teknologi besar menggunakan data bahasa untuk mengembangkan produk berbasis kecerdasan buatan tanpa mempertimbangkan implikasi sosial dan kulturalnya.
Bahasa Indonesia juga menjadi subjek perhatian di tengah kompetisi global dalam teknologi. Data linguistik yang berasal dari bahasa ini sering kali diekstraksi melalui interaksi pengguna dengan aplikasi digital, mulai dari media sosial hingga layanan berbasis suara. Sayangnya, pengumpulan data semacam ini sering kali dilakukan tanpa transparansi yang memadai, sehingga pengguna tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka berkontribusi pada komodifikasi bahasa mereka sendiri.
Privatisasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan aset yang dimiliki dan pengelolaan perusahaan dari negara kepada pihak swasta untuk mengurangi inefisiensi, informasi yang asimetri, biaya sosial, dan intervensi pemerintah yang mengakibatkan kegagalan pasar (Mardjana dalam Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2008). Jika hal ini diterapkan pada layanan berbasis bahasa Indonesia, masyarakat yang kurang mampu mungkin kehilangan akses ke alat-alat penting seperti aplikasi penerjemahan atau pembelajaran bahasa.
Privatisasi bahasa terjadi ketika perusahaan-perusahaan swasta mengambil alih pengembangan dan distribusi konten berbahasa Indonesia. Misalnya, platform-platform seperti Google Translate atau Duolingo menawarkan layanan penerjemahan dan pembelajaran bahasa dengan algoritma yang dikembangkan secara komersial. Meskipun memberikan akses mudah bagi pengguna, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kualitas dan akurasi penggunaan bahasa.
Salah satu risiko utama dari privatisasi bahasa adalah hilangnya kontrol atas penggunaan dan perkembangan bahasa itu sendiri. Ketika perusahaan swasta mendominasi penyediaan layanan berbasis bahasa, mereka memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana bahasa digunakan dan diajarkan. Ini dapat mengarah pada homogenisasi budaya linguistik di mana variasi dialek atau istilah lokal tidak lagi dihargai.
Dampak negatif lainnya dari privatisasi adalah potensi penurunan kualitas pendidikan bahasa itu sendiri. Dengan semakin banyaknya aplikasi pembelajaran berbasis algoritma yang tersedia secara gratis atau dengan biaya rendah, ada risiko bahwa pengguna akan lebih memilih metode belajar instan tanpa memahami dasar-dasar tata bahasa atau kosakata dengan baik. Hal ini bisa berdampak pada kemampuan generasi muda dalam menggunakan Bahasa Indonesia secara efektif.
Dampak ini dapat memperparah kesenjangan digital di Indonesia, di mana sebagian besar masyarakat masih bergantung pada teknologi yang terjangkau untuk mendukung pendidikan dan pekerjaan mereka. Selain itu, privatisasi juga dapat menyebabkan eksklusi bagi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Akses terhadap teknologi sering kali terbatas bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi atau tinggal di daerah terpencil. Hal ini menciptakan kesenjangan digital di mana hanya segelintir orang yang dapat memanfaatkan sumber daya berbahasa Indonesia secara optimal.
Ketika bahasa digunakan sebagai alat pemasaran atau produk komersial, ada risiko bahwa makna asli dan nuansa budaya akan hilang. (Irham dkk, 2022) peneliti sosiolinguistik yang fokus pada studi tentang dampak globalisasi terhadap penggunaan bahasa-bahasa minoritas, menekankan bahwa ketika sebuah bahasa diperlakukan sebagai barang dagangan, aspek-aspek penting dari identitas kolektif penuturnya bisa terancam punah.
Di tingkat global, bahasa-bahasa dominan seperti Inggris atau Mandarin sering kali memiliki keunggulan karena investasi teknologi yang besar. Namun, bahasa-bahasa seperti Indonesia sering kali kurang diperhatikan dalam pengembangan teknologi ini. Sebagai hasilnya, pengumpulan data linguistik bahasa Indonesia lebih cenderung berada di bawah kendali perusahaan asing, yang memiliki potensi untuk mendikte bagaimana bahasa tersebut digunakan dan dipersepsikan di dunia digital.
Platform digital sering kali memiliki kebijakan konten yang ketat yang dapat membatasi cara orang menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya, algoritma media sosial mungkin memprioritaskan konten tertentu berdasarkan popularitas atau potensi keuntungan iklan daripada berdasarkan nilai kultural atau edukatif. Ini dapat menyebabkan hilangnya keragaman suara dan perspektif yang seharusnya ada dalam diskusi publik.
Salah satu contoh nyata adalah bagaimana istilah asing sering kali mendominasi percakapan sehari-hari di media sosial. Istilah-istilah seperti “influencer,” “content creator” dan “viral” menjadi bagian dari kosakata sehari-hari meskipun ada padanan kata dalam bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menggunakan bahasa lokal, pengaruh globalisasi sering kali lebih kuat, banyak istilah asing mulai masuk ke dalam kosakata sehari-hari masyarakat Indonesia tanpa proses adaptasi yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan makna asli dari kata-kata tersebut serta merusak kekayaan linguistik lokal. Oleh karena itu, penting untuk menjaga integritas bahasa melalui kebijakan publik yang mendukung pelestarian budaya lokal.
Lebih jauh lagi, eksklusivitas akses ini tidak hanya terbatas pada masyarakat pengguna teknologi tetapi juga lembaga pendidikan dan riset yang ingin memanfaatkan data linguistik. Jika data-data linguistik bahasa Indonesia hanya tersedia melalui model berbayar, maka pengembangan penelitian bahasa menjadi terbatas hanya untuk pihak-pihak yang memiliki dana besar, sehingga mempersempit ruang inovasi.
Bahasa merupakan cerminan budaya dan identitas suatu bangsa. Privatisasi berisiko mengubah makna, struktur, atau konteks penggunaan bahasa Indonesia. Menurut (Baron, N. 2003) ketika algoritma kecerdasan buatan mengolah bahasa tanpa memahami nuansa budaya, hasilnya sering kali distorsi linguistik yang merugikan keaslian bahasa. Sebagai contoh, adaptasi bahasa Indonesia ke dalam konteks perangkat lunak sering kali menghasilkan terjemahan literal yang menghilangkan kekayaan budaya dan ekspresi lokal.
Jika dibiarkan, manipulasi data linguistik dapat mengarah pada homogenisasi bahasa, di mana variasi dialek dan idiom lokal tergeser oleh bentuk bahasa yang lebih "standar" sesuai kebutuhan pasar global. Kehilangan keberagaman linguistik dapat mengikis kekayaan budaya bangsa, yang selama ini terwujud dalam berbagai dialek dan bentuk bahasa Indonesia. Sebagai contoh, penguasaan data linguistik oleh perusahaan asing dapat digunakan untuk memengaruhi kebijakan lokal melalui propaganda atau manipulasi informasi.
Perusahaan-perusahaan teknologi besar sering kali mengumpulkan data dari interaksi pengguna dengan platform mereka untuk tujuan analisis pasar atau pengembangan produk baru. Data linguistik ini bisa jadi sangat berharga bagi perusahaan-perusahaan tersebut tetapi tidak memberikan manfaat langsung kepada komunitas penutur asli. Hal ini menjadi ancaman nyata dalam era digital, di mana data adalah kekuatan utama dalam membentuk opini publik dan keputusan politik. Lebih parah lagi, kedaulatan budaya bisa hilang jika masyarakat mulai bergantung sepenuhnya pada teknologi asing untuk kebutuhan bahasa mereka, sehingga kehilangan kendali atas bagaimana bahasa tersebut dipahami dan digunakan.
Fenomena privatisasi bahasa Indonesia di dunia digital membawa tantangan serius bagi keberlangsungan penggunaan dan perkembangan bahasa tersebut. Meskipun teknologi memberikan peluang baru untuk akses informasi dan pendidikan, kita harus tetap waspada terhadap dampak negatifnya terhadap identitas budaya dan keberagaman linguistik. Upaya kolektif diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan bahasa tetap berada di tangan masyarakat luas daripada dikuasai oleh kepentingan bisnis semata.
Dengan memahami risiko-risiko ini serta melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, akademisi, maupun Masyarakat kita dapat menjaga agar Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi komoditas tetapi juga tetap hidup sebagai bagian integral dari identitas bangsa.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI