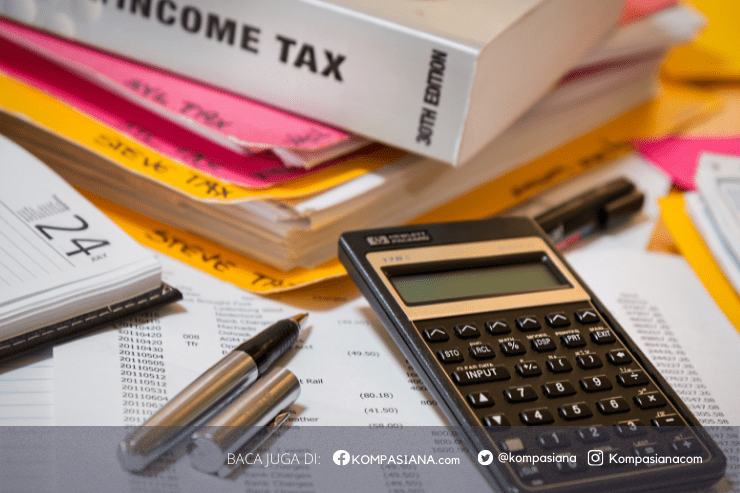Dibanding bersikap pesimis, masyarakat bisa turut serta memperbaiki ekonomi di tengah anjloknya nilai rupiah.
Depresiasi nilai rupiah baru-baru ini menjadi perbincangan ramai di media massa dan internet. Meski sebetulnya depresiasi sudah terjadi secara terus-menerus sejak beberapa tahun belakangan, nilai rupiah yang sudah menyentuh angka Rp15 ribu per dolar membuat heboh masyarakat. Pasalnya, angka tersebut hampir menyentuh titik terendah yang pernah mata uang garuda ini alami saat krisis finansial tahun 1997 silam.
Tekanan terhadap rupiah memang bisa memicu krisis. Hal demikianlah yang terjadi pada tahun 1997. Saat itu, pemerintah menghentikan campur tangan di pasar valas dengan maksud melindungi cadangan devisa dari spekulan. Keputusan tersebut ternyata direspon secara negatif oleh investor. Arus modal keluar dalam jumlah besar memicu depresiasi nilai tukar dalam jumlah besar di antara tahun 1997-1999.
Lembaga keuangan dan industri yang ketika itu menggantungkan keuangan mereka dari modal asing tidak mengantisipasi ini. Mereka berpikir pemerintah akan terus mengintervensi valas, sehingga tidak berhati-hati dalam mengelola keuangannya. Alhasil, depresiasi memicu lahirnya deflasi utang eksternal, yang pada akhirnya mengakibatkan perbankan dan industri kolaps.
Namun kondisi sekarang berbeda.
Sejak tahun 1997, Indonesia tidak lagi menggunakan sistem nilai tukar tetap di mana pemerintah menetapkan besaran rupiah terhadap dolar. Kini, devisa kita dikelola dengan cara mengambang. Artinya tarik-menarik permintaan dan penawaran menentukan besaran nilai tukar.
Logis, hal demikian semestinya memicu lembaga keuangan dan industri menggunakan asumsi anggaran dengan nilai tukar yang lebih dinamis. Dengan demikian, risiko keuangan akibat depresiasi lebih rendah.
Buktinya, hal ini bisa dilihat dari posisi utang eksternal Indonesia. Menurut catatan BI dan Kementerian Keuangan, pada triwulan ke-2 tahun 2018 ini, rasio utang eksternal terhadap GDP adalah 34% dengan dominasi utang jangka panjang sebesar 84.4% dan sisanya adalah utang jangka pendek sebesar 15.6%. Angka tersebut berbeda dengan tahun 1997, di mana utang eksternal mencapai 60% dari GDP dengan komposisi utang jangka panjang dan pendek masing-masing sebesar 76.5% dan 23.5%.
Di sisi lain, regulasi dan pengawasan keuangan Indonesia saat ini lebih ketat. Indonesia saat ini memiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengambil sebagian tugas BI untuk mengawasi pengelolaan lembaga keuangan dan perbankan. Keberadaan lembaga ini penting agar pengawasan terhadap lembaga keuangan lebih cermat dan fokus karena ada pembagian peran.
Sebagai pembanding, sebelum krisis 1997, BI keteteran mengawasi lembaga keuangan Indonesia, sehingga pengelolaan utang eksternal kurang terkendali. Hal demikian diungkapkan Gubernur BI saat itu, Soedradjat Djiwandono, dalam buku Mengelola Bank Indonesia dalam Masa Krisis. Ia menguraikan, pada tahun 1997, pemerintah terlambat menyadari masalah utang eksternal sampai akhirnya krisis menimpa.
Keterlibatan Masyarakat