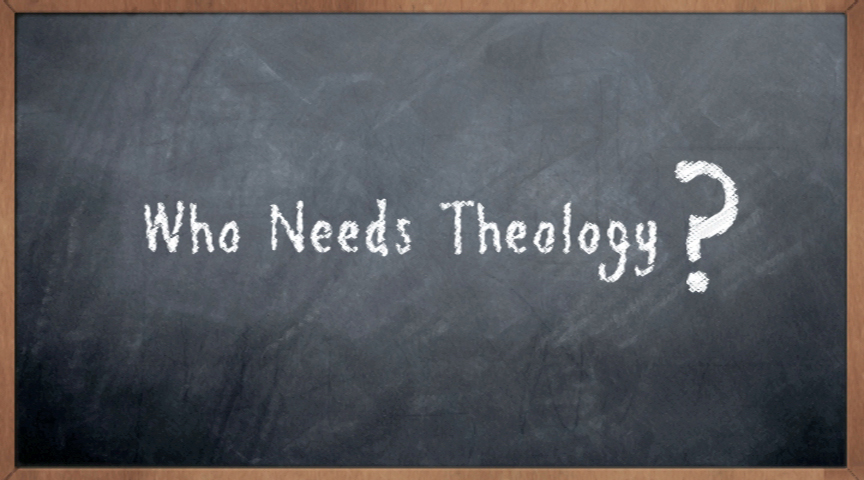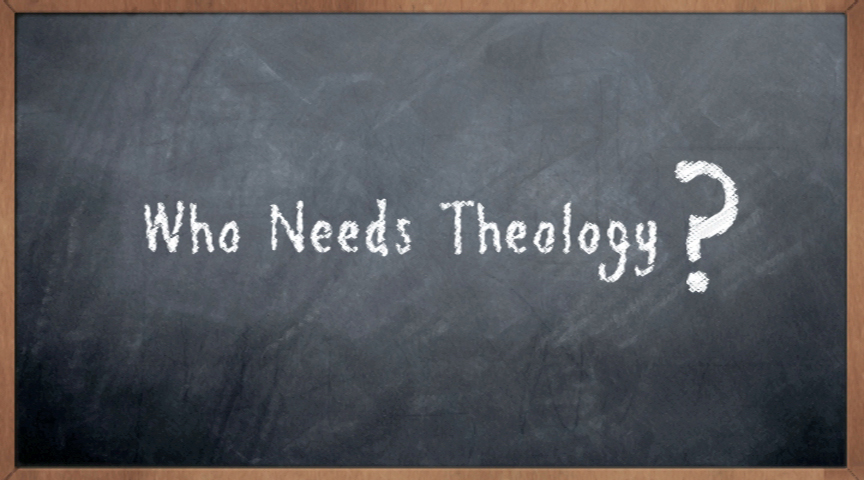[caption caption="Ilustrasi | sumber gambar: fultonchurch.org"][/caption]Apa arti beragama itu sebenarnya? Pertanyaan semacam tadi sering saya lemparkan ke alam semesta ini sambil berharap supaya membentur di kepala orang lain.
Bukannya apa, saya kadang-kadang suka heran kalau agama saat ini terkesan "bercerai" dengan ihwal ketuhanan. Dan mungkin masih banyak orang yang menilai kalau orang yang beragama itu sudah pasti bertuhan, makanya mereka mengira cukuplah hanya sekedar beragama. Jadi muncul lagi pertanyaan: apa iya demikian halnya? Kalau memang seperti itu persepsi yang ada di masyarakat, pantas saja kalau kita tidak menyentuh aspek teologis dari keyakinan tersebut. Apalagi kalau ada yang mengira dengan hanya menganut agama saja sudah cukup tanpa perlu mendalaminya; saya tak tahu harus mengatakan apa lagi.
Memang, kelihatannya pun persoalan teologis tidak memasyarakatkan. Apa teologi hanya sekedar ilmu sekolahan? Apa teologi hanya untuk kalangan tertentu? Jawaban saya, tentu tidak demikian kalau kita memang berprinsip pada agama, atau secara spesifik, berprinsip pada Tuhan. Lagipula, kalau Sang Pencipta adalah milik semua orang, kenapa permasalahan teologi malah berlaku hanya untuk sebagian masyarakat?
Lagian, berdasarkan pengalaman saya pribadi, teologi pun nyatanya bisa membuka jalan bagi mistisisme, yaitu laku spiritual dalam upaya mendekati Tuhan dan mematuhiNya. Dari hal itulah saya kira teologi memang kompatibel dengan semua orang.
Lagipula, seandainya kita sudah benar-benar berprinsip pada nilai ketakwaan, saya rasa kita tak perlu memikirkan perihal agama yang belakangan ini terasa rumit lantaran sibuk membicarakan hukum atau sibuk menjustifikasi umat beragama lain dan bersikap intoleran. Mungkin pun impresi tadi memang sudah sedemikian melekat. Tapi rasanya saya mau tak mau harus mengatakan bahwa orang yang berorientasi pada agama, dengan orang yang berorientasi pada Tuhan memanglah sangat berbeda. Tidak; agama bukanlah muara melainkan sebuah jalan. Muara itu hanya ada pada Tuhan. Dalam arti, seseorang jangan hanya berhenti stagnan pada agama. Nyatanya, saya pun memahami utilitas agama justru dalam usaha intensif pendekatan terhadap Tuhan.
Makanya persepsi saya terhadap agama yang tadinya terkesan sibuk dengan persoalan hukum dan mengkafirkan umat lain, akhirnya berubah sama sekali. Agama, bagi saya, memang tidak sebagaimana yang dipersepsikan orang banyak. Dan di sinilah saya menemukan kenyataan bahwa persoalan teologis itu memang tidak pernah tersentuh di kepala kita.
Dengan kata lain, kita tak pernah mau mencari tahu kenapa kita harus menyembah Tuhan; kenapa harus beribadah; kenapa harus beragama dan lain sebagainya. Saya menyebut fenomena ini sebagai "iman buta", dimana persoalan ketuhanan tidak tersentuh oleh aspek rasio. Padahal kita adalah makhluk rasional dimana kita mesti menyembah Tuhan dengan rasionalitas akal sehat. Dan lagipula, saya pikir, rasionalitas tadilah yang akan membuat kita semakin yakin dalam menjalani ritual keagamaan.
Logikanya, bagaimana kita mau mengenal Tuhan dan mengetahui esensi keyakinan (agama) kita kalau kita sibuk mengafirkan dan bersikap antipati terhadap umat beragama lain? Padahal, selain mendalami pengetahuan tentang keyakinan (agama) pribadi, mempelajari teologi agama-agama lain juga bisa menjadi faktor yang memperkuat keimanan. Lagi-lagi, bagaimana kita mau mendalami itu kalau belum apa-apa sudah bersikap antipati?
Mungkin hal ini pun tidak terlepas dari sikap ketakutan umat beragamanya sendiri. Dalam arti, kita takut terpengaruh oleh teologi umat beragama lain sehingga nantinya berpindah keyakinan. Padahal kalau memang agama yang dianut itu diyakini kebenarannya oleh sang pemeluk, pasti dia tak akan takut "mengintip" ajaran agama orang lain.
Memang, dari hal demikianlah saya kemudian menemukan bahwa salah satu metodologi belajar yang paling asyik dan paling berkesan itu adalah dengan metode komparatif. Tapi ini pun tak akan bisa dilakukan kalau kita tidak terbuka dengan hal-hal yang asing bagi kita, yang dalam konteks ini adalah teologi agama-agama lain.
Jujur, saya masih penasaran, kenapa para ahli agama pun tak mau mengajarkan hal itu kepada jamaahnya? Yang saya lihat, kebanyakan yang dikomunikasikan cuma doktrin satu arah yang terkadang hanya melegitimasi pendapat sang agamawan. Apa jadinya kalau orang banyak di depan tidak diajak untuk berpikir, untuk mempertanyakan, untuk berdiskusi dalam konteks keyakinan? Tidak; bagi saya tidak ada yang salah kalau kita mempertanyakan persoalan keimanan dan teologi. Lagian, kalau agama yang diyakini memang rasional dan benar, maka penganutnya pasti akan semakin mantap dalam pencarian kebenarannya.
Tapi, mungkin permasalahan mendasar kita tidak lain adalah menyangkut soal pikir berpikir. Bagi saya, perihal aspek yang satu ini memang menjadi langkah awal dalam pencarian seseorang akan kebenaran sehingga kemudian dia mantap meyakini agama dan Tuhan.
Nyatanya, kalau tidak berpikir, lalu seseorang akan mencari apa? Apa hidup hanya dijalani sebagaimana robot bergerak tanpa akal dan perasaan? Apa jadinya kalau akal dan perasaan itu tidak bergetar, tidak gelisah, tidak galau, tidak bergejolak menyaksikan kehidupan berserta fenomena-fenomenanya? Apakah kita hanya melihat dan mendengar semua itu tanpa masuk ke dalam pikiran lalu mempertanyakannya? Bagi saya manusia adalah makhluk pengolah. Dalam arti, dia tidak hanya mengabstraksi benda-benda yang ada pada dunia untuk kemudian menjadi sesuatu yang bernilai atau berguna (secara eksternal), tapi juga abstraksi tersebut juga terkait dengan soal pengetahuan (secara internal). Atau, kalau pengetahuan itu kembali diperdalam, dianalisis dan disusun secara sistematis, maka kita menyebutnya itu sebagai ilmu. Ilmu inilah yang kita sebut dalam subjek tulisan ini sebagai teologi.[]
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H