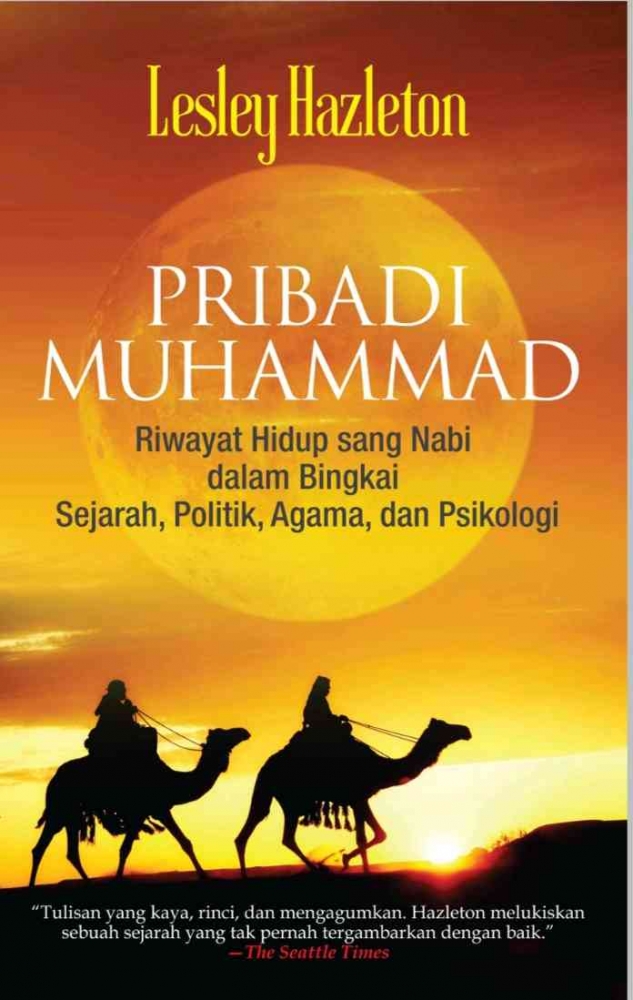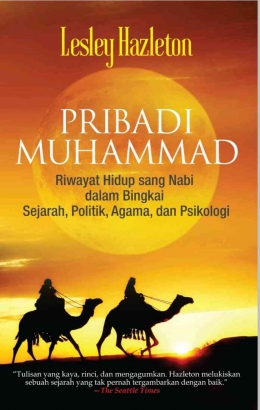Dr. Raghib Al-Sirjani sesungguhnya telah menulis sebuah buku tipis berjudul "Lasna fi Zaman Abrahah", bukan zaman Abrahah. Buku yang menganjurkan untuk membuang jauh-jauh imajinasi tentang keajaiban (yang bersifat supranatural) dimulai sejak zaman Nabi Muhammad (saw). Bahwa zaman ketika pasukan Abrahah diguyur batu-batu api dari langit merupakan akhir dari adanya intervensi kekuatan gaib dalam takdir manusia.
Sebuah tantangan tersendiri, sebab seorang nabi butuh mukjizat demi membuktikan kenabiannya. Lalu bagaimanakah membuktikan kenabian tanpa keajaiban sebagaimana mukjizat nabi-nabi terdahulu? Adakah umat yang jahiliah itu akan percaya?
Jalannya adalah dengan mengubah paradigma akan mukjizat atau keajaiban. Kemampuan berpikir dan bertindak rasional di antara segala bentuk irasionalitas di zamannya tentu adalah suatu keajaiban. Maka dari itu, mukjizat Muhammad adalah Al-Qur'an, yang letak keajaibannya adalah dengan percaya dirinya senantiasa menantang akal manusia untuk berpikir.
Mukjizat Al-Qur'an bersifat aqliyah (yang berhubungan dengan rasionalitas)--bukan hissiyah (bersifat fisik), demikian komentar Imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitabnya "Al-Itqan fi Ulumil Qur'an", cocok dengan Nabi Muhammad yang senantiasa berkutat dengan kerasionalan, atau hidup berdasarkan akal sehat.
Namun, sejarawan mainstream dari pihak sendiri kelihatannya masih mengarahkan sejarah Muhammad berdasarkan selipan unsur-unsur mistik. Dalam pengertian ini, Muhammad adalah tokoh sejarah yang kehendaknya diarahkan sepenuhnya oleh sang maha Gaib. Selalu ada intervensi supranatural pada setiap tindakan yang akan diwujudkannya. Akhirnya Muhammad dikesankan tak punya kehendak lebih selain menuruti wahyu belaka (salah satu dampak dari penafsiran secara terkstual akan dalil, "Wa maa yantiqu anil hawa ...").
Ada cara pandang lain, di sini saya mengajukan Lesley Hazleton yang menulis buku "The First Muslim: The Story of Muhammad", yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Alvabet menjadi "Pribadi Muhammad: Riwayat Hidup Sang Nabi dalam Bingkai Sejarah, Politik, Agama, dan Psikologi".
Testimoni pada halaman-halaman awal buku itu sudah memberikan bayangan, bahwa kelak Hazleton akan membuat Muhammad jauh dari kesan dikultuskan, atau diceritakan secara apologik sebagai manusia ilahi. Muhammad malah ditampilkan sebagai manusia pada umumnya yang bukan hanya berupaya maksimal memberdayakan akalnya, tetapi juga memang manusia yang punya insting (jika keberatan dengan istilah insting, maka boleh kita ganti dengan istilah fitrah dalam pengertian Muthahhari) yang tajam. Baik secara politik, strategi dan taktik berperang, maupun dalam hal seni memainkan emosi publik.
Cara pandang Hazleton sendiri dalam hal ini tampaknya sesuai dengan apa yang diyakini oleh Gadamer sebagai manusia modern (abad ke-20)--dengan segala cara pandangnya--yang memahami kehidupan di abad ke-7. Hazleton tidak hadir untuk merekonstruksi makna asli dari zaman itu, melainkan hadir untuk mempresentasikan peleburan horizon antara Hazleton dan zaman Muhammad. Jadilah buku itu mudah kita maklumi dalam imajinasi kita yang senantiasa menuntut kerasionalan ini.
Hazleton mengawali kisah Muhammad dengan dualitas identitas, yang juga merupakan perangainya. Muhammad kecil berasal dari suku Quraisy--suku paling terhormat kala itu--namun di sisi lain ia adalah anak yang tumbuh dalam kebiasaan-kebiasaan suku Badui, suku pinggiran yang kehidupannya cukup ekstrim (Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, di wilayah pedalaman suku Badui, Muhammad di tangannya selama 5 tahun). Dalam terang Hazleton, Muhammad adalah "bagian dari 'mereka' sekaligus bukan bagian dari 'mereka' (Quraisy)".
Dualitas ini juga yang akan menentukan perjalan Muhammad berikutnya hingga akhir hayat. Bahkan dualitas ini yang akan mendorong ciri utama ajaran yang dibawanya, yaitu kesetaraan, keadilan; membela kaum tertindas dan menentang segala bentuk kekuasaan berdasarkan superioritas kesukuan.
Ajaran Muhammad akan segera mendapat banyak simpatisan diam-diam, utamanya dari orang-orang yang posisinya tidak diuntungkan di dalam masyarakat, yaitu mereka yang tak punya kekuasaan maka cenderung tak bernilai. Sebaliknya, apa yang dibawa Muhammad seringkali merupakan protes terhadap praktik-praktik penguasa Mekah, menjadikan superioritas suku mereka untuk bersikap diskriminatif. Tuhan-tuhan selain Allah menjadi instrumen dalam meraup keuntungan baik dari segi ekonomi maupun kekuasaan.
"Laa ilaaha illallah", tiada Tuhan selain Allah, tidak saja bermakna memerangi kemusyrikan karena penyembahan Tuhan yang lain, tetapi juga berarti melawan ketidakadilan akibat kesewenang-wenangan pembesar-pembesar Quraisy. Meski awalnya dakwah di Mekah, demikian Hazleton, Muhammad masih bagaikan Mahatma Gandhi, melawan tanpa kekerasan.
Ketika hijrah pun, ketimbang tanda kenabian yang dibaca ada pada diri sang Nabi, penerimaan kehadiran Muhammad di Madinah lebih besar karena kemampuannya dalam mendamaikan suku Aus dan Khazraj, dua suku besar di Yastrib (nama selain Madinah) yang terkenal sering berpecah dan sulit didamaikan.
Di sinilah rupanya, di Madinah, manusia bernama Muhammad itu memperlihatkan dirinya sebagai manusia yang punya akal yang cemerlang serta insting yang tajam. Ketika akan menjamu pasukan Mekah di Badar, Muhammad tahu waktu (timing) yang tepat memasuki medan itu, sehingga pasukan pimpinan Abu Sufyan sudah jenuh duluan dan berbalik arah karena tak mendapati tanda-tanda pasukan Muhammad bakal datang.
Sebaliknya, pasukan Muhammad baru memasuki Badar dan segera menguasai pusat air bersih untuk menunggu pasukan Mekah selanjutnya di bawah komando Abu Jahal. Kedua watak pasukan Mekah ini berbeda. Abu Sufyan lebih suka mengandalkan perhitungan, lebih rasional--dan perhitungan itulah rupanya yang membuat Abu Sufyan berbalik arah--ketimbang Abu Jahal yang emosian dan cenderung gegabah.
Padahal pasukan Muhammad tak lebih dari tiga ratusan orang, namun dengan segera berhasil mematahkan pasukan Abu Jahal yang berjumlah seribu orang itu. Dia sendiri--Abu Jahal--tewas. Di sini Muhammad berhasil menggunakan prinsip jika tak unggul dalam hal kuantitas, maka harus unggul dalam hal kualitas.
Prinsip itu sekali lagi diuji pada perang Uhud. Kemenangan berpihak pada pasukan muslim walau dalam jumlah hampir sepersepuluh (kalau saja Hazleton benar) dari pasukan Abu Sufyan--seandainya saja pasukan pemanah di bukit menaati perintah Nabi. Muhammad mengandalkan strategi, pasukan Abu Sufyan hanya boleh datang dari depan. Caranya? Mereka membelakangi gunung Uhud, mengikuti bekas aliran lava yang sudah mengering. Sambil pasukan pemanah memback-up dari atas.
Prinsip, atau lebih tepatnya seni berperang Muhammad akhirnya cocok dengan strategi ala Sun Tzu bahwa "perang adalah penipuan". Indikasi ini yang terjadi pada perang Khandak, atau dalam sejarah dikenal dengan "perang parit". Abu Sufyan menanggapi ini, demikian Hazleton, sebagai kecurangan, melanggar tradisi berperang orang-orang Arab yang selama ini secara jantan berhadap-hadapan.
Hal yang mencolok, perang Khandak dalam sejarah yang ada disanjung sebagai kemodernan dengan Salman Al-Farisi sebagai ikonnya. Tetapi bagi Hazleton parit itu tak banyak membantu, perang itu memakan korban tak lebih dari sepuluh di pihak musuh. Namun begitu, menggali parit adalah hal baru dari produk akal manusia dalam perang Arab.
Tetapi serangkaian perang yang dikisahkan tidak selamanya tanpa perpecahan internal. Kekalahan di Uhud saja bisa dikata ada pengaruhnya dengan sepasukan pimpinan Ibnu Ubay dari Bani Nadir--salah satu suku Yahudi--yang enggan mengikuti pasukan Nabi, yang katanya terdiri dari pemuda-pemuda bersemangat tanpa perhitungan itu. Lalu sebagai pemimpin--di samping sebagai nabi--Muhammad mesti memberi pelajaran, kalau tidak, ketidaktaatan bisa menjalar ke yang lainnya. Sesuatu yang tak boleh dibiarkan.
Pelajaran yang diberikan adalah perkebunan kurma milik Bani Nadir yang merupakan sumber penghidupan mereka ditebang. Sebelumnya suku Yahudi yang lain, Bani Qaynuqa, juga telah diberi pelajaran dengan cara diusir sebab berani melangkahi Nabi dalam memutuskan suatu perkara.
Hazleton memperingatkan: "ingatlah, kini Muhammad yang berkuasa!" Pelajaran sekaligus hukuman yang paling tragis dialami oleh Bani Quraizhah. Satu kabilah selain wanita dan anak-anak, dipenggal di parit (Khandak). Lantaran terindikasi hampir saja melakukan kerjasama dengan pasukan Abu Sufyan di Khandak. Dikisahkan sebanyak empat ratus orang yang dipenggal, pendapat lain menyebut sembilan ratus. Pilih yang mana saja angka itu tetap fantastis.
Jika hal itu ditemui di abad ini, kebijakan Muhammad atas ketiga suku Yahudi tersebut akan divonis sebagai pelanggaran HAM berat. Namun Hazleton berupaya menuntun kita agar memahami bahwa begitulah seharusnya seorang pemimpin di abad ke-7, mesti mampu mempertahankan dan meningkatkan wibawa baik di hadapan pengikutnya maupun bagi pihak musuh. Apalagi konteks yang berlaku adalah perebutan pengaruh antara pemimpin Mekah (Abu Sufyan) di satu sisi dan pemimpin Madinah (Muhammad) di sisi lainnya.
Bayangkan, cara-cara yang ditempuh Muhammad seperti ini mampu mengantarkannya dari pemuda yang tak diperhitungkan di antara petinggi-petinggi Quraisy di Mekah, menjadi seorang pemimpin negara (Madinah) yang kepemimpinannya nyaris menyaingi penguasa (negara) kota Mekah. Hal itu semakin dibuktikan dengan tindakan Muhammad berikutnya yakni mengirim kabar ke Mekah bakal menunaikan Umrah pertama setelah hijrah. Bagi Hazleton, rencana ini merupakan satu gertakan yang membuat geger.
Abu Sufyan serta petinggi-petinggi Mekah lainnya dibuat dilema. Jika Muhammad dihalangi berziarah ke pusat penyembahan suci (Ka'bah), itu akan bertentangan dengan ketetapan leluhur bahwa tak boleh menghalangi peziarah siapapun dia. Namun jika tak dihalangi, Muhammad akan menarik simpati sebagian penduduk Mekah untuk bergabung, itu hanya akan menambah kekuatan Muhammad.
Terpaksa Muhammad dibuat menepi di Hudaibiyah. Kompensasi yang harus dibayar oleh Abu Sufyan adalah meneken Perjanjian Hudaibiyah; gencatan senjata. Bagi yang tidak memahami, mereka memandang Muhammad telah dikalahkan, perjalanan Umrah bermil-mil menjadi sia-sia.
Praktis Muhammad diabaikan tiga kali saat menyuruh menyembelih unta dan bercukur di tempat itu, yang seharusnya di pelataran Ka'bah. Namun apa boleh buat, nabi adalah ukuran amalan, akhirnya Muhammad mencontohkan amalan itu dan jamaahnya hanya bisa mengikuti tindakannya.
Tetapi bagi Muhammad, perjanjian Hudaibiyah adalah satu modal politik, di situ posisinya ditegaskan oleh Mekah sendiri sebagai satu pemimpin negeri yang berhadap-hadapan dengan pemimpin negeri lain, yang sebelumnya kepemimpinannya tak diakui--begitu Hazleton mengesankan.
Penegasan ini berguna bagi Umrah mendatang, sesuai dengan salah satu poin perjanjian bahwa Muhammad hanya boleh berumrah sekali setahun dan hanya selama tiga hari. Tiba saat itu, selama tiga hari Umrah yang dimaksud, Muhammad benar-benar mendapatkan keuntungan. Selain karena berhasil menikahi anak Abu Sufyan sendiri, juga Khalid sebagai salah seorang prajurit terkuat Mekah, serta Amr sang komandan ikut dengannya kembali ke Madinah.
Poin perjanjian lain adalah kebebasan suku-suku Badui untuk berafiliasi antara Mekah atau Madinah, dan imbalannya adalah perlindungan. Fathu Mekah (yang diterjemahkan sebagai penaklukan Mekah, oleh Hazleton dimaknai dengan dibuka atau dibebaskannya Mekah) sendiri bermula dari kesalahan salah satu suku yang berafiliasi ke Mekah. Hal yang memaksa Abu Sufyan berniat melakukan negosiasi dengan Muhammad di Madinah. Hal itu kemudian dilakukan secara diam-diam dan tiba-tiba saja Muhammad akan melakukan Fathu Mekah.
Di sini Hazleton akan menunjukkan adanya pembicaraan pendahuluan antara Abu Sufyan dengan Muhammad sebelum Fathu Mekah terjadi: Abu Sufyan sudah memperingatkan penduduk Mekah akan kedatangan Muhammad dengan jumlah pengikutnya yang tak dapat dibendung. Mestinya sebagai pemimpin, ia optimis menyusun kekuatan dan menghadapi Muhammad. Nyatanya ia malah menyuruh mereka yang ketakutan untuk berlindung di rumahnya, atau di rumah mereka sendiri kalau mau, dan keamanan mereka dijamin.
Kontras dengan yang selama ini kita pahami bahwa Fathu Mekah murni adalah sebuah kedatangan akbar tanpa didahului kesepakatan bilateral (antara Muhammad dan Abu Sufyan) yang tersembunyi itu.
Demikianlah bagaimana Hazleton menampilkan Muhammad sebagai manusia yang punya kemampuan berpikir di atas manusia rata-rata di zaman dan di dunianya--Arab, dari pemuda biasa menjadi kepala negara. Manusia Quraisy yang hidup terlatih dalam kerasnya hidup bersama suku Badui pedalaman, yang kelak hanya diposisikan sebagai penjaga unta oleh pamannya sendiri--Abu Thalib (versi Hazleton)--sebab wibawanya sebagai Quraisy dicopot oleh statusnya sebagai anak yatim-piatu. Muhammad adalah suatu keajaiban, yang bukan berupa keajaiban mistik.
Sayangnya ini bisa berpotensi dipahami demikan: bahwa Muhammad tak lain adalah pemimpin karismatik, piawai, dan visioner berskala lokal jazirah Arab, walaupun instruksi wahyu Allah selalu menyertai ataupun mendahului tindakannya. Padahal Muhammad adalah seorang nabi yang dituntut untuk menyebarkan ajaran Tuhan ke seantero penjuru bumi.
Satu hal yang tak berupaya dijelaskan Hazleton, yaitu dalam proses menerima wahyu, teori atau epistemologi yang dimiliki seorang nabi sehingga bisa menerima wahyu ilahi, ataukah indikator bagaimana Muhammad menjadi tokoh universal dengan wahyu yang dibawanya. Melainkan persoalan ini merujuk begitu saja sekurang-kurangnya pada dua rujukan primer yang dicantumkannya di bagian belakang buku, yaitu Ibnu Ishaq dan At-Thabari.
Mungkin saja Hazleton tidak begitu berkepentingan dengan rasionalisasi itu, sebab dia membicarakan kehadiran Muhammad sebatas konteks zaman dan wilayah kerjanya. Hal yang mungkin saja akan mengundang kecurigaan berikutnya, bahwa begitulah cara orientalis menulis. Berhubung Hazleton adalah seorang perempuan Yahudi yang bercita-cita menjadi Rabi sewaktu dia masih remaja.
Meskipun begitu, Hazleton juga melakukan pembelaan terhadap serangkaian tuduhan kaum orientalis terhadap Muhammad dalam bukunya itu. Terutama stigma libido seksual yang sangat tinggi, dibuktikan dengan istri yang banyak. Kita bisa melihat salah satu dampaknya di masa kini adalah karikatur penghinaan atas Muhammad pada beberapa sampul majalah Charlie Hebdo di Prancis.
Hazleton menepis tudingan semacam itu dengan berupaya menyadarkan mula-mula pada tidak adanya keturunan dari istri-istrinya kecuali Khadijah--dan juga "selir" (?) nya bernama Maria Al-Qibti, pun tidak dengan Aisyah sebagai istri Muhammad yang dominan dikisahkan dalam sejarah Islam.
Alasan itu dilapis dengan argumentasi pernikahan sebagai salah satu strategi dalam mengikat komitmen antar-suku, antar-kabilah, maupun antar-negeri. Hazleton mencitrakan Muhammad tampil memainkan peran ini dengan begitu piawai. Bahwa Muhammad sangat memahami pernikahan--pasca Khadijah--adalah jalan lain untuk membangkitkan kepercayaan dari pihak yang komitmennya telah diikat. Dengan begitu, Muhammad bisa dengan mudah memperluas pengaruhnya.
Hal lain dan mungkin yang paling hebat dari penggambaran Hazleton akan kepemimpinan Muhammad dalam mengubah tradisi masyarakat Arab, yaitu Muhammad adalah tokoh revolusi tatanan masyarakat Arab yang semula hidup tanpa pemerintahan--melainkan hanya berdasarkan kabilah-kabilah dan suku-suku beserta hierarki kekuatannya--diubah menjadi masyarakat yang terpimpin di bawah pengawasan wahyu, dalam struktur masyarakat yang egalitarian.
Wahyu (Al-Qur'an) itu sendiri kelak adalah mukjizat yang bukan berupa keajaiban supranatural. Melainkan keajaiban dalam hal ilmu pengetahuan, sesuai dengan tipologi manusia Muhammad, makhluk rasional pasca zaman Abrahah.
***
Judul: Pribadi Muhammad: Riwayat Hidup sang Nabi dalam Bingkai Sejarah, Politik, Agama, dan Psikologi
Judul Asli: The First Muslim: The Story of Muhammad
Penulis: Lesley Hazleton
Penerjemah: Adi Toha
Penerbit: PT. Pustaka Alvabet
Tahun: Cet. II, 2015
Tebal: 386 halaman
ISBN: 978-602-9193-74-9