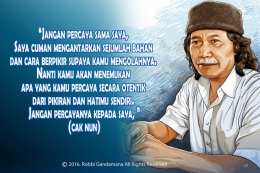Bersyukurlah orang yang mengenal dan mengikuti 'sepak terjang' Cak Nun karena tak perlu membaca berjilid-jilid buku untuk memahami ilmu kehidupan. Cak Nun benar-benar membuka pori-pori kecerdasan umat dengan pemikirannya yang dahsyat dan revolusioner.
Sebutan budayawan, penyair, seniman, atau apalah, itu hanyalah bungkus, hakikat beliau lebih dari itu. Ilmu agama, pengetahuan umum dan makrifat Cak Nun begitu istimewa, nggak salah kalau banyak orang menyebutnya sebagai kyainya para kyai.
Ini adalah puzzle-puzzle pemikiran beliau tentang umat dan pemimpin agama (Islam) yang saya himpun dari berbagai sumber. Saya terinspirasi menuliskan ini setelah membaca berita-berita di dumay, ulama sedang naik daun. Tapi sori Jek, saya tidak sedang bicara politik.
***
Umat Islam sekarang sama sekali kurang berpendidikan dalam soal Islam. Tidak ada tradisi ijtihad, tidak mengerti harus taat pada siapa. Kalau ada orang berbuat sesuatu, nanyanya, "Kyai siapa yang ngomong?", "Kitabnya apa?", tapi tidak ditanya, "Qur'annya apa?" Semua perbuatan pun harus berdasarkan dalil. Itu saking tidak berpendidikannya. Dan memang tidak ada mekanisme berpikir, padahal Islam adalah agama yang aqliyah (cara berpikir). Dan itu yang membedakan manusia dengan wedus.
Kalau nggak dipikir atau tanpa akal, itu sama kayak kambing yang disodori buku tebal penuh ilmu pengetahuan. Kambingnya cuman ndlahom, nggak paham. Mau secanggih atau sedetail apa pun sistem nilai dalam Islam, tak ada gunanya kalau manusia menghadapinya tanpa menggunakan akal.
Banyak orang tidak pernah berpikir mendasar, tidak pernah mengerti pijakan hidup, nggak pernah memiliki akar-akar nilai. Jadi akhirnya menafsirkan sesuatu begitu tidak berakalnya, begitu gemblungnya.
Maka yang harus disebarkan adalah etos tadabbur: berpikir secara menyeluruh yang sampai pada akhir-akhir dari indikasi-indikasi kalimat dan tujuan-tujuannya yang jauh.
Bertadabbur tidak berarti antitafsir. Tafsir dibutuhkan pada saat sesuatu harus ditafsirkan. Yang pokok dalam Islam adalah tadabbur: kamu mencari manfaat dari pergaulanmu dengan nilai-nilai Islam terutama Al Qur'an. Parameternya (ukuran keberhasilan) adalah yang penting kamu menjadi lebih baik sebagai manusia.
Paham atau nggak paham itu bukan parameter. Benar atau tidak benar pemahamanmu itu juga bukan parameter. Parameternya adalah setelah kamu baca dan mencintai Al Quran kamu menjadi lebih dekat kepada Allah apa tidak, lebih beriman apa tidak, kamu lebih baik menjadi manusia apa tidak.
Kenapa perlu menggalakan taddabur? Karena umat Islam sekarang tergantung pada ahli tafsir. Kita semua dibuat merasa tidak paham Al Qur'an. Kita tidak pernah dimerdekakan untuk otentik bergaul dengan Allah dan Al Qur'an. Kita harus selalu pakai makelar: ulama, kyai, ustadz, dst. Mereka menjadi 'makelar' di antara kita dan Al Quran, di antara kita dan Allah.
"Saya bukan makelar! Yang saya omongkan tidak harus Anda anut. karena Anda berdaulat atas diri Anda sendiri, Anda bertanggung jawab atas diri Anda sendiri di hadapan Allah. Jadi setiap keputusan, langkah, pikiran, dan sikap Anda harus berasal dari Anda sendiri karena nanti tanggung jawabnya juga Anda sendiri," kata Cak Nun.
"Saya tidak bisa mempertanggungjawabkan kelakuan Anda. Saya bukan Nabi Muhammad. Kalau Muhammad harus ditaati, karena bisa menolong kita. Sedangkan saya tidak bisa menolong Anda," lanjutnya.
Ke Al-Qur'an jangan pakai makelar. Kalau pakai makelar itu sebagai wacana atau mendengarkan, tapi tetap pertimbangannya ada pada kita. Selama ini umat Islam dibikin tidak pernah merasa paham Al Qur'an, untuk itu harus tanya pada kyai, ulama, dst.
Padahal kebenaran (sejati) itu tidak ada, yang bisa dilakukan manusia itu sebisa mungkin menuju kebenaran. Kebenaran itu ada 3: benarnya diri sendiri, benarnya orang banyak dan kebenaran sejati. Dan yang bikin kita bentrok itu karena seseorang atau umat ngotot dengan benarnya sendiri.
Suara kokok ayam versi orang Madura itu "kukurunuk", orang Sunda "kongkorongkong", orang Jawa "kukuruyuk". Yang benar yang mana? semuanya salah. Yang benar adalah taruh ayamnya di tengah ketiga orang tadi dan sama-sama mendengar suara kokok ayamnya.
Jarak antara kokok ayam dengan kita menirukan suara kokoknya itu namanya tafsir. Tafsir itu melahirkan madzhab dan pengelompokan-pengelompokan. Itu karena pendengarannya berbeda terhadap suara kokok ayam tadi.
Kita harus saling menyadari bahwa yang benar itu ayam. Antara tafsir 'kukuruyuk', 'kukurunuk' dan 'kongkorongkong' harus saling menyadari kelemahan masing-masing sehingga tercipta toleransi. Kalau nganggap benarnya sendiri, egois atau egosentris dengan tafsirnya sendiri maka akan terjadi bentrok.
Maka sebenarnya tidak ada tafsir yang betul betul benar atau benar-benar betul, nek wong Jowo, bener bener pener. Anda boleh menafsirkan menurut pikiranmu yang penting itu membuatmu menjadi lebih dekat, lebih cinta pada agama dan Tuhanmu. Dan tentu saja tidak menimbulkan kemudharatan umat.
Pandai-pandailah membedakan mana agama, mana terjemahan syariatnya, mana fiqihnya. Fiqih pun banyak versinya, fiqih A, fiqih B, dst. Tapi tetap default-nya adalah Al Qur'an. Sedangkan hadits itu diidentifikasi, dihimpun 300 tahun sesudah hidupnya Nabi Muhammad.
Jadi hadits itu berdasar katanya. Katanya ulama itu, perawi itu. Ada yang lulus, ada yang tidak. Jumlahnya dua juta dua ratus hadits, yang lulus di bawah seratus ribu. Itu pun belum tentu lulus. Kalau kira-kira tidak masuk akal, buang saja, hanya Al Qur'an yang dipakai.
Maka hadits pun harus diverifikasi. Apalagi jaman dulu tak ada alat perekam. Jadi kalimatnya tidak sama persis dengan yang tercantum di kitab hadits. Hanya Al Qur-an yang kalimatnya sama persis dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan tak bakalan bisa diubah.
"Saya sering bilang, jangan percaya sama saya, saya cuman mengantarkan sejumlah bahan dan cara berpikir supaya kamu mengolahnya. Nanti kamu akan menemukan apa yang kamu percaya secara otentik dari pikiran dan hatimu sendiri. Jangan percayanya kepada saya, " kata Cak Nun.
"Penjelasan saya itu khan menurut saya. Anda juga boleh menurut Anda, asal baik. Anda selalu berpikir bahwa jawaban saya itu kebenaran. Itu salah. Sama-sama belum tentu benar. Yang membuat kita sampai ke Allah adalah kita beritikad baik di dalam yang belum tentu benar itu. Tidak apa-apa nggak benar-benar banget. Presisinya nggak harus pas banget, hadap kiblat 24.5 derajat, akhirnya ke mana-mana bawa garisan," imbuh beliau.
Jadi antara kita dengan Tuhan jangan ada siapa-siapa. Kita sama Tuhan itu langsung. Bahwa kita mendengarkan kyai, ulama, ustadz itu wacana, tapi mereka tidak mewakili kita. Dan mereka tidak bisa menyelamatkan kita.
Apakah kyai bisa menyelamatkan kamu? Apakah ulama bisa menyelamatkanmu? Tidak bisa. Begitu juga dengan pemuka agama yang lain, tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan kamu sendiri di hadapan Allah. Maka kalau kamu beribadah pada Allah jangan ada siapa-siapa.
"Saya tidak mau ada di antara Anda dengan Tuhan," kata Cak Nun.
Susahnya pimpinan-pimpinan agama suka bertempat di situ. Menjadi 'gerhana' di antara Tuhan dengan umatnya. Karena di situ ada jabatan, kepemimpinan, akses eksistensi dan ekonomi.
"Saya bicara begini supaya Anda percaya sama Allah, bukan percaya sama saya. Makanya saya jangan jadikan panutan. Yang bisa kau ambil dari saya adalah sebagian yang relevan untukmu, sebagian kecenderungan saya yang pas untuk kamu. Dan itu sebenarnya kamu tidak meniru saya, tapi pihak yang sebelum saya: Nabi atau Tuhan sendiri, bukan saya. Saya cuma akselerator dari nilai dan kecenderungan itu," tegasnya lagi.
Kesimpulannya, kebenaran itu tidak pada siapa pun. Kecuali pada keputusan terakhirmu masing-masing. Karena itu nanti yang dihisab oleh Allah. Kamu boleh mendengar apa pun, boleh menafsirkan kayak apa pun, boleh melakukan apa pun setelah itu. Tapi sebenarnya yang dinilai adalah bahwa itu menjadi keputusanmu.
Jangan pernah punya keputusan yang tidak otentik pada dirimu. Artinya kalau shalatmu itu ya shalat kamu dan Allah, itu otentik. Bukan kamu plus Cak Nun, plus Kyai, plus Ustadz, plus Ulama dan Allah.
Wis ah..
(@) Robbi Gandamana, 15 Oktober 2016
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H