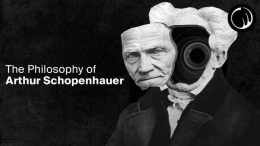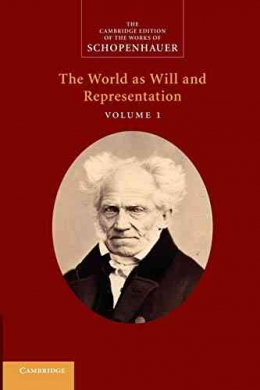Pendahuluan
Salah satu pertanyaan paling penting yang menjadi pokok persoalan filosofis terdalam sepanjang sejarah filsafat adalah apakah sebenarnya realitas itu? Sejak era permulaan filsafat, pertanyaan enigmatis tentang realitas dunia tersebut selalu menjadi hal yang paling penting untuk diuraikan. Para filosof barat sejak 2000 tahun yang lalu telah mencoba menggali lebih dalam kenyataan yang ada di dunia ini guna menjawab enigma tak terpecahkan itu.
Seorang filosof bernama Arthur Schopenhauer merupakan salah satu filosof di abad modern yang ingin memecahkan persoalan tersebut dengan melihat dunia sebagai kehendak dan representasi.
Baginya, dunia tidak lain adalah sebuah kehendak yang menjadi representasi dari diri. Subyek yang mempersepsi mutlak ada di hadapan obyek. Dari pemikiran tentang kehendak ini, Schopenhauer mengembangkan satu pemikiran filosofis tentang kehendak yang irasional, buta dan tak terhentikan. Kehendak ini ternyata menghasilkan penderitaan bagi manusia itu sendiri.
Manusia hanya berlangkah dari satu pintu penderitaan ke pintu yang lain. Cara yang terbaik adalah menerima dan menghadapi kenyataan bahwa penderitaan menjadi bagian dari kehidupan manusia.
Keberanian Schopenhauer untuk mengelaborasi hakikat realitas sebagai kehendak dan representasi patut menjadi bahan diskusi yang tak terbantahkan. Meskipun dia dikenal sebagai filosof pesimistis, Schopenhauer menyumbang gagasan bagi banyak pemikir di abad-abad selanjutnya.
Biografi
Arthur Schopenhauer adalah seorang filsuf idealis Jerman yang melanjutkan tradisi filsafat pasca-Kant. Schopenhauer lahir di Danzig pada tahun 1788. Ia mempelajari filsafat di Universitas Berlin dan mendapat gelar doktor di Universitas Jena pada tahun 1813.[1] Ia hidup sebagai bujang kaya berkat warisan orangtuanya.
Schopenhauer sering hidup dalam ketakutan dan merasa terancam karena ia memiliki banyak harta. Oleh sebab itu, dia sering tidur dengan pistol di sampingnya. Schopenhauer hidup sendiri dan rencana pernikahannya selalu berantakan. Dia menganggap hidup dengan banyak orang memuakkan dan membuang waktu baginya.[2]
Schopenhauer banyak menerbitkan tulisan, tetapi tidak laku dijual di masa mudanya. Kendati demikian, ketika ia telah menginjak usia lanjut barulah karya-karyanya mulai diminati banyak orang.
Pada tahun 1820, ia menulis sebuah buku yang sebuah buku yang berjudul "Dunia sebagai Kehendak dan Representasi". Dalam buku tersebut tersimpan gagasan-gagasan besar yang menjadi pokok pemikiran Schopenhauer.
Setelah menulis buku tersebut ia menjadi pengajar di Universitas yang sama dengan Hegel di Berlin. Setelah kalah pamor dari Hegel, Schopenhauer mengundurkan diri dari universitas dan kemudian menghabiskan sebagian besar hidupnya sendirian di Frankfurt, ia meninggal dunia di sana pada tahun 1860.[3]
Pengaruh Kant, Hegel, dan Budhisme dalam Filsafatnya

Dalam pandangan filsafatnya yang termuat dalam buku "The World as Will and Representation" (Die Welt als Wille und Vorstellung), Schopenhauer pertama-tama sangat dipengaruhi oleh filsafat Immanuel Kant, Hegel, dan juga pandangan Buddha.
Pemikiran Kant tampak mempengaruhi pandangan Schopenhauer yang melihat dunia sebagai ide dan kehendak.[4] Kant menyatakan bahwa pengetahuan manusia terbatas pada apa yang dapat dicerna oleh pancaindra (phenomena), sehingga benda-pada-dirinya-sendiri (noumena atau das Ding an sich) tidak pernah bisa diketahui manusia.
Misalnya, apa yang manusia ketahui tentang pohon bukanlah pohon itu sendiri, melainkan ide setelah pohon itu dipahami oleh pancaindra. Schopenhauer mengembangkan pemikiran Kant tersebut dengan menyatakan bahwa benda-pada-dirinya-sendiri itu bisa diketahui, yakni "kehendak".[5]
Selain Kant, Hegel juga mempengaruhi Schopenhauer dengan idenya tentang fenomenologi roh. Sebelumnya, filsuf terkemuka Hegel telah mempopulerkan konsep Zeitgeist, ide bahwa masyarakat terdiri atas kesadaran akan kolektifitas yang digerakkan di dalam sebuah arah yang jelas.[6] Hegel jelas sekali menekankan aspek rasionalitas di sini.
Bagi Hegel, kebenaran harus disamakan dengan keseluruhan, dengan kesatuan segala sesuatu yang ada. Idealismenya kemudian diletakkan dalam pandangannya "segala yang rasional adalah real dan segala yang real adalah rasional."[7] Hegel meletakkan gagasan idealisme pada rasionalitas.
Dengan demikian, realitas dipahami sebagai roh absolut di mana fenomena lahiriah yang mendapat pemaknaan merupakan produk rasio manusia. Schopenhauer dalam hal tersebut berseberangan dengan Hegel.
Ia tidak sepakat dengan pemikiran Hegel bahwa realitas itu rasional. Menurut Schopenhauer, dasar dari realitas adalah irrasional dan buta. Ia bukanlah kesadaran, melainkan ketidaksadaran. Schopenhauer menamakannya sebagai kehendak. Kesadaran dan rasio berada pada tataran permukaan saja, tetapi kehendak menjiwai segala sesuatu dan menjadi dasar dari segala sesuatu.
Dari pandangan Buddha, pandangan filosofis Schopenhauer dalam bukunya melihat bahwa hidup adalah penderitaan. Schopenhauer menolak kehendak. Apalagi dengan kehendak untuk membantu orang menderita.[8] Ajaran Schopenhauer adalah menolak kehendak untuk hidup dan segala manifestasinya, tetapi sejatinya Schopenhauer sediri takut dengan kematian.
Pandangannya tentang Dunia sebagai Kehendak dan Representasi
Schopenhauer menyebut kehendak (wille) menjadi representasi dari dunia. Dunia yang dimaksud di sini adalah noumenal world. Immanuel Kant, sang pencetus tesis dunia sebagai fenomena dan noumena, menyatakan ketidakmungkinan seseorang untuk mencapai realitas dalam dirinya sendiri (thing in-it-self). Menurut Schopenhauer, ketidakmungkinan seseorang untuk mencapai realitas tersebut bukannya tanpa solusi. Ia menyebut adanya "pintu belakang" untuk mencapai dunia noumena.
Menurut idealisme transendental Kant, manusia sebagai subyek, bukannya pencipta dunia pengalaman-pengalaman atau realitas, tetapi hanya pencipta syarat-syarat penentu terjadinya proses pengenalan atau pengetahuan.
Pemikiran ini didasarkan pada kemampuan manusia yang memiliki akal budi yang memampukannya mencerap obyek sebagai fenomena. Karena manusia tidak akan dapat sampai pada pengenalan obyek sebagai noumena. Schopenhauer rupanya tidak puas dengan pemikiran Kant mengenai noumena. Schopenhauer kemudian mengembangkan pemikiran Kant. Ia bertitik tolak dari pemikiran Kant tentang dunia sebagai obyek.
Obyek (dunia) hanya ada untuk pengetahuan subyek dan karenanya seluruh dunia diartikan hanya sebagai obyek dalam kaitannya dengan subyek, persepsi dari yang mempersepsi, dan singkatnya adalah ide.
Apabila dilihat secara khusus, menurut Schopenhauer, kehendak merupakan "desakan kuat yang tidak sadar, buta dan tidak bisa dihentikan." Kehendak memerlukan pemuasan sepenuhnya secara terus-menerus. Begitulah seterusnya sampai tidak berhingga. Namun justru pemuasan sepenuhnya dan tidak berhingga inilah yang tidak mungkin tercapai.
Keadaan ini menyiksa dan menyebabkan berbagai penderitaan dalam hidup. Bagi Schopenhauer, kehendak adalah sumber penderitaan dan karena kehendak mewujudkan dirinya dalam semua bidang kehidupan, maka kehidupan itu sendiri adalah penderitaan. Di sini, ia juga menolak kehendak untuk membantu orang menderita.
Baginya, kehendak untuk membantu orang juga tidak akan pernah terpuaskan, karena ketika manusia membantu sesamanya yang menderita, kehendak itu tidak akan terpuaskan, ia tidak akan dapat melepaskan diri dari kehendak itu sehingga ia akan mengalami penderitaan terus menerus. Dengan demikian, Schopenhauer sejatinya menolak sikap bela rasa. Tidak heran jika filsafatnya sering disebut sebagai filsafat pesimis-egoistis.
Bagi Schopenhauer, penyebab suatu penderitaan ialah kehendak untuk hidup itu sendiri. Kita menderita karena disiksa dan dirongrong oleh tuntutan-tuntutan kehendak untuk hidup.[9] Ada dua hal yang menjadi pertimbangan manusia, yaitu apakah ia hendak menyetujui kehendak (Bejahung des Willens) atau penyangkalan kehendak (Verneinung des Willens).[10] Ketika manusia justru menghendaki untuk memilih menyetujui kehendak, ia masuk ke dalam jurang penderitaan. Ia tidak pernah akan mengalami kepuasan, tetapi seperti kata Schopenhauer ia akan "keluar dari satu penderitaan untuk masuk ke penderitaan yang lain." Sedangkan jalan kedua yang ditawarkan ialah menyangkal kehendak. Satu-satunya solusi yang membawa manusia keluar dari penderitaan ialah menyangkal kehendaknya sendiri. Saat itulah ia mengalami sebuah pembebasan dari penderitaan.
Sejatinya, cara pemikiran Schopenhauer ini menarik. Namun, tetap saja memiliki kesalahan. Masalah dalam filsafatnya berkaitan dengan pandangannya atas pengetahuan tentang prinsip individuasi. Menurut Schopenhauer, berkat pengetahuan inilah manusia sadar bahwa dirinya adalah sama dengan semua makhluk hidup lain (dasar dari sikap bela rasa) sehingga dia tidak perlu memutlakkan diri dengan keinginannya (dasar sikap mati raga atau penyangkalan diri). Tanpa pengetahuan ini, manusia tidak akan mengalami pencerahan dan tetap berada dalam kegelapan.
Anggapan Schopenhauer ini menekankan dua hal, yaitu bahwa kesadaran manusia terbukti lebih kuat dibandingkan nafsu dan keinginannya, dan bahwa karena itu ia juga mampu memperhatikan keadaan kepentingan orang lain, di dalam hal ini berarti bahwa manusia bukanlah makhluk egois sebagai mana yang dipikirkan oleh Schopenhauer. Namun, jika kesadaran bisa menguatkan manusia menyangkal diri dan berbela rasa, bukankah demikian kehendak untuk hidup itu sendiri bukan merupakan dasar dari segalanya?[11]
Pengaruh Filsafatnya terhadap Filosof-Filosof Lain

Kendatipun demikian, pengaruh Scopenhauer dalam perkembangan pemikiran selanjutnya cukup besar. Ia membuka jalan bagi orang suatu psikologi tentang alam bawah sadar ala Freud. Pemikiran Schopenhauer tentang kehendak untuk hidup di kemudian hari mempengaruhi filsafat Nietzsche tentang kehendak untuk berkuasa (Der Wille zur Macht). Setengah abad kemudian, ajaran Schopenhauer ini memberikan inspirasi pada filsafat hidup (Vitalisme), misalnya pada pemikiran Henry Bergson (1859-1941). Selain itu, ia menghidupkan perhatian dan minat orang Barat pada studi kesustraan dan agama-agama Timur, terkhusus Buddhisme.[12]
Catatan Kaki
[1] Kathleen Marie Higgins, "Schopenhauer, Arthur", In Robert Audi (ed), The Cambridge Dictionary of Philosophy (London: Cambridge University Press, 1999), hlm. 820.
[2] Simon Petrus L. Tjahjadi, Petualangan Intelektual (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 329-333
[3] James Garvey, Dua Puluh Karya Filsafat Terbesar, penerj: CB. Mulyanto (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 189.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Lihat. Dr. Zubaedi, Dkk, Filsafat Barat: dari Logika Baru Rene Descrates Hingga Revolusi Sains ala Thomas Kuhn (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 87.
[8] Simon Petrus L. Tjahjadi, Loc. Cit.
[9] P. A. Van der Weij, Filsuf-Filsuf Besar tentang Manusia, penerj. K. Bertens (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 137.
[10] Simon Petrus L. Tjahjadi, Op. Cit., hlm. 336.
[11] Ibid.
[12] Ibid., hlm. 340.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H