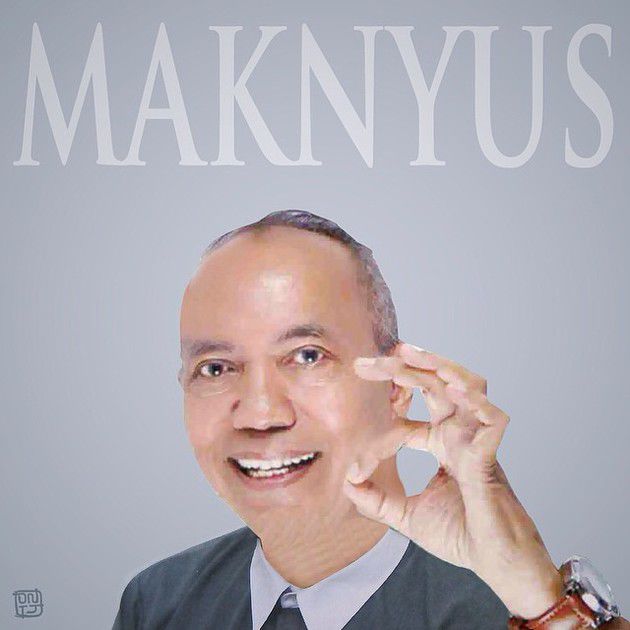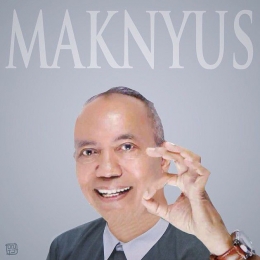Setelah BI merilis uang baru bersama harapan agar perekonomian Indonesia juga memasuki babak baru, Sis Dwi Estiningsih bercuit. Cuitannya mempersoalkan pilihan BI, atau siapapun otoritas di belakang pencetakan uang baru, dalam menjadikan 5 pahlawan “kafir” sebagai ikon pada lembar-lembar uang kertas tersebut.
Menurut Sis Dwi, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam berhak untuk melihat pilihan itu sebagai suatu hal yang mengganggu. Dibantu oleh pengetahuan Sis Dwi yang mumpuni di bidang psikologi (Sis Dwi ini master pada bidang ilmu tersebut), ia berhasil memenangkan segelintir massa.
Tidak sedikit netizen mengamini ide Sis Dwi, mempertanyakan secara skeptis tentang pahlawan-pahlawan yang ada di uang baru itu. Beberapa netizen bahkan dengan amat cerdas menarasikan pertanyaan menjadi pernyataan yang shahih. “Siapa sih dia ini?” kalimat berakhirkan tanda tanya itu lebih terdengar seperti vonis majelis hakim ketimbang pertanyaan pelajar yang belum hafal nama pahlawan.
Beberapa lainnya menggunakan pengandaian pars pro toto, menjelaskan fenomena besar semata-mata dengan subjektivitasnya. “Saya lahir tahun ’72, saya nggak pernah tahu pahlawan ini”. ujarnya sambil menuding Frans Kaisiepo tokoh yang berkontribusi dalam memasukkan Papua ke dalam peta Indonesia. Tanpa beliau, ujung timur peta kita akan berhenti di Maluku. Apa ndak wagu?
Sebenarnya saya lebih ingin menganggap perkataan Sis Dwi sebagai angin lalu dan apa yang ia lontarkan sebagai upaya menggalang lebih banyak followers. Akun Twitter dengan banyak followers bagaikan modal usaha 1 unit ruko milik Agung Podomoro, misal suatu waktu Sis Dwi sudah lelah nyinyir pastilah akunnya bisa dijual ke pedagang kaos turn back crime. Tetapi, tuntutan kesarjanaan yang membuat saya bangun lebih pagi dan membuka laptop, berusaha menyusun pledoi untuk anda semua baca.
Sebagai alumni Jurusan Sejarah dengan gelar S.S. (Sarjana Sastra, bukan Sarjana Sejarah apalagi Spesial Sambal), saya sering ditanya sanak famili mengenai persoalan ini. Hanya melalui tulisan ini, saya justru ingin menegaskan bahwa apa yang Sis Dwi persoalkan melalui twitternya bukan semata-mata urusan sejarah. Lebih luas lagi, pemilihan siapa pahlawan dan pengkhianat berdiri di atas sebuah platform yang amat kompleks dan membuat kenyiyiran Sis Dwi menjadi terdengar cenderung meremehkan.
Sejarawan adalah Pak Bondan Winarno
Sejarawan, menurut hemat saya, bekerja bagaikan Bondan Winarno yang tugasnya pergi mengunjungi berbagai restoran dan mengatakan maknyus ke semua makanan. Sate Padang Mak Syukur dia bilang maknyus, Sate Padang Ajo Ramon pun dia anggap maknyus. Jika kita bertanya pada Pak Bondan, Makanan apa yang paling maknyus daripada semua menu yang maknyus? pastilah Pak Bondan meminta sang penanya untuk mengelaborasi pertanyaannya. Pada kategori makanan apa? Di mana? Makanan utama atau kudapan? Begitulah kira-kira.
Sejarawan cenderung menenggelamkan diri dalam detail-detail yang menurut istilah mereka einmalig alias unik dan terjadi hanya satu kali pada ruang dan waktu tertentu. Sejarawan cenderung tertarik pada keping keping fenomena: penciptaan mobil, perjalanan haji sebelum pesawat diciptakan, perang candu, dan hal-hal lainnya. Sejarawan menganggap semua peristiwa yang dapat digunakan untuk membangun eksplanasi atas manusia sebagai sesuatu yang maknyus. Pada konteks pahlawan, sejarawan juga akan bertindak sebagaimana Pak Bondan. Jika ditanya: Siapa yang berhak diberi gelar pahlawan?, Sejarawan akan meminta sang penanya untuk menjembrengi pertanyaannya dengan lebih mendetail.
Di Makassar, Sultan Hassanudin adalah pahlawan tetapi di Bone, Arung Palakka adalah pejuang yang mereka kenang. Lepas dari klaim Sis Dwi dalam tanda pagarnya bahwa "untung saya belajar #sejarah, menurut saya, sejarah justru menghadirkan banyak "ruang tengah" yang menahan orang untuk menghakimi. Dalam bahasa latin, dikenal istilah: Sapientia et Historiam yang kurang lebih berarti "Belajar Sejarah membuat Bijaksana". Ruang tengah dan abu-abu itu jelas tidak disukai oleh banyak orang, terutama mereka yang gencar mempromosikan pandangan biner atas segala sesuatu. Nah, daerah abu-abu ini yang membuat sejarah selalu in a complicated relationship dengan proses pemberian gelar kepahlawanan.
Pemberian Gelar Kepahlawanan adalah Festival Jajanan Bango
Jika sejarawan adalah Pak Bondan Winarno yang bisa bilang maknyus ke semua makanan yang diliput dalam acaranya, maka pemberian gelar kepahlawanan itu saya ibaratkan Festival Jajanan Bango. Maafkan saya jika pengandaiannya melulu berkaitan dengan urusan mengunyah tetapi mudahnya memang diandaikan begitu. Berbeda dengan Pak Bondan yang bisa menebar maknyus ke semua makanan yang dia anggap endes, Festival Jajanan Kecap Bango tentu tidak bisa bertindak demikian.
Festival Jajanan Kecap Bango harus memilih makanan terbaik dari sebuah wilayah dan kemudian diundang ke acara mereka. Festival Jajanan Kecap Bango harus menentukan standard mereka atas definisi “makanan enak” di mana definisi tersebut disusun dan disepakati oleh tim yang dibentuk. Bayangkan Festival Bango akan diadakan di Jogja, gudeg mana yang harus dipilih dari ribuan penjual gudeg di Jogja? Tim Bango tidak bisa bilang “Semua gudeg dasarnya enak jadi kita undang semua”.
Nilai kepahlawanan tidak hadir begitu saja. Menurut hemat saya, nilai-nilai itu dikonstruksikan secara sengaja oleh orang yang ditugaskan oleh negara untuk mengangkat pahlawan dan memberikan tanda-tanda jasa. Di Indonesia, tim tersebut ada di bawah Kementerian Sosial yang beranggotakan ahli dari berbagai latar belakang.
Meskipun nggak pernah ketemu, saya percaya bahwa Pangeran Diponegoro nggak pernah perang sambil bilang ke pengikutnya “catat ya le, ini aku sedang mempraktekkan nilai kepahlawanan yang disusun oleh nilai kerjasama dan rela berkorban”. Melalui arsip dan sumber sejarah lain, tim ahli di era sekarang membangun imaji bahwa Pangeran Diponegoro itu rela berkorban berdasarkan sederet tindakan yang pernah ia tempuh.
Standard sebuah negara atas nilai kepahlawanan juga relatif. Apa yang dikerjakan oleh I Gusti Ketut Djelantik sangatlah berbeda dengan apa yang dihadapi oleh I Gusti Ngurah Rai. Lalu, apa yang menyatukan mereka menjadi pahlawan? Ya, definisi “makanan enak” menurut Bango itu, atau dalam hal ini: definisi “pahlawan”.
Intinya sih ya Sis Dwi benar kalau pahlawan yang dijadikan figur di mata uang itu dipilih oleh negara. Hanya, Indonesia Raya yang menanggap keberagaman sebagai ruhnya tidak meletakkan agama sebagai pertimbangan atas pemberian gelar kepahlawanan kepada seseorang. Sis Dwi juga benar, bahwa di dalam agama Islam siapapun yang tidak mengimani kepercayaan agama Islam bisa digolongkan sebagai kafir. Tetapi Sis Dwi lupa bahwa ketika para pahlawan memutuskan untuk berbuat sesuatu, mereka tidak membedakan siapa kafir dan siapa muslim. Mungkin Sis Dwi sudah tahu, ketika dua kelompok berbeda memiliki musuh bersama, mereka akan bersatu.
Tetapi, berat hati saya untuk membenarkan pernyataan Sis Dwi tentang non-muslim sebagai pengkhianat. Sebagaimana nilai kepahlawanan yang relatif, begitu pula ‘pengkhianat’. Jika pengkhianat menurut Sis Dwi adalah siapapun yang melawan pemerintah RI, maka Sis Dwi lupa memasukkan Darul Islam dan Partai Masyumi yang mendukung PRRI/Permesta. Kalau menurut Sis Dwi, pengkhianat adalah kolaborator kolonial Belanda, maka Sis Dwi pasti sedang lupa kisah Sentot Ali Basjah Prawirodirdjo, tangan kanan Pangeran Diponegoro yang pernah bekerja sebagai perwira pribumi pada tentara Belanda untuk Gubernur Van Den Bosch dalam Perang Paderi.
Intinya ya Sis Dwi, siapapun yang dipilih negara untuk mejeng di lembar-lembar uang itu, nilai nominalnya masih bisa dipakai untuk pergi ke awul-awul untuk membeli celana atau beli kemenyan di Pasar Kranggan. Menggunakan uang yang menurut Sis Dwi dihiasi oleh imaji kekufuran tersebut juga nggak membuat Sis Dwi berlumur dosa sebagaiama kegemaran Sis Dwi bercuit melalui media sosial yang juga tidak didirikan oleh orang Muslim. Jika ilmu ekonomi menyatakan bahwa nilai mata uang hanya terdiri dari nilai nominal dan nilai intrinsik, kenapa sih Sis Dwi harus menambahkan nilai ketiga pada mata uang yaitu nilai konspirasi?
Saran saya sederhana, sebagaimana foto Sis Dwi yang banyak tersebar di Sosial Media, Sis Dwi nampak riang tak terkira ketika ciprat-ciprat air di pantai. Dibanding ngetweet seperti kemarin dan membuat Sis Dwi harus diserbu massa dunia maya, saya pikir ciprat-ciprat air di pantai jauh lebih berfaedah.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H