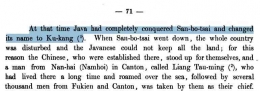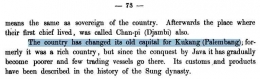Hal ini, dari kacamata modern, memang terlihat seakan-akan narasi ini bercerita tentang “komunitas Tionghoa” sebagaimana yang kita mengerti pada saat ini. Namun, jika kita mempertimbangkan jarak-waktu penceritaan, narasi ini kemungkinan menceritakan asal-usul orang Sumatra – khususnya di sini orang Jambi dan Palembang, terutama mereka yang berada di wilayah pesisir timur. Hal ini butuh untuk dimengerti dari kacamata sejarah dan bukan dari sudut pemahaman modern – yang memisahkan antara orang-orang Indonesia, sebagai bagian dari negara yang merdeka pada tahun 1945, dan orang-orang Cina sebagai bagian dari republik (baik sebagai Republik Cina atau sebagai Republik Rakyat Tiongkok) yang didirikan pada tahun 1912 dan/atau 1949.
Yang penulis maksudkan sudut pandang sejarah, kita harus mengingat bahwa interaksi ini sudah terjalin selama kurang lebih 943 tahun, katakanlah mulai dari awal masa pemerintahan kaisar Hsiau-wu (Xiaowu) dari dinasti Liu Song (454-464) hingga awal keruntuhan kerajaan San-bo-tsai pada 1397. Apakah dalam masa yang tidak singkat ini tidak terjadi “percampuran” (asimilasi) antara orang-orang yang hidup di nusantara (khususnya di wilayah-wilayah yang disebutkan dalam catatan-catatan tersebut) dengan orang-orang yang hidup dalam wilayah-wilayah dinasti-dinasti di Cina?
Hal ini belum ditambah keterangan tentang asimilasi (percampuran) itu sendiri, seperti yang tertulis dalam keterangan shifu Ma Huan, Ying-yai Sheng-lan (Yingya Shenglan - 1416) tentang “Jawa”; di mana pada bagian “Modjopait” (Moa-tsia-pa-i) diceritakan bahwa orang-orang Cina yang melarikan diri dari Canton (Guangzhou), Chang-chou (Zhangzhou), dan Ch’uan-chou (Quanzhou) yang tinggal di tempat ini telah menganut agama nabi Muhammad (Mahomedan) dan menjalankan ajaran Islam (hal. 49-50).

Keturunan orang-orang ini (entah siapa atau sekarang berada di mana), dalam kurun waktu 608 tahun sejak catatan itu dibuat, apakah tidak menjadi bagian dari orang Jawa yang kita kenal saat ini? Karenanya, hal yang sama kemungkinan juga terjadi pada orang-orang yang diceritakan dalam narasi sejarah kerajaan San-bo-tsai - di sini, khususnya di akhir masa jayanya.
Atau, orang-orang (yang berasal dari) Cina yang diceritakan dalam keterangan-keterangan catatan sejarah Cina ini, dalam kurun waktu sekitar 627 tahun, pada akhirnya sangat mungkin merupakan nenek moyang orang Indonesia saat ini: orang-orang yang telah berdiam, beranakpinak, dan pada akhirnya menjadi “orang asli” di wilayah-wilayah tersebut – dan tidak terbatas pada “komunitas Tionghoa” sebagaimana yang kita mengerti pada masa ini. Karenanya juga, jika kita memperhitungkan jarak-waktu penceritaan dengan masa ini, catatan sejarah Cina sesungguhnya turut menceritakan sejarah Indonesia modern – dan bukan hanya tentang komunitas tertentu saja.

Apa yang terjadi kemudian, atau pada masa kini, adalah apa yang sebetulnya dikenal sebagai: “terputusnya nasab”. Dalam artian, entah karena keterangan dalam catatan-catatan sejarah ini tidak lagi diketahui, lepasnya konteks “jangka-waktu” dalam pembacaan sejarah, interpretasi modern yang terbilang sempit, atau hal lainnya, sangat mungkin keturunan dari orang-orang yang diceritakan dalam catatan-catatan ini tidak lagi mengetahui jika mereka adalah keturunan dari orang-orang tersebut. Dan, untuk itu, terputuslah “nasab” atau, setidaknya, pemahaman terkait “hubungan” antara nenek moyang yang datang dari negeri Cina ini dengan keturunannya. Hal yang sama kemungkinan juga terjadi sebaliknya.
Dalam catatan sejarah dinasti Sung (Song), terdapat keterangan mengenai utusan-utusan asal San-bo-tsai yang secara rutin datang membawa persembahan untuk kaisar Cina. Kaisar Cina lalu bertitah agar orang-orang ini tidak (perlu) lagi datang ke istana - melainkan untuk mendirikan tempat tinggal (establishment – walau, mungkin, bisa juga diartikan sebagai: rumah singgah) di Ch’uan-chou (Quanzhou) di provinsi Fukien (Fujian) di Cina. Peristiwa ini, berdasarkan catatan tersebut, terjadi pada tahun 1178 Masehi. Jika orang-orang ini, pada masa-masa itu, memilih menetap di sana, bukankah dalam kurun waktu 846 tahun keturunan orang-orang ini pada akhirnya akan menjadi “orang asli” di wilayah tersebut? Namun, jelas, penelitian-penelitian lanjutan, seperti tes DNA akan sangat menentukan hubungan yang ada – yang sejatinya mengarah pada hubungan kekerabatan atau bahkan kekeluargaan (pertalian darah) di antara orang-orang yang berada di nusantara, khususnya di Sumatra, dengan orang-orang di Cina.
Hal-hal seperti ini jugalah yang sebetulnya menjadi alasan menarik untuk mempelajari sejarah: sebab sejarah mengingatkan kita sebagai manusia yang saling terhubung; yang, pada dasarnya, berasal dari nenek moyang yang sama. Mungkin, tepat apa yang dinyatakan dalam Al Quran: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS 49:13)". Atau, mungkin, tepat apa yang dipertanyakan dalam Alkitab: "Bukankah kita sekalian mempunyai satu bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita?" (Maleakhi 2:10) - walau interpretasi lain ayat ini menyatakan bahwa "Bapa" yang dimaksud adalah Sang Bapa (Tuhan Allah) yang disebutkan setelahnya.
Satu hal yang mungkin tidak banyak dimengerti adalah: ide tentang keesaan Tuhan sebetulnya dekat dengan ide tentang manusia yang berasal dari nenek moyang yang sama - karenanya: sebagaimana semesta tercipta dari satu pencipta lalu menjadi beragam "mahluk" dan kejadian yang saling terhubung, seperti itu jugalah perkembangan manusia. Ide ini, sepertinya, tersimpan dalam-dalam dalam kitab-kitab suci agama-agama di dunia. Namun, untuk saat ini, keterangan ayat Alkitab di atas mungkin bisa menjadi cerminan sederhana keterhubungan dari ide-ide tersebut.