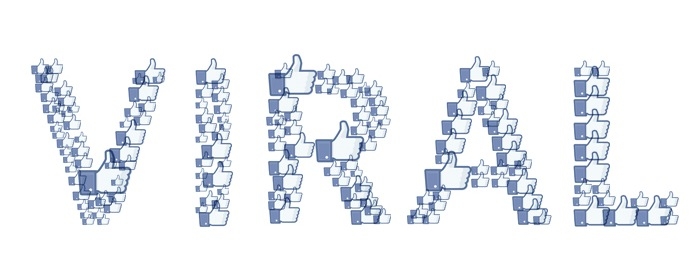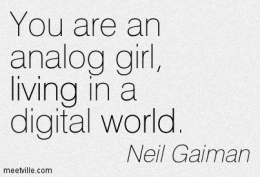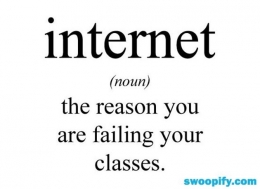“In an age of constant live connections, the central question of self-examination is drifting from ‘Who are you?’ towards ‘What are you doing?”
― Tom Chatfield, dalam How to Thrive in the Digital Age.
Trust is the glue of life. It’s the most essential ingredient in effective communication. It’s foundational principle that holds all relationship
Di dunia yang serba cepat ini, banyak orang ingin mempercepat segala urusan mereka dengan berbagai cara. Di dunia tempat banyak orang mendewa-dewakan Tuhan-Tuhan digital, apalagi. Apabila kita tidak mempergunakan akal sehat dan hati nurani, jebakan-jebakan telah menanti.
Kalau dahulu, Nabi besar umat Islam selalu bertanya perihal dari siapa berita itu berasal, dan apakah seseorang tersebut bisa dipercayai keterangannya sebelum mengambil kesaksiannya mengenai suatu peristiwa, saat ini sepertinya kita sering memilih untuk terlena atau abai saja.
“Ndak perlu lah cari tahu-cari tahu gitu, tar dikira kepo,”sergah seorang teman. Tampaknya berita yang viral di dunia media sosial, tak dirasa perlu lagi di-cek dan ricek kebenarannya. Viral berarti benar? Sungguh naif, ya, masyarakat era digital.
Kalau ada kabar angin terkait orang di lingkungan kita pun, bukankah telah menjadi adab kita untuk memverifikasi kebenarannya? Dan kalaulah iman kita adalah selemah-lemah iman, menghentikan laju berita tak jelas juntrungan dan asal-usulnya dengan tak ikut menyebarkannya barangkali pilihan terakhir.
Berita di lingkungan terdekat (real world, tentunya) relatif lebih mudah diklarifikasi. Tinggal mau atau tidak mau kita luangkan waktu untuk bertanya ke orang yang terkait berita. Atau pada sumber sekunder yang layak dipercaya. Yang trustworthy.
Namun bahkan berita dari mr socmed pun tak terlampau sulit diklarifikasi, asalkan kita bersedia luangkan waktu untuk melakukannya.
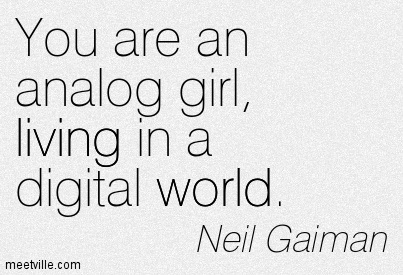
Beberapa waktu lalu ada berita tentang anak yang dilecehkan secara seksual di sebuah mall di Bandung. Sudah viral ke mana-mana, daan...ternyata hoax alias berita bohong belaka. Parahnya, ketika kita telah tahu berita itu hoax, mendadak orang yang secara sengaja atau tidak sengaja (emang bisa ya, nggak sengaja..hmm) share berita tersebut bersembunyi di balik tabir ketidakpedulian. Tidak peduli bahwa berita bohong yang disebarkannya beberapa waktu lalu itu menjadi fitnah bagi pemilik, pengelola, pegawai, dan konsumen/ pengunjung mall. Tidak peduli bahwa berita bohong yang tersebar luas itu berakibat menyebarluasnya keresahan di kalangan para orang tua, guru, maupun anak-anak / remaja yang sangat akrab dengan kegiatan jalan-jalan di mall.
Jadi, singkatnya, saya mau tanya nih: "Dosaan mana hayooo: pembuat berita hoax dan penyebar beritanya?" Yang jelas, sama-sama dosa, ya, kan?
Bukan Hoax Kok, Beneraan
Kalaupun sumpah mati berita itu bukan hoax...
Yuk kita pikir lagi. Sudah benar dan tepatkah perilaku kita ketika kita men-share berita dengan judul provokatif / menarik yang kita asumsikan perlu disebarluaskan, sebelum kita benar-benar membaca secara seksama isi berita tersebut. Sudah tepatkah perilaku kita ketika kita tak bisa menahan diri untuk tidak ikut-ikutan mem-bully seorang anak yang sex addict (kasus di Surabaya) beberapa waktu lalu. Padahal, tahukah kita betapa kompleksnya kasus sex addict yang menyangkut seorang anak?
Atau bahkan ketika kita yakin berita itu beneran, bukan hoax... sudah tepatkah perilaku kita, ketika kita tak bisa menahan diri untuk tidak nge-tweet ketika ada tagar-tagar terbaru yang menjadi trending topicsworldwide. Kicauan pengguna media sosial di Indonesia tergolong yang teraktif lho...
Begitu ada trending #awkarin aja, kita langsung ikut-ikutan nge-tweet, nga-share berita. Kira-kira, apa bukan perilaku kita yang semacam itu yang membuat kemunculan "awkarin-awkarin" baru mengingat remaja era sosial media yang sangat suka berada di tengah panggung dan menjadi pusat perhatian? Bagaimana kalau kemunculan karin itu, kita jugalah penyebabnya?
Ya. Pernahkan kita meluangkan waktu barang sejenak sebelum meng-klik tombol share? Meluangkan waktu sesaat untuk berpikir: apa manfaat perilaku kita itu?
Apa dampaknya? Atau hanya latah semata. Supaya kekinian dan eksis?
Can I Trust That?
Sejatinya yang membuat hidup kita lebih mudah, lebih efektif, dan lebih efisien. Termasuk kaitannya dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan di tempat kerja, personal, atau di mana saja yakni sesuatu yang menjadi awal yang memungkinkan hubungan antarmanusia itu terjadi. Sesuatu itu tak lain adalah trust. Apakah hal itu bisa atau layak dipercaya kebenarannya? Bukan semata karena viral dan happening banget.

Apabila kita: orang yang menyampaikan informasi tersebut merupakan figur yang bisa dipercaya, maka tak jadi soal media apa yang kemudian kita pilih untuk mengkomunikasikan sesuatu hal itu. Apabila kita memilih menjadi seseorang yang suka sembrono menyebarluaskan berita tak jelas atau tak benar atau tak bermanfaat, maka pilihan itu pula yang menjadi “investasi negatif” bagi diri kita. Yang akan kita tuai di suatu hari nanti.
Sedikit berandai-andai
Apabila kita memilih berperilaku jujur dan bisa dipercaya,
Apabila kita memilih untuk menyampaikan hal-hal secara benar dan tepat konteks,
Apabila kita memilih untuk meluangkan waktu memilih dan memilah konten informasi,
Apabila kita memilih belajar membedakan mana fakta dan mana opini,
Apabila kita memilih untuk menjadi benar, melebihi menjadi populer,
Apabila kita tidak mengukur self worth kita dari banyaknya likes, comments, ataupun tepuk tangan,
Apabila kita tidak mengukur peran seseorang di dunia dari banyaknya dia tampil di panggung dunia maya,
Apabila kita lebih mau meluangkan waktu untuk berpikir dan merenung sebelum berkicau atau memencet tombol share untuk menyebarluaskan sebuah pemikiran ataupun berita
Apabila kita tidak mudah menghakimi seseorang dari tampilannya semata,
Apabila kita lebih memilih banyak meneliti kekurangan dan kelemahan diri dibandingkan sibuk mencari-cari pada orang lain salah dan cela mereka,
Apabila kita memilih untuk lebih sering bertanya pada hati nurani dibandingkan bertanya pada search engine,
Apabila kita memilih untuk lebih sering meng-upgrade kemampuan daripada meng-upgrade penampilan,
Apabila kita lebih sering meng-update kepekaan personal dan sosial dibandingkan meng-update foto dan status di media sosial,
Apabila kita lebih meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dari hati ke hati dibandingkan broadcast di puluhan grup media sosial yang kita punya,
Apabila kita lebih punya waktu untuk tersenyum pada seorang anak daripada menebar fake smile untuk foto profil yang keren maksimal,
Apabila kita lebih punya waktu untuk memberi makan sebuah perut keroncongan dibandingkan mengungggah ratusan foto selfie makanan lezat di restoran,
Apabila kita lebih punya waktu untuk memeluk orang tercinta dan bertanya kabar daripada menghujaninya dengan pelukan dan ciuman emoticon dari gadget di genggaman,
Apabila kita lebih bersedia meluangkan waktu untuk percaya pada mata dan pendengaran kita sendiri dan bukannya selentingan-selentingan yang menjadi viral,
Apabila kita lebih bersedia menjadikan hati nurani sebagai hakim daripada ikut terseret virus latah dan menjadi corong berbagai kebohongan era digital.
Apabila kita memilih menjadi yang sedikit itu,
Kita bisa berharap banyak dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik...
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H