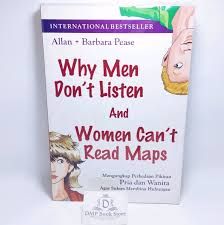"Aku tidak mengertimu. Tetapi aku memahamimu. Karena aku mencintaimu." (Nagabonar dalam film Nagabonar Jadi 2, 2008)
Di saat pandemi seperti saat ini, menonton film di bioskop rasanya seperti sebuah kemewahan. Aku pun hanya bisa mengenang masa-masa manis, saat bisa menonton film di bioskop tanpa khawatir dan tanpa ketakutan terjangkit virus korona seperti saat ini.
Memori manis itu membawa saya pada adegan menonton film sekuel Nagabonar (1987) berjudul Nagabonar Jadi 2 pada 2008, di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.
Nah, ada satu kalimat kuat yang nyantel betul di benak saya saat itu. Kalimat itu diucapkan Nagabonar (diperankan Deddy Mizwar) saat menasihati Bonaga, putera tunggalnya yang diperankan oleh Tora Sudiro.
"Aku tidak mengertimu. Tetapi aku memahamimu. Karena aku mencintaimu."
Kalimat dahsyat itu diucapkan Nagabonar saat ayah dan anak itu terlibat pertengkaran karena sang anak menganggap ayahnya yang mantan pejuang kemerdekaan itu tidak mengerti aspirasi dirinya sebagai pebisnis muda di era pasca-Revolusi Kemerdekaan 1945.
Saat itu aku tersentak di deret depan sebuah bioskop.
Mengerti berbeda dengan memahami?
Sebuah tafsiran baru yang menggugah, gumamku.

Nagabonar Jadi 2, film komedi situasi yang apik itu juga mengusung nilai nasionalisme dan religi yang, awalnya aku kira akan terlalu basi atau menggurui, digarap dengan ringan dan renyah dicerna dalam senyum dan tawa.
Terobatilah kekecewaan saat mengantre di loket tiket ketika hanya mendapat bangku kosong di deret terdepan, yang berarti harus membuat otot leher bekerja lebih keras menegakkan kepala agar kuat mendongak selama kurang lebih dua jam durasi film.
Sama seperti buku, hematku, film yang baik adalah yang dapat menginspirasi kita berbuat lebih baik atau mendapat pencerahan.
Ibarat makanan, ia bukan camilan (snack) yang sekadar habis tandas di piring dan berakhir di kolon atau usus besar kita. Tapi ia selayaknya gado-gado yang jejak rasanya (after-taste) tetap tertinggal di lidah. Ia selalu membuat kita ingin kembali mencicipi. Lagi dan lagi.
Aku tertarik menyelami logika Nagabonar, tokoh rekaan karya Asrul Sani yang konon terinspirasi dari kisah hidup Jenderal Mayor Timur Pane di Sumatra Utara semasa Revolusi Kemerdekaan 1945.
Sebagai sastrawan yang juga turut angkat senjata di era Revolusi Kemerdekaan, tentu almarhum Asrul Sani mafhum betul perihal suasana batin rakyat Indonesia saat itu dan pernak-pernik kehidupan revolusi.
Dengan dukungan akting Deddy Mizwar, aktor senior langganan peraih Piala Citra, Timur Pane, tokoh pejuang mantan pencopet yang membentuk laskar pejuang bernama Barisan Marsose (terdiri dari para pencopet dan pencoleng) itu terasa hidup kembali dan begitu nyata.
Mengerti dan memahami
Nah, "mengerti" tampaknya lebih dekat dengan mengetahui, yang mensyaratkan wawasan detail teknis atas suatu hal.
Sementara "memahami" lebih karib dengan nilai rasa atau empati atas sesuatu. Bisa jadi keduanya bersatu dalam diri seseorang. Bisa jadi keduanya terlerai. Toh, keduanya adalah dua hal yang berbeda.
Barangkali inilah yang dapat menjelaskan mengapa di era 2000-an sempat viral berita seorang janda tua beranak sebelas di sebuah desa di Jawa Tengah yang sanggup seorang diri membesarkan kesemua anaknya menjadi sarjana dan orang sukses.
Apa kuncinya?
"Saya cuma orang bodoh, tidak lulus SD. Yang saya tahu saya bertanggung jawab atas anak-anak saya," jawab polos sang janda tua di hadapan wartawan.
Dalam skala yang berbeda, aku baru memahami makna perlakuan ibuku bertahun-tahun lalu.
Sewaktu SD, sejak mulai diajari mengetik (dengan mesin tik manual) dan menulis oleh kakak sulungku di kelas 3, aku keranjingan menulis apa saja. Puisi, cerpen, artikel sampai komik aku buat dalam sebuah buku tebal pemberian salah seorang tetanggaku, Mas Pendi.
Tetanggaku itu juga yang berjasa mendongengiku tentang kisah-kisah pewayangan mulai dari Bharatayudha, Ramayana sampai Makuta Rama. Termasuk memasok buku-buku pewayangan yang dikumpulkannya dari serial pewayangan di harian Berita Yudha yang diklipingnya sendiri. Legenda perjuangan para kesatria wayang itulah yang kerap menjadi inspirasi tulisan-tulisanku saat itu.
Jika sudah bergairah menulis, kadang sejak sepulang sekolah sampai larut malam. Terlebih lagi jika liburan sekolah. Biasanya ibuku akan segera menarik buku dan pena dari tanganku, jika demikian.
"Udah, tidur sono!" ujarnya tegas.
Ibuku seorang yang periang dan humoris. Tapi ia tegas dan disiplin. Barangkali bawaan tomboy semasa remaja.
Ketika sudah menikah pun, ibu sering menggantikan ayah memanjat pohon nangka untuk mengambil buahnya untuk dijual, atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang cukup maskulin lainnya.
Dulu aku sering kesal jika ibu sudah menarik buku dan pena dari tanganku.
Dulu aku bilang,"Ibu nggak ngerti sih!"
Mungkin ia memang tidak tahu atau tidak mengerti. Sekolahnya hanya sampai kelas 5 Sekolah Rakyat (sebutan SD saat itu).
Tapi ia tentu memahami bahwa puteranya butuh istirahat. Mungkin ia tidak mengerti apa yang ditulis puteranya ini, tapi ia memahami betapa puteranya punya potensi.
Barangkali itulah yang membuat ibu memotivasiku untuk langsung mengikuti ujian kelulusan Madrasah Ibtidaiyyah (setara SD) sementara aku masih kelas 4 SD. Waktu itu kebijakan pemerintah Orde Baru memungkinkan hal tersebut.
Sebagaimana lazimnya anak Betawi di era 80-an, aku bersekolah ganda dalam waktu yang bersamaan. Pagi di SD Negeri, dan siang sampai sore di Madrasah Diniyah untuk belajar ilmu agama. Kami menyebutnya Sekolah Arab.
Selepas Maghrib, ada pengajian anak-anak yang dibimbing seorang ustaz di dekat rumah.
Selepas Isya, sebetulnya ada pelajaran tambahan bela diri silat Betawi dari sang ustaz.
Tapi aku lebih sering absen. Sebab biasanya selepas latihan silat, aku terlalu lelah dan langsung terkapar tidur.
Padahal aku suka sekali menonton film di TVRI (satu-satunya stasiun TV di Indonesia saat itu) yang saat itu hanya ditayangkan di ujung program, sekitar pukul 11 malam.
Hanya perempuan yang bisa memahami?
Ujian kelulusan yang diikuti murid kelas 6?
Aku setengah mati menolak dorongan ibu. Perasaan tidak mampu dan minder mendominasi diri.
Malah ibu yang justru yakin dengan kemampuanku.
Alhasil, mungkin juga karena doa kaum ibu yang konon makbul, aku berhasil lulus dengan nilai cukup baik.
Terima kasih, Ibu. Engkau ternyata lebih memahamiku lebih daripada aku memahami diriku sendiri.
Ah, mengerti dan memahami sungguh menarik ditelusuri.
Seperti logika Jenderal Nagabonar, sang janda tua yang luar biasa dan juga ibundaku yang telah tiada, bahwa "memahami "bersumber dari cinta dan tanggung jawab.
Tak perlulah bergelar doktor atau jumpalitan pencitraan turba atau blusukan untuk sekadar memahami derita rakyat yang terhimpit beban ganda krisis ekonomi dan krisis pandemi kesehatan saat ini.
Cukuplah pahami derita rakyat dari suara yang kadang hanya tersalurkan di media sosial, yang itu pun kerap kali dibungkam, entah dengan regulasi atau dengan sengatan para pendengung (buzzer) profesional.
Kita hanya perlu mendengar dengan tulus jerit lapar anak-anak malnutrisi, atau tulus berempati kepada keluarga-keluarga yang berantakan karena orangtua saling bercerai atau justru berbunuhan karena perkara ekonomi yang kian menjepit di tengah pandemi yang tak kunjung berakhir.
Seorang kawan bilang,"Hanya perempuan yang bisa memahami."
Sejenak aku tercenung.
Sebagaimana perkataan orang bijak,"Behind great men there are great women."
Di balik kebesaran seorang laki-laki selalu ada peran perempuan di belakangnya.
Ya, karena dorongan perempuan seperti ibu atau istri, seorang laki-laki dapat maju.
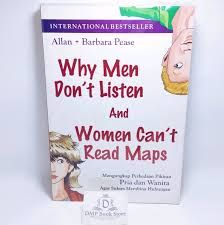
Inilah yang menjadikan perempuan memiliki intuisi yang lebih peka dan penginderaan yang lebih luas sehingga perempuan mampu membuat penilaian dengan begitu cepat dan tepat tentang orang-orang dan situasi mereka berdasarkan intuisi saja.
Lihatlah peran Khadijah yang menyokong perjuangan Rasulullah Muhammad SAW menyebarkan Islam dengan harta dan jiwanya di tengah tindasan kaum kafir Quraisy durjana dan dominan.
Meskipun akhirnya Khadijah harus berpulang lebih dahulu ke haribaan Allah sebelum melihat keberhasilan perjuangan suami tercintanya.
Demikian juga adanya semangat Fatmawati (sebelumnya bernama "Fatimah"), istri pertama Bung Karno, yang menjahit sang saka Merah Putih dengan tangannya sendiri untuk dikibarkan saat Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Meskipun akhirnya putri tokoh Muhammadiyah Bengkulu itu memilih meninggalkan Bung Karno karena menolak dimadu.
Tapi apakah hanya perempuan yang Tuhan karuniai kepekaan untuk memahami?
Sehingga jika terjadi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selalu lelaki saja yang dipersalahkan?
Dan dilabelkan pada keningnya stempel "egois"?
Memahami bukanlah masalah gender atau jenis kelamin

"....Mama sangat menghendaki anak perempuan tatkala saya masih di kandungan....Tidak heran bila Mama selalu membelikan saya pakaian berwarna lembut yang lebih pantas untuk anak perempuan. Sebenarnya saya ingin memberontak, tetapi khawatir Mama akan bertindak lebih nekat," ujar seorang lelaki malang dalam Lelaki Yang Menangis (Akar Media, 2007).
"Nggak tahu terima kasih ya kamu," Mama melotot saat saya menunjukkan wajah tak senang pada T-shirt merah muda yang diberikannya. "Harganya mahal, tahu? Kalau kamu nggak mau, Mama kasih baju yang gambarnya bunga-bunga."
Itulah salah satu kisah nyata seorang lelaki yang mengalami kekerasan secara psikologis oleh perempuan yang merupakan ibunya sendiri.
Kumpulan kisah nyata mengenai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap laki-laki yang disusun oleh Rini Nurul Badariah (penulis dan penerjemah yang berdomisili di Kota Bandung, Jawa Barat) ini mengurai fakta bahwa perempuan juga manusia. Ia punya potensi berbuat baik sehingga derajatnya terangkat mulia sekaligus berpotensi berbuat buruk hingga terpuruk setara dengan binatang.
Sistem patriarki, yang antitesisnya adalah emansipasi perempuan, mungkin menguntungkan kaum lelaki. Namun ada paradoks di dalamnya.
Persepsi bahwa kaum lelaki adalah makhluk yang superior menisbikan bahkan menihilkan realitas bahwa perempuan juga dapat berlaku sebagai penindas atau penganiaya baik secara fisik, mental atau psikologis.
Toh, perempuan juga manusia. To err is human, manusia itu tempatnya berbuat salah.
Sejatinya, "memahami" bukanlah masalah gender dan juga bukan dominasi gender tertentu. Ia adalah masalah kemanusiaan dan peradaban.
Siapa pun makhluk yang manusiawi dan beradab, ia punya cinta dan tanggung jawab.
Laksana besarnya cinta Jenderal Nagabonar kepada Bonaga yang diasuhnya seorang diri selepas kematian Kirana, sang istri tercinta.
Laksana dalamnya rasa tanggung jawab seorang janda tua di Jateng dalam membesarkan kesebelas anaknya tanpa peduli istilah patriarki atau emansipasi.
Ah, andai saja para jenderal yang berebut kuasa di panggung politik negeri ini menghayati logika "memahami" ala Jenderal Nagabonar, yang notabene senior mereka, tentu indahlah hidup ini.
Sebab, apa kata dunia jika berhasrat membina tapi tak bisa tulus memahami rakyatnya?
Jakarta, jelang Ramadhan
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H