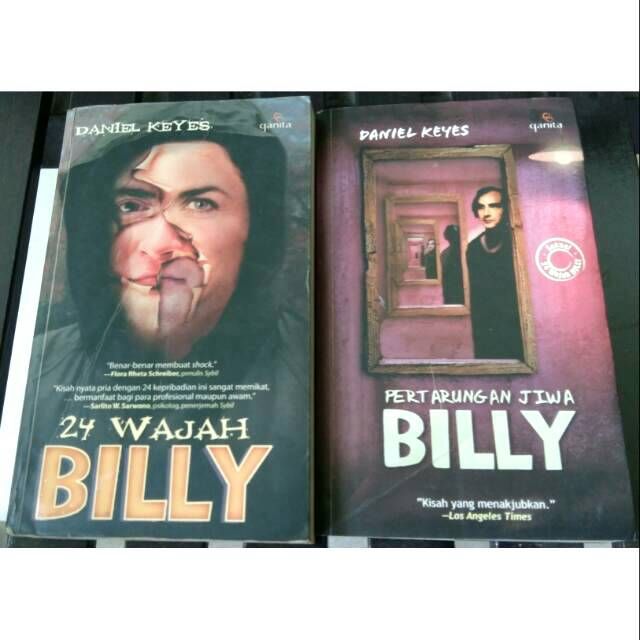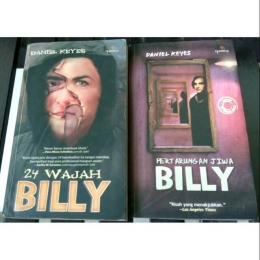Persis seperti pepatah, life is stranger than fiction, kehidupan nyata lebih aneh dari cerita fiksi, demikianlah yang tergambar dalam novel ini. Betapa kehidupan Billy yang demikian dramatis dan filmis cocok sekali diangkat ke layar lebar (sekaligus disunting) oleh tokoh utamanya sendiri dengan judul The Crowded Room yang disutradarai oleh Joel Schumacher dan dibintangi oleh aktor Leonardo Di Caprio pada 2015.
Kelemahan novel ini, jika boleh dikatakan demikian, adalah gaya penerjemahan yang kaku bahkan terkesan letterlijk (terlalu harfiah) serta kurang cermat dengan data yang berpengaruh memperlambat lajunya mesin cerita.
Di samping itu, novel ini cenderung terlalu bergaya ala Jakarta (baca: cair) seperti kata-kata tauk atau ga yang ditaruh dalam tuturan narasi, yang kurang dapat dibenarkan dari segi EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) atau yang sekarang dikenal sebagai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
Kalaupun diniatkan sebagai sebuah hal yang sah dalam sastra, karena novel adalah sebuah karya sastra, yang menjunjung kreativitas, gaya cuek tersebut mengurangi keanggunan bangunan cerita yang kokoh atau seperti pengganjal laju tuturan. Kecuali, jika ditempatkan dalam dialog, yang tentunya sesuai konteks, misalnya dalam percakapan yang dilakukan Billy, dalam pribadi Allen, yang berbisnis narkoba atau sumpah-serapah Ragen atau Tommy yang berwatak keras dan antisosial.
Untungnya semua celah tersebut tertutupi dengan materi cerita yang dahsyat. Tetapi tentu novel ini akan lebih nikmat dibaca jika penerjemahannya lebih akurat dan cermat.
Di samping itu, dalam membaca novel ini, kita dipaksa memamah sederet fakta dan hasil riset ilmiah yang, bagi kalangan selain kedokteran dan pskiatri, agak lelah mencernanya.
Namun, mungkin demikianlah konsekuensi novel yang berdasarkan kisah nyata. Ia dituntut harus tetap fasih bercerita seraya anggun berkompromi dengan tuntutan pasar serta industri yang menuntut standar mainstream novel fiksi.
Yakni, antara lain, dialog yang terarah, klimaks, ketegangan dan antiklimaks, yang dicapai dengan salah satu bentuk kompromi yang diakui penulis sendiri yakni dengan menciptakan dramatisasi-dramatisasi atas dasar "kebebasan penyair" (hal. 16), tidak dengan tujuan menambah seru cerita karena bahan bakunya sendiri sudah sangat mendukung. Tetapi agar lebih masuk dalam logika masyarakat yang terbiasa dengan kaidah bacaan fiksi konvensional.
Akhir cerita novel yang menggantung mungkin terasa kurang greget atau kurang bersantan dalam selera konvensional yang terbiasa dengan akhir cerita yang umumnya tuntas (happy ending atau sad ending).
Namun, memang harus demikian, karena selain tokoh utama masih hidup dan berkutat dengan dunianya yang baru setelah menjadi pribadi yang utuh, tema tentang mengenal diri memang takkan pernah berakhir, tiada titik, hanya koma.
Nah, inilah yang membuat novel baheula ini tetap asyik dinikmati dan tidak basi, karena nilai-nilai yang ada di dalamnya adalah nilai universal yang langgeng adanya dalam peradaban manusia.