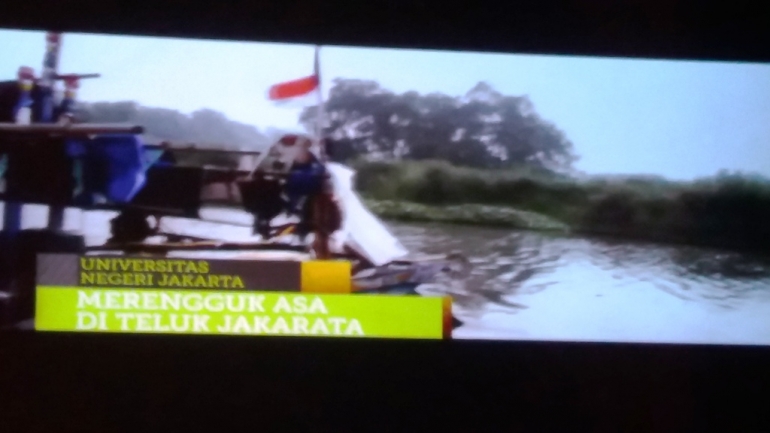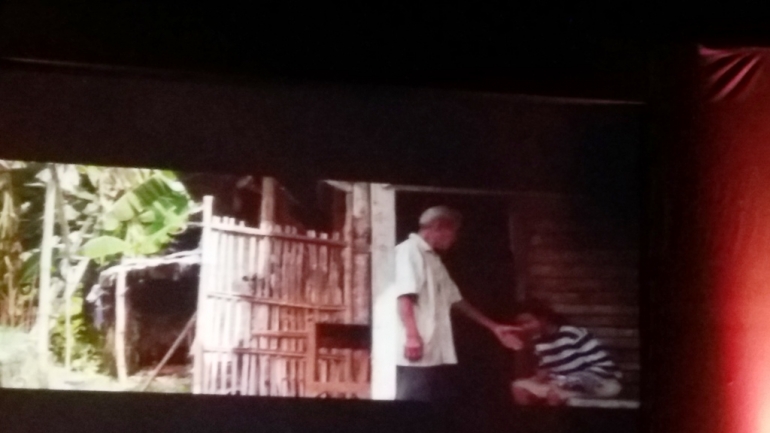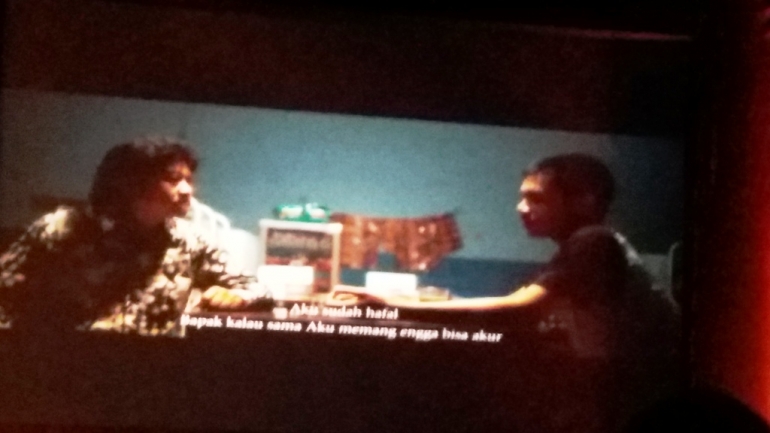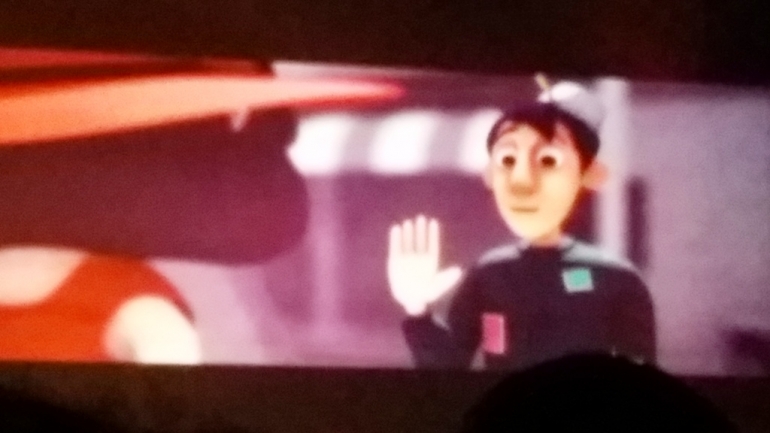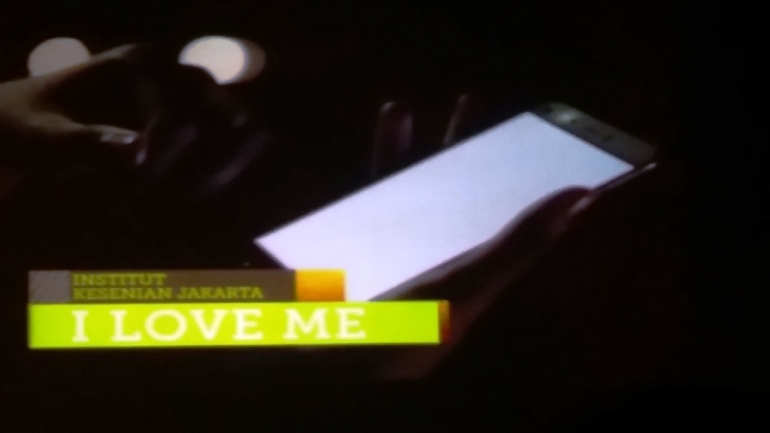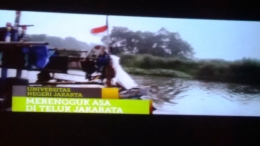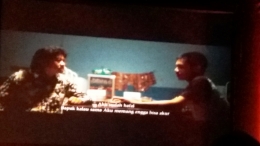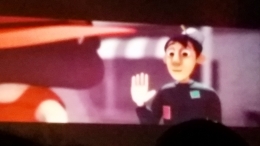Jikalau seseorang ditanya cara menanamkan nilai humanisme, jawaban yang akan keluar umumnya tak akan jauh dari seputar topik pengasuhan keluarga, pendidikan sekolah, dan kegiatan keagamaan. Jawaban yang tak salah namun juga tak sepenuhnya tepat. Nilai-nilai humanisme atau kemanusiaan memang bukan isu yang ringan maupun menyenangkan. Tapi bukan berarti tema humanisme tak bisa dikemas dalam bentuk yang lebih unik dan menarik kan?
Saya masih ingat betul nilai humanisme dalam dua buah film asing yang menjadi tugas mata kuliah ‘Seni Apresiasi Film’ saat kuliah S1 dulu. Sama-sama diadaptasi dari novel sejarah berlatar perang di dua negara yang berbeda, film The Kite Runner di Afghanistan dan The Boy in the Striped Pyjamas di Jerman saat Perang Dunia tahun 1945 mampu mengaduk-aduk emosi para penonton dengan meninggalkan pesan kemanusiaan yang mendalam untuk selalu diingat. Bisa jadi, kesan kuat itu belum tentu dapat terekam jika seseorang hanya membaca buku novelnya. Bagaimana tidak? Bukan hanya para mahasiswi yang menangis saat menonton keduanya, bola mata para mahasiswa pun tampak berkaca-kaca selama pemutaran film berlangsung. Kedua film drama tersebut menyampaikan pesan humanisme yaitu pentingnya bertindak jujur (sekalipun menyakitkan) dan persahabatan universal (tanpa memandang SARA).
Para dosen pengajar mata kuliah tersebut juga menyampaikan bahwa “tema mayoritas film yang diproduksi di suatu negara biasanya menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat di negara tersebut.” Wajarlah saat negara - yang kini dikomandoi Donald J. Trump - Amerika Serikat berulangkali memproduksi film superhero dan animasi yang kental nuansa kecanggihan efek teknologi visualnya. Memang di negara adidaya itulah, banyak perusahaan raksasa teknologi kelas dunia berpusat. Ya, media audio dan visual berupa film memangsangat tepat untuk mengajarkan dan menyebarluaskan nilai humanisme kepada khalayak dan masyarakat luas tanpa harus berkesan menggurui.
Malam Final FFPI 2016 Kompas TV di Bentara Budaya Jakarta, Jum'at 20 Januari 2017 (Dokpri)
Lalu, bagaimana dengan di Indonesia? Sejalan dengan pendapat para dosen film, Mbak Rosiana ‘Oci’ Silalahi selaku perwakilan dari Kompas TV saat membuka acara malam final
Festival Film Pendek Indonesia (FFPI) 2016 di Bentara Budaya Jakarta (Jum’at, 20 Januari 2017) turut menuturkan bahwa “
film adalah cerminan suatu bangsa sehingga harus terus dipublikasikan secara berkesinambungan.” Maka itulah, konsistensi Kompas TV dalam menggelar kompetisi FFPI untuk kategori pelajar dan mahasiswa sejak tahun 2014 lalu patut diapresiasi oleh segenap rakyat Indonesia.
FFPI 2016 atau kali yang ketiga ini mengusung tema “Humanisme.” Tahun 2016, rangkaian kegiatan FPPI Kompas TV dimulai dari workshop penyusunan ide cerita film (12 Mei – 28 Oktober 2016) untuk pelajar dan mahasiswa di 10 kota di Indonesia yaitu Jakarta, Tangerang, Palembang, Medan, Lampung, Banjarmasin, Gorontalo, Denpasar, Yogya, dan Pekalongan. Pengisi workshop yaitu dosen dari Fakultas Film dan Televisi Universitas Multimedia Nusantara (UMN).
Adapun jumlah yang terdaftar sebagai peserta FFPI 2016 yaitu sebanyak 276 film sehingga akhirnya terpilih 10 finalis – lima finalis dari kategori pelajar maupun mahasiswa – yang pemutarannya di malam final FFPI 2016 Jum’at minggu lalu dapat disaksikan oleh para pihak media dan 20 orang Kompasianer terpilih. Dipandu oleh pembawa acara (MC), Mbak Dita, acara final FFPI 2016 dimulai pada pukul 17.30 WIB. Inilah review dari kesepuluh film finalis FFPI 2016 Kompas TV tersebut.
Rosiana Silalahi memberikan sambutan dari Kompas TV (Dokpri)
Toleransi (Masih) Ada di Sini Nilai humanisme berupa ‘toleransi dalam suasana keberagaman’ tak pelak memang menjadi trending topic terhangat di Indonesia sejak pertengahan tahun 2016 lalu. Fenomena sosial tersebut mampu dipotret dengan apik dan menarik oleh dua film finalis FFPI 2016. Ide mereka tentang toleransi cukup sederhana namun tepat mengena dalam kehidupan sehari-hari.
Film “2 Hari”karya SMA 1 Negeri Muara Enim-Palembang mengisahkan tentang murid pindahan dari Jakarta bernama Bela (Aling) setelah dua hari bersekolah di daerah. Di sekolah barunya, Bela – seorang non-muslim dan Tionghoa – sekelas dengan mayoritas murid Melayu muslim dan juga berjilbab. Sebelum pindah ke daerah, beberapa teman lama Bela di Jakarta menakuti-nakuti dirinya tentang diskriminasi yang mungkin akan diterimanya kelak sebagai minoritas. Bela sempat ketakutan dan malas-malasan pada hari pertama di sekolah barunya.
Kenyataannya? Bela mendapati langsung adanya ‘kantin kejujuran’ di sana yang sudah berlangsung lama. Bukan itu saja. Bela juga melihat sendiri, pihak sekolah memberlakukan semua murid dengan adil tanpa memandang status sosial ekonominya. Di akhir film, Bela pun bisa menyimpulkan bahwa “jikalau 1 pohon rusak, belum tentu 1 hutan lantas menjadi rusak.”
Toleransi menjadi nilai humanisme yang disampaikan film
Tema humanisme tentang toleransi juga ditampilkan oleh film
“Terminal” karya SMK Negeri 2 Kuripan-Nusa Tenggara Barat. Berlokasi di terminal bus yang identik dengan suasana keras dan kejahatan – sebut saja mulai dari copet, jambret, calo – seorang pria muda yang menjadi penumpang bus disadarkan bahwa hati yang suci
tetap ada di terminal. Seorang remaja sekaligus tukang asongan yang dikasari olehnya sehingga menumpahkan semua makan siangnya – dengan jumlah dan menu seadanya - tetap berlaku baik saat pemuda tersebut hampir saja kehilangan tasnya. Padahal kesempatan untuk membalas dendam sangat terbuka lebar.
Terminal juga masih banyak memiliki orang berjiwa humanis di dalamnya (Dokpri)
Menurut keterangan guru pembimbing dari SMKN 2 Kuripan-NTB, film
“Terminal” dimaksudkan untuk memvisualkan nilai humanis dari kehidupan terminal. Film itu juga aslinya bertempat di Terminal Mandalika NTB dengan sebagian besar pemerannya murid kelas 2 SMK.
Kepedulian Sosial (Bukan) Hanya via Media Sosial
Inilah tema humanisme lainnya yang belakangan ini juga menjadi tren kekinian. Para pengguna media sosial (sepertinya) memang cenderung lebih aktif di dunia maya untuk urusan kepedulian sosial daripada melakukannya langsung di kehidupan nyata. Apa ini karena meng-klik jempol tanda like, posting dan share info, serta mengunggah multimedia – foto dan video – di media sosial jauh lebih mudah dibandingkan dengan beramal secara riil (donasi uang, waktu, dan tenaga) ya? *self-correction
Ada dua film kategori mahasiswa yang memotret fenomena humanisme melalui media sosial saat ini. Film “I Love Me” karya Institut Kesenian Jakarta mengisahkan seorang mahasiswi yang kesehariannya tak lepas dari meng-update info dan foto terbaru via media sosialnya dari mulai bangun tidur hingga malam hari. Setelah menemui pengamen cilik jalanan, barulah hati nuraninya tersentuh. Tentu saja, momen itu harus tetap disebarkan via salah satu akun media sosialnya. Namun, mahasiswi itu malah mendapatkan arti sejati kepedulian sosial secara nyata dari seorang penjual nasi goreng keliling yang berbaik hati meminjamkannya power bank.
Kepedulian sosial memang sejatinya (tak) hanya via media sosial (Dokpri)
Film
“Di Ujung Jari” karya Universitas Bina Nusantara (Binus) juga menyajikan fenomena humanisme antara dunia maya dan nyata. Seorang mahasiswa yang hidup sebagai anak kost dikisahkan tak bisa berpisah dari
smartphone miliknya sehingga tak peka dengan lingkungan sekitarnya, dari di kamar kost, kampus, sampai saat makan bareng di restoran. Bahkan untuk urusan keluarga, mahasiswa tersebut malah menomorduakannya. Setelah
smartphone miliknya dijambret di malam hari dan dirinya ditolong oleh seorang pengemis jalanan – yang selama ini tak pernah dipedulikannya meskipun sering melewatinya – barulah mahasiswa tersebut menyadari bahwa
kepedulian sosial itu bukan melulu sebatas posting di media sosial.
Masih berlokasi di Jakarta, namun kali ini tak lagi berhubungan dengan media sosial, tema humanisme berupa kepedulian sosial ditunjukkan oleh film
“Merengguk Asa di Teluk Jakarta” karya Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Film dokumenter pendek tersebut berfokus pada kehidupan
‘Manusia Perahu’ di Teluk Jakarta yang jauh dari layak. Pak Bunila, seorang nelayan di sana, mengakui dalam sehari adakalanya tidak memperoleh penghasilan. Putranya, Hafiz (11 tahun) sudah putus sekolah karena tidak ada akses ke sekolah. Para manusia perahu itu juga mayoritas pendatang sedangkan syarat untuk bisa tinggal di rumah susun yaitu harus memiliki KTP Jakarta. Mau tak mau, mereka harus tinggal di perahu sebagai satu-satunya tempat tinggal yang tersedia sekaligus alat mencari nafkah. Para manusia perahu tersebut
hanya berharap agar pemerintah bisa lebih memperhatikan kesejahteraan mereka dan menjaga kebersihan air laut.
Di balik gemerlapnya Jakarta, ada manusia perahu di Teluk Jakarta yang memerlukan pemberdayaan kesejahteraan (Dokpri)
Setelah tiga film sebelumnya berlokasi di Jakarta, film
“Kihung (Jalan Menikung)”karya SMK Negeri 5 – Bandar Lampung bercerita tentang kepedulian sosial yang bisa diwujudkan pada bidang pendidikan berupa
akses transportasi berwujud jalan dan jembatan. Para penduduk desa Kihung mengalami kesulitan setiap kali anak mereka akan pergi sekolah karena
satu-satunya jembatan bambu – dulu dibangun secara swadaya oleh masyarakat desa - yang menghubungkan sungai dengan lokasi SDN Inpres terdekat, rusak dan patah. Jadilah para siswa SD dari desa Kihung harus menempuh jalan becek bertanah liat yang curam dan menyusuri bebatuan licin pada aliran sungai yang deras setiap pagi selama satu jam. Setelah menonton film yang disutradarai oleh M. Erwin itu, bagi murid sekolah di kota, kemacetan jalanan jelas bukan alasan untuk bermalas-malasan. Murid dari desa Kihung sudah membuktikan dengan melewati jalan menikung yang tentunya sangat layak untuk segera menjadi prioritas pembangunan daerah.
Para siswa Desa Kihung Lampung tetap bersemangat ke sekolah sekalipun harus melintasi sungai deras (Dokpri)
Cinta (Seharusnya) Memang Tak Bersyarat Bicara cinta memang tiada habisnya. Begitu pula saat menyangkut tema humanisme, cinta jelas kesatuan yang tak terpisahkan. Kisah cinta pun tak melulu tentang hubungan asmara dua sejoli, namun juga lebih luas makna dan lingkupnya. Misalnya cinta tulus pada keluarga, baik keluarga karena hubungan darah, pernikahan, atau bahkan keluarga angkat.
Film
“Izinkan Saya Menikahinya” karya SMA Rembang-Purbalingga dan
“Different” karya Universitas Bina Nusantara sama-sama mengangkat kisah cinta antara seorang pria wanita yang mengalami tantangan karena hadirnya perbedaan. Bagi pasangan Suryati dan Suryono (berprofesi sebagai militer) - dalam
“Izinkan Saya Menikahinya” yang semakin menarik karena disajikan dalam bahasa lokal daerah Tegal, Brebes, Banyumas, dan sekitarnya yaitu
ngapak – cinta yang dijalin sejak SMA, peresmiannya yang sudah di depan mata harus menghadapi hambatan yang di luar kemampuan mereka selama ini. Adapun bagi seorang wanita kaya dan pria sederhana, – dalam
“Different”– mereka berdua saling terus mencoba untuk menembus lebarnya jurang pemisah di antara mereka berdua.
Uniknya, kedua kisah cinta tersebut berakhir dengan ending yang kontras. Penasaran dengan akhir kisah mereka berempat? Silakan Kompasianer saksikan langsung di Kompas TV nanti ya hehehehe……
Kemiskinan tak lantas membuat cinta seorang ayah berkurang kepada anak angkatnya (Dokpri)
Selain cinta antara lawan jenis, film
“Mata Hati Djoyokardi” karya SMA Khadijah Surabaya dan
“Omah”karya Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta satu ide dalam mengangkat tema cinta dalam keluarga, terutama
cinta tiada batas dari seorang ayah kepada buah hatinya. Bedanya, Pak Djoyokardi (61 tahun) adalah ayah angkat dari seorang anak perempuan dengan keterbelakangan mental, Indah (12 tahun). Lebih mengharukannya lagi, Pak Djoyokardi sendiri hidup dalam keterbatasan ekonomi namun hal itu tak menyurutkan sikap mulianya dalam membesarkan Indah seorang diri. Sementara itu, hubungan ‘benci tapi rindu’ antara seorang ayah dan putra kandungnya dalam
“Omah” menyadarkan penonton bahwa kebersamaan dalam keluarga itu memang harus rutin dilakukan sekalipun terpisah jarak dan waktu. Jika sampai terlalu lama dilewatkan, maka siapa yang tahu umur dari anggota keluarga.
Kisah 'benci tapi rindu' antara seorang ayah dan putranya dalam film 'Omah' (Dokpri)
Dan para pemenang FFPI 2016 adalah….. Tahun 2015 lalu, saya juga berkesempatan menyaksikan malam final FFPI 2015 yang bertemakan “Indonesiaku, Kebanggaanku.” Menurut saya, setelah dua kali menghadiri malam final FFPI dari Kompas TV, film pendek yang diproduksi pelajar (junior) dan mahasiswa (senior) sama-sama mampu menyajikan kombinasi ide dan tampilan visual yang memikat, meyakinkan, serta memukau para penontonnya. Andaikan tidak diberitahukan sebelumnya, para penonton pasti akan kesulitan untuk menentukan dengan tepat, manakah film yang diproduksi pelajar dan manakah film hasil mahasiswa.
Film 'Different' menjadi satu-satunya film animasi dalam final FFPI 2016 (Dokpri)
Sedikit perbedaannya – di luar unsur tema lomba – yaitu adanya sebuah film animasi berjudul
“Different” pada FFPI 2016. Di tahun 2015 lalu, tidak ada film animasi yang menjadi finalis FFPI 2015. Menurut
Makbul Mubarak, selaku salah seorang dewan juri, kriteria
penentuan kesepuluh finalis FFPI 2016 ini adalah
“bagaimana sebuah film pendek dapat menafsirkan humanisme secara original dan rasanya menjadi manusia yang sesungguhnya serta menawarkan perspektif segar tentang humanisme atau kemanusiaan”. Bagi saya pribadi, siapa sangka, konflik sosial-politik pada tahun 1965 di Indonesia dapat diramu menjadi sebuah tema humanisme tentang cinta yang mengharu-biru.
Sama seperti FFPI 2015, FFPI 2016 ini juga tidak sebatas penilaian secara teknis pembuatan film. Tak heran, selain satu finalis berupa film animasi, ada pula tiga film dokumenter pendek yaitu“Kihung (Jalan Menikung)” , “Merengguk Asa di Teluk Jakarta”, dan “Mata Hati Djoyokardi”. Dewan juri lainnya, Ifa Isfansyah menambahkan, “penilaian film tidak hanya secara teknisnya. Tapi, lebih ke gagasan film yaitu film tematik tentang humanisme yang saling mengisi dengan unsur teknis film.” Sebab itu pula, film di FFPI 2016 tidak dikotak-kotakkan menjadi film fiksi, animasi, ataupun dokumenter. Inilah keenam finalis juara FFPI 2016:
Ifa Isfansyah selaku salah seorang dewan juri menyampaikan kriteria penilaian FFPI 2016 (Dokpri)
Kategori MahasiswaJuara 1 : I Love Me (IKJ)
Juara 2 : Different (Binus)
Juara 3 : Merengguk Asa di Teluk Jakarta (UNJ)
Kategori Pelajar
Juara 1 : Izinkan Saya Menikahinya (SMA Rembang Purbalingga)
Juara 2 : Mata Hati Djoyokardi (SMA Khadijah Surabaya)
Juara 3 : Terminal (SMK Negeri 2 Kuripan NTB)
Inilah para sineas muda juara FFPI Kompas TV 2016 (Dokpri)
Peluang terjaringnya bibit-bibit unggul sineas muda yang unggul dari seluruh daerah di Indonesia tentu saja sangat potensial diawali dari ajang FFPI ini. Indonesia yang heterogen secara geografis (wilayah) dan demografi (masyarakat) dapat menghasilkan ide film yang luar biasa beragam dari aspek kuantitas maupun kualitas. Mbak Oci pun lantas berpesan kepada para 10 finalis FFPI 2016 agar “
selalu mengharumkan nama Indonesia sebagai sineas, baik di kancah nasional hingga internasional.”
Bagi yang tidak menghadiri acara final FFPI 2016 lalu, KompasTV akan segera menayangkannya dalam waktu dekat. Cek terus ya perkembangannya. Selamat untuk seluruh finalis dan pemenang FFPI 2016. Salam sinema Indonesia juara.
Tunggu segera penayangan film FFPI 2016 di Kompas TV ya (Dokpri)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
Lihat Inovasi Selengkapnya