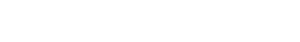Dalam debat ke-4 cawapres, Minggu 21 Januari 2024 muncul istilah greenflation. Cawapres Prabowo, Gibran Rakabuming yang melontarkan istilah ini.
Greenflation/Green inflation atau inflasi hijau berhubungan dengan kenaikan harga-harga produk ramah lingkungan akibat kenaikan harga-harga bahan baku. Faktor lain adalah kenaikan biaya dari berbagai aspek transisi energi itu sendiri.
Transisi yang Kompleks.
Transisi energi bukan hanya menyangkut perubahan jenis energi, seperti perubahan dari energi fosil, ke energi baru dan terbarukan (EBT). Dari batubara dan minyak bumi, ke energi surya, tenaga hidro, biofuel yakni bioetanol, biosolar atau pembangkit geothermal.
Perubahan jenis energi mengharuskan transisi sistem sosio teknis yang menjadi fondasi produksi dan konsumsi energi.
Aspek sosio teknis mencakup (1) regulasi dan rezim pengaturan energi; (2) dukungan politis (3) mekanisme pasar efisien yang menjamin pasokan dan permintaan; (4) Teknologi energi fosil ke teknologi energi terbarukan.; (5) budaya konsumsi dan norma kolektif yang membentuk pilihan jenis energi yang digunakan
Pada aspek regulasi, transisi berhubungan dengan sistem insentif yang mendorong produksi dan konsumsi energi tertentu. Sampai sekarang, UU EBT belum disahkan oleh DPR. Lambannya penetapan mengindikasikan rendahnya dukungan politis terhadap pertumbuhan EBT.
Patut diduga bahwa lobi kelompok kepentingan energi fosil menghambat penetapan UU EBT. Ada kebutuhan untuk mempertahankan subsidi batubara dan pengembalian keuntungan dari 'sunk investment'. Investasi triliunan telah dibenamkan di sektor fosil terutama pembangkit listrik berbasis barubara.
Dalam sektor teknologi, transisi berkaiatan dengan perubahan atau penyesuaian teknologi yang berbasis fosil ke teknolgi EBT.
Perubahan teknologi terjadi pada sisi produksi dan konsumsi. Penutupan pembangkit batubara perlu diganti dengan pembangkit hidro berbasis waduk, mikro hidro atau pembangki geothermal
Pada sisi pasar, mekanisme pasar perlu diperkuat untuk menjamin permintaan. Tidak ada produsen energi independen yang mau menghasilkan listrik tenaga surya atau panas bumi, jika tidak ada permintaan. Aturan mengenai harga mempengaruhi kemauan investor untuk membangun pembangkit energi terbarukan.
Sebelum tahun 2022, pemerintah dikritik karena menetapkan harga EBT per Kwh hanya sebesar 80 % dari biaya pokok produksi setempat.
Merespon kritik ini, pemerintah mengubah kebijakan harga melalui Perpres 112/2022. Dalam aturan ini harga merupakan hasil negosiasi antara produsen dan PLN.
Aspek budaya dan norma ikut menentukan transisi. Greenisme, yakni norma tentang perilaku hijau belum menjadi bagian dari kultur dan perilaku masyarakat Indonesia.
Transisi menjadi lebih mudah kalau EBT telah menjadi bagian dari norma dan perilaku sosial. Ini tercermin dari preferensi masyarakat terhadap energi terbarukan.
Cerminan dari prefensi ini adalah kebanggaan menggunakan energi terbarukan. Ketika seorang anak muda mengatakan bahwa 'yang gaul itu yang terbarukan' maka bisa dikatakan EBT menjadi bagian dari identitas dan gaya hidup orang muda.
Greenflation
Transisi berkaitan dengan perubahan di sektor energi dan perubahan keseluruhan mode produksi. Perubahan membutuhkan biaya. Dampaknya investasi hijau dapat mendorong kenaikan harga-harga secara keseluruhan.
Pada sektor energi, greenflation berhubungan dengan (1) biaya perubahan teknologi pembangkit; (2) skala ekonomis pembangkit; (3) biaya oportunitas dan (4) biaya penyesuaian pada sisi permintaan; (5) perubahan mode produksi di sektor yang menerapkan prinsip pembangunan hijau.
Pada aspek teknologi pembangkit, transisi dari pembangkit fosil ke EBT meninggalkan pertanyaan tentang siapa dan berapa kerugian investasi yang telah dibenamkan di sektor pembangkit fosil. Ambisi 'zero emmision', misalnya, menuntut penutupan seluruh pembangkit batubara.
Pertanyaannya adalah siapa, dari mana dan berapa pengganti kerugian investasi yang telah dibenamkan untuk membangun pembangkit itu. Jumlah dana tidak sedikit dibutuhkan dan karena itu 'coal phase out' bukan proses yang murah.
Skala ekonomis beberapa pembangkit EBT jauh lebih rendah dibanding pembangkit fosil. Skala ekon0mis berhubungan seberapa besar pertambahan produksi sebagai dampak investasi untuk penambahan satu satuan input. Semakin sedikit ongkos investasi dan input, semakin makin besar jumlah produksi dan keuntungan, semakin ekonomis sebuah investasi.
Dalam pembangkit EBT, seberapa besar energi yang dihasilkan dan keuntungan yang diperoleh sebagai dampak dari setiap penambahan unit atau jumlah pembangkit.
Kalkulasi Ismail Nur Hidayat (https://id.quora.com) menyimpulkan bahwa untuk membangun pembangkit batubara 100 MW, dibutuhkan lahan seluas 125.000 m2 lahan. Sedangkan untuk pembangkit surya membutuhkan ruang lahan atau atap sebesar 200.000 meter persegi.
Jika dalam bentuk lahan, pembangkit surya berskala besar di perkotaan akan jauh lebih mahal karena harga lahan sangat tinggi. Pembangunan pembangkit skala besar di luar Jawa lebih murah karena biaya lahan murah. Masalahnya adalah tingkat permintaan rendah karena jumlah penduduk sedikit.
Selain itu, energi surya dan juga juga angin yang intermiten (tidak stabil) sepanjang hari karena bergantung pada perubahan sinar matahari dan kecepatan angin. Untuk bisa stabil, dua energi ini membutuhkan pembangunan teknologi penyimpanan, dalam bentuk baterai, yang membuat total investasi menjadi jauh lebih mahal
Produksi energi terbarukan memiliki biaya oportunitas yang besar. Ini adalah hilangnya kesempatan untuk memproduksi barang lain demi menghasilkan energi terbarukan.
Dengan kata lain, hal yang dikorbankan demi memproduksi energi terbarukan. Upaya menghasilkan bioetanol berbasis jagung, harus menghilangkan kesempatan untuk menggunakan jagung sebagai bahan pangan.
Untuk menghasilkan biosolar dari CPO, kita harus mengorbankan kesempatan memanfaatkan minyak sawit sebagai bahan minyak goreng.
Untuk membuka lahan sawit kita kehilangan kesempatan untuk mempertahakan hutan yang memproduksi oksigen, biodiversitas dan obat-obatan berbasis tumbuhan. Penggunaan bahan pangan sebagai sumber energi juga dapat menciptakan kelangkaan yang mendorong inflasi.
Pada sisi permintaan, penyesuaian jenis teknologi, misalnya modifikasi mesin juga ikut menaikkan biaya transisi ke energi hijau. Jika seluruh mode produksi industri berbasis energi fosil diganti dengan energi terbarukan, biaya penyesuaian juga tidak sedikit.
Akibatnya seluruh proses 'hijaunisasi, dengan tujuan 'dekabornisasi' menyebabkan naiknya harga-harga. Kenaikan harga-harga pada sisi produksi energi akan diterjemahkan ke dalam kenaikan harga-harga di sisi permintaan. Harga Sembako yang diproduksi dengan energi hijau juga akan ikut mengalami kenaikan.
Riset dan pengembangan juga tidak murah. Hal ini menjelaskan mengapa banyak riset hanya berhenti di level 'niche' (ceruk) teknologi seperti pusat-pusat penelitian.
Pengembangan teknologi energi ombak dan arus laut belum mampu mencapai tahap produksi masal dan komersialisasi. Sebabnya adalah untuk menciptakan teknologi yang murah dan mudah dioperasikan, butuh duit banyak dan waktu yang panjang.
Keadilan dekarbonisasi?
Siapa yang harus menanggung ongkos 'hijaunisasi' atau dekarbonisasi? Jawaban atas pertanyaan ini berkaitan dengan keadilan transisi energi.
Berbagai lembaga internasional telah merumuskan prinsip-prinsip transisi yang adil. Keadilan lingkungan adalah salah satu prinsip itu. Peningkatan produksi dan konsumsi biosolar tidak boleh menghabiskan hutan tropis demi perluasan kebun kepala sawit.
Prinsip lain adalah keadilan antar kelompok sosial. Penutupan pembangkit batu bara meniadakan lapangan kerja ratusan ribu orang yang bergantung pada sektor ini. Ada beberapa pertanyaan tentang keadilan.
Ke mana para pekerja pembangkit, penambang, pengangkut, tenaga ahli, pemasok, pedagang perantara. Bagaimana nasib mereka. Kompensasi apa yang mereka terima.
Sektor ekonomi mana yang harus dikembangkan untuk menyerap mereka. Perluasan kebun kelapa sawit memiliki sisi keadilan. Bagaimana hidup dan kesejahteraan komunitas-komunitas yang bergantung pada hutan.
Selain itu, transisi tidak boleh melanggar hak asasi. Pembangunan pembangkit surya, geothermal tidak boleh melanggar hak atas tanah dan hutan. Sebuah sistem kompensasi adil harus diterapkan dalam proses pembangunan berbagai pembangkit energi terbarukan.
Misalnya, warga tidak bisa digusur begitu saja dari lahan demi pembangunan pembangkit surya. Jumlah ganti rugi harus cukup untuk mengembangkan sumber pendapatan di sektor lain.
Aspek penting lain adalah keadilan akses energi. Transisi harus tetap menjamin akses warga ke energi yang terjangkau dan dapat diandalkan. Selama ini pembangkit batu bara telah menjadi tulang punggung penyediaan energi murah bagi penduduk kota. Jika pembangkit fosil ini ditutup, perlu ada pengganti yang dapat menjamin akses ke energi. Tenaga Hidro berbasis waduk dan panas bumi adalah dua pengganti yang dapat diandalkan.
Jika gagal menyediakan pengganti, akses ke energi mungkin akan kembali ke tahun 2000-an saat kota-kota besar mati listrik, sedangkan kampung-kampung terisolasi masih gelap gulita. Beberapa sudah mengalami kabel masuk desa, tetapi listrik belum masuk. Atau listrik mati melebihi minum obat yang hanya 3 kali sehari.
Penutup
Transisi energi memang tidak mudah, tetapi bisa dilakukan dan harus dilakukan. Ambisi transisi sebaiknya dilakukan bertahap, tidak tergesa-gesa, misalnya demi memenuhi 'kehendak' masyarakat global.
Aspek-aspek penting seperti biaya, stabililitas pasokan energi, akses yang adil, kompensasi kerugian perlu mendapat perhatian.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya