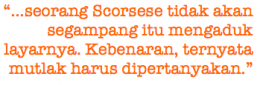Seperti mengalami déjà vu, film Martin Scorsese Shutter Island mengingatkan saya pada teori puncak gunung es psikoanalisis Freud. Mohon maaf, pembaca, menurut teori ini anda belum kenal 90% dari diri anda sendiri. Takut? Ah, Scorsese dengan licin memupuk ketakutan kita dalam setting pulau basah dengan hujan yang tak berhenti turun dan badai yang menampar-nampar.
[caption id="attachment_102532" align="alignnone" width="633" caption="Leonardo DiCaprio, Ben Kingsley dan Mark Ruffalo. Imdb.com"][/caption]
Sejak opening scene, Scorsese sudah mengajak penonton untuk ikut bertamasya pada teori Freud ini. Marshal Teddy Daniels (Leonardo Di Caprio) mabuk laut dalam perjalanan menuju pulau Shutter bersama Chuck Aule (Mark Rufallo) guna menyelidiki kasus menghilangnya seorang pasien rumah sakit jiwa, Rachel. Laut kelabu, langit sendu, settingnya tahun 1945.
Pulau Shutter yang terpencil di samudra serta merta mengingatkan pada puncak gunung es yang disampaikan Freud. Belum cukup, adegan kepala keamanan memperkenalkan fasilitas rumah sakit serta pengelolanya, bak mewakili lapis pertama otak manusia ala Freud: level conscious, apa yang nampak, simbolisasi si puncak gunung es.
Pelan-pelan kita dibawa Scorsese pada lapis demi lapis otak seturut Freud berteori, sampai telak pada bagian terdalam, yang memuat ego, superego, dan identitas siapa anda sejatinya.
Tidak ada yang janggal dari film ini yang tata sinematografi digarap apik Robert Richardson (juga DOP-nya Kill Bill 1 & 2 besutan Tarantino). Sampai setengah jalan, alurnya masih mengikuti jamaknya film-film detektif: ada kasus, pihak berwajib mengusut, lantas ada konflik dalam penyelidikan.
Ekspektasi penonton, apalagi ini film Hollywood; maju tak gentar, yang benar akan menang.
Nah, ini dia masalahnya. Apalagi, tentu seorang Scorsese tidak akan segampang itu mengaduk layarnya. Kebenaran, ternyata mutlak harus dipertanyakan. Alhasil penonton film yang diangkat dari novel Denis Lehane ini terbelah oleh realitas yang dari awal sudah dikumur-kumurkan, versus ‘realitas’ yang ditonjokkan pada paruh kedua film ini.
Saya jadi ingat pada teori realitas dalam komunikasi massa. Sabda disana, suatu peristiwa baru menjadi sebuah realitas kalau sudah dikabar-kabar oleh media. Kalau media massa adalah sebuah society, artinya, realitas adalah apa yang dikostruksikan society terhadap suatu peristiwa.
Dalam kasus Marshal Teddy, suatu keadaan menjadi realitas seturut konspirasi society yang dalam hal ini adalah Dr. Cawley (Ben Kinsley), timnya, serta petinggi militer.
Makanya, selama 138 menit, Scorsese meramu film ini dalam suspense yang tidak hanya melumat Teddy dalam pencariannya. Namun juga anda, penonton yang makin lama makin duduk gelisah oleh daya pikat cara bertutur sang auteur.
Bukan Scorsese namanya kalau penonton filmnya tidak senewen saat dan setelah menikmati layarnya. Ia tidak latah mendalangi penonton. Dengan lihainya, ia justru mengajak penonton untuk ‘berinteraksi’ ikut menyusun kepingan jigsaw untuk mengkonstruksi makna.
Dasar auteur, Scorsese melumatkan keberpihakan penonton pada tokoh protagonis. Dibantu oleh ‘konspirasi’ yang dipimpin Dr Cawley, penonton lantas diceburkan pada ‘realitas’ lain tentang identitas tokoh utama. ‘Konspirasi’ serta ‘realitas’ dalam kalimat terakhir sengaja saya tempatkan antara dua tanda petik, karena lagi-lagi, ini tergantung cara pandang anda, atau kemana anda berpihak.
Pintar sungguh plot ditekuk hingga penonton harus berpikir mana realitas mana ilusi. Siapa yang waras? Teddy? Benarkah ia sebagaimana yang dikonstruksi dalam setengah alur pertama yang US marshal, mantan veteran perang beristri Dolores (Michelle Williams) yang tewas terbunuh dalam insiden kebakaran, atau pasien RS jiwa bernama Edward, atau Andrew yang gila karena membunuh istrinya?
Konspirasi mana yang benar? Bahwa Shutter Island adalah institusi rahasia yang melibatkan militer dan ilmuwan keji yang ‘me-lobotomize’ otak pasien untuk dijadikan tentara kejam, ataukah persekutuan professional ilmuwan dan militer yang ingin ‘menyembuhkan’ Edward/Andrew dari kegilaannya?
Akting matang Di Caprio dan Ben Kinsley menjadikan film yang skenarionya digarap Laeta Kalogridis (lebih dikenal sebagai eksekutif produser film Avatar) menjadi makin menusuk sampai ke otak penonton, yang pulang-pulang harus berargumentasi tentang siapa sebenarnya protagonis dalam kisah ini.
Realitas vs ilusi, dan betapa atas nama sains (ini pun kalau saya memutuskan bahwa tokoh Teddy adalah protagonis sampai ke ujung), manusia bisa berubah menjadi lebih kejam melebihi laknat yang pernah dilakukan oleh Nazi Jerman.
Saya ikhlas senewen menikmati film ini. Silahkan komen realitas mana yang anda percaya setelah selesai menonton dan dibikin puyeng pula. [Nenen]
Omelan asyik lainnya:
Hantu Genderuwo, Pemenang Palem Emas Cannes 2010: Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives
Inception, Awas Perangkap Raun-raun di Alam Mimpi!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H