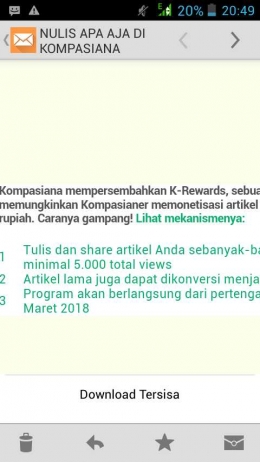Iklan Kompasiana di emailku baru bisa kubuka di dusun, tidak di pondokku. Hampir seperti pemberitahuan mengenai 'sayembara-sayembara' penulisan, baik yang hanya kubaca judulnya atau telah kubacai isinya, hanya membuatku iri saja.
Laman Kompasiana-ku sendiri barangkali sudah hampir empat (4) tahun kosong tak pernah kuisi karyaku lagi. Beberapa kawan kompasianer yang akhirnya bertemu di media sosial facebook sering bertanya, "Kok sudah lama sekali tidak menulis?"
Bukan tidak menulis, aku tetap menulis. Hanya sekarang lebih banyak menggunakan media kertas, coretan tangan. Uh, aku jadi ingat betapa aku ingin sekali memiliki mesin ketik!
Aku tetap menulis di buku-buku tulis yang kumiliki selama tinggal di tengah kebun kopi ini. Tulisan tangan, yang kata Dani suamiku, hanya aku sendiri yang bisa membacainya.
Tahun-tahun awal, mulai Juni 2014, aku tinggal di kebun kopi, di Dusun Sungai Tebal, Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, sangat sulit. Terlebih untuk alasan sepele : charge hp, charge laptop! Aku mesti menunggu hari dimana listrik swadaya dari Pembangkit Tenaga Microhidro di Sungai Nilo Kecil menyala. Listrik menyala 24 jam hanya di hari Minggu dan Rabu, saat itu. Minggu karena anak-anak libur sekolah. Hari Rabu karena hari pekan atau hari pasar (di sini umumnya orang menyebut Kalangan) sedang berlangsung. Aku harus menunggu dua (2) hari itu untuk menumpang isi baterai.
Hari biasa hidup, hanya saja harus pagi-pagi benar aku 'turun' ke dusun, sebelum pukul 9, atau sore setelah pukul 16. Sore, terlalu petang untuk aku pulang lagi ke pondok jika harus menunggui baterai penuh.
Di dusun, 45 menit jalan kaki melalui dua tebing (bukit) dari pondok kami, sinyal internet juga bagus, H. Tidak seperti saat di pondok, E pun naik turun tak karuan. Padahal, Dani sudah memasang alat penangkap sinyal setinggi 10 meter dari total panjang kabel 20 meter. Kiriman email, atau memaksa diri membuka website bikin baterai hpku ngedrop, pun tetap tak bisa terbuka (nanti kubikin cerita soal ini lebih khusus).
Suatu kali ada staf redaksi sebuah buletin memintaku menulis sepenggal pengalaman hidup keluargaku di Solo. Sudah tentu ada deadline-nya. Tulisan sudah kusiapkan dalam bentuk tulisan tangan. Hari itu hari Minggu, aku lupa tanggalnya. Hari yang panas, membuat tenggorokan kering dan jantung berdegup kencang saat menanjak di tanjakan Meri (nama yang aku dan Dani bikin untuk kepentingan kami sendiri). Tebing di seputaran kebun milik Meri itu memang aduhai. Tidak nanjak tegak, tapi lempeng ajeg nanjak panjang dan lama dari arah pondok kami. Baru saat mendekati puncak saja tanjakannya agak tajam.
Tiba di turunan Sungai Nilo Kecil, sebetulnya aku curiga, kok tidak ada bunyi dengung dari pondok kecil di tepi sungai itu. Bunyi dengung itulah yang biasanya menandakan hidup tidaknya dinamo yang disimpan di pondok bercat putih itu. Melewati jembatan, tanjakan madu --sebab di sana ada pohon besar yang senantiasa ada lebah dan sarangnya, membuat jantung berdegup kencang dan tenggorokan kering untuk kedua kalinya. Tanjakan madu merupakan tanjakan terakhir menuju Dusun Sungai Tebal.
Bajuku basah kuyup bermandi keringat setiba di rumah Mbak Warniah istri Mas Darto yang orang Indramayu itu. Listrik di rumah mereka jadi langganan tempat kami menumpang mengisi baterai. Oya, kami pun seringkali menitipkan power bank pada mereka. "Mati listrike, Mbak," kata Mbak Warniah yang sering kami panggil Mak Rasti. Rasti anak kedua pasangan ini.
Memang ya mati. Dari saat ketemu rumah pertama saya tidak melihat lampu menyala, atau ada suara-suara dari tv atau orang memutar musik, seperti jika listrik sedang hidup. Kabarnya, air yang mengalir kurang kuat untuk memutar turbin. Apa boleh buat, saya kembali pulang, 45 menit jalan kaki lagi tanpa hasil.
Aku harus menunggu hari Rabu. Tidak mengapa, bisa sekalian membeli keperluan dapur. Belanja di pekan biasanya harganya agak lebih murah. Aku senang, sebab listrik menyala. "Munggaho wae, Mbak, neng kene rame, ndak keganggu (Naik saja, di sini --tokonya- ramai orang, nanti terganggu)," pinta Mak Rasti.
Aku mulai mengetik. Toh kalau sedang berada di depan laptop, tulisan tangan tidak begitu kupedulikan lagi. Otak yang berlari harus kukejar dengan jemari.
Oh Tuhan.. Tuts laptop tua kami ternyata tidak mau mengeluarkan angka yang kubutuhkan. Angka 8, angka 9 macet. Sejak awalpun keyboard laptop terus mengeluarkan huruf e tanpa saya kehendaki. Menulis di laptop membuat aku senewan.
Usai mengetik, tulisan itu langsung kukirim melalui email. Dalam badan surat, dengan menanggung malu kutulis permintaan maaf. Angka 8 dan 9 seharusnya ditulis angka, bukan delapan atau sembilan.
- -
Iklan di kompasiana kubacai. Menarik. Lalu?
e-mandiri. Lha ini...
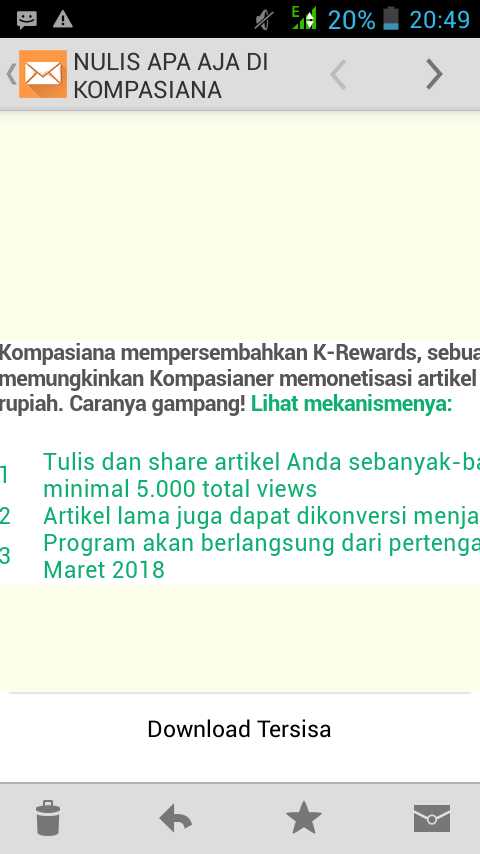
April 2017 lalu, sebelum KTPku kadalursa, aku mengurus perpindahan alamat rekening BRI-ku di Kantor Unit Pasar Bawah, Bangko. Di buku rekening, alamatku masih Solo, sementara alamat setelah menikah adalah Bandung. Dari pondokku ke Bank BRI di Bangko, butuh waktu 45 menit jalan dan 3 jam bermobil. Pagi gulita nan dingin harus bangun, jalan kaki ke dusun secepatnya agar tidak ketinggalan mobil travel ke kota.
Costumer service itu mengecek ini itu juga menelpon BRI Kanca Tapaktuan, Aceh Selatan, menerangkan ini itu cukup lama. Memang tahun 2008 lalu, aku mendaftar di sana.
"KTP dan KK Ibu Ninuk ini agak meragukan. Ini saya check....Ibu Ninuk sudah melakukan rekam data di Solo ya. Alamat eKTP masih Solo. Artinya....saya tidak tahu nih apakah KK dan KTP yang ini (yang sedang dipegangnya) asli," katanya. Aku bosan mengulang-ulang bahwa aku mendapat KTP dan KK sebab aku sudah mengajukan pindah penduduk di Solo, dan sekarang sudah tercatat sebagai penduduk Kota Bandung.
Ia mengatakan, tidak bisa membantu sekalipun hanya mengubah alamat di buku rekening. KK dan KTP keluaran Pemkot Bandung tidak laku. "Yang penting tidak rusak saja ATMnya," ujar si ibu berbaju biru itu menasehati. Ia juga memberi keterangan, jika pun menutup rekening Tapaktuan, aku tidak bisa membuat rekening BRI lagi karena e-KTP masih Solo.
Oh, terkutuklah kau para koruptor eKTP!
Maka sejak itu, sekalipun pelanggan Kopi Luwak liar Lembah Masurai menyarankanku membuat rekening selain BRI, aku enggan. Hati ini terus mengutuk para koruptor eKTP itu. Betapa...tak rewangi bangun subuh untuk mengejar mobil ke kota, menahan pusing dan mual sepanjang jalan yang mengular itu, ternyata gagal. Biang kerok kegagalan mengurus rekening, apalagi kalau bukan korupsi trilyunan rupiah itu. Huh!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H