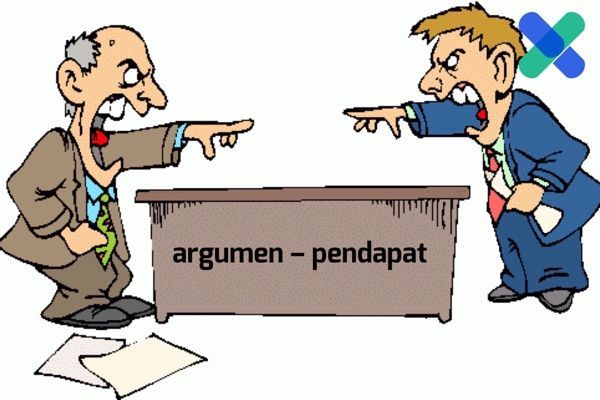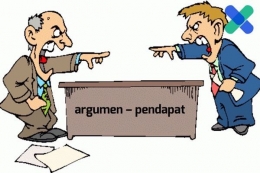Emosi ikut tersulut ketika menonton narasumber program acara TV yang saling berdebat. Argumentasi tarik urat penuh emosional terjadi, bahkan para narasumber sama-sama saling bersuara dan saling tumpang tindih hingga tidak terdengar apa yang sedang mereka argumentasikan.
Emosi pun turut tersulut ketika ada tokoh politik yang saya kagumi disindir kebijakannya melalui sosial media, bahkan saat membaca komentar pedas dari netizen lain, yang malah masuk ke ranah pribadi, rasanya pengen adu ngegas membela tokoh politik yang saya kagumi.
Tapi rasa hati saya langsung terhenyak begitu mendengarkan beberapa narasumber yang saya tonton dalam tayangan salah satu program TV, sebut saja Haris Azhar, seorang aktivis HAM, dan Imam B. Prasodjo, seorang sosiolog Indonesia.
Juga ada Budiman Sudjatmiko, anggota DPR RI PDI P dan Dandhy Laksono, yang merupakan aktivis HAM, mereka berdebat dalam satu kesempatan program debat tentang Papua di YouTube Channel Watchdoc.
Argumentasi yang keluar dari bibir beliau semua sarat akan wawasan dan pemahaman di lapangan. Mereka mendengarkan dulu pendapat lawan bicara hingga selesai, baru kemudian mengeluarkan pendapat.
Mereka sangat menghargai perbedaan pendapat, sarat akan emosional saat adu pendapat agak jauh dari pribadi mereka. Setidaknya tidak nampak diwajah. Mereka tidak saling berusaha untuk tarik-menarik agar sependapat, atau terlihat menang kalah.
Hal ini membuat saya bertanya-tanya, apakah ada hubungan antara tingkat intelektualitas seseorang dengan cara mereka berargumentasi?
Saya sendiri tidak terlalu mendapatkan jawabannya secara pasti, karena ada juga orang yang berpendidikan tinggi disekitar saya yang juga mudah emosi saat adu argumentasi.
Mencari jawaban, saya malah menemukan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa kecenderungan kita mudah marah saat silang pendapat karena dipengaruhi oleh sistem media sosial yang melakukan penyeragaman konten dengan akun sosial media yang berbeda.
Yap, saking smart-nya, smartphone kita seringkali mengarahkan post, foto, ataupun feed yang bersifat sama. Misal kita doyan nonton mukbang, nah, bisa jadi feed pencarian kita akan terisi dengan video atau foto yang berhubungan dengan mukbang.
Hal ini terjadi juga dalam membaca pemberitaan dari akun-akun sosial media, smartphone kita akan mengarahkan pada akun sosial media yang memiliki opini atau pemberitaan yang satu alur.
Hal ini saya alami ketika saya mendukung satu tokoh politik. Saya memiliki kecenderungan untuk mencari berita atau opini yang mendukung beliau. Yang berbeda pendapat, tentu tidak pernah saya lihat.
Maka itu, muncullah feed pencarian yang akun sosial medianya mendukung beliau. Banyaknya akun sosial media yang muncul dengan pembelaan dan pemberitaan.
Serta adanya bukti bahwa tokoh politik yang saya dukung itu sangat baik, akhirnya secara tidak sadar pola pikir saya terbentuk untuk sepakat dengan semua yang dilakukan tokoh politik tersebut selalu benar, oposisi selalu salah.
Suatu hari, saya penasaran dengan berita-berita dari oposisi tokoh tersebut. Kemudian terjadilah penyeragaman konten dari akun sosial media yang berbeda-beda, ada saja salahnya tokoh politik tersebut dan ada bukti-bukti yang mendukungnya.
Dari yang tadinya saya kesal membacanya, dan menganggap banyak editan, hingga akhirnya saya menemukan suatu fakta bahwa selama ini sosial media telah menggiring pikiran dan kepribadian saya untuk berpihak.
Penelitian Snsp.org menyebutkan penyeragaman konten membuat kita secara tidak langsung membentuk sebuah komunitas. Orang-orang yang memiliki pendapat yang sama, pemikiran dan kesukaan yang sama akan bersatu untuk membentuk suara mayoritas, sedangkan orang-orang yang tidak sependapat akan dianggap minoritas.
Jadi ketika ada orang yang berseberangan pendapat, orang tersebut akan dianggap tidak baik dan dicaci.
Saya rasa hal tersebut bisa memberikan efek fanatisme dalam diri seseorang. Dan tidak menutup kemungkinan akan terbawa ke kehidupan sehari-hari, dimana kita cenderung berteman dengan orang yang sepemikiran dan sependapat saja. Ketika terjadi perbedaan pandangan, kita tidak lagi menggunakan akal sehat dalam berargumentasi, rasa untuk membela kelompoknya muncul tanpa disadari.
Mungkin juga emosi itu muncul karena kita sebenarnya tidak paham dengan apa yang terjadi dilapangan, kita hanya melihatnya dari secuil informasi yang beredar di sosial media yang disajikan oleh akun-akun yang ternyata memiliki opini dan pemikiran yang sama.
Karena banyaknya berita dan pendapat yang sama, maka kita anggap kejadian tersebut menjadi sebuah kebenaran yang mutlak.
Maka ketika ada perbedaan pendapat, penyerangan secara emosional pun akhirnya dilakukan, bahkan ketika kita terdesak tidak bisa membela karena kurangnya pengetahuan fakta dilapangan, penyerangan terhadap personal pun dilakukan. Secara tidak sadar, kita berusaha membela komunitas. Rasa yang berlebihan, menutup logika.
Hmm.. mungkin saya bisa mengatakan bahwa homogenitas pendapat ini disebabkan oleh pengaruh sosial media, yang kemudian menurunkan daya kritis kita, karena kita terbiasa menyerap informasi yang hampir sama, walau dari berbagai akun sosial media.
Apabila terus dibiasakan, tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi katak dalam tempurung, walaupun sudah berpendidikan sangat tinggi.
Untuk mengurangi pemaksaan pendapat, mungkin akan ada baiknya kita berlatih untuk mencari informasi yang saling berbeda. Tentunya dari media yang resmi.
Misalnya saja, kita mesti tahu media A B C itu dimiliki oleh siapa, sehingga kita bisa tahu media tersebut akan menempatkan diri dipihak yang mana dan kecenderungan konten beritanya akan seperti apa.
Kemudian, kita mencari media yang kira-kira berseberangan dengan pemilik media, kemudian membaca bagaimana informasi yang diberitakan media tersebut dari kejadian yang sama. Apakah kedua media tersebut memiliki informasi yang sama, atau berbeda.
Kemudian kita tarik kesimpulannya, dengan begitu kita mungkin akan belajar untuk menerima perbedaan pendapat. Karena bisa jadi ada pro kontra dalam satu kejadian, karena perbedaan pandangan dan kepentingan.
Dan ketika kita berdiskusi dan terjadi perbedaan pendapat dengan orang lain, kita akan condong bisa menghargainya dan menyadari bahwa pola pikir, latar belakang keluarga, agama, budaya, dan pendidikan itu sangat beraneka ragam.
Karena informasi yang kita terima disosial media cenderung seimbang. Kecenderungan kita untuk menghomogenitaskan pendapat pun bisa dikesampingkan karena wawasan yang luas.
Referensi bacaan :
Niedbala, Elizabeth. 3 Mei 2019. Ingredients for Conflict : Why We Get so Angry When People Disagree with Us. Diakses dari Spsp.org pada tanggal 16 Maret 2021
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H