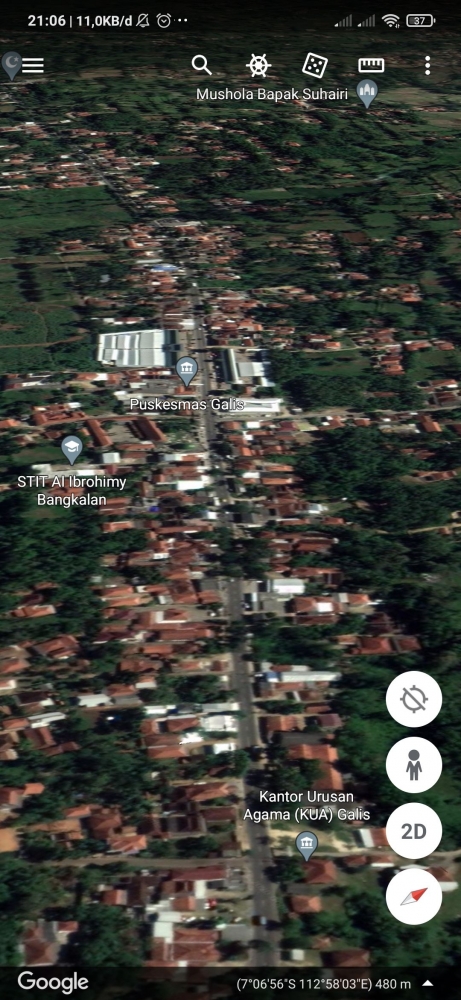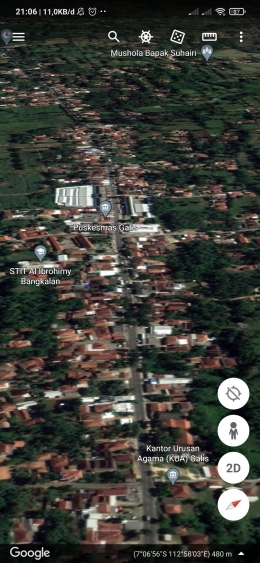Disitu, orang-orang ada yang berkendara ke barat jauh, atau timur jauh. Kebanyakan berwarna hitam atau putih, di atas aspal yang markanya putus-putus seperti kertas yang harus digunting.
Sebelah kirinya, masjid Jami keemasan, kubahnya hijau tua, jamaahnya tua-tua. Yang muda membariskan motor mereka menghadap Utara. Rukun berbagi rokok eceran sambil khusuk menikmati ibadahnya.
Seberang jalannya, kantor pos yang sudah tutup, warung nasi pecel, ibu-ibu sibuk mengusir pendatang, lalat-lalat lapar, sementara yang lewat hanya musafir yang berpuasa.
Dunia masih berwarna, meskipun warnanya tua dan lemah, selemah abu-abu, tidak jelas, langitnya tidak menarik, semua orang hidup untuk orang lain. Yang sudah mati seperti mereka yang disemayamkan di sebelah masjid, juga dulunya hidup untuk orang lain.
Lampu jalan tenaga Surya, di musim hujan segala macam makhluk malas bekerja. Pangkalan ojek sepi, yang sudah punya nomor antrian menunggu penumpang sambil meramal angka keberuntungan, mereka hidup bukan untuk bininya.
Aku sudah belasan tahun, dan ratusan kali keluar masuk pintu gerbang ini. Waktu sangat cepat, atau mimpiku yang teramat lambat, karena saat semua berubah dan pohon-pohon mangga itu puas berbuah, aku tidak merasakan apa-apa.
Badan ini tiada lagi bertambah tinggi, hanya cita-cita yang meninggalkanku teramat tinggi.
Tak bisa kembali, aku sendiri.
Musim dan musik berganti puluhan kali, puisi dan polisi tukar posisi. Hujan dan tangisan tak bisa sembunyi lagi. Ekspektasi dan ekspresi saling berkompetisi, mengalahkan. Membunuh. Semuanya mati.
Bila saatnya shalat, aku shalat. Tuhan masih ada. Meski jarang diajak bicara. Formalitas. Frustasi. Atau keduanya dicampur saja siapa peduli.
Saat hendak tidur, yang paling indah hanya musik jazz, atau genre lain yang improvisasinya tidak dibatasi. Atau lagu-lagu asing lainnya. Semua yang baru. Karena yang lama semuanya sama saja. Sama-sama seperti itu, mudah dibaca. Ditebak begitu saja akhir ceritanya.
Bila aku bermimpi indah, aku tidak pernah lagi mengharapkannya, jika terbangun saat sedang bahagia, aku tak kecewa. Seindah indahnya mimpi cuma mimpi, seburuk-buruknya kenyataan hanya kenyataan.
Sejak aku dipahami, bahwa kenyataan milik manusia itu tidak benar, mulai saat itulah bagiku, mimpi atau prestasi sama saja. Hidup dan mati sama saja.
Di jalan itu, mobil-mobil berhenti, sepeda motor, jamaah masjid, ibu-ibu penjaga warung, anak-anak muda yang rokoknya sudah habis, tukang ojek, semuanya menghampiriku.
Aku lari,
Mereka mengejar,
"Ada apa?" Teriakku,
Mereka mendekat.
Aku kabur
"Tunggu, tunggu!!!"
Mereka teriak
Sekelumit cerita yang ingin ku lanjutkan tapi percuma.
Buatmu, apa pentingnya cerita itu, atau apa pentingnya diriku.
Galis, 7-1-2021
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H