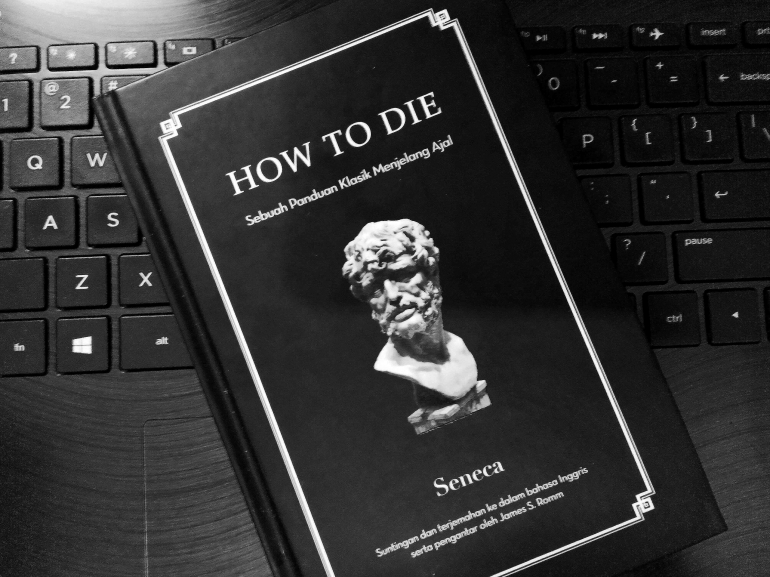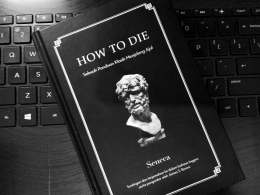Di saat-saat terakhirnya, Caligula, yang mulanya menyangkal prospek kematiannya sendiri, tiba-tiba menyambut kengerian maut saat dia menunggu pasukan pemberontak masuk. "Ketakutan juga punya akhir," ujarnya.
"Segera aku akan mencapai kekosongan yang melampaui segala pengertian, di mana hati mengenal peristirahatan." Ironisnya, dalam upaya terakhir untuk menyangkal kematiannya sendiri, kata-kata final Caligula adalah, "Aku masih hidup!"
Caligula yang saya ceritakan itu adalah Caligula-nya Albert Camus. Tapi, terlepas dari unsur fiksi (dan puisi) yang dijejalkan Camus, tokoh Caligula bukanlah tokoh fiksi semata. Dia adalah seorang Kaisar Romawi yang dikenal luas karena kekejaman dan kegilaannya.
Ada cerita dari Dio Cassius bahwa Caligula pernah memutuskan untuk mengeksekusi Seneca, yang saat itu sudah jadi senator muda. Namun, seorang pengagum Seneca meyakinkan Caligula bahwa Seneca sudah sakit-sakitan dan karenanya akan mati tak lama lagi.
Seneca, sebagai politikus sekaligus filsuf Stoik, tampaknya telah belajar banyak dari sekian kematian atau penistaan akibat titah kaisar. Dia menyaksikan orang-orang di sekitarnya lebih memilih mati ketimbang hidup disiksa, dan sebagian yang lain justru terlalu cinta hidup.
Sikap kedua itu agaknya menjadikan Seneca resah. Sebab, tatkala orang terlanjur candu pada dunia, merekalah yang sesungguhnya paling menderita. Mereka senantiasa diteror oleh maut, bahwa suatu ketika entah bagaimana, mereka bisa ujug-ujug kehilangan segalanya.
Tentu keliru bila menganggap Seneca mengutuk kehidupan sepenuhnya. Pada saat yang lain, dia juga kagum kepada mereka yang tetap berjuang mempertahankan hidupnya di hadapan maut, memberontak pada "takdir" yang menindas selama diri punya kendali.
Tepatnya, Seneca menasihati orang-orang sezamannya dan sesudahnya bahwa kematian adalah keniscayaan bagi sesuatu yang hidup. Kematian bukanlah kebalikan dari kehidupan, melainkan bagian darinya. Cinta hidup berarti bersedia untuk mati.
Dan karena tak semua orang berkenan menerima fakta semacam itu, maka satu-satunya cara yang layak bagi Seneca adalah dengan mengakrabkan diri pada kematian agar rasa takut yang selama ini bergejolak bisa terkendali dan, mudah-mudahan, diterima.
"Barang siapa tak memahami cara mati yang baik, dia akan menjalani hidupnya dengan buruk," tuturnya.
Menerima kefanaan
Kehidupan, kalau dipikir-pikir, hanyalah sekadar perjalanan menuju kematian. Setiap hari kita mendekati kematian, bahkan sejak kita terlahir. Kematian adalah kondisi dari penciptaan kita. Itu adalah bagian dari diri kita. Kita lari dari diri kita sendiri.
Kita mungkin berpikir hidup dan mati benar-benar berurutan: kita hidup, lalu kita mati. Yang benar adalah bahwa kematian berbaur dan menyatu dengan hidup kita sepanjang waktu. Kita tak mati karena kita sakit. Kita mati karena kita hidup.
Terlebih, jika mati berarti tiada, maka sebenarnya kita sudah "pernah" mengalami itu. Sebab, sebelum terlahir, kita tiada. "Kita mengira maut hanya akan tiba sesudah kehidupan, padahal sesungguhnya kematian datang sebelum dan sesudahnya," tulis Seneca.
Kendati begitu, fakta bahwa setiap orang sadar dirinya fana, kematian tetap saja membuat kita takut dan ngeri. Lebih buruknya, ketakutan itu juga kerap merenggut kebahagiaan kita. Dan bilamana orang menemukan dirinya tak bahagia, dia semakin takut, dan seterusnya.
"Kita semua tahu hal yang sama akan menimpa kita semua," ucap Seneca, "tapi takut menghadapi ajal itu sendiri sering kali menjadi penyebab kematian." Dan karena kita takut, kita menghindar untuk memikirkannya, bahkan untuk sebatas mengakuinya.
Memelihara rasa takut akan kematian bukan saja teror yang tak berkesudahan, tapi juga keserakahan. Kita menginginkan lebih banyak hari, lebih banyak tahun, dan ketika kita diberkati untuk menerimanya, kita masih menginginkan lebih.
Kita bahkan ragu bisa memperbaiki diri seiring waktu yang lebih lama itu. Jika kita telah hidup satu hari saja, kita telah menjalani semuanya.
Manusia unggul dalam menyangkal kebenaran yang menggelisahkan, dan tak ada kebenaran yang lebih menggelisahkan daripada kematian. Kita bersenang-senang di suatu waktu sampai kita lupa bahwa matahari menyinari keseharian kita. Jam berapa, ya, sekarang?
Tiba-tiba kita tersentak oleh waktu. Kita tak lagi belia. Kadang kita butuh sandaran untuk bisa berdiri lama. Wajah yang kita lihat di cermin tampak asing; dahinya sudah mengerut dan tulang pipinya semakin menonjol. Berapa lama lagi, ya?
Beberapa dari kita mungkin putus asa, merasa sia-sia, untuk menyuntik diri mereka sendiri dari gigitan waktu. Tapi, kata Seneca, "Ketika saat-saat terakhir yang tak terelakkan itu tiba, pergilah dengan pikiran yang tenang."
"Bayi, anak kecil, atau orang-orang gila tak ada yang takut pada kematian; sangat menyedihkan bila nalar sehat kita tak memberi kita rasa damai yang sama seperti dibuahkan oleh [kepolosan]."
Cara agar tenang menghadapi kengerian yang (nyaris) absolut itu adalah dengan membuatnya akrab, menerima bahwa pada dasarnya kita semua fana. "Bersiaplah untuk kematian; orang yang mengingatkan hal ini juga meminta kita untuk mempersiapkan kebebasan."
Lanjut Seneca, "Orang yang belajar cara untuk mati telah melupakan cara untuk menjadi budak." Ini karena ketika kita mengelak dari maut, setiap kesenangan lainnya dipadamkan. Menerima kefanaan diri kita sendiri, paradoksnya, berarti mengakui kebebasan kita sendiri.
"Mari kita hilangkan keanehannya, kenali, biasakan," ujar filsuf lainnya yang lebih modern, Michel de Montaigne. "Janganlah kita memikirkan apa pun sesering kematian. Setiap saat, mari kita bayangkan dalam imajinasi kita dengan segala aspeknya."
Baik Seneca maupun Montaigne sama-sama mengingatkan kita bahwa kematian bisa datang kapan saja. Penulis drama Yunani Aeschylus diduga terbunuh oleh cangkang kura-kura yang dijatuhkan oleh elang. Kita harus selalu mawas dan siap untuk pergi.
Kematian bukanlah sesuatu yang kita kuasai, seperti catur atau ukulele. Ini bukanlah suatu keterampilan. Mungkin mempersiapkannya adalah sebentuk keterampilan, tapi kematian itu sendiri adalah orientasi. Kematian bukanlah cacat dari kehidupan, melainkan hasil alamiah darinya.
Oleh sebab itu, kita sebaiknya mulai mendekati kematian secara perlahan bukan sebagai malapetaka, tapi sebagai sesuatu yang indah dan niscaya, seperti daun musim gugur yang jatuh dari pohon di bulan November.
Memaknai kematian, memaknai kehidupan
Prospek kematian secara menakjubkan memusatkan pikiran. Sebagaimana diutarakan Ernest Becker dalam bukunya yang terkemuka The Denial of Death (1973), "(maut) adalah sumber utama aktivitas manusia."
Entah kita menerima atau menyangkal prospek kematian, intinya tetaplah sama: alur hidup kita sering ditentukan olehnya. Jika orang menerima, atau menolak, kefanaannya, mereka akan bertindak sesuai keyakinan itu.
Antropolog terkenal A. M. Hocart pernah berpendapat bahwa orang-orang primitif tak begitu diganggu oleh rasa takut akan kematian. Bahkan, lebih sering daripada tidak, mereka gembira dan merayakan prospek kematian mereka sendiri.
Supaya adil, perlu disebutkan bahwa mereka berbuat begitu karena mereka percaya kematian adalah promosi terakhir, ritual pamungkas sebelum diangkat menuju kehidupan yang lebih tinggi, menuju kenikmatan abadi dalam berbagai bentuk.
Sebagian besar manusia hari ini, terlepas dari peran yang diberikan agama, tampaknya cukup kesulitan untuk meyakini betul-betul hal semacam itu (lagi), yang akhirnya membuat ketakutan akan maut begitu kentara sebagai bagian dari susunan psikologis kita.
Namun, dengan cara yang aneh, kita sebenarnya bisa tetap "merayakan" prospek kematian itu. Dalam hal ini, cara yang saya maksud adalah dengan memaknainya. Atau singkat kata, memaknai kematian berarti memaknai kehidupan.
Becker menyebut ini "antidot yang pahit", sebab dia berusaha berdamai dengan dirinya sendiri saat menatap maut. Asumsi bahwa kematian itu mengerikan memang tak terelakkan. Tapi, alih-alih menghindari kesadaran ini, kita justru perlu menghadapinya sebaik mungkin.
Tatkala kita mampu merasa nyaman dengan fakta kematian kita sendiri, (mudah-mudahan) kita akan mampu memilih nilai kita secara lebih bebas, tak terkungkung oleh hasrat akan keabadian, dan membebaskan kita dari segala dogma yang berbahaya.
Pada titik ini, kita menjadikan kematian sebagai sebuah cahaya yang mampu menerangi bayangan makna-makna kehidupan. Tanpa kematian, semua terasa percuma. Semua pengalaman, semua nilai, tiba-tiba menjadi nol.
Demikianlah, penting untuk menghadapi kenyataan tentang kematian kita sendiri, sebab ini menyaring segala nilai yang buruk, rapuh, dan dangkal dari hidup kita. Jika tidak, saat kita hidup dengan rasa keabadian, kita mungkin akan nekat untuk melakukan apa pun.
Caligula, dalam lakon Albert Camus, mengaku sebagai wujud "takdir". Dengan begitu, fakta bahwa takdir ada dalam setiap babak sejarah manusia, dia meyakini dirinya akan langgeng. Dan akibat keyakinan tak sopan itu, dia membunuh siapa pun yang dikehendakinya.
Tanpa pernah mengakui tatapan kematian di hadapan kita, nilai yang sifatnya dangkal akan tampil sebagai sesuatu yang penting, dan sebaliknya. Kematian adalah satu-satunya hal yang bisa kita ketahui secara pasti.
Oleh sebabnya, itu harus jadi kompas kehidupan kita: memberi petunjuk arah dari nilai dan keputusan kita lainnya. "Ketakutan akan maut menandakan kita masih takut untuk hidup," ujar Mark Twain. "Seseorang yang hidup secara paripurna siap mati kapan saja."
Jadi, sebagaimana tutur Seneca, "Apa pun yang kau jalani, arahkan selalu pandanganmu pada kematian."
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H