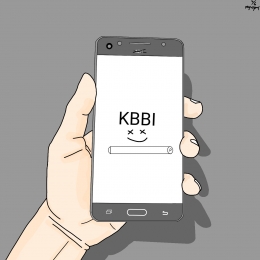Awalnya bahasa pemersatu, eh malah jadi bahasa perbedaan mutu.
Masalah berbahasa Indonesia masih menjadi kendala orang masyarakat Jawa. Sebenarnya maslah seperti ini tidak hanya dihadapi oleh orang daerah saja, tetapi juga setiap bangsa di seluruh dunia.
Dasarnya bahasa Indonesia dibuat dan disepakati untuk menyatukan semua bahasa yang ada di nusantara. Bahasa Melayu menjadi bagian awal yang diangkat, karena bahasa tersebut tidak memiliki kasta. Lebih lanjut guna menghindari imperialisme berbahasa. Namun bahasa Indonesia tidak semerta-merta menjadi bahasa ibu. Karena keberadaan bahasa daerah juga perlu dilestarikan. Tak khayal keadaan yang seperti ini mewarnai konflik-konflik berbahasa.
Lucunya bahasa Indonesia tidak terlalu diminati oleh sebagian besar masyarakat Jawa yang berdiam diri di tanah kelahirannya. Hal ini tentu saja sangat dilumrahkan. Mengingat bahasa Jawa menjadi bahasa ibu mereka.
Berbeda dengan orang-orang perantauan, mereka yang pernah menginjakkan kaki di kota Jakarta atau pun sekitarnya. Mereka akan sangat terbuka menggunakan bahasa Indonesia. Baik untuk penduduk yang menetap, sesama perantau, ataupun sesama komunitas Jawa di perantauan.
Gara-Gara Kelamaan di Kota
Lagi-lagi kemajuan kota urban dan segala daya tariknya telah menciptakan stereotip di kalangan penduduk tradisional yang konservatif. Keterbukaan kota-kota maju di negeri ini telah banyak menarik minat penduduk dari berbagai penjuru pelosok dengan latar budaya dan bahasanya masing-masing. Mereka merantau dalam upaya mencari penghidupan, menjauhkan dirinya dari kampung halaman.
Lambat tahun, mereka mendiami kota tersebut dalam waktu yang cukup lama. Sampai pada generasi berikutnya yang dilahirkan dan dibesarkan pada kota maju itu. Sehingga terasa wajar apabila mereka mengaku bahwa dirinya berasal dari kota maju itu, bukan tempat kakek neneknya berasal. Ketertarikan terhadap bahasa daerah dapat hilang pada generasi berikutnya.
Alhasil kemajuan sebuah kota metropolis dibarengi pula dengan kecemasan akan hilangnya sebuah ciri kebahasaan daerah. Meskipun begitu, masih banyak pendatang di tanah urban yang masih menerapkan bahasa daerah mereka dalam lingkungan komunitas yang kecil. Tetapi pengaruh ibu kota masih sama terasanya.
Alkisah seorang pemuda yang baru saja menggelandang di ibu kota. Ia pulang ke kampung halaman di Jawa Tengah dengan tujuan menghabiskan suasana lebaran bersama keluarga tercinta. Sesampainya di kampung halaman, si pemuda bertutur sapa dengan bahasa Indonesia dengan salah seorang kerabatnya. Bukannya mendapatkan balasan hangat, ia malah dikasih amanat.
Contoh kasus:
A: "Apa kabar Mas?
B: " Alhamdulillah, sehat."
A: "Lama tidak jumpa."
B: "Wah-wah, suwe neng Jakarta omongane malyu-melayu. Wis kelalen apa primen sampean?!"
Dalam dialog di atas, tokoh A menyapa tokoh B dengan bahasa Indonesia tanpa ada masalah. Baru kemudian tokoh B mempermasalahkan tokoh A, karena lawan tuturnya kembali menggunakan bahasa Indonesia untuk bertutur.
Masalah di atas muncul akibat tokoh A menggunakan bahasa Indonesia berulang kali, sehingga tokoh B merasa bahwa tokoh A telah mengalami perubahan. Tokoh B menduga kalau Jakarta telah merubah tokoh A dalam berbahasa. Akhirnya situasi tersebut tidak mendapatkan satu kesepakatan. Alasannya karena tokoh B mengharapkan tokoh A berdialog dengan bahasa Jawa.
Dalam kasus di atas, kota Jakarta dianggap telah merubah budaya berbahasa tokoh A. Entah kenapa kota Jakarta menjadi simbol akan hilangnya identitas kedaerahan seseorang dalam berbahasa. Padahal inti dari permasalahan itu ialah karena tidak adanya kesepakatan berbahasa Indonesia.
Dari permasalahan ini, penulis menemukan distorsi sosial berbahasa Indonesia. Di mana kedudukan bahasa Indonesia terdengar cukup tabu untuk diucapkan. Terlepas dari kesalahan tokoh A dalam melihat situasi bertutur.
Menurut lawan bicara si pemuda itu, berbahasa Indonesia di daerahnya sendiri bukanlah perilaku yang terpuji. Ia menganggap si pemuda itu telah lupa dengan identitas asalnya. Bagi sebagian banyak orang di Jawa tengah, berbahasa Jawa adalah bentuk perilaku ke-jawaan seseorang. Maka berbahasa Indonesia di tanah Jawa dengan sesama Jawa, tidak menghargai bahasa daerahnya sendiri dan keluar dari identitas ke-jawaan.
Bahasa untuk Membangun Citra
Di Jawa Tengah, ragam bahasa Jawa kromo mengisi ruang-ruang formal seperti, lingkungan sekolah, Kantor Kecamatan atau instansi formal lain. Di luar itu, ragam kromo kerap digunakan untuk bertutur dengan seseorang yang lebih tua. Sehingga pemuda tadi tidak mendapatkan perlakuan yang hangat untuk berbahasa pemersatu ini.
Namun sebuah paradoks muncul ketika sesama orang Jawa yang sebaya ataupun tidak berbahasa Indonesia dalam situasi lain. Dalam kasus-kasus alih kode, bahasa Indonesia kerap muncul sebagai bentuk eksistensi diri. Apalagi kasus alih kode antara bahasa Jawa ke bahasa Indonesia di lingkungan Jawa. Tujuannya agar terlihat lebih terpelajar.
Seperti contoh kasus berikut ini:
A: "Sampean kayong apal temen dalanan Jakarta ya. Kayong beres pengalamane."
B: "Jenenge golet pengalaman."
A: "Berarti sukses sing pengalaman?"
B: "Modal sukses itu ya pengalaman."
A: "Bener, pancen hebat sampean."
Ada perubahan bentuk bahasa yang digunakan tokoh B dalam bertutur dengan tokoh A. Semula tokoh B berdialog dengan bahasa Jawa dialek ngapak untuk menanggapi ucapan tokoh A. Namun tokoh B merubah bentuk bahasanya ke bahasa Indonesia untuk menunjukkan kualitas dirinya.
Berbeda dengan dialog sebelumnya, dalam kasus ini kedua tokoh saling menyepakati keberadaan bahasa Indonesia. Meskipun tokoh A tidak bertutur dengan bahasa Indonesia juga. Faktor penyebabnya karena tokoh A mencoba terbuka dengan keadaan di luar bahasa Indonesia itu sendiri. Yaitu pengalaman lawan tuturnya, tokoh B.
Jika dalam kasus sebelumnya kota Jakarta dianggap memberikan pengaruh akan hilangnya identitas bahasa daerah yang cenderung negatif, pada kasus kali ini justru sebaliknya. Bahasa Indonesia yang dituturkan tokoh B mendapatkan perlakuan baik. Hal itu terjadi karena adanya pengaruh dari luar bahasa Indonesia itu sendiri. Yaitu pribadi si tokoh B.
Lebih lanjut lagi, ternyata paradoks yang serupa muncul di atas mimbar. Seorang kepala daerah berpidato dengan bahasa Indonesia untuk menunjukkan kebolehannya. Para hadirin yang berisi orang-orang dewasa, tua dan sesepuh mengindahkannya begitu saja. Sementara di lingkungan kantor, para pegawai terbiasa menggunakan ragam bahasa Jawa kromo. Artinya kepala daerah tadi sama seperti si pemuda yang baru mudik. Hanya saja faktor jabatan dan situasi membuatnya lebih dihargai.
Citra Penutur Terhadap Bahasa
Lagi-lagi bahasa Indonesia dapat diterima oleh masyarakat daerah karena citra dari si penutur. Entah kenapa hal-hal di luar tata bahasa Indonesia senantiasa mempengaruhi kedudukan bahasa pemersatu.
Jika masalah orang Jawa yang berbahasa Indonesia di tanah Jawa selalu membutuhkan situasi, maka yang terjadi adalah bahasa Indonesia tidak sepenuhnya diterima oleh orang Jawa di tanahnya dalam aktivitas sehari-hari. Kecuali bagai orang Jawa yang pernah merantau ke kota Jakarta. Bahasa Indonesia akan menjadi hal yang sangat biasa untuk digunakan kapan saja.
Di sini penulis melihat adanya tidak keterbukaan masyarakat Jawa dalam menerima bahasa Indonesia di tanah mereka. Terkecuali bagi mereka yang pernah menginjakkan kaki di ibu kota. Atau orang-orang yang mengenal situasi bertutur, tahu kapan saatnya bahasa Indonesia digunakan.
Dalam hal ini, tentu saja cita-cita bangsa menggunakan bahasa pemersatu tidak dapat dikatakan gugur. Tetapi mengalami perubahan tujuan. Yang semula sebagai bahasa pemersatu malahan berubah sebaliknya, menjadi pembeda antara individu dengan individu lainnya.
Mirisnya, secara sadar masyarakat daerah menyimbolkan kota Jakarta sebagai kota yang meruntuhkan identitas kedaerahan. Dan masyarakat daerah mempunyai paradigma kalau bahasa Indonesia berasal dari kota metropolis itu. Padahal di kota Jakarta banyak masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana layaknya orang Jawa berbahasa Jawa di tanahnya sendiri.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H