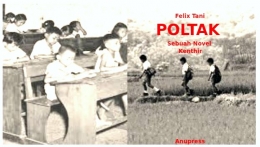Di dalam bubu itu terlihat bergeleparan ikan-ikan yang terperangkap. Ada empat ekor ihan, Neolissochilus thienemanni, ikan Batak. Selebihnya ikan pora-pora, Mystacoleucus padangensis.
"Ayo. Kita pulang." Berkata demikian, Ama Rumiris segera bergegas. Meninggalkan Poltak dan Berta di belakang.
"Ayo pulang, Berta. Kau jalan di depanlah," ajak Poltak.
Keduanya meniti pematang sawah, santai, kembali menuju rumah yang tak seberapa jauh.
Sambil berjalan, Poltak spontan bersenandung. "Pangeol-eolmi solu. Solu na di tonga tao. Molo matipul holemi solu. Maup hudia nama ho. Pangeol-eolmi boru. Boru na so mariboto. Molo mate amantai boru. Maup hudia nama ho."
Itu andung-andung, senandung ratapan, karya Tilhang Gultom dalam lakon Si Boru Tumbaga yang selalu dimainkan kelompok opera Serindo dalam tiap pertunjukannya. Senandung itu mencemaskan nasib anak perempuan yang tak punya saudara laki-laki.
"Gemulai engkau biduk. Biduk di tengah danau. Bila dayungmu patah biduk. Kemana gerangan engkau hanyut. Gemulai engkau putri. Putri tanpa saudara laki. Bila ayahanda berpulang. Kemana gerangan engkau bersandar."
Dalam masyarakat Batak lama, jika seorang ayah tidak dikarunia anak laki-laki, hanya anak perempuan, maka harta-bendanya akan dikuasai saudara laki-lakinya saat dia meninggal dunia.
Berta hanya dua bersaudara perempuan dengan Rumiris, kakaknya. Senandung itu, tanpa disadari Poltak, mengena pada dirinya.
"He, Poltak. Itulah gunanya pariban. Jadi sandaran." Berta tiba-tiba menjawab senandung Poltak.
"Hah?" Poltak kaget. Mulutnya ternganga.